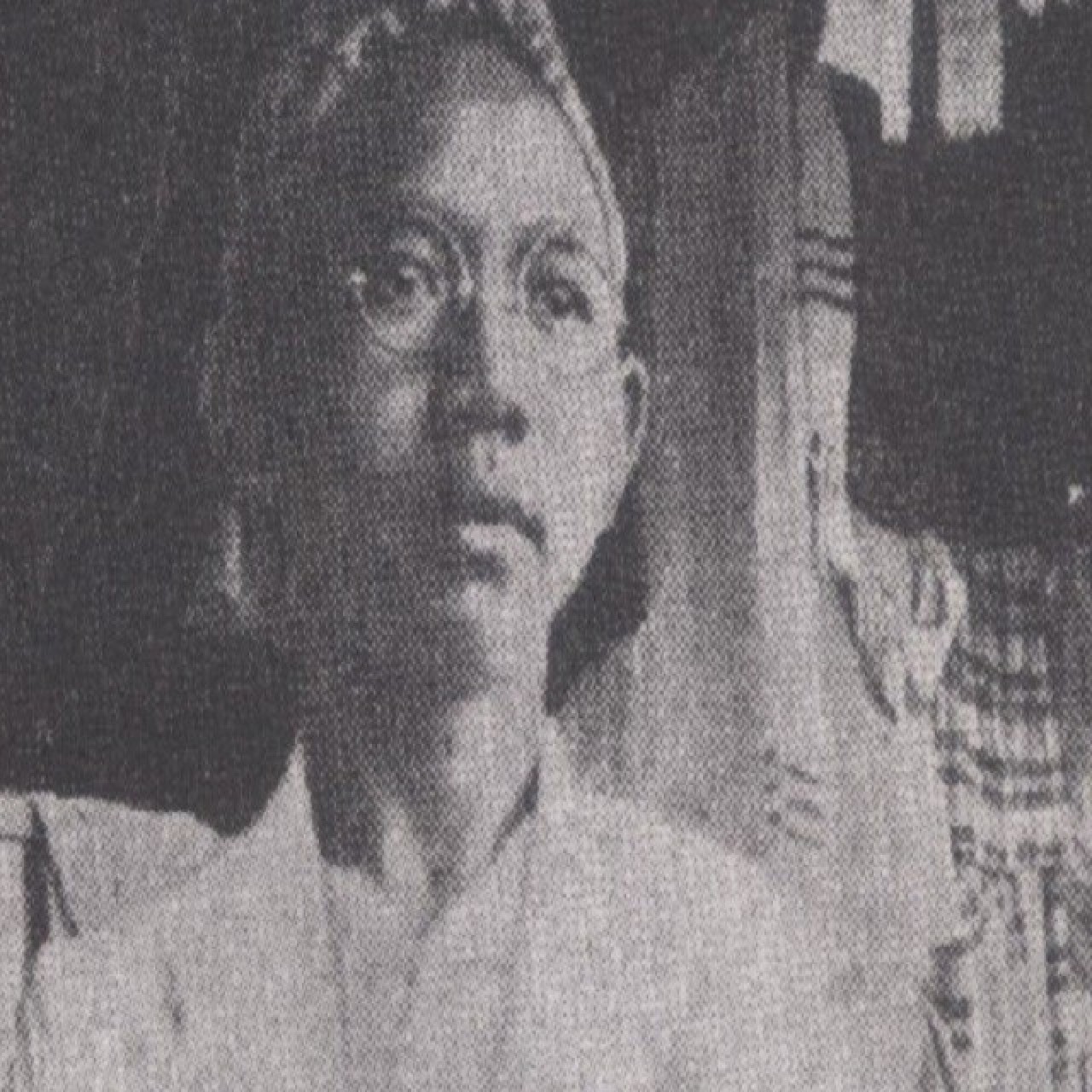Ilustrasi: KH Hasyim Asy'ari (tengah) bersama KH Dawam (kanan) dan KH Jazuli Usman. Foto sekitar 1917-an, depan mihrab Masjid TBI. (Foto: dok. NU Online)
Jabatan Rais Akbar diberikan kepada Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari setelah jam’iyah Nahdlatul Ulama dideklarasikan pada 16 Rajab 1344 bertepatan 31 Januari 1926. Namun setelah KH Hasyim Asy’ari meninggal dunia pada 25 Juli 1947, gelar Rais Akbar tidak digunakan lagi. KH Abdul Wahab Chasbullah yang menggantikan Kiai Hasyim Asy’ari lebih memilih sebutan Rais ‘Aam.
KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013: 457) mencatat, dengan sikap tawadhu’, Kiai Wahab Chasbullah tidak bersedia menyandang gelar Rais Akbar yang menurut Kiai Wahab hanya tepat untuk Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, saudara misan (sepupu) yang juga gurunya.
Melalui Muktamar ke-17 NU tahun 1947 di Madiun, Jawa Timur, ia resmi menggantikan peran KH Hasyim Asy’ari yang wafat untuk memimpin NU dan Masyumi kala itu.
KH Hasyim Asy’ari merupakan pemegang sanad ke-14 dari kitab Shahih Bukhari Muslim. Keilamuan agama ia perdalam di tanah hijaz dan banyak berguru dari ulama kelahiran Nusantara di Makkah seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfudz Termas, Syekh Yasin Al-Fadani, dan ulama-ulama lainnya.
Sebutan hadlratussyekh sendiri menggambarkan bahwa ayah KH Wahid Hasyim tersebut merupakan mahaguru, mahakiai. Bahkan, Muhammad Asad Syihab dalam buku Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari: Perintis Kemerdekaan Indoensia (1994) menyebut Kiai Hasyim dengan sebutan al-‘Allamah. Dalam tradisi Timur Tengah, istilah tersebut diberikan kepada orang yang mempunyai pangkat keulamaan dan keilmuan yang tinggi.
Meskipun Kiai Hasyim Asy’ari mumpuni dalam ilmu agama, tetapi ia tidak menutup mata terhadap bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi terjajah. Kegelisahaannya itu dituangkan dalam sebuah pertemuan di Multazam bersama para sahabat seangkatannya dari Afrika, Asia, dan juga negara-negara Arab sebelum Kiai Hasyim kembali ke Indonesia.
Pertemuan tersebut terjadi pada suatu di bulan Ramadhan, di Masjidil Haram, Makkah. Singkat cerita, dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan di antara mereka untuk mengangkat sumpah di hadapan “Multazam”, dekat pintu ka’bah untuk menyikapi kondisi di negara masing-masing yang dalam keadaan terjajah.
Isi kesepakatan tersebut antara lain ialah sebuah janji yang harus ditepati apabila mereka sudah sampai dan berada di negara masing-masing. Sedangkan janji tersebut berupa tekad untuk berjuang di jalan Allah SWT demi tegaknya agama Islam, berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam.
Bagi mereka, tekad tersebut harus dicetuskan dan dibawa bersama dengan mengangkat sumpah. Karena pada saat itu, kondisi dan situasi sosial politik di negara-negara Timur hampir bernasib sama, yakni berada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa Barat. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 1985)
Sesampainya di tanah air, KH Hasyim Asy’ari menepati janji dan sumpahnya saat di Multazam. Pada tahun 1899 M, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Dari pesantren ini kemudian dihimpun dan dilahirkan calon-calon pejuang Muslim yang tangguh, yang mampu memelihara, melestarikan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kiai Hasyim Asy’ari merupakan ulama abad 20 yang telah berhasil melahirkan ribuan kiai.
Dari muktamar ke muktamar, KH Hasyim Asy’ari dan ulama-ulama pesantren tidak pernah melepaskan diri dari problem bangsa dan problem-problem kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia kala itu, bahkan bervisi global. Muktamar sebagai forum tertinggi jam’iyah NU digunakan sebagai wadah transformasi sosial menuju masyarakat yang maju dan bermartabat.
Penulis: Fathoni Ahmad
Editor: Kendi Setiawan