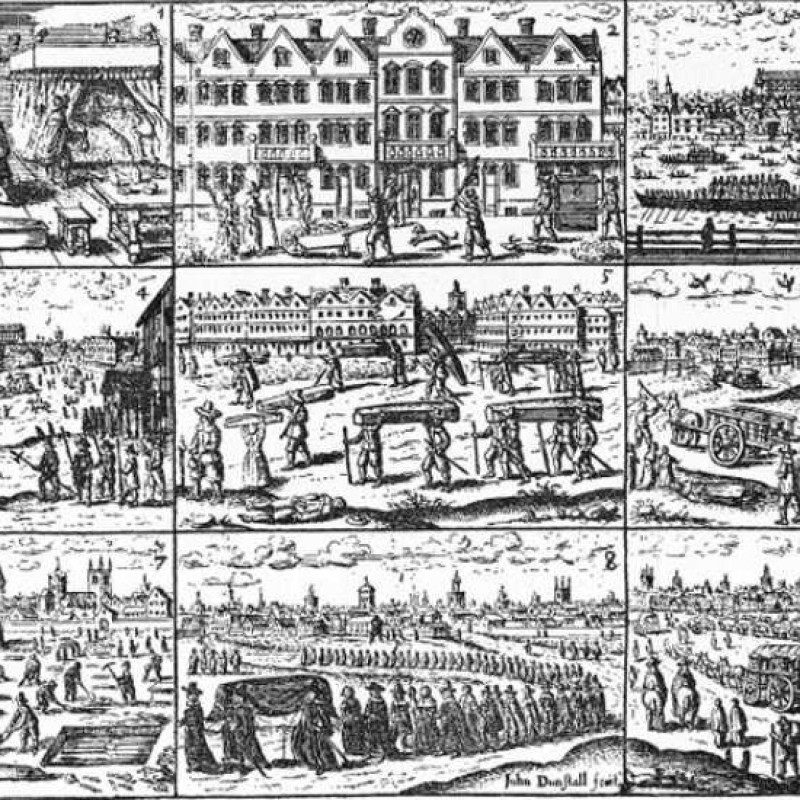Pada masa pandemi Covid-19 ini kita, khususnya saya, memiliki waktu cukup luang sehingga dapat menemani anak-anak nonton berbagai film kartun yang tayang di televisi. Seyogyanya sebuah film, disamping berfungsi sebagai hiburan, film juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat (Heru Effendy, 2009).
Artinya, adegan dan dialog yang disajikan dalam film kartun, besar kemungkinan akan juga mempengaruhi tingkah laku anak-anak dalam berinteraksi dengan orang tua di dalam rumah, dan berinteraksi sesama teman-teman sebayanya di sekolah maupun di lingkungan tempat anak tinggal. Dari film kartun, anak-anak memperoleh refrensi tentang berbagai istilah dan adegan yang mungkin tidak mereka jumpai ketikaberinteraksi sehari-hari dengan orang tua dan saudara-saudaranya di rumah.
Persoalannya, tidak seluruh dialog dan adegan dalam film kartun itu layak dikonsumsi anak-anak. Setidaknya, berdasarkan pendapat Eisenberg dan Mussen sebagaimana yang dikutip oleh Dayakisni dan Hudaniah (2009), terkait dengan peran film sebagai media edukasi, adegan dan dialog dalam film dapat dikategorikan ke dalam dua jenis perilaku.
Ironisnya, sebagaimana perilaku prososial, perikau antisosial ini juga berpotensi serta merta diadopsi oleh anak-anak dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.Karena, menurut Jean Piaget (R.E. Slavin, 2012), anak-anak yang berusia 2-7 tahun ini baru masuk tahap perkembangan praoperasi. Pada level ini, anak-anak tidak dapat membedakan nilai yang terkandung dalam setiap dialog atau adegan yang disajikan di film kartun. Sehingga belum mampu secara mandiri membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut norma apapun.
Jika kita menengok teori perkembangan mandiri yang digagas oleh Steinberg (1995), kita juga sampai pada kesimpulan bahwa anak yang berada di rentang usia 2-7 tahun tidak dapat secara mandiri (autonomy) memilah mana yang boleh dipratikkan karena hal itu baik menurut norma di masyarakat atau mana yang harus ditinggalkan karena hal itu bertentangan dengan norma yang dianut bersama. Karena kemandirian yang dimiliki anak usia tersebut baru pada level kemandirian emosional (emotional autonomy), sedangkan kemandirian dalam menentukan nilai (values autonomy) terjadi saat akan menginjak usia dewasa.
Artinya, tanpa kehadiran orang dewasa saat anak-anak menonton film kartun, maka anak-anak tidak akan dapat membedakan betapa kontradiktifnya nilai yang terkandung antaraperilaku curang dan sportif, misalnya. Jika Ferdinand De Saussure (Sobur, 2009) dalam teori semiotikanya menegaskan bahwa pesan itu terdiri dari signifier (penanda) dan signified (petanda), maka di sini anak-anak hanya dapat menangkap signifier-nyasaja, yaitu aspek material dari dialog dan adegan yang disajikan.
Sedangkan aspek signified-nyayang merupakan substansi atau nyawa dari penanda tersebut belum dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak secara mandiri. Sehingga perilaku curang dan sportif sebagaimana contoh di atas, di benak anak-anak usia 2–7 tahun dianggap bukan sesuatu yang bertentangan. Maka tidak heran kita mendapati anak-anak kita mempratekkan perilaku antisosial saat berinteraksi dengan kita atau teman sebayanya, dan kita ketahui bahwa itu ia adopsi dari adegan pada film kartun yang ditonton sebelumnya.
Dengan demikian, maka anak-anak sebenarnya belum dapat membedakan nilai yang terkandung dalam perilaku antisosial dan perilaku prososial yang tersaji dalam bentuk dialog dan adegan pada film kartun. Bagi anak-anak, kedua perilaku tersebut dianggap bukan sesuatu yang berbeda, dan tentu saja tidak memahami dampak sosial yang ditimbulkan dari dua perilaku tersebut.
Fakta inilah yang menurut hemat saya akan mengusik ketenangan banyak orang tua terhadap beberapa film kartun tertentu yang menyajikan contoh perilaku prososial dan antisosial sama masifnya, seperti yang disajikan di dalam film Si Entong versi animasi. Narasi film ini dibangun fokus pada dua tokoh utama.
Pertama, tokoh Si Entong sebagai tokoh protagonis, yang selalu berperilaku prososial, seperti bersikap jujur, suka berbagi, suka bekerjasama, dan suka menolong. Kedua, tokoh Memet, yang perilakunya selalu antisosial atau bertolak belakang dengan Si Entong: suka curang, tidak sportif, tidak jujur, dan menghalalkan segala cara untuk ‘menjatuhkan’ Si Entong dalam banyak kesempatan. Saya cermati betul, hampir setiap episode film ini terpusat pada konflik dan perseteruan kedua tokoh ini, yang selalu dipicu dengan perilaku tidak terpuji Memet.
Jika kita mengamini teori tahap perkembangan Jean Piaget di atas, kemudian didukung dengan teori perkembangan kemandirian dari Steinberd serta metode semiotika versi Ferdinand De Saussure, maka alih-alih menjadi media edukasi yang efektif bagi anak-anak, justru film Si Entong versi animasi ini melalui tokoh Memet juga memberikan referensi kepada anak-anak tentang berbagai contoh perilaku tidak terpuji atau antisosial. Karena dalam film serial ini, anak-anak dapat informasi sama masifnya antara perilaku prososial dan perilaku antisosial. Sehingga berpotensi anak-anak akan mengadopsi keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
Saran saya, dalam memproduksi film, khususnya yang menyasar ke anak-anak, harusnya kita kebih kreatif dalam menyusun narasi ceritanya. Kita dapat belajar ke tetanggabagaimana narasi atau plot dalam film Ipin dan Upin dirumuskan. Serial Ipin dan Upin ini memiliki karakteristik yang sama dengan Si Entong, yaitu berlatar cerita persahabatan beberapa anak lintas etnis yang hidup di lingkungan yang sama. Bedanya, pada film Ipin dan Upin tidak ada anak yang diplot menjadi tokoh antagonis.
Narasi film Ipin dan Upin dibangun atas dasar persahabatan, kerjasama,serta semangat kolaborasi dan anti kompetisi. Ini saya kira penting sekali karena dapat mengeliminasi anak-anak mendapat asupan tentang perilaku antisosial melalui film.
Meskipuntanpa adanya konflik dan tokoh antagonis yang harus dikalahkan, serial Ipin dan Upin tetap menarik untuk ditonton. Sampai di sini saya berpendapat bahwa serial Ipin dan Upin terlihat lebih relevan dianggap sebagai sarana edukasi untuk membangun karakter generasi muda Abad 21 yang menjadikan kolaborasi sebagai salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki pada Abad 21. Berbeda dengan film Si Entong versi animasi sebagaimana yang saya uraikan di atas.
Penulis adalah Pengajar di Unusia dan Wakil Sekretaris LP Ma’arif NU PBNU