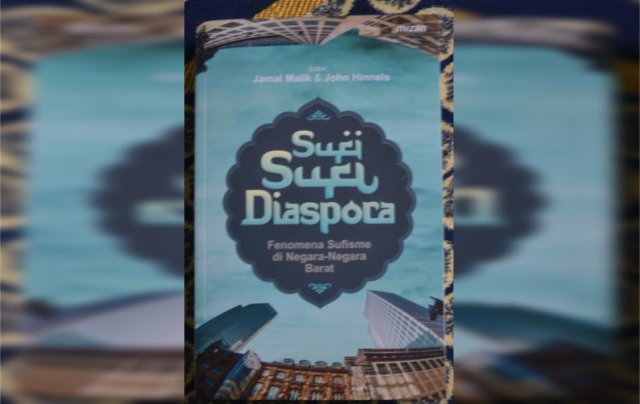Di tengah perkembangan agama Islam ke negeri-negeri Barat, khususnya di kawasan Amerika dan Eropa, muncul sebuah dinamika tentang tasawuf. Migrasi keluarga muslim dari beberapa negara Asia dan Turki, menjadi bagian dari terbentuknya diaspora muslim yang kemudian menunjukkan identitas berupa aliran tasawuf. Perkembangan ini, juga menarik minat dari warga negara di kawasan Eropa dan Amerika, tentang makna sufisme sebagai gerakan alternatif yang mengusung toleransi, cinta kasih dan keindahan.
Buku Sufi-Sufi Diaspora: Fenomena Sufisme di Negara-Negara Barat yang diedit oleh Jamal Malik & John Hinnels menjadi karya menarik untuk menjelajahi perkembangan sufisme di kawasan Eropa dan Amerika. Jika, selama ini negara-negara Eropa dan Amerika dianggap sebagai negeri sekuler, ternyata sufisme memiliki daya tarik yang mempesona di negara-negara tersebut.
Buku ini, menunjukkan bahwa sufisme pada umumnya, dan sufisme di negara-negara Barat pada khususnya, menyediakan beragam artikulasi budaya yang saling berinteraksi dalam ranah publik yang makin beragam, di tengah masyarakat post-modern dan post-sekular. Dalam konteks ini, sufisme memiliki model artikulasi yang beragam dan bersifat altenatif, serta pembentukan visinya tentang Islam yang kaya dalam khazanah spiritualitas dan budaya, menjadikan sufisme menarik perhatian orang-orang Barat.
Gelombang sufisme
Dalam catatan Gisela Webb, sufisme masuk di dunia Barat dalam tiga tahapan: pertama, dimulai pada 1920-an yang didasarkan pada pengetahuan oriental. Gelombang ini, membawa kaum sufi ke Amerika Serikat dalam rangka membawa ajaran mereka ke belahan dunia yang dapat diduga hampir tidak ada spiritualitas apapun. Gelombang kedua, berlangsung sepanjang 1960-an dan 1970-an, dan ditandai dengan kebangkitan-kebangkitan warisan muslim yang hilang dan pencarian spiritualitas di kalangan orang Amerika. Sedangkan, gelombang ketiga, ditandai dengan kehadiran Bawa Muhaiyadden Fellowship yang dimulai pada 1970an di Philadelphia, yang memfokuskan diri pada spiritualitas universal (hal. 36).
Sufisme tidaklah tunggal (monolitik) sebagaimana tidak tunggalnya hukum Islam. 'ortodoksi Islam' atau fundamentalisme Islam. Sebaliknya, menurut Jamal Malik, sufisme sangatlah pluralistik, kompleks, berbeda-beda, bahkan terkadang bertentangan. Sebab, ada perbedaan kepribadian di kalangan guru sufi dalam mengajarkan sufisme, sehingga ide-ide sufisme berubah dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, bergantung pada konteks dan fungsinya (hal. 17). Dengan demikian, lingkungan dan konteks sosial politik sangat mempengaruhi perkembangan serta identitas kelompok sufi di negeri-negeri Barat.
Menurut Jamal Malik, persoalan yang menarik dari fenomena perkembangan sufisme di Barat adalah perdebatan tentang identitas. Menurutnya, hal penting yang terkait dengan isu kontruksi dan rekonstruksi sejarah dan tradisi dalah persoalan identitas anggota-anggota gerakan dan tarekat: dari perspektif internal maupun eksternal. Menurut analisis Jamal Malik, identitas campuran dianggap sebagai prosedur dalam pergaulan antara referensi diri dan referensi yang-lain. "Identitas bisa diubah dengan mengikuti konteks, dan karenanya relatif bersifat situasional, majemuk atau kolektif. Identitas lebih bersifat terbuka ketimbang tertutup. Dengan demikian, identitas bukan sesuatu yang terberi, melainkan dalam proses menjadi, yang menjadi bermakna di dalam konteks" (hal. 50).
Tipe sufisme
Dalam buku, Marcia Hermansen membagi gerakan sufi di Barat menjadi tiga tipe: gerakan hibrida, perenial dan cangkokan. Tipe hibrida, adalah gerakan yang menunjukkan kaitan erat dengan sumber muatan Islam, yang menempel dalam kerangka non-Islam. Gerakan ini, menarik minat kalangan imigran, orang-orang yang terlahir di Barat ataupun yang tersosialisasi di lingkungan baru. Tipe perenial, umumnya mewakili kelompok yang dekat dengan ide bahwa kebenaaran merupakan dasar semua agama (hal. 32).
Perkembangan sufisme di negara Barat, karena terkait konteks dan persaingan antar institusi juga mengakibatkan konflik di kalangan mereka. Konflik ini, baik dalam skala internal maupun eksternal menjadi bagian dari dinamika persebaran sufisme di Barat. Dalam narasi buku ini, konflik tidak perlu dianggap sebagai patologi sosial atau penyimpangan, akan tetapi juga dipandang sebagai kontribusi dalam stabilitas dan daya rekat masyarakat yang berkembang. Berbagai kecenderungan konflik dan pola saling bergantungan ini, terekam dalam transformasi Tarekat Sulaymanci yang diulas dalam riset Jonker, transformasi tarekat Nimatullahi yang dianalisis Lewishon, serta Tarekat Haqqaniyah yang dikaji Damrel dan Nielsen.
Tentu saja, konflik bukan berarti perkelahian ataupun pertentangan yang berlarut-larut. Konflik yang ada merupakan bagian dari dinamika untuk menghadirkan pandangan-pandangan Islam yang selaras dalam diri warga Barat. Salah satu contohnya, perkembangan sufisme di negeri Inggris. Ron Geaves mengkaji tentang bagaimana dinamika kelompok sufisme di Inggris Raya. Dalam catatan Geaves, perkembangan sufisme di Inggris tidak mudah, karena diwarnai dengan perdebatan dan kritik dari pengikut neo-wahabisme. Kelompok neo-wahabi ini, sebagian besar dari anak-anak muda yang sudah tidak terlalu terikat dengan asal-muasal negeri orang tuanya. Imigran dari Timur Tengah, maupun Turki yang masuk ke Inggris menjadi diaspora muslim, yang kemudian mewujudkan identitasnya dalam beberapa tradisi sufisme.
Di Inggris, perkembangan sufisme juga mendapat pertentangan berupa kritik dari kaum neo-wahabisme. Kaum muda yang cenderung mengikuti pandangan neo-wahabisme, seringkali mengkritik bahwa sufisme hanya sebagai takhayul yang menyimpang yang tertanam dalam praktik dan kepercayaan tradisi pedesaan sub-benua India itu, serta dicemari oleh kontak Islam dengan agama Hindu (hal.278). Persoalan tentang imigran juga menjadi bahan kritik terhadap kaum sufi, yang dianggap hanya mengagungkan negeri asal, tanpa mau beradaptasi dengan perkembangan negeri di kawasan Inggris.
Buku ini, memberi sumbangan yang berharga karena menghadirkan narasi sufisme yang berbeda dengan arus mainstream di dunia Islam. Perkembangan sufisme di negeri Barat, tidak hanya tentang hadirnya Islam, akan tetapi lebih dari itu sebagai sebuah transformasi identitas. Sufisme dengan demikian, menjadi simbol toleransi dan humanisme, karena tidak dogmatis, fleksibel dan anti-kekerasan, tidak berupaya ke arah pembentukan suatu tatanan ketuhanan yang monolitik. Sufisme dianggap sebagai titik awal untuk adaptasi Islam, terutama dalam konteks praktik Islam versi Eropa serta bagi perjumpaan antar agama.
Info Buku:
Judul: Sufi-Sufi Diaspora: Fenomena Sufisme di Negara-Negara Barat
Penulis: Jamal Malik & John Hinnels (ed)
Penerbit: Mizan, 2015
ISBN: 978-979-433-879-7
Peresensi: Munawir Aziz, Peneliti Islam Nusantara, aktif di Gerakan Islam Cinta (islamcinta.co)
Terkait
Terpopuler
1
KH Said Aqil Siroj Usul PBNU Kembalikan Konsesi Tambang kepada Pemerintah
2
Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah PBNU Hadir Silaturahim di Tebuireng
3
Silaturahim PBNU Sesi Pertama di Tebuireng Selesai, Prof Nuh: Cari Solusi Terbaik untuk NU
4
Kiai Sepuh Respons Persoalan PBNU: Soroti Pelanggaran Pemakzulan dan Dugaan Kekeliruan Keputusan Ketum
5
KH Ma’ruf Amin Ikuti Forum Sesepuh NU, Sampaikan 4 Sikap untuk Redam Persoalan di PBNU
6
Hasil Lengkap Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng
Terkini
Lihat Semua