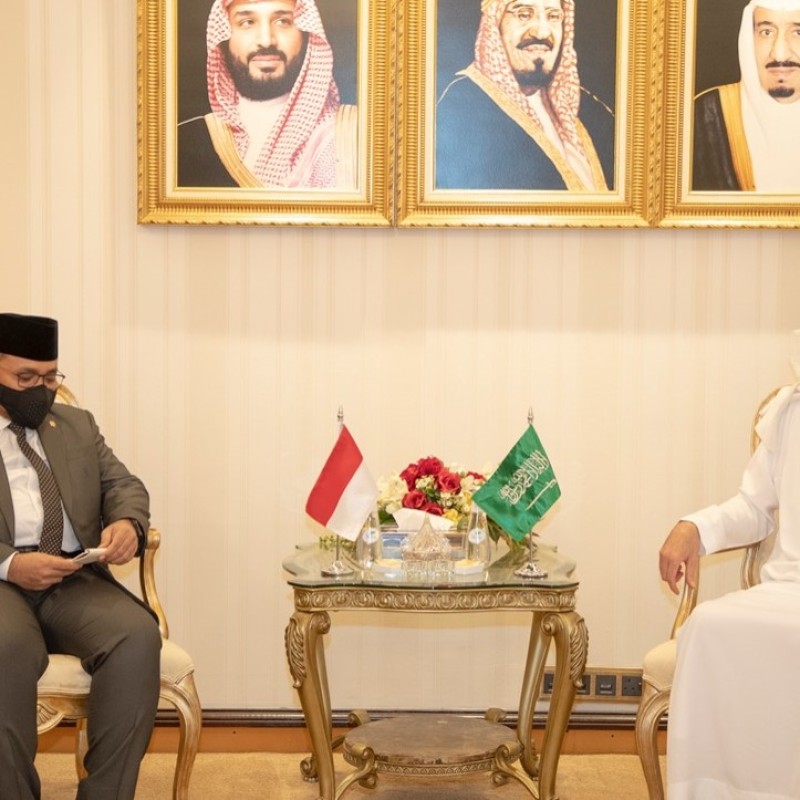Berhaji menjadi impian setiap umat Islam. Betapa untuk melaksanakan haji ini dibutuhkan biaya dan tenaga yang tak sedikit. Pasalnya, bukan saja dalam persoalan pelaksanaannya saja, tetapi hal yang paling berat dari ibadah haji di sebelum abad 20 justru adalah perjalanannya yang menempuh hitungan bulan. Karenanya, hal ini menjadi satu prestise sendiri bagi mereka yang mampu. Belum lagi dorongan ideologis dan doktrin para kiai untuk menggenapi keislaman dan keimanan. Tak pelak, alang rintang seberat apapun berani mereka tempuh demi tujuan tersebut.
Sayangnya, kenekatan umat Islam Nusantara itu tak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. Bukan saja perihal peribadatan haji itu sendiri, melainkan yang tak kalah penting adalah soal perjalanannya. Medan yang ditempuh selama perjalanan tidak ada dalam bayangan. Kepercayaan pada orang lain yang demikian kuat justru menjadi bumerang.
Baca Juga
Kisah di Balik Sebutan ‘Haji Singapura’
Ketika sampai di Pelabuhan Jeddah, mereka sudah disambut dengan para pemandu ibadah haji. Orang Nusantara menyebut pemandu dengan sapaan Syekh. Sebagai seorang pemandu, syekh tentu memiliki kemampuan berbahasa yang piawai. Selain berbahasa Arab sebagai bahasa ibunya, syekh ini juga mahir bercakap dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca masyarakat Nusantara di zamannya.
Syekh tentu tidak hanya mengarahkan jamaah dalam menjalankan ibadah, tetapi juga mencarikan penginapan, hingga menyewakan unta untuk perjalanan. Dalam catatan Prof Dien Majid dalam Berhaji di Masa Kolonial (2008: 123), kedua hal tersebut penting mengingat sebagian besar jamaah Nusantara datang ke Makkah jauh sebelum waktu ibadah haji tiba.
Syekh ini bukan pekerjaan yang sukarela. Mereka hadir karena memang untuk mencari penghidupan. Dien Majid dalam buku yang sama (2008: 124) menulis, bahwa mereka mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dengan jamaahnya.
Lebih dari sekadar pembantu, syekh juga hadir memberikan pinjaman ketika bekal jamaah tak cukup. Sebab, syekh perlu menjalin hubungan yang baik dengan jamaah karena jejaringnya bisa berkembang untuk kerja sama menjaring calon jamaah baru di tahun-tahun berikutnya. Namun, dalam catatan Eric Tagliacozzo dalam bukunya yang berjudul Southeast Asians and The Pilgrimage to Mecca (2013: 77), syekh yang memberikan utang tersebut biasanya merupakan penduduk Arab yang tinggal di Asia Tenggara. Utang ini terpaksa dilakukan karena pemerasan dari syekh sendiri yang membuat mereka kehabisan bekal.
Pemerasan yang dilakukan syekh ini ditengarai akibat tekanan yang cukup besar dari pemerintah setempat. Pasalnya, mereka harus menyetorkan sejumlah penghasilannya kepada pemerintah sebagai pajak atas pendapatannya. Tak pelak, jamaah haji ini menjadi korban dari eksploitasi mereka. Karenanya, banyak timbul pemerasan dengan dalih tertentu yang di luar perkiraan jamaah sehingga bekal mereka habis untuk hal tersebut.
Cerita ini, dalam catatan Henry Chambert Loir pada buku Naik Haji di Masa Silam: Kisah-kisah Orang Indonesia Naik Haji (2019: 50), bukan barang baru mengingat cerita serupa pernah disampaikan oleh Ibn Jubayr pada abad 12. Hal ini juga tidak berubah setelah peralihan kekuasaan pemerintah ke Ibnu Saud pada abad 20. Artinya, tidak ada perubahan berarti yang dilakukan, orang-orang Jawi atau Jawa dan Melayu tetap menjadi sasaran empuk syekh masyarakat Arab dan oknum yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Terlebih mereka tidak menguasai bahasa Arab dan pengetahuan mengenai tata cara ibadah haji itu sendiri. Mereka percaya saja pada apa yang diarahkan oleh syekh.
Hal ini juga disampaikan Michael Christopher Low dalam tulisannya The Infidel Piloting the True Believer: Thomas Cook and the Business of the Colonial Hajj dalam buku The Hajj and Europe in the Age of Empire (2017: 76), bahwa Syarif Makkah menekan para syekh untuk dapat menguasai para jamaah dari Jawa, Melayu, dan India. Akibatnya, mereka membebankan biaya kepada para jamaah dengan menaikkan harga-harga kebutuhan, mulai kapal, penginapan, unta, tenda, hingga hampir seluruh kebutuhan mereka.
Bukan hanya oleh syekh, jamaah haji Nusantara juga ‘dimanfaatkan’ oleh pedagang, orang Badui dan lain-lain tanpa ampun. Henry mengutip Snouck Hurgronje (1931), orang Arab menjuluki jamaah haji dengan menghina, yakni farukha (jamak kata farkh, ayam itik), dan baqar, hewan ternak.
Tak ayal, orang Melayu dan Jawa di mata orang Arab dalam catatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan HAMKA, bahwa jamaah tak ubahnya sebagai kambing-kambing di mata orang Arab. Bahkan Abdul Majid Zainuddin dalam Proses Haji menurut Pimpinan Haji Malaysia dalam buku Haji di Masa Silam, sebagai sapi perah.
Penulis: Syakir NF
Baca Juga
Kisah Ulama Berhaji Tanpa ke Tanah Suci
Editor: Fathoni Ahmad