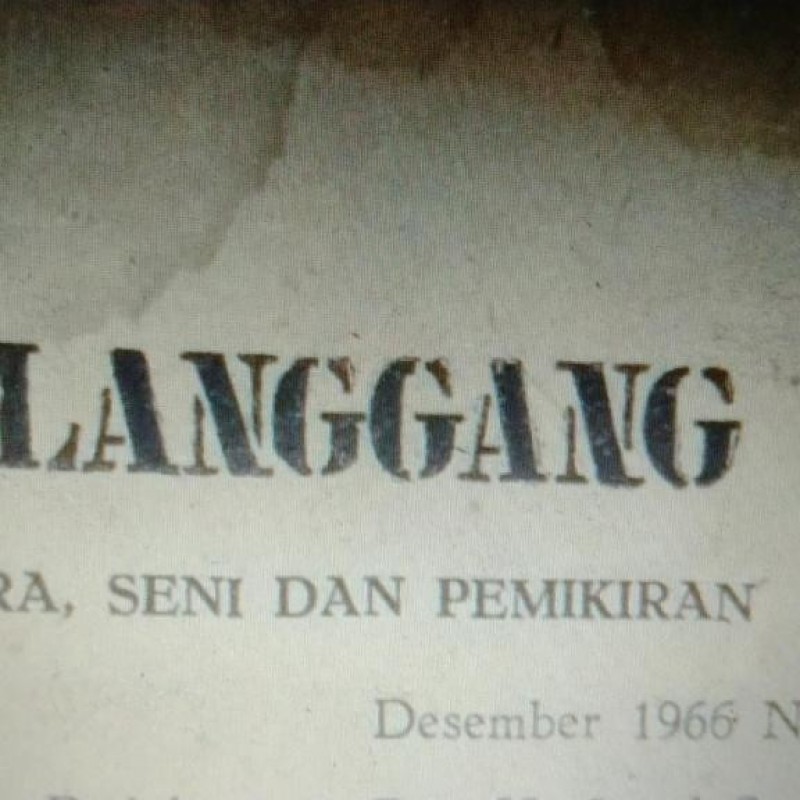"Alip enun tasjid jeer in, nun alip elam-elam tasjid jabar nal, lam jabar la, he jabar ha innallaha... dst... dst..."
Suatu waktu aku sedang menamani Kang Haer membuat kaligrafi di tajug. Sebentar lagi Lebaran. Cat dinding luar dan dalam tajug diperbarui sehingga kaligrafi yang sebelumnya terhapus. Harus diperbarui juga
Waktu itu, aku sebetulnya hanya membantu Kang Haer memegang wadah kapur atau membantu mengangkat dan memindahkan tangga. Aku belum bisa apa-apa. Juga tak setiap santri terampil membuat kaligrafi. Hanya santri yang ahli yang bisa membuat kaligrafi bagus.
Di atas mimbar Kang Haer membuat lafadz "Allah", di bawahnya "Muhammad", di sebelahnya kiri kanan lafadz para sahabat, "Abubakar", "Umar", "Usman" dan "Ali" (radiallahu anhum).
Lafadz-lafadz itu sudah selesai kemarin. Hari ini menyelesaikan lafdz di bilik di atas jandela. Lafadnya itu ternyata ayat Al-Qur’an, "Innad dina 'indallahil islam".
Pukul sebelas Kang Haer menyelesaikan pekerjaannya. Menurutku, sangat bagus. Sampai saat ini aku tak mampu menulis sebagus itu.
Setelah bagian itu selesai, Kang Haer beralih ke bagian dalam di atas pintu masuk.
"Coba baca lafadznya!" pinta Kang Haer kepadaku.
"Ajilu bisshalati qablal faut, wa ajilu bit taubati qablal maut."
"Apa artinya?" tanya Kang Haer sembaru mulai menulis.
Aku berpikir keras, tapi tetap saja tak mengerti.
"Masak tidak tahu?" ucap Kang Haer lagi sambil tetap menulis.
"Kata ajilu fi'il atawa isim?"
"Fi'il," jawabku.
"Kenapa disebut fi'il?" tanya Kang Haer.
"Sebab tak ada alip-elam atawa tanwin," jawabku.
"Fi'il apa itu?" tanya Kang Haer.
Aku terdiam.
"Fi'il mudore bukan?"
"Bukan."
"Sebab tak ada alif, nun, ya atau ta."
"Coba lanjutkan sarafna. Apa fi'il madinya lafadz itu."
"Ajala," kataku menebak.
"Benar", kata Kang Haer. "Tuh, sudah ketahuan, bukan fi'il mudore, bukan fi'il madi, jadi fi'il apa?"
"Fi'il... amar," kataku masih ragu-ragu.
"Betul fi'il amar. Coba terjamahkan!"
Setelah dituntun Kang Haer, aku meraba-raba.
"Segeralah bertobat sebelum lupa dan segeralah shalat sebelum maut...".
Kang Haer memujiku.
“Shalat rasanya tidak pernah lupa,” aku membatin. “Tapi bagaiman dengan taubat?” lanjutku dalam hati?”
Banyak sekali dosa yang belum aku taubati. Padahal bisa jadi besok atau lusa aku meninggal.Siapa tahu. Bisa jadi nanti malam. Sangat berbahaya meninggal sebelum bertaubat.
Waktu aku berpikir seperti itu, aku kaget sebab ingat pernah mencuri ikan dari kolam milik ajengan. Memang waktu itu yang turut serta banyak santri, tapi aku menjadi pelopornya.
Dalam hati, aku akan bertubat sebelum Lebaran. Kemudian meminta maaf kepada ajengan pada hari Lebaran. Namun, apa betul aku masih hidup sampai Lebaran? Siapa tahu aku meninggal sebelum lebaran? Siapa tahu? Allah berkuasa mencabut nyawa kapan saja, sementara berdasarkan lafadz kaligrafi tadi, segeralah bertaubat sebelum maut!
Tanpa berpikir panjang, aku berlari pontang-panting. Kang Haer berteriak memanggil tanpa tahu apa-apa. Aku tak menengoknya sama sekali. Tujuanku berlari ke rumah ajengan mau bertaubat habis-habisan, mau minta maaf habis-habisan sambil menangis habis-habisan. Sebab menurut Ajengan, bertaubat dengan mengluarkan air mata itu sangat bagus.
Ajengan ada di beranda rumahnya. Waktu itu sedang tak berpeci.
Aku datang menghadapnya dan langsung menangis sebelum bercerita.
Ajengan sepertinya kaget.
"Kenapa?" tanyanya.
“Takut meninggal sebelum Lebaran," kataku terputus-putus.
Setelah beberapa saat menangis, aku terdiam. Bukan karena apa-apa karena aku selintas melihat si dia yang berkerudung merah di dalam rumah.
Kemudian aku menceritakan dosa mencuri ikan ajengan dan memohon dimaafkan.Ajengan memaafkan lahir-batin, dunia akhirat.
"Sayang sekali kamu bertaubat di siang hari sebab batal puasa kalau menangis."
Senang sekali mendengar ajengan yang memaafkan, tapi merasa kecewa sebab aku ternyata batal puasa.
Kemudian aku pamit, pergi ke kobong. Tanpa ragu-ragu aku langsung minum. Si Atok kaget bukan main. Aku kemudian menceritakan apa yang terjadi. Dan menurut ajengan puasaku batal.
Tanpa diduga, si Atok pun menangis.
“Aku banyak dosa. Maka aku menangis.”
Sejam setelah itu, saat santri-santri lain menahan lapar, aku dan si Atok sedang melahap nasi liwet hangat dengan sambel goang.
Ketika Si Umar datang, liwet tinggal keraknya. Sepertinya jika liwet masih ada, tentu dia juga akan menangis dengan alasan bertaubat.