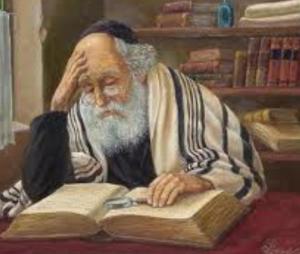Tanpa pemahaman sejarah, jiwa generasi muda akan kosong. Mereka akan menjadi orang-orang pintar yang menjual bangsa dan negaranya. Orang-orang yang korupsi itu, kan, orang pintar (Kompas/9/12/12).
<>
Pernyataan ini membuat saya gelih, miris dan berpikiran aneh. Membuat saya ingat kata orang paham bahwa “orang paham” dan “orang pintar” berbeda.
Kalau boleh mengartikan dengan sederhana bahwa orang paham adalah orang yang mampu memahami antara dunia material dan dunia non-material sehingga ketika bekerja lebih banyak ikhlasnya (tampa pamrih) daripada kepentingannya, misalnya orang-orang yang paham sejarah dan orang yang paham budaya lokal yang sampai saat ini masih dipertahankan di daerah-daerah tertentu. Orang pintar adalah orang yang sudah banyak menghisap ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu pengetahuan tersebut tidak memberikan perubahan apa-apa dalam diri orang pintar, misalnya orang korupsi.
Menurut filolog dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarat, Oman Faturrahman bahwa tradisi intelektual Islam Indonesia sudah mapan sebagai produsen Ilmu pengetahuan sejak abad ke-17, bukan sekedar konsumen atas karya-karya intelektual Islam dari Timur Tengah. Ini menandakan bahwa kita memiliki kesadaran sejarah atau dengan kata lain kita memiliki kesadaran belajar dari orang paham, sejarah sudah banyak menyimpan data-data pemahaman tentang kehidupan, misalnya manuskrip di Aceh (baca: Aceh) yang menyimpan banyak ragam mulai dari bidang keilmuan yang menggambarkan tradisi intelektual Islam, hingga gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti info gempa, gerhana matahari, dan obat-obatan.
Di Solo misalnya ada gerakan untuk menyelamatkan budaya bangsa yaitu Yayasan Sastra Lestari yang dirintis oleh Supardjo sejak 1996 (baca:Solo). Dengan menerjemahkan dan melakukan digitalisasi naskah kuno. Anehnya gerakan murni kerja tanpa pamrih dan murni kepentingan bersama dalam menyelamatkan budaya bangsa. Dimana negara kita? Karena menurut para filolog manuskrip adalah kekayaan intelektual bangsa yang harus diselamatkan.
Jadi jelas, bahwa Indonesia mengandung banyak nilai-nilai filosofi kehidupan. Inilah kekayaan Indonesia, mulai dari budaya, adat, sejarah, tradisi intelektual, manuskrip-manuskrip, hanya saja kita sekarang tidak memiliki tradisi untuk belajar memahami tradisi intelektual yang bercorak “Indonesia” itu. kita lebih suka merayakan budaya Barat, daripada budaya kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan kemudian dimanakah nilai-nilai itu “terkubur”. Untuk menjawab hal itu, kita lihat Indonesia hari ini dan pemuda hari ini. Indonesia yang jauh dari nilai-nilai kearifan lokal. Lantas bagaimana menjadi Indonesia?
Salah satu dari sekian banyak jalan untuk menjadi Indonesia adalah dengan kembali pada apa yang di sebut “Diri” oleh Muhammad Iqbal. Diri di sini adalah Indonesia itu sendiri, yang banyak menyimpan mental sejarah yang mampu menjadikan Indonesia yang mandiri dalam segala bidang, terutama keilmuan, dan filsafatnya.
Akhirnya banyak mahasiswa yang mendirikan Komunitas untuk berjuang sendiri, tanpa bantuan pemerintah, karena perihatin terhadap terabaian sejarah. Sejarah menjadi menara gading yang hampa di mata koruptor, tapi sejarah sebuah formula kehidupan bagi orang-orang yang paham akan bangsa dan negara.
Orang paham, mereka mengerti apa makna gotong royong, keramahan, kesopanan, dan musyawarah, yang kini nilai-nilai itu tidak di kenal kembali. Orang-orang tidak mau lagi untuk menoleh ke masa lalu, padahal masa lalu menjadi cermin kita untuk belajar, dan memahami. Kita kehilangan basis epistemologi yang disebenarnya di dalam manuskrip itu telah ada. Akhirnya benar apa yang ditulis oleh Putu Setia bahwa orang cerdas (paham) dan jujur tersisih, orang dengki dan pembohong menjadi pemimpin.
Epistemologi Islam
Epistemologi Islam menjadi penting untuk dikaji lebih jauh sebagai sebuah alternatif terhadap sistem epistemologi Barat yang begitu mendominasi wacana epistemologi kontemporer, tak terkecuali di Indonesia. Menurut Mulyadi Kartanegara epistemologi dan filsafat ilmu, kalau memang mau dibedakan, ditulis oleh sarjana Indonesia bercorak Barat, hanya satu atau dua karya epistemologi Islam yang dapat ditemukan di Nusantara ini.
Ini akibat terputusnya generasi muda, ada yang hilang dari sejarah kita. mengapa kita terlalu mengikuti Barat, akhirnya nilai ke “diri”an kita sebagai Indonesia hilang. Walau pun Barat tidak harus dikesampingkan, akan tetapi kata Mulyadi Kartanegara (2003) ketika prestasi ilmiah yang begitu gemilang dari sains modern seharusnya tidak menghalangi kita untuk melihat sisi negatifnya, misalnya dalam bentuk dampak dan implikasi sekulernya terhadap sistem kepercayaan agama kita.
Oleh karena itu, sikap kita untuk selalu kritis dan hati-hati terhadap sains modern yang kini banyak mempengaruhi pemikiran kita, sehingga kita menjauh dari budaya bangsa sendiri. Namun, saya yakin, kalau kita belajar dan bersikap kritis tidak akan lahir pandangan yang sepihak (parsial) dalam melihat dan memahami manuskrip-manuskrip. Tanpa perbandingan antara budaya Indonesia dengan budaya Barat, sikap kritis tersebut sulit dicapai karena kita tidak bisa membedakan dengan yang lain, seperti tidak mungkinnya kita mengenal dengan baik “wanita” tanpa dibandingkan dengan laki-laki.
Oleh karena itu, sikap kritis dan waspada harus tetap menyertai sikap apresiatif terhadap sains modern. Agar bangunan filosofis dalam Islam tidak runtuh, sebab perkembangan pemikiran yang berkembang di Dunia Islam, harus kritis terhadap pemikiran ilmiah dan filosofis Barat, yang menurut Mulyadi Kartanegara telah terlalu berpihak pada sekularisme dan materialisme.
Dengan kembali pada jati diri bangsa dan negara, memahami kekayaan budaya Indonesia sebagai kekayaan intelektual, kekayaan mental, budaya yang ada dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia akan menjadi basis yang memukau dalam mencapai cita-cita Pancasila.
MATRONI MUSERANG, peneliti di Lembaga Kajian Budaya, Agama dan Filsafat (LiSafa) Pasca-sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.