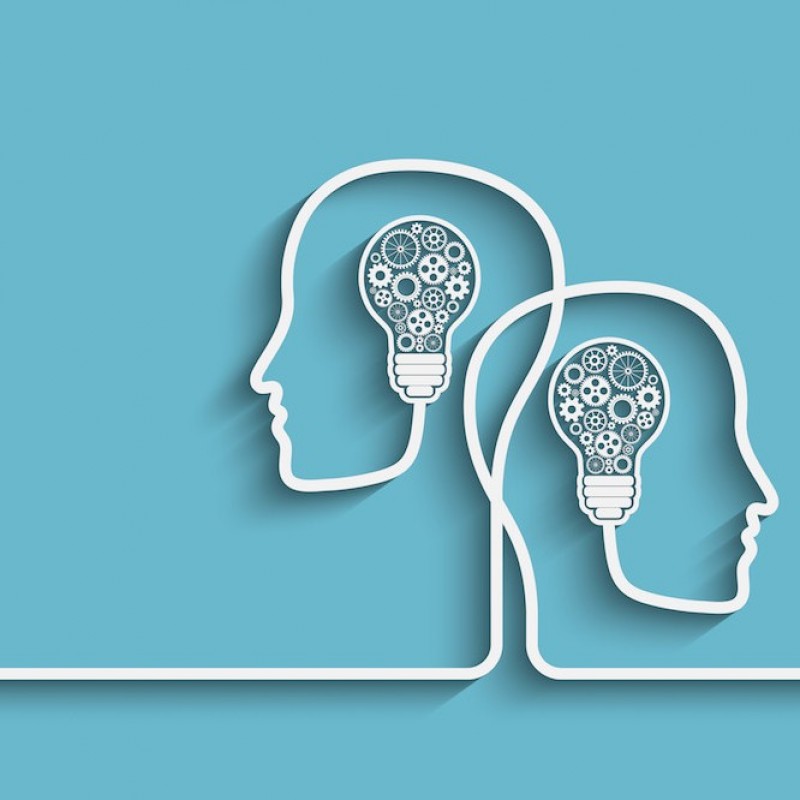“Muslim tanpa masjid” merupakan istilah yang pernah dikenalkan salah seorang intelektual Kuntowijoyo yang kemudian menjadi judul buku kumpulan esainya. Daya analisis ilmiah dan intelektual penulisnya, memang tampak kuat saat itu, dan mungkin baru bisa dirasakan di era sekarang ini. Berbekal buku itu, seolah layak bagi penulisnya untuk disejajarkan dengan Nurkholis Madjid yang akrab di panggil Cak Nur dan KH Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur.
Beda Kuntowijoyo dengan kedua tokoh terakhir yang telah disebutkan tadi, adalah ia berangkat murni dari seorang cendekiawan, pemikir ideologis, dan sekaligus sastrawan jalanan, yang akrab berkecimpung dalam dunia akademis dan pendidikan. Ujungnya, ia tidak memiliki basis massa untuk menopang pergerakan. Kerja nyatanya adalah menyampaikan pemahaman dan penalaran lewat dunia akademis kepada para mahasiswa, lewat undangan seminar-seminar, atau ceramah-ceramah ilmiah.
Lain halnya dengan Cak Nur dan Gus Dur. Cak Nur memiliki basis kuat intelektual dan akademisnya lewat Paramadina yang dibidaninya dan basis massa mahasiswa HMI. Itu wajar saja karena memang Cak Nur pernah menjadi petinggi di organisasi mahasiswa ini. Sementara itu, Gus Dur memiliki basis kultural yang lebih kuat lagi melebihi Cak Nur. Basisnya tidak hanya berkutat di kalangan mayoritas masyarakat Muslim Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah dipimpinnya, melainkan juga di kalangan mahasiswa PMII, bahkan komunitas agama lain serta penganut kepercayaan di Indonesia yang sering dibelanya, seperti komunitas Konghucu.
Jargon yang dibawa Gus Dur melalui konsep pluralisme terbukti berbeda dengan konsep pluralitasnya Cak Nur sehingga menyisakan adanya dua kutub dukungan yang kuat terhadap mereka berdua dan bahkan kutub inilah yang kemudian mengantarkan Gus Dur dalam memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia, di awal-awal reformasi.
Adapun topik Muslim tanpa masjid, setidaknya yang menjadi fokus perhatian Kuntowijoyo di sini, berfokus pada gerakan yang super terstruktur dari anak-anak muda Muslim perkotaan. Eksklusivisme menjadi karakteristik dari gerakan tersebut--mereka menjaga jarak dari dua kutub gerakan mahasiswa yang selama itu berkembang.
Gerakan dari Muslim tanpa masjid ini tidak sebagaimana lazimnya kemunculan NU dan Muhammadiyah di awal sejarahnya. NU jelas kemunculannya dari keprihatinan basis Islam kultural yang bernuansakan santri Pesantren terhadap Wahabisme di Arab, dengan awal melembaga sebagai Komite Hijaz. Oleh karenanya, cita rasa yang muncul di permukaan adalah kultur kepesantrenannya, mazhab yang dianutnya, serta tidak tercerabut dari akar budaya masyarakat Indonesia, seperti ketakziman pada kiai atau tokoh yang dituakan.
Adapun Muhammadiyah, sejak awal berdirinya memang sudah bangkit dari dunia akademisi dan pendidikan. Itulah sebabnya, ia dicirikan sebagai berkultur modernisme karena kontribusinya dalam dunia tersebut. Akibatnya, geneologi gerakan yang mencuat di permukaan dari keduanya pun juga tampak dan bisa diketahui karakteristiknya. NU dicirikan sebagai Islam kultural, sementara Muhammadiyah dicirikan sebagai Islam modern.
Karena geneologi yang mudah didistingsikan itu, Kuntowijoyo kemudian melihat ada pola geneologi lain keislaman yang tidak masuk dalam dua geneologi yang sudah ada dan mapan di Indonesia kala itu. Dan ini yang kemudian dicatat oleh Kuntowijoyo sebagai gerakan “Muslim tanpa Masjid.” Sebagaimana ini kemudian digambarkan dalam sajak bait puisi karyanya:
“Generasi baru Muslim telah lahir dari rahim sejarah, tanpa kehadiran sang ayah, tidak ditunggui saudara-saudaranya. Kelahirannya bahkan tidak didengar oleh Muslim yang lain. Tangisnya kalah keras oleh gemuruh teriakan-teriakan reformasi” (Kuntowijoyo, 1999).
Kuntowijoyo melihat bahwa geneologi ini lahir dari belahan dunia pendidikan SD, SMP dan SMA dengan pengalaman pendidikan yang hanya digembleng dan tunduk di bawah pembekalan yang disampaikan oleh para mentornya. Tepatnya, lahir dengan dibidani oleh kelompok Rohis (Rohani Islam) yang menjadi bagian dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di setiap lembaga tersebut. Dan pemahaman mereka ini rupa-rupanya tidak terkawal dan terdeteksi sejak dini oleh dua lembaga yang sudah mapan sebelumnya di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.
Saat mereka, para keluaran dari Rohis ini, melanjutkan studinya di universitas-universitas serta perguruan tinggi, mereka disatukan kembali dalam budaya membentuk halaqah dengan lingkup terbatas. Di sini mereka mendapatkan gemblengan dari para murabbi (tutor rohani) dan dicekoki oleh berbagai selebaran, berita, buletin, majalah, CD yang tidak diketahui sumber dan validitasnya. Semangat keislaman mereka yang tinggi, dijauhkan dari gemblengan ala pesantren dan masjid-masjid yang sudah ada, guna menjaga geneologi baru yang tengah dibangun dan dipupuk itu.
Inilah kelompok yang kemudian yang disemati oleh Kuntowijoyo sebagai Muslim tanpa masjid. Jadi, maksud dari judul buku itu adalah untuk menunjuk pola gerakan penanaman watak keislaman yang eksklusif (tertutup) serta tidak melalui jalur yang sudah mapan, seperti pesantren dan masjid-masjid. Kultur mereka sebagai yang menyempal dari dua geneologi religiusitas dan keislaman ala Indonesia.
Lebih lanjut, dalam pandangan Kuntowijoyo, sosok Muslim tanpa masjid ini mulai berani menampakkan kekuatannya dalam peta perpolitikan Indonesia di awal reformasi. Ketika mahasiswa Muslim dan beberapa mahasiswa lainnya menduduki Gedung DPR/MPR, ada sekelompok mahasiswa Muslim lainnya yang berada di luar gedung DPR/MPR. Saat terjadi peristiwa pengumuman lengser keprabon oleh H.M Soeharto, para mahasiswa semua bersuka cita dan melakukan sujud syukur secara bersama-sama.
Dan ketika dinyatakan bahwa BJ Habibie sebagai pengganti dari Pak Harto kala itu, terjadilah keterbelahan mahasiswa Muslim. Para mahasiswa yang ada di gedung DPR/MPR sontak menyatakan penolakan. Ini yang kemudian membuat Kuntowijoyo bertanya: ada apa dengan mahasiswa Muslim itu?
Sementara itu mahasiswa Muslim dan beberapa ormas lain yang ada di luar gedung ternyata justru menyatakan hal sebaliknya. Mereka mendukung diusungnya BJ Habibie seiring beliau sebagai tokoh yang merepresentasikan umat Islam kala itu. Pergerakan mahasiswa Muslim di luar gedung yang menuju ke gedung DPR/MPR hampir menimbulkan bentrok massa. Namun, hal itu bisa dilerai oleh petugas keamanan sehingga tidak terjadi kerusuhan.
Menariknya, karena saat itu bertepatan dengan bulan puasa, para mahasiswa Muslim yang ada di gedung DPR/MPR ini kemudian merencanakan untuk menggalang kekuatan dan hendak melakukan demo besar-besaran kembali seiring diangkatnya BJ Habibie sebagai presiden. Namun, berhasil dilerai oleh Gus Dur dengan alasan bisa mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi, apakah mereka berhenti sampai di situ?
Ternyata tidak. Mereka menggelar sebuah acara yang dilaksanakan di halaman parkir Universitas Atmajaya dengan alasan doa dan tarawih bersama terhadap korban reformasi. Gerakan ini kemudian sempat disindir oleh Cak Nur sebagai yang diragukan kemurniannya muncul dari hati nurani mahasiswa. Ada faktor X yang tidak bisa disebutkan oleh Cak Nur. Buntutnya ternyata benar, bahwa ada gerakan politis yang hendak dilakukan oleh mereka. Hanya saja yang kemudian patut dijadikan pertanyaan adalah apa motif politik itu?
Tidak terdeteksinya gerakan ini oleh Cak Nur, ternyata kemudian disoroti oleh Kuntowijoyo. Karena lama ia mengamati peta gerakan Muslim kampus ini, ia kemudian mengajukan sebuah tesa pemikiran bahwa itu pasti bersumber dari pola kajian yang selama ini dilakukannya. Kemudian pengamatan itu dilanjutkan olehnya terhadap bahan-bahan mentoring. Ternyata benar, bahwa mereka lebih suka merujuk pada kajian-kajian yang disampaikan oleh Hasan al-Banna, Sayyid Qutub, Syekh Taqiyuddin al-Nabhani, Ali Syariati dan Al-Maududi yang memang sempat beredar luas di kalangan mahasiswa kampus, termasuk PT Agama Islam Negeri.
Buahnya kemudian terjadi akumulasi kepentingan yang mengatasnamakan diri sebagai penegak khilafah. Sebagian darinya mengakumulasi dalam wadah partai politik yang hingga saat ini masih eksis di Indonesia, dan mereka didirikan oleh para tokoh yang suka mengambil referensi keislaman dari Syekh Hasan al-Banna dan Sayyid Qutub. Adapun sisi lain yang tidak mau mewadah dalam kelembagaan politik kala itu, menyempal sendiri bergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia. Dan mereka ini yang sering merujuk kepada Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.
Kedua ciri dari peta gerakan Muslim tanpa masjid ini memang hingga detik ini masih punya eksklusivitas (ketertutupan) ajaran dan doktrin yang kuat. Dan semua itu, titik awalnya berangkat dari Rohis dan jamaah-jamaah pengajian kampus yang meninggalkan akar dua geneologi keislaman Indonesia dengan berbagai jargon yang dimilikinya.
Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri Pulau Bawean dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBMNU PWNU Jawa Timur