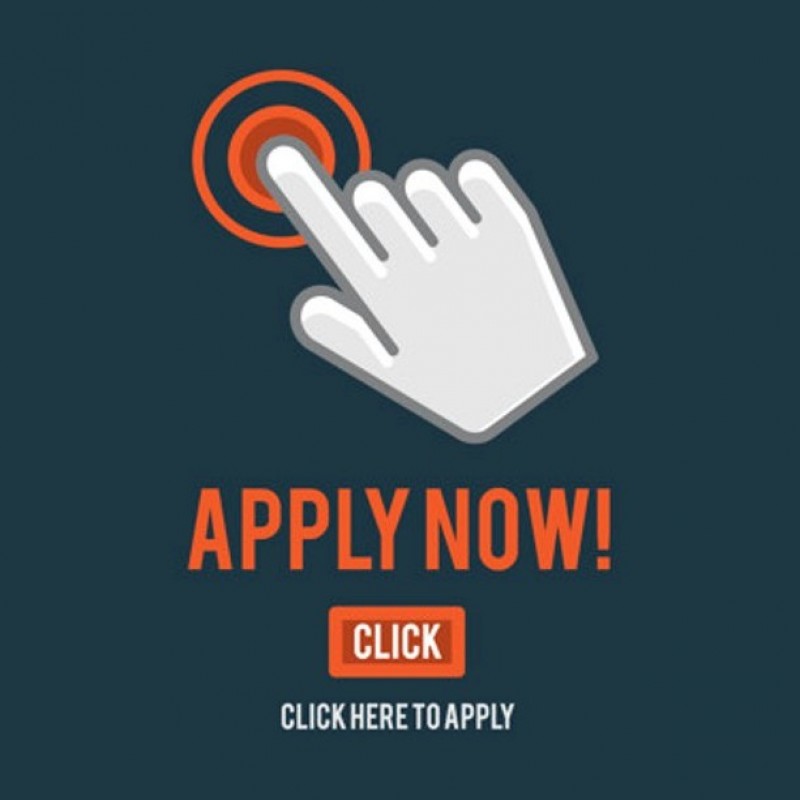Abduh Pabbaja, Penggerak Literasi Keagamaan dari Parepare
Jumat, 8 Mei 2020 | 08:45 WIB

Karya tulis Abduh Pabbaja juga berpengaruh pada aspek ketauhidan, penghargaan, dan perwujudan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. (Foto: Istimewa)
Demikian salah satu simpulan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019. Para peneliti mengungkapkan, karya tulis yang dihasilkan Abduh Pabbaja berupa syair-syair keagamaan berbahasa Bugis. Sementara aksara yang digunakan adalah Lontara.
Aksara Lontara aktif digunakan sebagai tulisan sehari-hari maupun sastra Sulawesi Selatan setidaknya sejak abad 16 M hingga awal abad 20 M sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan oleh huruf Latin. Saat ini, aksara Lontara masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal. Namun, dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.
Aksara Lontara adalah sistem tulisan abugida yang terdiri dari 23 aksara dasar. Seperti aksara Brahmi lainnya, setiap konsonan merepresentasikan satu suku kata dengan vokal inheren /a/ yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Arah penulisan aksara Lontara adalah kiri ke kanan.
Pada penelitian tersebut, aksara Lontara dapat digunakan sebagai media pengembangan literasi yang menopang unsur kebudayaan dan lokalitas Bugis yang juga tidak bisa dilepaskan dari muatan-muatan utama keislaman sebagai penggerak utamanya.
Perwujudan pengembangan literasi berbasis syair-syair keagamaan yang dihasilkan oleh Abduh Pabbaja itu kemudian diimplementasikan dalam pendidikan keagamaan di Pesantren Al-Furqan Parepare yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Karya yang sangat khas Bugis ini juga sedemikian akrab pada berbagai elemen usia yang pengkajian dan analisis pemahaman mendalam terhadapnya memungkinkan pengejawantahan karakteristik keagamaan khas Bugis. Dalam karya itu, juga menggambarkan betapa aksara dan Bahasa Bugis dilestarikan dengan baik.
Perhatian Abduh Pabbaja terhadap dunia pendidikan membuatnya juga layak disebut sebagai "sang pencerah" di kalangan anak muda. Hal ini juga sesuai pemikirannya dalam aspek adab anak muda dalam menuntut ilmu yang ditaungkan hasil karya tulis berjudul mir’atun linnasyi’in (atellongenna anak mula mpekkek’e), yaitu penerangan bagi penuntut ilmu.
Peneliti juga mengungkapkan, ada masyarakat yang mengubur naskah kuno di dalam tanah dengan maksud mengamankan dari ancaman kebakaran dan perampasan. Meskipun dikubur dengan peti kayu atau besi, naskah tersebut tidak terhindar dari kerusakan dan kehilangan jejak.