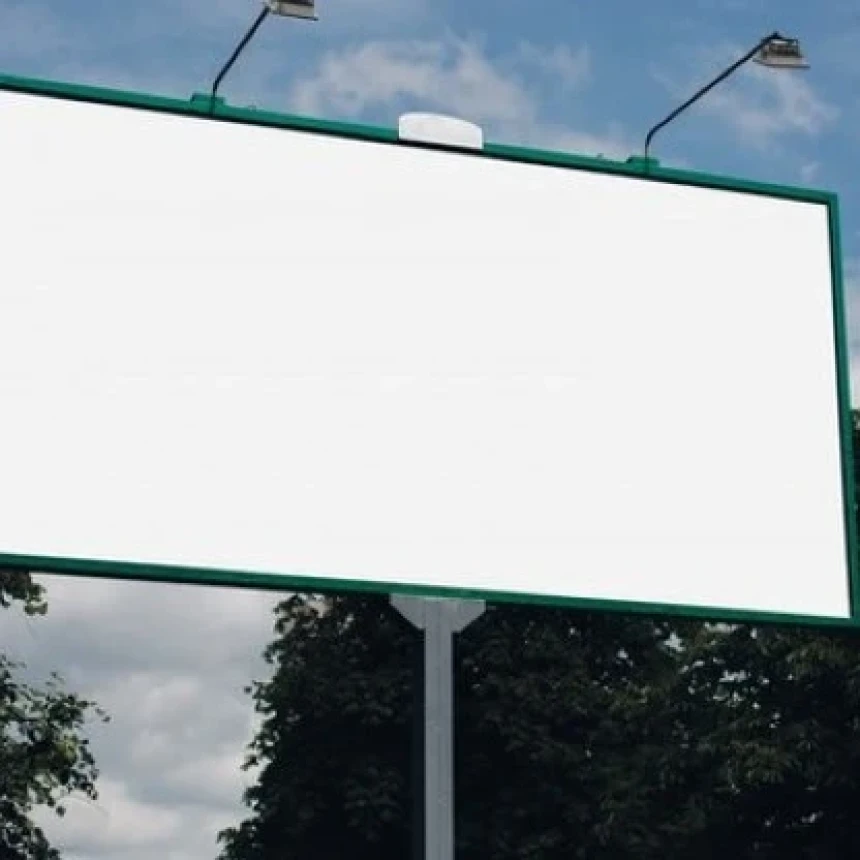Dayat selalu memakai peci hitam yang miring ke kanan. Entah sejak kapan ia memakainya begitu, tapi sejak itu pula banyak orang mulai memanggilnya Ustadz Peci Miring. Ia sendiri tidak keberatan. Bahkan bangga. Menurutnya, gaya itu adalah tanda bahwa dirinya berbeda. Sedikit lebih nyentrik, tapi tetap saleh.
Setiap habis azan, Dayat akan berdiri di depan masjid kecil kampungnya dan mulai berceramah. Tidak ada undangan, tidak ada jadwal resmi. Ia merasa punya hak untuk menasihati siapa pun. Kadang topiknya tentang dosa perempuan yang tidak berjilbab panjang. Kadang tentang laki-laki yang tidak ikut jamaah Maghrib. Kadang tentang pemuda yang nongkrong sambil tertawa keras.
"Sekarang zaman akhir, Saudara-saudara!” serunya suatu sore. "Banyak orang merasa cukup dengan shalat, padahal lidahnya masih kotor. Banyak orang mengaku beriman tapi malas menegur kemungkaran!"
Orang-orang yang baru pulang dari sawah berhenti di tepi jalan. Ada yang mendengarkan, ada pula yang sekadar lewat dengan kepala menunduk. Dayat tidak peduli siapa yang mendengar. Yang penting, kata-katanya keluar.
Namun, suatu sore, sesuatu mengusiknya.
Ia melihat Darto, si maling kambuhan yang baru saja keluar dari penjara, duduk di depan warung Bu Yati. Darto tersenyum kepada anak kecil yang menangis karena es krimnya jatuh. Lalu, tanpa banyak omong, Darto membelikan es krim baru. Anak kecil itu tertawa lagi.
Dayat memicingkan mata.
"Lihat saja,” gumamnya pada teman di sampingnya, "sebentar lagi dia pasti maling lagi. Kebaikannya itu cuma kamuflase.”
Temannya mengangguk setengah hati. Tapi di dalam dada Dayat sendiri, kalimat itu serupa pantulan yang membentur balik. Tapi kenapa aku tidak tergerak membelikan es krim untuk anak itu? pikirnya sebentar, sebelum buru-buru diusirnya pikiran itu dengan istighfar.
Beberapa hari kemudian, Dayat berceramah lagi di langgar.
“Saudara-saudara, jangan tertipu dengan orang yang tampak baik padahal hatinya busuk! Banyak di luar sana yang pura-pura peduli, tapi dalam hatinya penuh maksiat. Munafik! ”
Kata-katanya disambut angganggukan. Dari barisan belakang, Darto masuk, membawa dua kantong plastik berisi air mineral dan roti.
"Buat jamaah, Ustadz,” katanya sopan. “Saya lihat tadi banyak yang haus.”
Dayat tertegun. Ingin rasanya ia menolak. Namun tatapan orang-orang membuatnya diam. Ia hanya mengangguk dan menerima dengan senyum kaku.
Sepulang dari langgar, Dayat tidak langsung pulang. Ia duduk lama di serambi rumahnya. Angin malam menyinggahi wajahnya yang basah oleh keringat. Dalam hatinya, berputar pertanyaan yang tak enak, "Apakah kebaikan hanya milik orang suci?"
Hari berganti.
Kampung itu punya satu masalah klasik, got tersumbat. Bau menyengat menguar ke mana-mana, tapi tak ada yang mau membersihkan. Hingga suatu pagi, Dayat lewat dan melihat Darto jongkok di tepi got, tangan berlumur lumpur, menggali dan mengangkat sampah-sampah plastik.
Anak-anak menonton sambil menutup hidung. Orang-orang dewasa berpura-pura tidak lihat.
Dayat hampir saja berjalan terus, tapi langkahnya berhenti. Ia menatap lelaki itu, yang di masa lalu pernah mencuri ayam iibunya. Darto jongkok tanpa pamrih, membersihkan kotoran yang bukan urusannya.
"Apa yang kau lakukan, To?” tanya Dayat mendekat.
"Ya ini, membersihkan. Kalau nunggu orang sadar, kampung ini keburu jadi rawa,” jawab Darto sambil tertawa kecil. “Saya kan juga bagian dari kampung ini, Ustadz.”
Dayat menelan ludah. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari ayat mana pun.
Sejak hari itu, ada yang berubah di dalam dirinya. Tidak tampak jelas di luar, ia tetap dengan peci miringnya, tetap berceramah, tetap merasa tahu banyak. Tapi setiap kali ia memandang orang yang ia anggap “tidak saleh”, matanya kini lebih lambat menghakimi.
Sampai suatu siang, ketika Dayat sedang di warung, datang kabar bahwa Darto meninggal.
Bukan karena penyakit atau kecelakaan. Ia meninggal karena menolong anak kecil yang jatuh ke sungai. Ia tidak sempat keluar. Tubuhnya terseret arus.
Warung mendadak sunyi. Dayat menatap meja kayu di depannya, lalu menunduk. Ia merasa dadanya diisi sesal.
Malam itu, kampung ramai. Orang-orang menyiapkan pemakaman. Dayat ikut membantu, meski ia tidak tahu harus membantu apa. Ia hanya mengikuti arus. Mengangkat, menggali, menyalami.
Ketika jenazah dibawa, ia memperhatikan wajah Darto yang tenang. Orang-orang yang dulu menolak bersalaman dengannya kini menitikkan air mata.
Dayat berdiri agak jauh, lalu tiba-tiba ia melepaskan pecinya. Untuk pertama kali, kepalanya tanpa tutup.
Ada sesuatu yang terasa ringan di ubun-ubun.
Beberapa hari setelah pemakaman, Dayat tidak lagi sering berceramah di jalan. Orang-orang sempat heran. Mereka mencari-cari Ustaz Peci Miring di sore hari, tapi yang mereka temukan hanyalah Dayat yang sedang membantu anak-anak memperbaiki sepeda, atau menuntun orang tua ke Puskesmas.
Suatu kali, seorang jamaah muda datang kepadanya dan bertanya,
"Ustadz, kok sekarang jarang ceramah?”
Dayat tersenyum kecil.
“Mungkin lidah saya sudah terlalu sering bicara, sementara tangan saya belum sempat bekerja.”
Anak muda itu mengangguk, tapi tak sepenuhnya paham. Dayat tahu itu. Ia pun tak bermaksud menjelaskan lebih jauh. Ada hal-hal yang tak perlu dijelaskan, cukup dijalani.
Suatu sore, Dayat duduk di tepi sawah. Ia melihat langit berwarna jingga, mendengar suara jangkrik, dan mencium bau tanah basah. Entah kenapa, hatinya terasa tenang sekali.
Ia teringat Darto. Lelaki yang dulu ia anggap kotor, yang ternyata justru menyalakan lentera kecil di hatinya.
“Tuhan itu lucu,” gumam Dayat pelan. “Kau pikir Ia hanya berdiam di masjid, ternyata Ia juga bersemayam di tangan kotor seorang maling.”
Ia tertawa pelan, hampir seperti menertawakan dirinya sendiri.
Sejak itu, Dayat tidak lagi memiringkan pecinya. Ia memakainya lurus, sederhana, tanpa gaya. Kadang ia bahkan melepasnya ketika berbicara dengan anak kecil, tukang becak, atau perempuan penjual sayur.
Bagi Dayat, kebaikan Tuhan bisa hadir lewat orang yang dicibir, lewat tangan yang kotor, lewat tawa seorang anak kecil yang kembali dapat es krim.
Dan setiap kali ia melihat seseorang berbuat baik, sekecil apa pun, Dayat tahu, di situlah Tuhan sedang membagikan kebaikan-Nya. Tidak di atas mimbar, tidak di ceramah, tidak di dalam kotak yang ia banggakan dulu.
Ia sadar, kebaikan bukan hak istimewanya.
Kebaikan adalah obralan besar Tuhan.
Suatu malam, angin berembus lewat jendela rumahnya. Di meja ada kitab usang yang dulu selalu ia bawa ketika ceramah. Kini ia membacanya pelan, tanpa perlu mengutip untuk menghakimi.
Ia hanya ingin mengerti, bukan untuk menang.
Dalam sunyi itu, Dayat menutup kitab, lalu berbisik lirih,
“Terima kasih, Tuhan, telah mengajariku lewat orang yang dulu kupandang rendah. Ternyata, Engkau tak menaruh kebaikan dalam satu kotak saja. Engkau menaburkannya di mana-mana, bahkan di tempat yang dulu kuhina."
Lalu Dayat memejamkan mata.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mengenakan peci itu dengan lurus.