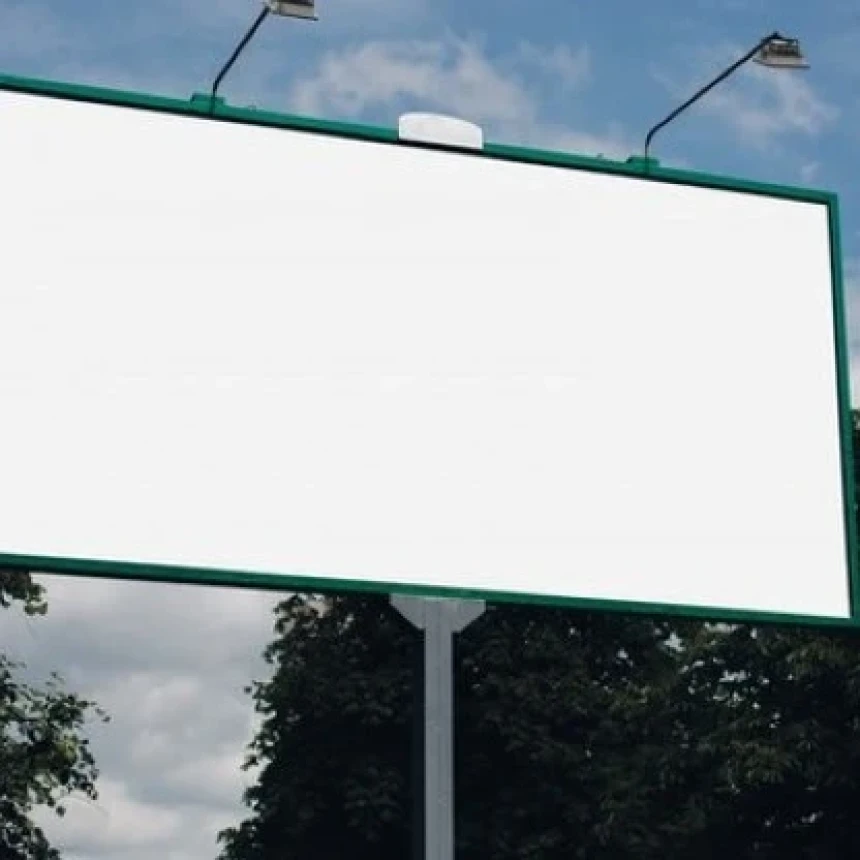Cerpen:Erwin Abdillah
Mengawali pagi, aku melamunkan misi ini. Taruhannya nyawa dan tanpa bala bantuan. Aku tak ingin ditanam di lereng gunung ini dan segera melanjutkan penyamaranku di kota lain. Satu sesapan teh dan menatap puncak gunung itu sekali lagi. Tiba-tiba aku merasa di rumah, tak ingin ke mana-mana lagi. Ah, tapi misi belum selesai. Bau melati menyeruak dari teh yang baru kuseduh, membawa kenangan yang akrab, nyaris seperti pelukan seorang ibu. Makhluk yang tak pernah kutemui wujudnya.
Pukul delapan pagi, matahari sembunyi di tumpukan awan. Tamparan angin memaksa mataku setengah menutup. Bau tanah bercampur potongan rumput meliputi tempat kami duduk berhimpitan dalam mobil bak terbuka. Elsapek, sebutan mobil segala medan ini. Cangkul-cangkul beradu mengeluarkan nada serupa suara gamelan. Seperti tahanan, aku dijaga dua orang di depan dan dua di belakang.
Di kananku Tomorejo sibuk menata tembakau dalam papir. Lelaki paruh baya itu membuat melinting seperti meditasi. Di kiriku Sapar, pemuda perkasa yang arti namanya bagus, perjalanan, petualangan. Mungkin dari Safar, bulan kalender Hijriyah. Ia menggumamkan tembang Jawa dari pentas Lengger mengimbangi ketukan cangkul.
“… Babadana, panggenan sun tilasana. Yo la elo, elo ya elo laa.”
Kebun teh ditelan kabut. Elsapek dihajar jalan batu licin dengan cekungan yang diukir ban truk pengangkut pasir dan batu dari atas. Di kanan kiri kami hamparan daun tembakau segar, menguarkan aroma sengak. Mingsri, kata Tomorejo, zat lengket kehitaman yang tertulis di kemasan rokok: tar dan nikotin. Lahan di sepanjang jalan itu milik keluarganya sejak pecah Perang Jawa yang dipimpin Diponegoro.
“Kalau hujan terus, tembakau hilang harganya, enteng.” katanya.
Aku, bagi mereka, adalah Hendrik. Mahasiswa S2 peneliti tanah. Sebulan sudah mereka berbagi makanan denganku, tidur seatap, mengizinkanku merecoki pekerjaan, dan bertanya ini-itu soal tambang. Kemarin malam mereka melibatkanku dalam pertemuan keluarga.
Mereka mengajakku memperbaiki parit di lahan penting: Wates. Batas antara lahan keluarga Tomorejo dan lahan Manten Lurah Karso, orang nomor satu di Pager Agung. Keluarganya paling ditakuti seantero kabupaten. Limpahan air dari lahan Karso yang ditambang kerap merusak tanaman di bawah. Potret sempurna kehidupan desa. Hak orang kecil dilanggar mereka yang punya kuasa dan senjata. Berurusan dengan Karso artinya siap kalah, mati. Aparat berseragam dan hukum milik mereka. Mungkin inilah cara termudah bertahan di desa, menjadi seorang pasifis.
Manten Karso meloloskan anak dan menantunya menjabat anggota dewan bermodal tambang liar. Kata Sapar, usia Karso hampir 80 tahun tetapi tak mau mati.
“Karso itu bersekutu dengan setan,” kata Sapar.
Aku percaya, setan itu sebenarnya uang miliaran rupiah. Karso tega membunuh anggota keluarganya jika berani berkhianat. Konon seorang menantunya juga mati karena sebab yang tak jelas. Jika berhasil, aku adalah batu kecil yang akan membunuhnya dan keluarganya. Itu pun jika aku selamat, lalu seluruh dunia bisa melihat borok di lereng Sindoro ini. Kantong-kantong tambang liar ratusan hektar ini didiamkan pemerintah dan dibekingi aparat. Daftar nama yang meng-uangkan tambang ini sudah masuk dalam catatanku. Ada nama gubernur sampai bupati. Ada belasan nama orang terkenal, termasuk anak mantan presiden dan seorang pemilik startup teknologi.
“Mas Hendrik bisa membantu di bawah bersama Sapar merapikan saluran. Begitu kabut tebal terlihat, kita turun,” Tomorejo berkata dari kejauhan.
Ia membawa empat orang bersamanya menuju saluran atas, salah satunya menenteng sesaji dan dupa. Saluran air warga rusak. Sapar membawaku ke sana pada minggu pertama menjelajah lereng Barat Daya. Tepat di samping mata air, ada bebatuan candi tempat warga meletakkan sesaji. Itulah satu-satunya tempat yang dekat dengan tambang Karso dan belum dijamah. Mata air itu menghidupi Pager Agung sepanjang ratusan-ribuan tahun lalu. Air itu diyakini menyembuhkan. Di desa ini air gratis, teh dan kopi mengolah sendiri, udara segar dan dingin tanpa AC. Kemewahan seperti ini tak lama lagi akan direbut orang-orang kota yang rakus, lalu menanam villa mewah yang mencaplok rumah-rumah kayu tua.
Sapar memperhatikan caraku memotret sekeliling. Ia mengamati hamparan tambang di bukit seberang kami berdiri. Ada sebuah backhoe di ketinggian 1300 mdpl. Sapar berjaga dari anak buah Karso yang terus mengawasi keluarganya. Aku selalu membawa kantong sampel untuk memungut tanah di sekitar sebagai samaran. Sapar lihai membantu, rupanya ia memperhatikan kerjaku.
Pemuda lulusan SMP itu punya ingatan tajam. Ia mengingat jenis tanaman, baunya, lokasinya, sampai kegunaannya. Dari warna ulat tembakau, ia bisa memprediksi kualitasnya saat dipanen. Pekerjaan kami hampir selesai ketika ia bertanya tentang asal-usulku. Ia pernah curiga dengan tampangku yang katanya tak asing.
“Kampung sebelah isinya keluarga Karso. Dulu ada menantunya yang mukanya mirip sampean. Raut wajahnya ramah tapi tegas, suka menanam pohon di sekitar lereng.” kata sapar sambil menoleh.
Ia mendengar sesuatu dan mengajakku kembali.
“Pegawai Karso menemui kami tadi. Kita diundang pesta khitanan cucunya, kita harus ikut semua, termasuk tamu. Mas Hen?” Tomo menunggu reaksiku, lalu semua melihat ke arahku.
Aku mengangguk pasrah. Perjalanan pulang terasa singkat. Tomorejo menyebut tentang tawaran Karso membeli tanah keluarga besarnya.
“ Dulu sekali, bapak ditawari Karso 200 ribu per meter. Setahun berikutnya 400. Terakhir karso mau membeli dua juta,” raut mukanya mengeras.
Lahan keluarga Tomorejo ada lima hektar lebih jika ditambah kebun kopi Sapar. Sepuluh miliar Rupiah pasti mengusik isi kepala keluarga besarnya. Tomorejo memegang keputusan dalam keluarga karena yang tertua. Bapaknya semacam demang, kini ia menjabat kepala dusun. Semua anak dan keponakannya bersekolah hingga kuliah, haram menjual lahan warisan. Hanya Sapar yang memilih dibelikan sapi ketimbang dibiayai kuliah.
Sore itu semua laporan aku cadangkan ke email dengan catatan penting. Aku kawatir terjadi sesuatu padaku. Ada data berisi foto, video, juga profil dari seluruh pemilik lahan yang sebenarnya, juga cara operasi perusahaan aslinya. Aku sudah membuat bagan hubungan mereka semua beserta nilai transaksi. Semua aku kumpulkan dari remah-remah.
Aku rajin menyambangi warung makan tempat pekerja berkeluh-kesah, juga menguping obrolan orang mabuk di pentas Lengger. Aku harus menyuap beberapa pegawai pemerintah dan aparat keamanan untuk data angka. Tidak heran kalau warga desa khawatir, mereka tak punya perlindungan sama sekali. Semua warga pernah merasakan banjir akibat tambang, tapi tak pernah ada laporan ke pemerintah setempat. Tentu saja kepala desa yang mengatur semuanya. Mereka takut kehilangan pekerjaan dan nyawa.
Karso bukanlah pemilik asli usaha tambang liar yang tersebar di lima desa. Orang besar yang duduk di belakang layar sana mengantongi ratusan Miliar rupiah dari kaki Sindoro tanpa peduli warga kehilangan air dan longsor yang membunuh warga. Pemerintah tidak bisa menindak. Satu-satunya yang mereka pedulikan cuma pajak.
“Nyawa hilang tiap minggu, tapi uang datang tiap hari. Bagaimana bangsa kita bisa membangun tanpa pasir batu Sindoro yang kita tambang ini?” kata Sapar menirukan Karso dalam pidatonya di desa.
Kata-kata itu mujarab bagi warga miskin yang bertaruh nyawa bekerja menambang manual ketika alat berat tak mampu menjangkau. Nyawa mereka dibayar murah, namun tak cukup buat sekadar makan apalagi menyekolahkan anak.
Aku berangkat menunggangi motor Sapar memisahkan diri dari kerabat Tomorejo. Semua gawai aku tinggalkan di ransel darurat, mengikuti instingku. Setelah belokan terakhir di punggung bukit, aku melihat bangunan megah dari kejauhan. Rumah itu lebih cocok disebut istana, luasnya melebihi kantor bupati. Puluhan mobil mewah terparkir di halaman. Aku melihat rombongan Tomorejo tampil paling lusuh dibanding tamu berbalut jas dan sepatu mahal. Wajah mereka curiga melihatku dari atas sampai bawah. Aku merasa tidak asing dengan rumah itu. Mungkin mirip hotel yang pernah aku tempati.
Meja VIP penuh, dijejali bokong pejabat kabupaten dan keluarga Karso dari luar kota. Kami dituntun menuju ruangan sebelahnya, berbaur dengan warga lain, semuanya petani tembakau. Mereka masih sibuk makan dan minum. Rombongan Tomorejo disambut langsung Manten Karso setelah acara doa dan ucapan selamat.
Dari pojok ruangan besar itu aku melihat wajah Karso dengan jelas. Entah sihir apa yang dipakai manusia itu, ia tak nampak seperti orang tua renta. Suaranya serak menggelegar seperti dalang yang tengah mengisi suara tokoh raksasa. Anehnya aku tak merasa terganggu. Ada sesuatu yang akrab dari nada bicara Karso, nyaris aku menganggapnya seperti kakek sendiri. Mungkin itu kesaktian Karso yang membuat siapapun mengalah padanya, termasuk Sapar. Wibawanya seperti raja tua yang menolak mati. Kata-katanya lancang seperti Bima Sena. Tak ada basa-basi. Kekagumanku terpantau mata Sapar yang awas menjaga keluarganya.
Tepukan keras di pundak menyadarkanku dari pidato Karso yang hangat diselingi tawa. Sapar memaksaku melipir untuk merokok. Ada pendopo dihias taman di belakang rumah. Aku menenteng minuman hangat sambil melihat koleksi tanaman di lorong panjang. Anggrek mahal dan tanaman konservasi terawatt sempurna. Pohon Nogosari disulam dengan ranting markisa memagari lorong yang hanya diterangi lampu oranye itu. Di ujung sana ada seorang perempuan tua, melihat ke arahku.
“Mrenea, Nang. Kapan pulang?” Suara perempuan itu sampai di telingaku lirih, senyumnya ramah seakan mengenalku, pasti salah orang.
Sesopan mungkin aku menyapa wanita rupawan itu. Fotonya versi muda ada dalam laporanku, Nurani, Putri tertua Karso. Seorang pembantu berlari kecil seperti kecolongan. pundakku dipegangnya erat dan tatapannya membuatku membeku.
"Dhuh sutané pun ibu, anyawa wong bagus." kata-katanya asing, ia lancang membelai pipiku. Matanya berkaca-kaca.
Nada itu menenangkanku. Membangkitkan sesuatu dalam dadaku, seperti suara ibuku sendiri. Yang dalam ingatanku tak pernah ada. Aku masih berusaha menerjemahkan gurat muka dan air matanya yang meleleh. Kata-kataku lenyap.
“Maaf mas, ibu sedang kurang sehat, sering salah memanggil nama orang.” Perempuan yang tadi berlari sudah ada di samping kami.
"Anak ibu sudah meninggal, kalau hidup mungkin sekarang seusia mas ini. Maaf, silahkan dilanjutkan jalan-jalannya.” kata pembantunya sopan, ia menyesal membiarkannya tanpa penjagaan.
Aku sungguh tak berkeberatan. Ia menuntun Nurani berjalan membelakangiku. Tapi kepalanya masih berusaha menengok ke arahku. Aroma melati dari tangannya tertinggal di bajuku, membawaku pada masa yang lain. Panggilan Sapar membuatku beranjak. Raut mukanya seperti melihat hantu, meminta ditemani. Telunjuknya mengarah pada pigura kecil diantara beberapa pigura besar di ruang galeri.
“Mas! Lihat mas Hen, ini foto orang itu! Aku ingat. Dia meninggal saat bencana longsor. Orang ini dulu sering mengajak anak-anak desa menanam kopi.” Sapar tak sabar menunjukkan temuannya.
“Dia sering membawa buku baru ke balai desa. Anaknya sering dibawa bermain bersama kami. Anaknya memang mirip kamu!” Katanya yakin.
Foto lelaki itu bisa kulihat jelas bersanding dengan Nurani waktu mereka muda. Di tengah mereka bayi usia setahun. Foto itu hanya setengah meter dari tempatku berdiri. Tapi rasanya mataku mendadak buram. Aku sulit merasakan tanganku saat mengeluarkan dompet. Jemariku bergetar menyusuri tiap lipatan. Mencabut satu foto kecil yang dirobek di empat ujungnya. Aku mendekatkannya pada pigura. Sontak kedua kakiku kehilangan daya. Telingaku tiba-tiba suwung. Aku makin susah melihat, ada banjir di mataku, kubendung dengan tanganku.
“Mas, itu foto bayinya sama!” Sapar mengguncang pundakku. Bau melati itu memenuhi udara, membawaku pada masa yang hilang. Aku kembali menjadi bayi itu, tak bisa berdiri tegap dan terus menangis. Bedanya, bayi itu tak tahu siapa dirinya. Sedangkan aku mengingat tawa karso. Mengingat rumah ini. Aku mengingat hulu dari perjalanan ini. Semuanya.
“Oh, Sapar!”
Lereng Sindoro Selatan, 17 Agustus 2025
Erwin Abdillah. Lahir di Wonosobo dan mengakrabi lereng Sindoro-Sumbing sejak belia. Berprofesi sebagai jurnalis di Pikiran Rakyat Media Network dan Penulis Buku “Empat Abad Wonosobo: Narasi Sejarah dari Dokumen Hindia Belanda, Serat dan Babad” terbit 2025.