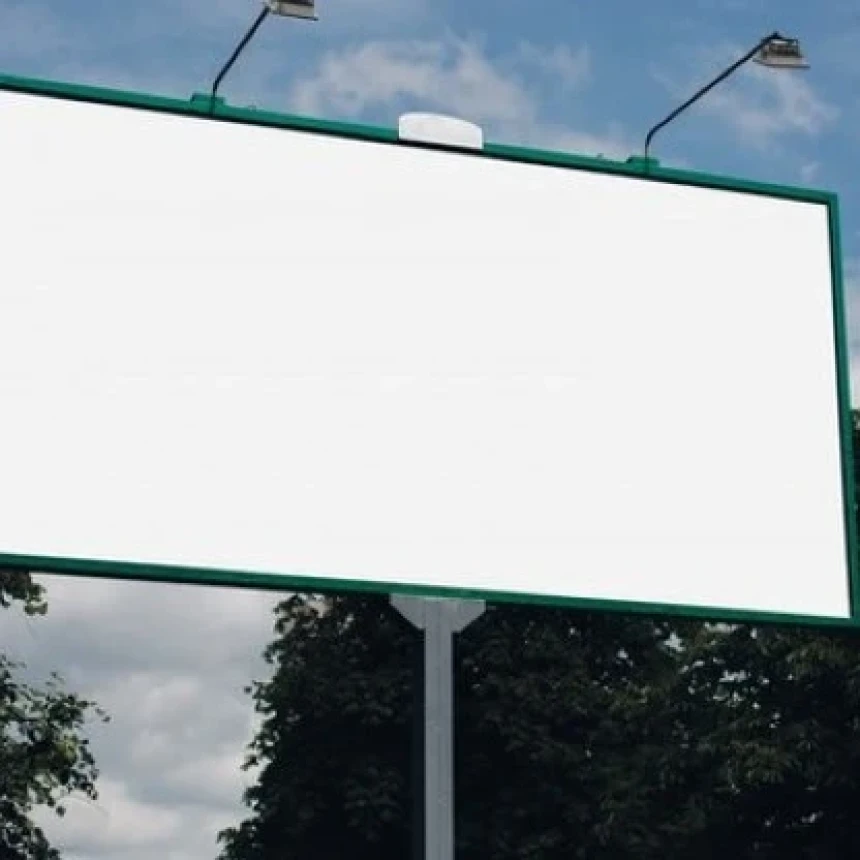Akhir-akhir ini desaku di kaki Gunung Slamet semakin sepi. Orang-orang akan mengunci pintu rapat selepas turun dari langgar setelah Shalat Isya. Malam-malam sebelumnya juga memang sepi. Tetapi akhir-akhir ini sepi itu lain dari sepi biasanya, sepi itu ditemani oleh rasa takut. Penyebabnya adalah tentang desas-desus ninja dengan pakaian hitam yang berkeliaran di tengah malam, lalu mengetuk pintu, membunuh, dan pergi tanpa jejak.
Belum ada kejadian memang di desaku, namun desas-desus itu semakin kencang menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain. Dari koran yang aku baca, teror ninja di daerah lain menyerang para kiai.
"Apa mereka yang di atas belum puas menciptakan ketakutan? Adanya penembak misterius saja membuat denyut nadi rakyat naik turun. Tanpa ada pengadilan, tahu-tahu mati diterjang peluru, dibungkus karung, dibuang entah ke mana. Eh, sekarang muncul ninja,” ucap Kholis di teras mushala selepas Isya.
Raut wajah Kholis merah, menahan geram. Gara-gara penembak misterius alias petrus, ia harus kehilangan anak satu-satunya. Hingga kini, tak ada yang tahu di mana keberadaan Dani. Terakhir kali sebelum Dani raib, Kholis mendengar kabar kalau Dani menjadi penguasa salah satu pasar di Jakarta.
“Jaga bicaramu, jangan keras-keras,” timpal Qodir, “Dinding, sekarang punya mata dan telinga. Jangan sampai kamu dibawa, lalu diinterogasi, dituduh merah.”
Mendadak suasana menjadi hening, mereka yang ada di teras langgar, kini larut dalam pikiran masing-masing.
*
Desa-desa di kaki Gunung Slamet dikenal sebagai gudang kiai. Maka desa-desa tersebut membentuk tim ronda yang terdiri dari para pemuda tanggung untuk menjaga para kiai. Desaku tidak mau ketinggalan dengan desa-desa tetangga. Para pemuda desaku yang bertugas ronda, sebelumnya telah didoakan oleh Kiai Tori. Selain itu juga mereka dibekali dengan bambu petung yang telah dirajah.
"Ini bambu petung telah dirajah sama Kiai Tori, sekali pentung, ninja akan tumbang,” ujar Hanan menunjukan sebilah bambu petung dengan panjang 2 meter. Pada bambu tersebut terdapat tulisan-tulisan Arab berwarna hitam.
"Kamu nggak ikut ronda?"
Aku menggelengkan kepala mendapatkan pertanyaan tersebut. Belum sempat aku mengatakan alasan kenapa tidak ikut ronda, Hanan sudah menyelanya sambil berlalu pergi, “Penakut kamu.”
Sebenarnya aku juga ingin ikut bersama dengan Hanan dan kawan-kawan yang lain, namun bapak melarangnya. Ia memintaku untuk menjaga kakekku Mbah Wasroh.
"Di tengah situasi seperti sekarang ini, mbahmu juga perlu dijaga,” ujar bapak.
"Mbah kan bukan kiai. Jadi mana mungkin ninja itu akan datang ke rumah?"
"Justru itu, para pemuda akan fokus ke rumah-rumah kiai, siapa tahu ninja malah datang ke rumah mbah. Kamu perlu tahu ya, mbahmu itu pernah mondok di Cirebon, Kediri. Cuman ya itu di pondok lebih senang ilmu kanuragan. Setelah selesai nyantri, alih-alih mengajar ngaji, malah membuka pengobatan alternatif. Ia sering diminta tolong menyembuhkan orang kesurupan, memindahkan jin. Maka berbeda halnya dengan saudara-saudaranya yang dipanggil kiai, orang-orang memanggilnya dengan sebutan mbah."
Malam itu suara kentongan saling bersahutan disertai dengan teriakan-teriakan. Pagi harinya orang-orang membicarakan perihal suara keributan tersebut. Diketahui bahwa semalam ninja datang ke desa sebelah, Desa Tenjo.
Katanya para peronda memergoki lima orang dengan pakaian layaknya ninja Jepang berwarna hitam di depan rumah Kiai Badar. Mereka sama kagetnya, tetapi para peronda lebih takut. Alhasil mereka pada lari ke segala arah sambil memukul kentongan. Lalu mendengar suara tersebut, para peronda di desa-desa tetangga ikut memukul kentongan.
Selepas sarapan, bapak memintaku untuk menemani mbah ke Desa Tenjo.
"Mau menengok Kiai Badar?"
"Bukan, Kiai Badar justru tidak apa-apa. Justru malah Man Kharis yang terluka parah."
Man Kharis merupakan anak dari Mbah Fatimah. Nah, Mbah Fatimah sendiri merupakan salah satu adik perempuan Mbah Wasroh.
“Man Kharis bukannya masih di Pesantren Kediri?”
"Sudah boyong dia, baru seminggu yang lalu pulang.”
Di rumah Mbah Fatimah sudah ramai orang-orang, tua-muda, laki-laki perempuan. Man Kharis dibaringkan pada tikar pandan di ruang tamu. Wajahnya bonyok tidak karuan, darah kering menempel di bajunya yang sudah koyak. Matanya menutup seperti orang tidur, tetapi nafasnya masih ada. Ia tidak kunjung juga siuman. Aku menduga banyak tulangnya yang patah.
“Si Kharis ini tidak apa-apa kan kang?" tanya Mbah Fatimah.
"Tidak apa-apa, untung saja Kharis ini daya tahan tubuhnya kuat. Kalau orang biasa mah sudah pindah alam."
Entah apa yang dilakukan Mbah Wasroh, Kharis siuman juga. Ia hanya mengusapkan air yang telah didoakan. Begitu bangun, ia langsung memaki teman-temannya yang meninggalkannya sendirian.
"Mereka menggunakan pakaian serba hitam, tertutup semuanya. Aku bertarung dengan kelimanya sekaligus, mulanya aku percaya diri bisa mengalahkan mereka, sebab aku ikut pencak silat di pondok. Tetapi ternyata kelima orang ini ahli bela diri juga, gerakannya jelas sekali gerakan orang terlatih."
Kejadian yang menimpa Man Kharis membuat desa-desa tetangga, termasuk desaku semakin bersiaga. Penjagaan terhadap rumah-rumah kiai diperketat, yang ikut ronda pun semakin banyak. Pamanku Man Judin yang sebelumnya bodo amat dengan adanya ninja pun berencana nanti malam akan ikut ronda. Usut punya usut, ia mendengar kabar bahwa ninja juga menyasar para bujang lapuk. Tentu saja aku tergelitik dengan perkataan Man Judin.
"Dari yang aku dengar, jasad bujang lapuk akan dijadikan sebagai tumbal pembangunan. Maka dari itu aku harus ikut ronda supaya berada dalam keramaian."
Karena Man Judin ikut ronda, maka malam harinya di rumah kakek hanya ada tiga orang, yakni aku, kakek, dan nenek. Seperti biasa aku tidur hanya dengan beralas karpet di ruang tamu, dekat dengan kamar kakek.
Ketika sedang enak-enaknya tidur, pintu diketuk keras dengan nada teratur. Tentu saja aku kesal bukan main dengan ketukan yang aku kira adalah Man Judin.
"Iya, iya, ganggu orang tidur saja. Dasar bujang kerek (bujang lapuk)."
Begitu aku buka pintu, ternyata bukan Man Judin. Di depanku berdiri laki-laki tinggi semampai dengan rambut pendek hampir pelontos, memakai jaket kulit hitam, celana panjang hitam, dan sepatu bot hitam. Seketika keringat dingin langsung hinggap dalam badanku. Dalam hati aku bertanya apakah ini yang disebut dengan ninja.
"Mbah Wasroh ada?"
Belum sempat aku menjawabnya, Mbah Wasroh keluar dari kamarnya dengan mengenakan peci hitam, kaos oblong putih, dan sarung hitam. Lalu ia berjalan mendekat ke arah kami.
"Mbah jangan melawan kalau tidak mau terjadi apa-apa. Mbah sudah ditunggu di jalan perbatasan desa. Mari ikut."
Mbah Wasroh pun memintaku untuk tenang. Ia pun berjalan mengikuti pria tersebut. Segera aku bangunkan nenek dan menceritakan apa yang barusan terjadi. Tidak ada raut wajah panik sedikitpun dalam wajahnya.
"Kamu nggak usah khawatir, mbah kamu itu sakti. Dulu pas tahun 1955 di zaman gerombolan, mbah kamu ditembak nggak mempan. Sudah sana panggil bapakmu."
Aku pun pulang ke rumah, bapak tentu saja kaget dan khawatir mendengar ceritaku. Aku dimintanya untuk memanggil Man Judin. Sementara itu ia ke rumah kakek. Man Judin yang aku temui di pos ronda awalnya tidak mau pulang, tetapi begitu aku katakan kalau ini adalah permintaan bapak, ia mau pulang. Memang ia paling takut dengan bapak. Sesampainya di rumah, Man Judin langsung disemprot habis-habisan oleh bapak.
"Seharusnya kamu di rumah jaga bapak, malah ikutan ronda," semprot bapak. Man Judin pun hanya diam mematung mendengar ocehan bapak.
Malam itu rasanya terasa panjang, saudara-saudara bapak dipanggil ke rumah. Semuanya berkumpul di ruang tengah. Nampak jelas raut kekhawatiran di wajah mereka, hanya nenek yang wajahnya biasa saja. Ia meminta anak-anaknya untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun mereka tetap bersikukuh untuk tetap menunggu.
Tepat ketika bedug bertalu, tenda satu jam lagi adzan Subuh, pintu ada yang membuka. Ternyata itu adalah Mbah Wasroh. Kini semuanya menjadi lega. Lalu bapak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menjawab bahwa di perbatasan desa sudah menunggu dua orang dan sebuah truk.
"Kedua orang tersebut penampilannya sama persis dengan yang menjemputku, truknya berwarna hijau. Lalu salah satu dari mereka, yang nampaknya adalah pemimpinnya memintaku untuk naik ke truk."
Lalu Mbah Wasroh menceritakan bahwa dirinya teringat akan perkataan dari gurunya bahwa ketika dalam keadaan bahaya supaya membaca Surat Insyirah tujuh kali tanpa bernafas. Ajaib, truk mati, tidak bisa dinyalakan. Lalu Mbah Wasroh diminta untuk turun, truk bisa nyala lagi. Begitu Mbah Asroh naik, truk mati lagi.
"Barangkali karena takut dipergoki warga, sebab sebentar lagi Subuh, lantas mereka memintaku pulang."
"Ngobrol apa saja sama mereka?” tanyaku.
“Ngobrol banyak sama pria yang nampaknya adalah pemimpinnya.”
*
"Kamu ini Islam atau Merah?”
“Jangan kira, kami tidak punya informasi tentang kamu. Kamu pernah melindungi mereka kan yang disebut dengan gerombolan. Bapakku terbunuh di sini oleh peluru gerombolan,” katanya di samping truk.
Tangannya bergerak menuju saku di celana, diambil korek dan rokok. Lalu ia nyalakan. Kemudian ia menawarkan kepada pria tua di hadapannya. Namun Mbah Wasroh tolak.
“Diriku bergerak atas dasar kemanusiaan. Para gerombolan di kaki Gunung Slamet ini kan dulunya pejuang yang merasa dianaktirikan oleh negara yang diperjuangkannya. Mereka berjuang di palagan Surabaya, Ambarawa,” kata Mbah Wasroh, “Lalu apa salahnya aku menolong mereka?”
“Lalu apa pembelaanmu terkait kenapa melindungi orang-orang merah di tahun 1965?”
“Mereka tak tahu apa-apa, tak tahu apa itu merah, tak tahu apa itu Lanin. Tak adil rasanya, jika mereka harus kehilangan nyawa. Begini, intinya diriku bergerak atas dasar kemanusiaan.”
“Lalu kenapa kamu melindungi apa yang disebut dengan aktivis?” tanyanya lagi, “Apa kamu tidak tahu bahwa mereka berbahaya untuk negeri ini.”
“Berbahaya untuk negeri ini atau berbahaya untuk seseorang yang tidak mau kehilangan jabatannya?” timpal Mbah Wasroh, “Aku tak takut dengan kematian, toh umurku sudah tua. Boleh percaya, boleh tidak. Rezim ini sebentar lagi tumbang, sudah terlalu banyak kerusakan yang ditimbulkan. Meskipun kelak tumbang, tetapi penyakit yang diakibatkannya tak akan pernah benar-benar hilang."
Malik Ibnu Zaman lahir di Tegal Jawa Tengah. Menulis cerpen, puisi, esai, dan resensi yang tersebar di beberapa media online. Buku pertamanya yang sudah terbit sebuah kumpulan cerpen berjudul Pengemis yang Kelima (2024).