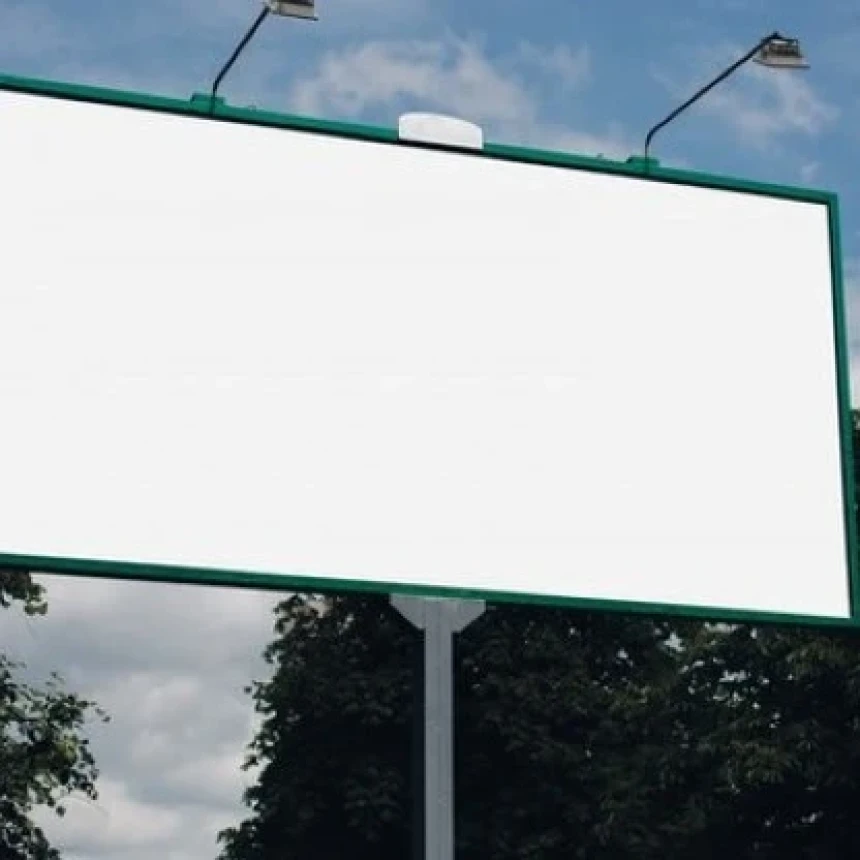Wakidi lupa kalau dia memakai sandal jepit baru pada tahlilan rutin malam Jumat di lingkungannya. Dia terlalu asyik membantu tuan rumah untuk membereskan piring dan gelas. Menyadari bahwa dia dan Dhomir adalah jamaah terakhir yang tersisa, tiba-tiba dia tertawa. "Kang Dhomir, sandalku pasti hilang lagi. Hihihi…"
Secepat kilat, dia meletakkan piring di lantai berbalut tikar plastik itu. Dia lari ke luar rumah. Di halaman yang diterangi lampu namun masih samar-samar, terlihat beberapa sandal. “Satu, dua, tiga dan empat pasang. Mana punyaku?” katanya dengan penuh kesal dan penasaran.
“Sandalmu hilang, Di?” seru salah satu jamaah, dia meranggkap sebagai tukang pengeras suara dan pembawa tikar. “Punyaku yang biru, ya,” lanjutya.
“Iya,” jawab Wakidi pasrah.
Dhomir yang penasaran, juga ikut keluar. “Ikhlaskan saja, Di,” katanya menasehati.
Urusan sandal memang tidak seberapa. Dilihat dari harga, ia cuma Rp10 ribu bukan barang mewah, cukup mudah membeli sandal jepit baru. Namun, kehilangan, walaupun sepele, tetap terasa menyakitkan. Lebih-lebih, hilangnya di tempat sakral. Pengajian, di mana para jamaah berdoa untuk para arwah. Sehingga, siapa pun yang datang adalah orang berhati tulus dan ikhlas. Semata-mata mengharapkan pahala atas untaian doa, bacaan Tahlil, Alfatihah, Tahmid dan surat-surat pendek lainnya.
Alasan datang untuk mencuri sandal baru pun juga tidak masuk akal. Apa untungnya? Lalu, apakah dia harus menanyakan satu per satu jamaah yang datang pada satu minggu berikutnya? Jika berhasil menemukan pelaku tersebut, haruskah melaporkan ke polisi lalu menuntut hukuman atas sakit hati yang dirasakannya?
Dengan hati getir dan perasaan hancur, dia masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan kembali membereskan piring dan gelas sisa para jamaah yang telah memakainya.
Sepengetahuan Wakidi, dia sering menjadi korban sandal hilang. Seingat dia dalam satu tahun ini, dia sudah dua kali. Tepat ketika dia membeli sandal jepit baru, korban lainnya adalah Haji Arifin. Genap tiga orang yang kehilangan sandal jepit baru dalam satu periode berjalan jamaah tahlil ini. Sementara Dhomir, selama ini walaupun selalu menemani Wakidi menjadi jamaah terakhir yang turut membereskan sisa makanan dan minuman jamaah, kehilangan sandal hanya satu kali. Dia bersiasat untuk selalu memakai sandal jepit jelek hasil tukar tersebut saat malam tahlilan.
"Kalau sandal jelek kenapa tidak hilang ya, Di?” ungkapnya sambil tertawa berdera-derai.
Ihwal mengapa Wakidi dan Dhomir selalu menjadi jamaah terakhir yang pulang adalah kebiasaan para jamaah menyuruh siapa yang muda untuk membantu tuan rumah menyajikan konsumsi. Di antara para jamaah, Wakidi dan Dhomir adalah pemuda, bujang, pada waktu awal mereka ikut tahlilan. Alasan ini tidak bisa ditolak. Itulah para sinoman seperti di acara pernikahan. Akhirnya, keduanya selalu mendapat giliran buncit, yakni, setelah selesai menyajikan makanan dan minuman kepada para jamaah.
Mereka berdua bersepakat bahwa menjadi sukarelawan adalah ladang pahala. Ia akan menjadi tinggalan yang bermanfaat untuk mereka kelak, nama mereka akan baik, dikenang oleh para jamaah.
Melihat Wakidi yang telah kehilangan untuk yang ketiga kalinya, Dhomir memberi usul. “Lain kali kita berangkat terakhir, Di.”
“Tidak bisa, Kang, justru kita malah di dalam ruang, mendekati dapur,” jawab Wakidi.
“Oh… ya. Para jamaah yang datang lebih awal selalu berjejal di teras. Kalau tidak mencukupi, nah, mereka akan masuk ke ruang tamu. Begitu ruang tamu penuh, mereka ke ruang tengah,” kata Dhomir, kelihatan mengingat-ingat perilaku jamaah.
“Lebih enak datang lebih awal duduk di luar, makan dan minum lebih awal, dan bisa pulang lebih awal pula,” jawab Wakidi mengamini pernyataan Dhomir. “Itulah mengapa, kita sebaiknya berangkat lebih awal.”
“Sama saja. Toh, siapa lagi yang peduli, selain kita. Mereka mungkin lelah atau bagi yang tua, punggungnya sakit akibat duduk lama. Hihihi,” ungkap Dhomir.
Untuk menyiapkan makanan dan minuman jamaah, beranjak dari duduk mutlak dilakukan. Posisi bersila memang nyaman. Berdiri pun terasa berat karenanya. Kaki kanan dan kiri sama-sama melipat masuk menyilang. Itu juga alasan malas berdiri
"Betul, Kang Dhomir. Kapan hari ketika giliran Haji Kabul menjadi tuan rumah, justru kitalah yang dipanggil ke dapur. Mengapa tidak salah satu jamaah dekat pintu dapur saja?”
“Aneh memang. Ngomong-ngomong, kamu nggak ikhlas, Di?”
“Ya, ikhlas!” jawab Wakidi tersentak. “Kehilangan sandal yang nggak ikhlas. Kalau untuk mengambil piring makanan di dapur, demi Allah, ikhlas, Kang.”
“Itu pahala yang tidak ternilai. Membagi makanan itu memudahkan orang lain. Amalan terbaik adalah memasukkan rasa bahagia kepada orang lain.”
“Karena pahala besar itu tumbalnya sandal jepitku yang hilang. Hihihi.”
“Di zaman ini, sulit mencari orang yang mempunyai empati. Orang-orang maunya enak. Apa-apa mudah. Butuh ini terpenuhi, kurang itu tercukupi. Lebih-lebih, banyak orang yang mempunyai HP. Mereka sebentar-bentar membuka. Padahal, tidak ada sesuatu yang bersifat mendesak.”
“Setuju, Kang. Orang jatuh bukannya ditolong, malah divideokan.”
“Kalau jiwa kita terasah, sisi kemanusiaan kita juga akan muncul, menjadikan kita semakin bijaksana. Perjuangan terberat kita adalah melawan diri sendiri. Mengecilkan ego, memperbesar lapang dada. Itulah jihad yang sebenarnya.”
“Betul, Kang.”
“Cuma Rp10 ribu kok, harga sandalmu. Hihihi.”
"Aku ingin meniru caramu. Sandal hasil tukar akan aku pakai tahlilan. Sandal baru akan kupakai untuk berpergian atau bergaya.”
"Kenapa harus di tempat sakral di mana orang berkumpul berdoa, ya, Kang?”
“Nah, itu lupakan berpikir aneh-aneh. Jangankan hanya tahlilan, di masjid saja, orang juga kehilangan sandal. Kotak amal juga raib digondol maling. Di dunia ini tidak ada yang aneh. Lain kalau di surga.”
“Aku mikirnya Tuhan tidak adil, kurang baik apa kita ini. Berbuat baik masih diuji dengan kehilangan.”
“Sebenarnya, Tuhan bisa membuat semua umat manusia, baik satu macam saja atau jahat semua. Tapi, di situlah keagungan Tuhan. Tuhan mencari siapa di antara kita, umat yang memiliki rasa cinta terhadap sesama makhluk-Nya.”
“Ataukah, aku ini kurang amal, ya, Kang?”
“Tidak ada yang tahu. Tuhanlah yang tahu siapa umat terbaik. Bisa jadi ini menjadi pengingat bahwa kita harus lebih bersyukur, masih banyak hamba Tuhan bertidakkecukupan nasibnya. Kita perlu membantu mereka. Kalau mempunyai uang lebih, berikan uang tersebut kepada fakir-miskin, janda-janda miskin atau anak yatim yang membutuhkan biaya untuk pendidikannya.”
“Ini latihan buatku, Kang. Rasa kehilangan agar menjadi lebih ikhlas untuk berbagi kepada mereka.”
“Iya, sepakat, kawan.”
***
Lain cerita ketika Haji Arifin kehilangan sandal jepit barunya. Sebagai orang berusia lanjut, dia bisa dimaklumi apabila beliau lambat menghabiskan makanannya. Kebetulan dia duduk di dekat dapur. Walaupun dekat dengan pintu dapur, beliau tidak ikut membagikan makanan dengan cara memberikan ke sebelahnya. Oleh karena itu, ada salah satu jamaah menggantikan peran tersebut.
Pun demikian, dia juga tidak mendapatkan piring makanan lebih awal. Seperti kesepakatan tidak tertulis, piring itu digeser satu per satu untuk diberikan ke jamaah paling luar. Hingga menyelesaikan makan nyaris bersamaan dengan Wakidi dan Dhomir.
Ketika pulang beliau pun dengan santai menuju halaman di mana sandal para jamaah tergeletak.
“Lho, sandal saya di mana, ya?” serunya.
“Hilang Pak Haji,” jawab Wakidi menerka. Kebetulan Wakidi ada di teras. Dia sedang membereskan piring dan gelas para jamaah. Dilihatnya satu per satu siapakah pemilik sandal sisa jamaah itu.
“Kang Dhomir, kemari,” seru Wakidi. “Sandal Pak Haji hilang!”
Terlihat, ada empat pasang sandal. Tentu milik Wakidi, Dhomir, tukang pengeras suara dan sisanya, milik orang yang menukar sandal Haji Arifin. Sisa tersebut pasti akan menjadi milik Haji Arifin. Mereka serempak berkumpul, secara spontan berembuk mengenai pemilik salah satu di antara empat pasang tersebut.
“Sandal merah punya saya,” ungkap Wakidi dengan bahasa yang halus.
“Hijau punya saya,” kata Dhomir.
“Biru punya saya,” kata tukang pengeras suara. “Sisanya milik Pak Haji. Tidak ada lagi.”
Walaupun mereka bertiga menyampaikan dengan bahasa yang halus untuk menghormati, nampak beliau sedikit kecewa. Melihat sandal lusuh, buruk, tipis dan berlainan warna itu Pak Haji dengan santai berkata. “Nah, itu rezeki saya,” katanya sambil berkelakar.
Keempat orang tersebut tertawa, kemudian Pak Haji berpamitan pulang. Tidak ada protes atau ceramah kepada mereka, apalagi kata-kata kotor muncul dari mulut orang tua tersebut. Beliau pasrah, begitulah dunia.
"Silakan, Pak Haji,” ungkap ketiga orang tersebut menjawab pamitan Pak Haji.
“Assalamualaikum,” ungkapnya, sambil memakai sandal terakhir.
“Waalaikum salam,” jawab mereka bertiga serempak.
Mereka bertiga saling diam. Tukang pengeras suara tiba-tiba memandang Wakidi dan Dhomir, lalu berkata. “Kalau memakai sandal orang lain terasa, lho, di kaki. Pasti ada unsur kesengajaan!”
“Bisa jadi,” jawab Wakidi.
“Lupakan itu,” ungkap Dhomir.
Wakidi tiba-tiba merasa bersyukur. Dia tidak akan pernah dituduh sebagai pencuri sandal jepit baru. Itu karena dia selalu pulang terakhir. Paling tidak di mata Haji Arifin, lebih-lebih di mata para jamaah tahlil apabila nanti terjadi kehilangan serupa.
Jember, 26 September 2025