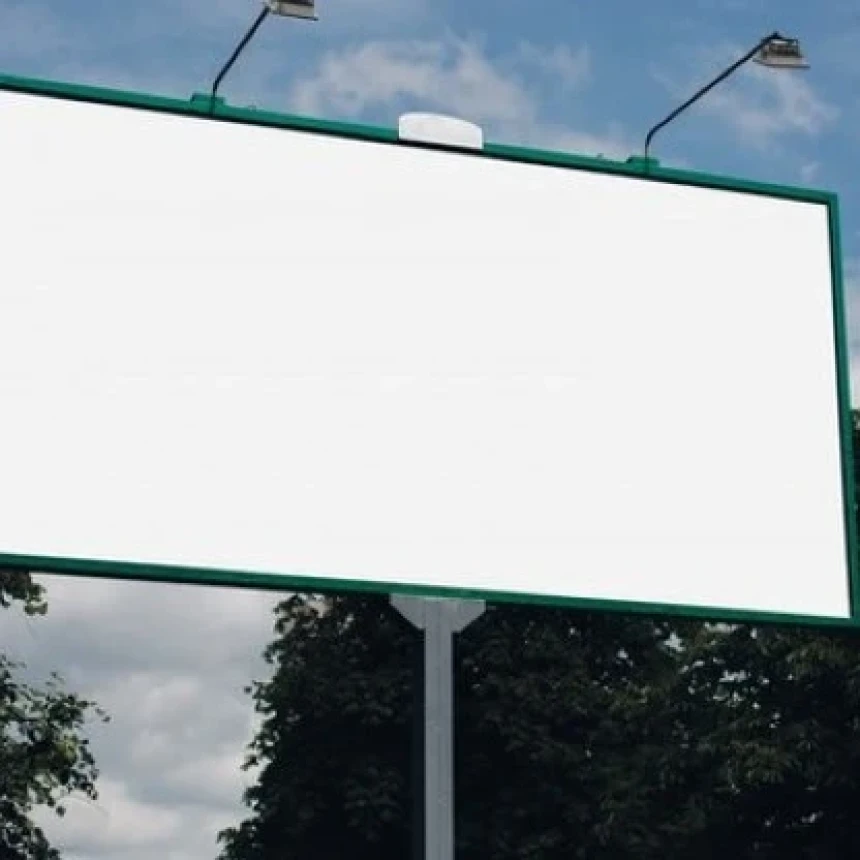Ia tak menyangka bahwa jabatannya sebagai kepala desa justru bukan berakhir oleh tutupnya usia, melainkan oleh todongan pistol. Hatinya merasa susah, bukan karena tak lagi bisa mengelola tanah bengkok, tapi karena ketidakberdayaannya menyelamatkan mereka dari golok jenderal yang ingin naik takhta.
Natsir menjabat kepala desa satu tahun sebelum orang cebol bermata sipit menginjakkan kaki di Tanah Jawa. Jabatan ini diwariskan dari mendiang ayahnya.
Ia adalah sedikit dari kepala desa di kaki Gunung Slamet yang tak digulingkan oleh warganya satu bulan setelah Dwitunggal memproklamasikan kemerdekaan. Natsir mendengar bahwa banyak kepala desa dan keluarganya di-dombreng, yakni diarak keliling desa. Pakaiannya dilucuti dan diganti dengan karung goni. Lalu setelah diarak, dipaksa minum air mentah dalam tempurung, dan makan dedak. Tak sedikit pula dari kepala desa itu kemudian berakhir tragis.
Tak ada asap jika tak ada api. Begitu pula dengan kemarahan warga, tentu ada pemantiknya. Pada masa pendudukan Jepang, banyak kepala desa yang cari selamat sendiri tanpa memedulikan warganya. Mereka bisa makan enak, sementara warganya terancam busung lapar. Belum lagi mereka getol mendata warganya untuk ikut romusha.
Natsir berbeda dengan kepala desa lainnya. Kedermawanannya sudah dikenal jauh sebelum menggantikan ayahnya yang mangkat. Ia makan sama seperti yang dimakan warganya. Selain itu, berkat kemampuan lobinya, tak seorang pun warganya yang dikirim ke Sumatra untuk membangun rel kereta api di sana.
Perihal tak ada warganya yang menjadi romusha, beredar desas-desus bahwa hal itu disebabkan kesaktian yang dimilikinya. Ada yang mengaitkannya dengan kebiasaannya puasa ngrowot, waktu sahur dan berbuka hanya makan umbi-umbian. Ada pula yang menghubungkannya dengan leluhurnya, yang merupakan salah satu panglima dalam Perang Jawa.
Desas-desus ini semakin gencar tatkala meletus Agresi Militer Belanda I dan II. Desanya tak tersentuh sama sekali oleh pembersihan yang dilakukan oleh Tentara Belanda. Maka dari itu, banyak pejuang kemudian bersembunyi di desanya.
Baginya, jabatan kepala desa bukanlah alat untuk dihormati, bukan pula untuk memperkaya diri. Kemuliaan seseorang akan datang dengan sendirinya, tanpa diminta, asal berbuat sesuai hati nurani. Maka dari itu pergolakan politik, ideologi, kepentingan di elite atas, tak dipedulikannya. Baginya, yang terpenting adalah menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Hal itu pula yang membuatnya dengan sadar menolong para gerombolan dari kejaran tentara.
Setiap tengah malam, para gerombolan turun gunung menuju rumahnya, hanya untuk sekadar melepas lapar. Pada awal tahun 1950-an, jumlah mereka yang datang masih banyak, tetapi memasuki tahun 1960-an, jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Banyak di antaranya terbunuh oleh peluru tentara atau menyerah. Meski begitu, kedatangan mereka tetap membuat anak dan istri Natsir diam-diam cemas.
"Pak, apa sebaiknya untuk beberapa malam ke depan mereka nggak usah datang ke rumah?” tanya Ijah, istrinya. “Kata Muram, seminggu ke depan tentara akan getol melakukan patroli di desa kita.”
“Betul, Pak. Aku dengar langsung dari seorang tentara di pasar,” sahut Muram.
Natsir tak bergeming. Ia melangkah menuju ruang tamu sambil membawa nampan berisi nasi dan lauk, meninggalkan Ijah dan Muram yang tenggelam dalam pikiran masing-masing di depan tungku yang baru padam.
“Besok malam, aku mau mengadakan selamatan nikah anak keduaku. Kalian jangan lupa datang, acaranya selepas Isya,” ucapnya.
“Tetapi begini, Kang Natsir. Aku mendengar tentara akan patroli besok malam di desa kita,” papar Doel.
“Nggak usah khawatir. Aku jamin keselamatan kalian.”
Muram tak habis pikir dengan tindakan yang dilakukan oleh ayahnya. Tindakan tersebut bukan tanpa risiko. Paling berat ditembak di tempat, paling ringan dijebloskan ke Pulau Nusakambangan entah berapa tahun. Ditambah lagi, desas-desus yang ia dengar di masyarakat menyebut para gerombolan sebagai orang jahat. Mereka berlindung di balik agama untuk membunuh. Siapa pun yang tidak sepaham, tidak peduli tua, muda, wanita, atau anak-anak, akan dibunuh. Namun, sifat-sifat itu tak ditemukan pada diri Man Doel dan kawan-kawannya. Matanya terlihat teduh, tak ada tanda kebengisan. Setiap kali datang ke rumah, ia selalu membawa sesuatu dari hutan.
Ketika Muram menanyakan hal tersebut kepada bapaknya, Natsir menjawab, “Itu namanya perang urat syaraf, perang intelijen. Menyebarkan desas-desus, membuat kepanikan di tengah masyarakat.”
Lebih lanjut, Natsir menjelaskan bahwa para gerombolan muncul karena dianaktirikan oleh negara. Akar permasalahan ini berawal dari program Re-Ra (restrukturisasi dan rasionalisasi) di tubuh tentara. Melalui Re-Ra, jumlah personel tentara direncanakan dipangkas hingga setengahnya, dengan ketentuan hanya mereka yang memiliki ijazah yang tetap dipertahankan. Akibatnya, kelompok santri tidak memperoleh ruang dan tersingkir dari jalur karier militer, padahal mereka ikut terjun dalam berbagai palagan pertempuran.
Tahun 1963, Doel dan kawannya turun gunung. Setelah dua bulan mendekam di Penjara Slawi, mereka dipindahkan ke Purwokerto. Sebulan di Penjara Purwokerto, mereka kembali dipindahkan ke Pulau Nusakambangan. Pilihan Doel membuat Natsir sedikit bernapas lega. Setidaknya, kawan semasa mondok di Jawa Timur itu tidak mati oleh bayonet tentara. Ditambah lagi, kabar yang ia dengar dari radio menyebutkan bahwa para gerombolan akan diberikan amnesti oleh presiden. Tentu saja setelah melalui rangkaian indoktrinasi.
Ketenangan Natsir tak berlangsung lama, hanya seumur jagung. Ia memang tak begitu paham politik. Tak mengerti apa itu hijau, apa itu merah. Tetapi dari berita yang ia dengar dari radio sudah cukup menjelaskan bagaimana peliknya situasi. Ditambah lagi kabar dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa tentara sedang memburu kepala simpatisan Partai Merah.
Natsir paham betul siapa saja dari warganya yang terafiliasi ke Partai Merah. Hatinya terketuk untuk melindungi mereka. Bersama dengan Muram, ia merencanakan untuk menyembunyikan mereka ke hutan, tempat dulu Doel bersembunyi. Ia mengerti betul jalan menuju ke sana.
“Apakah harus, anak dan istri mereka juga turut bersembunyi? Apakah tidak sebaiknya tetap berada di desa?” tanya Muram.
“Harus, tidak boleh tidak. Mereka yang merasa di atas angin sudah pasti gelap mata, tak peduli benar atau salah. Sudah pasti keluarga simpatisan juga akan dihadapkan pada popor senjata. Maka dari itu, sebelum Subuh besok, mereka harus meninggalkan desa.”
Obrolan mereka harus terhenti oleh suara ketukan di pintu. Nadanya terdengar tergesa-gesa. Mendadak, mereka berdua menjadi kaku di tempat duduk. Otak mereka sedang dihadapkan pada dua pilihan: membuka atau tidak. Natsir paham betul bahwa itu bukan suara ketukan dari warga desanya, karena semua warganya paham bahwa ia tak menerima tamu di atas jam dua belas malam.
“Muram, buka pintunya!” perintah Natsir. “Nanti kamu diam saja, jangan ngomong apa-apa. Biar aku yang menghadapinya,” lanjut Natsir, kali ini dengan nada berbisik.
Di hadapan mereka kini duduk dua sosok dengan tubuh tegap. Rambut cepak menambah kesan bengis pada wajah masing-masing. Jaket kulit hitam melekat di badan, sementara sepatu bot hitam terlihat berlumur tanah lempung bercampur warna merah.
“Lama tak berselimut dinginnya angin malam Gunung Slamet. Terakhir kali aku ke mari tahun 1958, guna memburu para gerombolan. Setelah itu aku dipindah-tugaskan ke Sumatera Barat. Negeri ini memang selalu bergejolak, bukan begitu, Pak Natsir?” katanya dengan kalimat tanya mengintimidasi. Lalu ia mengeluarkan pistol dari balik jaketnya dan meletakkannya di atas meja. Cara ia meletakkan membuat air kopi di gelas beriak.
“Oh iya, perkenalkan, namaku Kapten Sabar. Ini ajudanku, Sersan Jono.”
“Pak Natsir dan Nak Muram tak perlu repot bangun pagi-pagi besok. Toh percuma saja. Mereka yang hendak kalian selamatkan, kini sudah berkumpul bersama dalam satu lubang.”
Sabar lalu menodongkan pistol ke arah Natsir. “Doel banyak cerita tentang kebaikanmu. Kebetulan saat itu aku bertugas di Nusakambangan. Sebenarnya, keterangan dari Doel sudah cukup membuat Pak Natsir dijebloskan ke penjara. Dan tindakan Pak Natsir yang hendak menyelamatkan orang kiri sudah cukup menjadi alasan pisahnya nyawa dari jasad Bapak.”
“Beruntung, Bapak punya menantu yang baik hati. Aku menghargai jasa-jasanya menjadi informan kami. Ia meminta agar mertuanya dibiarkan hidup. Waryolah yang menyusun daftar nama simpatisan kiri yang ada di kecamatan ini. Oh iya, satu lagi, mulai detik ini, Pak Natsir bukan kepala desa, dan Waryo yang akan menggantikan.”
Sabar memasukkan kembali pistolnya ke dalam jaket. Ia bergegas pergi tanpa mengucapkan permisi, lalu diikuti oleh ajudannya. Natsir hanya diam mematung, dengan tatapan kosong, lalu tubuhnya ambruk, pingsan. Hari-harinya berlalu ditemani kesedihan, bukan karena kehilangan jabatan kepala desa, melainkan karena merasa gagal melindungi tangan-tangan tak berdosa. Satu tahun kemudian, Natsir meninggal dunia, dengan ditemani perkataan getir: seandainya dia bergerak lebih cepat.
Malik Ibnu Zaman lahir di Tegal, Jawa Tengah. Menulis cerpen, puisi, esai, dan resensi yang tersebar di beberapa media online. Buku pertamanya sebuah kumpulan cerpen berjudul Pengemis yang Kelima (2024).