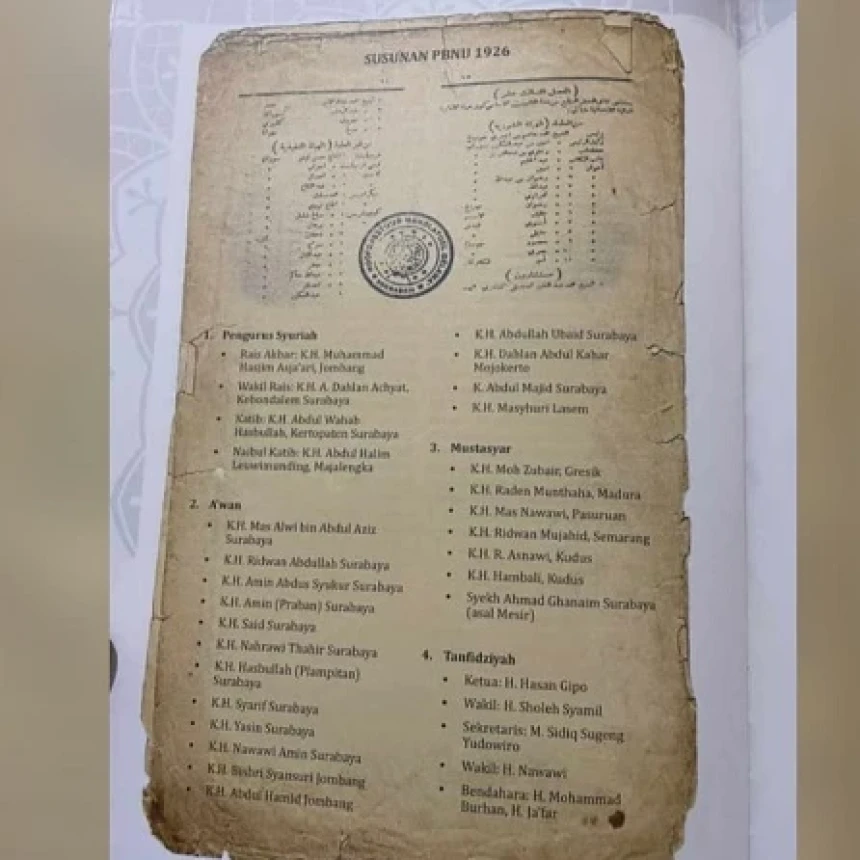Dinamika dan Konflik dalam Kabinet Dwikora Presiden Soekarno
Kamis, 7 November 2024 | 10:45 WIB
Komposisi Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan menteri kabinet terbanyak di ASEAN. Jumlah ini melampaui kementerian dalam kabinet pemerintahan Thailand dengan 35 menteri.
Selain itu, jumlah pejabat di kabinet Merah Putih 2024-2029 ini juga yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia sejak Orde Baru dan Reformasi. Hanya Kabinet Dwikora (1964-1966) masa Demokrasi Terpimpin yang memiliki jumlah menteri yang kurang lebih sama dengan Kabinet Merah Putih ini.
Kabinet Kerja I, II, dan III (1959-1964)
Pada awalnya, dari masa kemerdekaan hingga berakhirnya periode Demokrasi Liberal, Indonesia menerapkan sistem Parlementer yang menjadikan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Baru kemudian, seiring diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia beralih menerapkan sistem presidensil, di mana seorang presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Dalam sistem presidensil, pengangkatan para menteri dan pemetaan komposisi kabinet adalah sepenuhnya hak prerogratif presiden. Memasuki periode Demokrasi Terpimpin yang dirintis sejak tahun 1957 dan benar-benar diterapkan mulai Juli 1959 itu, dominasi kewenangan dan kekuasaan Presiden Soekarno begitu besar dan cenderung diktator (Ricklefs 2010, 533). Ia dengan leluasa memilih “para pembantunya” dalam setiap kabinet yang dibentuk.
Kabinet pertama Presiden Soekarno masa Demokrasi Terpimpin dinamakan Kabinet Kerja (puluhan tahun kemudian nama kabinet ini dipakai lagi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo). Kabinet Kerja I dimulai 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960, dengan total 45 pejabat di dalamnya. John D. Legge dalam buku Soekarno Sebuah Biografi Politik, menuturkan bahwa Kabinet Kerja terdiri dari para menteri dan para menteri muda. Tiga kepala staf (AD, AU, AL), Kepala Polisi, dan Jaksa Agung diangkat sebagai menteri-menteri ex officio, terkait jabatannya.
Mereka, semenjak dilantik harus melepaskan hubungan dengan partai politik sekalipun sebelumnya merupakan anggota partai-partai. Dan tidak seorang pun pemimpin partai besar ada dalam kabinet ini, hingga komposisinya menunjukkan hilangnya pengaruh kepartaian (Legge 1972, 357–58). Bahkan tokoh-tokoh seperti Subandrio (Menteri Luar Negeri) keluar dari PNI, dan Johanes Leimena (Wakil Menteri Pertama) keluar dari Partai Kristen (Ricklefs 2010, 552).
Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1960 tertanggal 18 Februari 1960, dilakukan reshuffle kabinet sekaligus melantik anggota-anggota kabinet baru. Kabinet ini dinamakan Kabinet Kerja II, dengan 41 orang pejabat di dalamnya, dan setahun kemudian ditambah dua departemen lagi (bidang pendidikan) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1961 tertanggal 21 Maret 1961. Kabinet Kerja II berjalan dua tahun.
Pada 6 Maret 1962 diumumkan pembentukan Kabinet Kerja III dan bertugas sejak 8 Maret 1962 hingga 13 November 1963. Pembentukan Kabinet Kerja III didasarkan pada Keppres No. 94/1962 tentang Reorganisasi Kabinet Kerja. Di dalamnya terdiri dari 55 menteri berikut para wakilnya.
Terakhir, ada Kabinet Kerja IV atau yang lebih dikenal Kabinet Kerja Gaya Baru. Kabinet ini ditetapkan pada 13 November 1963 dan bertugas sejak 23 November 1963 hingga 27 Agustus 1964. Penetapannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963, yang di dalamnya terdapat kurang lebih 65 pejabat mengisi kabinet ini (Simanjuntak 2003, 125–207).
Dinamika Konflik dalam Kabinet Dwikora
Setelah berakhir Kabinet Kerja I, II, III, dan IV, masa Demokrasi Terpimpin diwarnai oleh hiruk pikuk Kabinet Dwikora yang dianggap sebagai “kabinet 100 menteri”. Kabinet ini beroperasi dari tahun 1964 hingga tahun 1966 dalam situasi politik dalam negeri Indonesia, serta politik di luar negeri yang tengah memanas. Penamaan kabinet ini berkaitan dengan upaya Indonesia dalam melancarkan operasi “Ganyang Malaysia.”
Jargon “Dwikora” diciptakan Soekarno pada 3 Mei 1964 untuk menciptakan taktik yang lebih agresif melawan Malaysia (Crouch 1999, 76). “Dwikora” artinya dua komando rakyat; yang isinya berbunyi 1) “perhebat ketahanan revolusi Indonesia” dan 2) “bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk menggagalkan negara boneka Malaysia”.
Lebih jauh, jargon Dwikora ini berujung pada wacana pengadaan 21 juta sukarelawan untuk kampanye anti-Malaysia, dan pembentukan Komando Siaga (Koga) yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan militer terhadap Malaysia (Sundhaussen 1986, 326).
Pada awalnya, dalam Kabinet Dwikora terdapat 110 Mentri atau Pejabat Setingkat Menteri. Namun karena situasi politik di Indonesia terjadi turbulensi akibat tragedi G30S 1965, termasuk adanya tiga tuntutan rakyat (Tritura), kabinet ini dirombak pada Februari 1966 menjadi Kabinet Dwikora II dengan jumlah 132 pejabat di dalamnya. Pergantian posisi pejabat di kabinet ini diwarnai friksi politik yang memanas. Konflik antara faksi tentara dengan Presiden Soekarno meruncing. Aksi demonstrasi yang disponsori tentara menentang pemerintah pun semakin menguat. Sehingga, Presiden Soekarno perlu melakukan perombakan Kabinet Dwikora untuk menyelamatkan kekuasaannya (Ricklefs 2010, 597).
Presiden Soekarno me-reshuffle Jenderal Abdul Haris Nasution, tokoh sentral di militer (TNI). Kementerian Koordinator Pertahanan dan Keamanan yang dijabat oleh Nasution, dihapus lalu dipecah menjadi dua yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Urusan Pengamanan Khusus. Kementerian pertahanan dijabat oleh Mayor Jenderal Sarbini Martodihardjo yang sangat disegani di kalangan Angkatan Darat sebagai bekas panglima divisi-divisi Brawijaya dan Diponegoro. Wakilnya, diangkat Mayjen Moersjid. Baik Sarbini maupun Moersjid, keduanya memiliki kedekatan dengan Soekarno. Sementara Menteri Negara Urusan Pengamanan Khusus diemban oleh Kolonel Imam Sjafei. Presiden Soekarno mengharapkan Sjafei dapat meredam aksi demonstrasi mahasiswa yang sedang bergejolak setiap hari.
Dalam perombakan kabinet ini, Presiden Soekarno terlihat benar-benar “mewaspadai” kelompok militer. Nasution bukan hanya diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri, tetapi juga jabatan kepala staf angkatan bersenjata yang telah dibinanya sejak 1962, dibubarkan oleh Presiden Soekarno (Legge 1972, 460).
Presiden Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi bersinergi dengan Nasution. Pengangkatan Sarbini sebagai Menteri Pertahanan (sebelumnya menjabat menteri urusan veteran dan mobilisasi), merupakan strategi sang presiden untuk meredam perlawanan kelompok tentara, setidaknya di tubuh kabinetnya.
Di tubuh Angkatan Laut, Laksamana Madya Martadinata yang erat dengan Nasution di masa lalu, diganti dengan Laksamana Muda Muljadi, seorang Soekarnois. Begitu pula Panglima KKO Mayor Jenderal Hartono yang ditunjuk sebagai deputi menteri Angkatan Laut, jabatan yang tidak terdapat di angkatan-angkatan lain. Berikutnya ada Panglima Angkatan Udara Sri Muljono Herlambang, dan Panglima Kepolisian Sutjipto Judodihardjo, keduanya dianggap setia hanya kepada presiden (Crouch 1999, 194).
Pada kondisi ini, Nasution melawan. Ia mangkir ketika dipanggil menghadap Presiden, dan menolak melakukan serah terima. Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru berkomentar, “Jenderal Sarbini dan Jenderal Moersjid datang ke rumah mendesak saya untuk serah terima Hankam, karena saya tetap tidak bersedia menyerahkan Hankam” (Nasution 1987).
Penolakan Nasution membuat Sarbini kebingungan, apakah ia harus menerima atau menolak jabatan menteri pertahanan. Ia kemudian minta arahan dari Sultan Hamengkubowono IX. Sultan Yogya menyarankan agar jabatan itu diterima Sarbini, dengan alasan khawatir terjadi pertumpahan darah, dan kalau Sarbini menolak, maka dari “unsur Gestapu” yang akan diangkat. Sarbini akhirnya menerima jabatan tersebut, sekalipun tidak pernah mengalami pelantikan sebagai menteri baru karena Nasution tidak bersedia menghadiri upacara serah terima yang lazim.
Bagi Nasution, adalah sebuah dosa jika menerima begitu saja keputusan yang menurutnya tidak adil dari presiden (Crouch 1999, 195).
Banyaknya resistensi dari pihak militer dan dari para aktivis membuat pelantikan Kabinet Dwikora II tak berjalan mulus. Bertepatan dengan pelantikan kabinet, pada 24 Februari 1966 para demonstran yang terorganisasi rapi melakukan aksinya secara serentak di Jakarta, memblokir jalan-jalan di sekitar Istana. Mereka bergerak atas seizin Angkatan Darat. Seorang aktivis bernama Arief Rahman Hakim, mahasiswa kedokteran UI, tertembak di depan gerbang Istana. Akibatnya, kemarahan massa semakin memuncak. Hingga pada hari berikutnya amukan massa diarahkan kepada Kedutaan Besar Cina (Legge 1972, 461).
Situasi keamanan tak kunjung kondusif. Sidang terakhir Kabinet Dwikora II pada 11 Maret 1966, diwarnai oleh aksi para demonstran dan kehadiran pasukan tak dikenal di sekitar Istana. Sampai-sampai, Soekarno tidak menyelesaikan rapat, dan segera pergi ke Bogor menggunakan heli, meninggalkan rapat yang masih berlangsung. Peristiwa ini menjadi titik awal lahirnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 dari Presiden Soekarno kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto.
Nahas bagi Soekarno, surat itu malah digunakan oleh Soeharto untuk menangkapi 15 menteri Kabinet Dwikora II dengan tuduhan terlibat G30S. Oleh karena itu, terhitung sejak pelantikannya pada 24 Februari 1966 hingga demisioner pada 27 Maret 1966, Kabinet Dwikora II atau “Kabinet 100 Menteri” hanya bertugas selama satu bulan. Kabinet berikutnya adalah Kabinet Dwikora III yang hanya bertahan 5 bulan karena keburu digantikan oleh Kabinet Ampera. Kekuasaan Presiden Soekarno benar-benar di ujung senjakala, hingga akhirnya digantikan oleh Soeharto sebagai pejabat presiden, 12 Maret 1967.
Agung Purnama, pengurus Lakpesdam NU Jawa Barat, dosen tetap Jurusan SPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan mahasiswa S3 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.