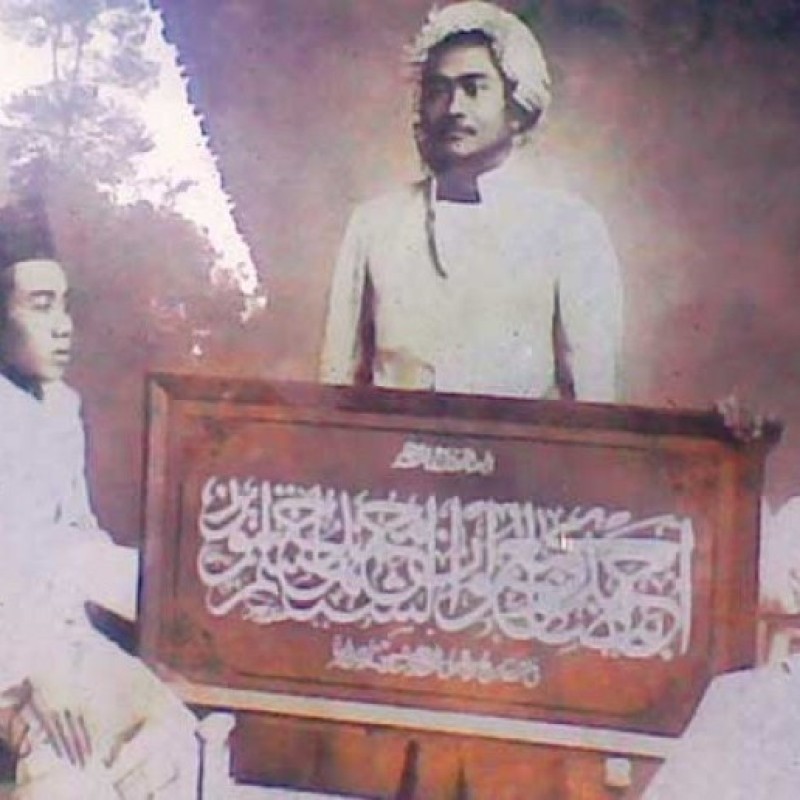Di dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama, konflik tidak pernah sekadar pertengkaran elite. Ia selalu merupakan gema dari sesuatu yang bergerak lebih dalam. Sesuatu yang menggeser fondasi imajinasi sosial yang selama puluhan tahun mengikat jutaan orang pada satu rasa kebersamaan.
Ketika pada akhir 2025 publik dikejutkan oleh tarik menarik legitimasi antara syuriyah dan tanfidziyah, banyak orang tergesa menjelaskannya sebagai rebutan posisi atau splinter politik menjelang muktamar. Tetapi bila kita mendekatinya dengan kesadaran antropologis semacam yang ditawarkan Clifford Geertz, konflik ini tampak bukan sebagai serangkaian peristiwa administratif, melainkan sebagai retakan dalam pusat makna yang menopang keberadaan NU sebagai dunia simbol, bukan sekadar organisasi formal.
NU sejak kelahirannya bukan tubuh yang dibangun melalui rasionalitas modern, melainkan sebuah jejaring pengalaman keagamaan yang memadukan karisma ulama, ritus pesantren, genealogis keilmuan, dan rasa hormat yang diinternalisasi sejak masa kanak-kanak dalam kehidupan santri. Banyak santri belajar bahwa kekuasaan dalam tradisi ini bukan sesuatu yang diperebutkan, tetapi sesuatu yang diwariskan secara halus melalui kedekatan spiritual dan longgokan ingatan kolektif tentang siapa yang menjadi murid siapa, siapa yang pernah diijazahi siapa, dan siapa yang namanya selalu disebut dengan nada takzim dalam pengajian.
Dalam horizon kultural seperti ini, jabatan ketua umum bukan sekadar kursi organisasi. Ia menjadi tanda dari hubungan vertikal antara seorang figur dengan rantai simbolik yang menghubungkan dunia sosial hari ini dengan tradisi keulamaan yang diyakini menyambung hingga masa Nabi. Ketika jabatan semacam itu dipersoalkan secara terbuka, yang terguncang bukan hanya legitimasi seorang individu. Yang terguncang adalah keyakinan bahwa pusat simbolik NU masih stabil.
Geertz pernah menulis bahwa kekuasaan dalam kultur Jawa dan dunia Islam tradisional bekerja bukan terutama melalui kemampuan memaksakan kehendak, melainkan melalui kemampuan menjaga bentuk bentuk representasi yang dianggap sakral. Dalam konteks NU, representasi itu selama ini hadir dalam tubuh kiai yang duduk tenang dan jarang bicara keras di panggung politik. Sosok yang lebih menjadi poros ketenangan daripada dirigen kompetisi.
NU tumbuh dengan anggapan bahwa selama figur pusat itu solid, umat di pinggiran akan merasa terlindungi oleh kontinuitas makna. Namun ketika dua struktur otoritas dalam NU, syuriyah dan tanfidziyah, mulai saling menafsir batas wewenangnya, apa yang retak bukan sekadar harmoni struktural, tetapi kesepakatan tak terucap tentang siapa yang pantas menjadi penjaga pusat itu. Surat edaran, konferensi pers, pernyataan soal legalitas dan keabsahan prosedur adalah gejala permukaan dari tarik menarik simbol yang jauh lebih dalam. NU selama ini hidup di wilayah di mana kebenaran moral lebih kuat daripada validitas dokumen. Ketika dokumen dan prosedur tiba tiba menjadi arena utama, tubuh budaya NU digiring ke lanskap epistemik yang asing.
Masuknya NU ke wilayah ekonomi ekstraktif mempercepat proses pergeseran itu. Banyak orang melihat tambang sebagai sumber keuntungan, tetapi secara kultural tambang adalah tanda masuknya NU ke dalam dunia di mana legitimasi tidak lagi diukur melalui sanad, melainkan melalui kontrak, modal, dan persyaratan legal. Di dalam dunia tambang tidak ada ruang bagi logika karisma. Yang ada adalah angka di laporan keuangan dan struktur kepemilikan perusahaan.
Ketika NU merapat ke dunia seperti ini, yang bergeser bukan hanya aktivitas ekonomi ormas, tetapi juga struktur dasar makna kepemimpinan. Jabatan di puncak NU tiba tiba tidak hanya membawa beban moral, tetapi juga beban korporatif. Ini menciptakan benturan antara logika sakral yang menghidupi NU dan logika teknokratis yang menghidupi industri.
Dua logika itu tidak punya bahasa yang sama. Dalam tradisi pesantren seseorang dianggap layak memimpin karena matang secara spiritual dan punya garis keilmuan jelas. Dalam dunia industri seseorang dianggap sah memimpin karena memegang hak legal dan beban tanggung jawab administratif. Ketika konflik jabatan meledak di tengah situasi seperti ini, yang terjadi bukan sekadar persaingan dua kubu, tetapi perjumpaan antara dua kosmologi politik yang tidak mudah dipertemukan.
Reaksi akar rumput NU yang merasa malu atau gelisah memperlihatkan dimensi antropologis yang penting. Dalam masyarakat yang bertumpu pada pusat sakral, konflik di tingkat elite bukan sekadar drama politik. Ia adalah ancaman terhadap kepastian moral. Warga NU di daerah yang terbiasa memaknai organisasi mereka sebagai rumah keagamaan tiba tiba menyaksikan suara suara yang saling bertentangan dari figur figur yang sebelumnya dianggap satu nafas. Mereka tidak sedang bertanya siapa yang benar dalam peraturan. Mereka sedang bertanya siapa kini yang menjadi rujukan iman sosial.
Pertanyaan itu mengandung kegentingan yang tidak terlihat dalam perdebatan administratif. Jika pusat simbolik kehilangan otoritas tunggal, pinggiran akan kehilangan koordinat makna. Dalam istilah Geertz masyarakat butuh peta moral untuk memahami posisinya dalam dunia yang lebih luas. Ketika dua figur pusat saling menegasikan wewenang satu sama lain, peta itu koyak dan orientasi budaya terganggu.
Baca Juga
Jembatan Budaya itu Bernama Gus Dur
Apa yang terjadi pada NU hari ini juga menunjukkan bahwa batas antara sakral dan profan semakin keruh. Selama puluhan tahun NU memiliki kemampuan unik untuk berada dekat kekuasaan negara, tetapi tetap mempertahankan jarak simbolik yang membuatnya tidak larut dalam logika politik praktis. Ulama boleh menghadiri istana, duduk dengan pejabat, atau berinteraksi dengan elite politik, namun otoritas spiritual mereka tidak diukur dari seberapa besar akses mereka ke negara. Otoritas itu selalu kembali kepada relasi batin antara ulama dan umat. Konsesi ekonomi seperti tambang mengubah konfigurasi itu. Ia membuka ruang di mana kedekatan dengan negara tidak lagi hanya menghasilkan pengaruh simbolik, tetapi juga akses material yang dapat mengubah dinamika internal.
Dalam kondisi seperti ini, NU menghadapi risiko baru yaitu hilangnya kemampuan untuk membedakan legitimasi spiritual dari legitimasi administratif dan ekonomis. Konflik elite kemudian bukan sekadar soal kepemimpinan, tetapi soal batas-batas kategori yang sebelumnya dianggap jelas.
Di dalam kebudayaan, fase seperti ini disebut masa liminal. Sebuah masa ambang di mana struktur lama sudah tidak sepenuhnya berfungsi dan struktur baru belum sepenuhnya lahir. Masa ini ditandai oleh kebingungan, kegaduhan, bahkan pertanyaan dasar tentang identitas. Apakah NU masih rumah keagamaan ketika ia juga menjadi pelaku ekonomi. Apakah ulama masih menjadi poros tunggal otoritas ketika dokumen dan legalitas mulai menentukan arah organisasi. Apakah jabatan masih simbol kesalehan sosial atau telah berubah menjadi posisi strategis dalam lanskap kekuasaan modern. Pertanyaan pertanyaan itu belum dijawab karena memang belum ada kosakata budaya yang mapan untuk menjelaskannya. NU belum pernah menghadapi situasi di mana pusat simboliknya ditarik secara bersamaan oleh logika karisma dan logika korporasi.
Oleh karena itu, menilai konflik ini sebagai kemunduran adalah penyederhanaan yang malas. Yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai negosiasi ulang tentang bentuk baru otoritas dalam NU. Di dalam negosiasi ini ada kemungkinan lahirnya bentuk kepemimpinan yang berbeda dari model sebelumnya. Bentuk yang tidak hanya bertumpu pada garis keulamaan, tetapi juga pada akuntabilitas publik. Bentuk yang tidak hanya disandarkan pada kesakralan pribadi, tetapi juga pada legitimasi transparan. Jika pada masa lalu pusat NU ada pada figur yang dianggap membawa kesunyian moral, mungkin pada masa depan pusat itu akan berada pada sintesis antara kesunyian moral dan keterbukaan administratif. Dan sintesis semacam itu tidak akan lahir tanpa melalui benturan keras seperti yang terjadi hari ini.
Konflik ini membuka kenyataan bahwa NU sedang mengalami transformasi kebudayaan. Transformasi yang tidak dipicu oleh niat individu untuk berkuasa, tetapi oleh tekanan zaman yang membawa organisasi ini masuk ke dalam medan baru di mana legitimasi harus dibuktikan tidak hanya secara sakral tetapi juga secara rasional. Jika hal ini berhasil diolah, NU dapat menemukan bentuk yang lebih matang dalam memadukan identitas keagamaannya dengan tuntutan modernitas.
Namun jika gagal, NU berisiko kehilangan kemampuan untuk menjadi pusat makna bagi jutaan umat yang bergantung pada NU bukan hanya sebagai lembaga, tetapi sebagai horizon hidup. Di titik ini pertaruhan NU bukan reputasi, bukan nama tokoh, bukan aset ekonomi. Pertaruhan NU adalah kemampuannya menjaga dirinya sebagai dunia simbol yang memberi arah bagi warganya. Bila konflik ini menjadi pintu bagi lahirnya kesadaran baru tentang batas batas otoritas, cara baru mengatur kekuasaan, dan kedewasaan dalam memaknai hubungan antara ulama, pengurus, negara, dan umat, maka kegaduhan ini bukan kehancuran. Ia adalah proses panjang di mana sebuah tradisi besar sedang merumuskan kembali dirinya di hadapan dunia yang berubah lebih cepat daripada ingatan kolektif mampu mengikutinya.
Virdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate