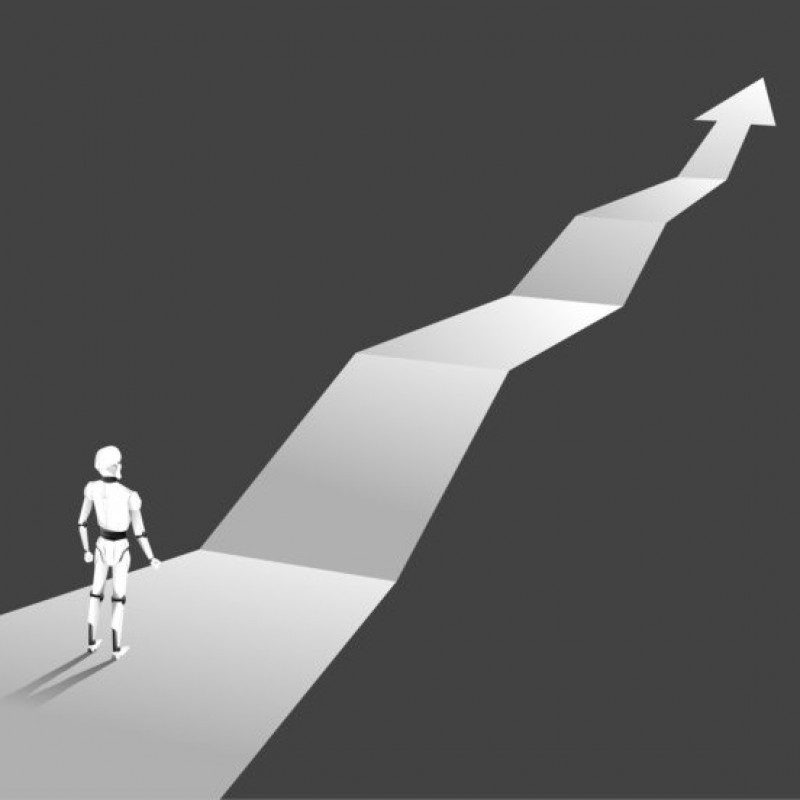Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia—khususnya dalam ranah keagamaan, kerap kali muncul penahbisan kolektif pada satu sosok manusia lain yang dianggap terpilih. Lalu lahirlah istilah yang kini kita kenal sebagai kristus, mesiah, mahdi, ratu adil, atau satriyo piningit pinandhito. Lebih tinggi dari itu ada lama, paus, santo, wali, buddha, nabi, dan rasul. Dalam khazanah Islam, wali saja bertingkat levelnya. Pun dengan nabi, yang kemudian dikategorikan sebagai ulul ‘azmi.
Sampai di situ, berarti masih ada lagi manusia paling terpilih dari yang sudah terpilih. Kenapa mereka bisa sampai terpilih, jelas itu urusan Tuhan. Tapi bagaimana mereka menunjukkan kualitasnya hingga kemudian menjadi manusia pilihan, ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Ditilik dari sudut pandang mana pun, apalagi dilengkapi dengan cara pandang, batas pandang, dan jarak pandang, mereka semua sah disebut sebagai manusia tercerahkan. Kesadaran mereka menyembul keluar dari dalam kegelapan peradaban. Lantas menghela zaman menuju Cahaya Kebenaran.
Manusia kiwari cenderung mengalami kesalahan fatal dalam memahami soal ini. Memuja sosok, figur, personanya, lantas jadi tetiron. Sudah pasti hal tersebut sulit dilakukan. Sebabnya mudah saja. Di dunia kita saat ini, kendati ada tujuh miliar manusia yang sedang berjalin kelindan, namun hanya satu saja manusia yang seperti Anda dan saya. Maka yang terpenting dilakukan, menggamit nilai yang mereka wariskan untuk kita hidupkan pada masa sekarang. Apa visi besar Muhammad, dan dengan cara apa ia mewujudkan misinya.
Dalam Al-Quran, ada sebuah ayat yang diturunkan Allah guna mempertegas posisi Nabi Muhammad saw di tengah kaumnya, “Sungguh aku ini hanya manusia biasa sepertimu, yang diberi Wahyu...” (QS Penghuni Gua [18]: 110). Pada tataran itu, kita sama dengan beliau; sederajat tapi tak setara. Dilahirkan, tumbuh, berkembang, dan mati. Nilai keunikan manusia sebelum mewadag di panggung raya kehidupan, sudah dimulai sejak alam rahim. Dari seluruh proses awal mula kejadian kita itu, baru perkara sperma saja yang tabirnya mulai tersingkap oleh masyarakat ilmiah.
Rata-rata pria menghasilkan sekira 525 miliar sel sperma seumur hidupnya. Bayangkanlah betapa reniknya kita dulu sebelum jadi seperti sekarang. Nah, 40 juta sampai 1,3 miliar sel itu terpancar dalam sekali ejakulasi—menuju ovum, dan hanya satu saja yang berhasil mendarat sempurna. Tampil sebagai pemenang. Pada kasus tertentu, ada yang kemudian sampai kembar. Berdasar penalaran itu, sadarkah kita betapa sesungguhnya setiap manusia yang lahir ke dunia adalah pilihan Tuhan?
Kita unik tak identik. Pun sama memiliki jempol, tak pernah ada sidik jari yang persis. Diberi dua bola mata, ternyata lain jenis tiap retina. Lahir dari perut ibu yang sama, mati dengan cara berbeda. Sama berlidahnya, pusparagam bahasanya. Menjalani hidup di bumi yang serupa, tapi serba-serbi kebudayaannya. Dianugerahi akal-pikiran, menghasilkan kebinekaan yang puspawarna. Intinya, manusia itu luar biasa. Berkembang dinamis dari masa ke masa. Ruang berganti ruang. Tak pernah ada yang benar-benar tetap bagi kita—sejauh ini.
Entah lahir sebagai lelaki, perempuan, khunsa (berkelamin ganda, red), androgini, semua dipilihkan jalan ninjanya masing-masing. Pun ada manusia yang kembar, mereka tetap berbeda dalam banyak hal, apalagi terkait kehidupan yang kelak dijalani. Jadi ini berkenaan dengan soal kesadaran yang jumbuh dari alam pikiran kita. Mental yang kemudian membentuk spiritualitas. Analoginya begini. Anda pernah masuk ke sebuah hutan di ujung kampung. Ternyata di sana ada sekelompok harimau yang nyaris memangsa Anda—tapi akhirnya Anda berhasil menyelamatkan diri.
Ketika kampung Anda dihantam banjir bandang, para penduduk lari sipat kuping ke dalam hutan itu, yang berada di punggung gunung—tanpa berpikir panjang. Saat itulah naluri kemanusiaan Anda berdenyar. Tak perlu menunggu komando siapa pun, terutama kepala dusun, Anda akan tampil di depan dan memberitahu bahaya yang kelak akan mengancam mereka, sekaligus memberitahu bagaimana cara melarikan diri apabila para harimau muncul dari keentahan.
Begitulah kiranya yang dilakukan manusia tercerahkan. Sebelum didapuk menjadi nabi dan rasul, Muhammad hilir mudik ke gua Hira’ selama rentang waktu lima belas tahun. Ditemani seorang pemuda bestari, ‘Ali bin Abi Thalib yang kerap melayaninya. Mereka menyendiri dalam sepi. Menjauhkan diri dari kedegilan peradaban jazirah Arabia. Masuk dalam kesunyian. Senyap dari segala keinginan. Mengheningkan cipta. Hanung dalam suwung.
Kelak nanti, keduanya tampil sebagai pemuka umat manusia yang dilamun derita nestapa kehidupan. Akal pikiran mereka yang terang benderang, menuntun banyak orang keluar dari kegelapan yang menyesatkan. Laku lampah batin seperti itulah yang kini sudah ditinggalkan. Sebagai seorang Muslim, sunnah terbesar itu mestinya pantas digugu-ditiru. Bukan sekadar meniru cara hidup Muhammad yang lahir pada abad ke-6 M. Jikalau semua yang tidak dilakukannya disebut bid’ah, cilaka betul hidup kita sekarang. Bid’ah berjela-jela.
Tahannuts yang lazim dilakukan para nabi-rasul dan manusia sempurna, tak ubahnya upaya kembali ke titik nadir, saat kita masih mengambang di alam buaian. Tak tahu apa-apa, tak ada apa-apa, bahkan kita tak tahu sedang mengada, yang ada hanya Allah semata. Inilah yang dinamakan Kesadaran Ilahiyah. Puncak dari yang tertinggi. Mengatasi segala sesuatu, dengan memahami segala sesuatu sebagai bagian tak terpisah dari diri sendiri. Karena kita semua di semesta ini, adalah partikel Tuhan (higgs boson).
Bila kita lahir sebagai manusia pilihan, wajar adanya Al Quran mengatakan bahwa kita dititah menjadi khalifah fi l-ardh: pemimpin di muka bumi, setidaknya bagi diri pribadi (QS Sapi Betina [2]: 30). Sebab dipilih Tuhan, maka apa pun yang kita pilih, adalah pilihan-Nya. Itulah pentingnya mengenal diri, agar kita mengenal Tuhan. “Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu.” Ada hadits qudsi lain yang nuansa redaksinya tak jauh beda: “al-insanu sirri wa Ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairihi: manusia itu rahasia-Ku dan Aku rahasia manusia, dan rahasia itu adalah sifat-Ku, dan sifat-Ku tiada lain adalah Aku.”
Syekh al-Akbar Muhyi al-Din ibn ‘Arabi menukil sebuah hadits qudsi dalam kitab karangannya, al-Risalah al-Wujudiyah, Tajaliyyat, al-Ittihad al-Kawni (h. 139):
“’Araftu Rabbi bi Rabbi: aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku.”
Dengan sabda itu, Nabi saw memberi isyarat bahwa engkau bukan engkau. Sebaliknya, engkau adalah Dia tanpa engkau. Bukan berarti Dia masuk ke dalam dirimu. Bukan berarti engkau masuk ke dalam Diri-Nya. Bukan berarti Dia di luar dirimu. Bukan pula engkau di luar Diri-Nya. Pahamilah ini, wahai para Pejalan...
Tak ayal, semua manusia menyimpan rasa penasaran teramat sangat pada Tuhan, Allah Rabb l-‘Alamin, lantaran Dia bathin bagi kita, dan kita dhahir bagi-Nya. Ke mana pun tujuanmu pergi, engkau sedang melangkah ke haribaan Diri-Nya. Siapa sahaja yang kautemui, sesunguhnya engkau hanya bertemu Dia nan Abadi. Napas kehidupan berembus dari kedalaman rahasia perjumpaan kita, dengan Keagungan Cahaya Mahacahaya, di langit dan di bumi.
Walakin, kami pungkasi risalah sederhana ini dengan sebuah puisi karya seorang mistikus agung, Hamzah Fansuri, yang digubahnya pada abad-17 M di bumi Swarnadwipa, dengan judul “Man ‘Arafa”:
“Man ‘arafa nafsahu hadits Nabi
Faqad ‘arafa Rabbahu tujuan diri
setelah sampai mengenali diri
maka tercapailah ketenteraman hati
la ilaha illallahu ucapan dzahir
bila mungkir menjadi kafir
atas hakikat manusia lahir
cari maknanya dibalik tabir
Wujud Qidam di dalam fana’
meng’isbatkan Allah al Baqa
Shalat daim besar menfaatnya
agar tercapai ketenangan jiwa.”
Ren Muhammad, pendiri Khatulistiwamuda yang bergerak pendidikan, sosial budaya, dan spiritualitas; Ketua Bidang Program Yayasan Aku dan Sukarno, serta Direktur Eksekutif di Candra Malik Institute