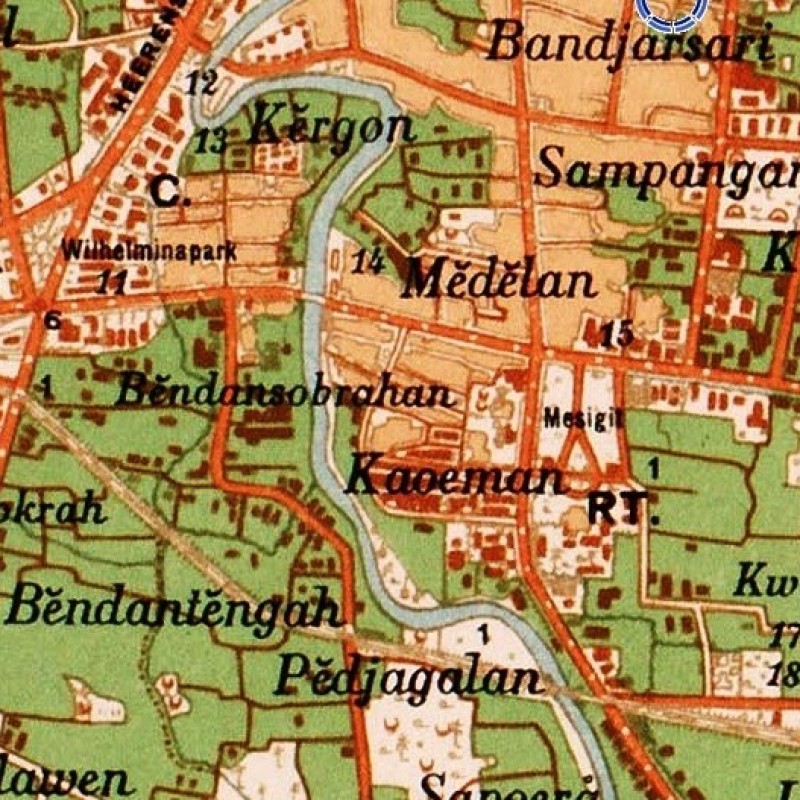Santri Bawean Gresik mengarungi lautan untuk mengikuti upacara Hari Santri 2019. (Foto ilustrasi: NU Online/M Jauhari Utomo)
Di tengah ramainya kasak-kusuk pembicaraan soal Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) belakangan ini, muncul ajakan dari beberapa kolega untuk berangkat ke Lampung. Kami bukan bagian apa-apa dari muktamar; peserta tidak, panitia pun tidak. Jadi kira-kira hanya akan menjadi ‘rombongan teratur’ (agar tidak disebut ‘rombongan liar’).
Sudah menjadi kebiasaan di beberapa muktamar terakhir, ada kelompok ‘rombongan teratur’ yang turut hadir namun punya agenda sendiri, entah sekadar reuni atau acara yang lebih serius semisal diskusi. Tapi kumpul-kumpul itu tentu di luar agenda muktamar secara resmi, sekadar inisiatif dari kelompok-kelompok tertentu yang masih terkait dengan identitas NU.
Cuma masalahnya, jadi tidaknya saya berangkat, masih tergantung hitung-hitngan urusan ongkos, begitu kira-kiranya.
***
Selain ‘rombongan teratur’ (ataupun juga ‘rombongan liar’ jika ada), terdapat orang-orang yang memang hadir di arena sebagai ‘penggembira muktamar’, yang datang dengan benar-benar bermodal rasa gembira, tanpa agenda khusus selainnya. Itulah mengapa, acara bazar, pasar malam, atau hiburan juga diselenggarakan di ajang muktamar untuk para penggembira.
Mungkin penggembira muktamar model seperti ini sudah tidak sebanyak di masa lalu. Dulu orang cenderung menjadikan keramaian sebagai wahana hiburan. Ketika ada tontonan, misalnya, orang bisa mencari hiburan di luar tontonan itu sendiri yaitu keramaiannya. Hiburannya bisa sekadar jalan-jalan plus membeli jajan atau oleh-oleh.
Tak terkecuali juga di ajang seputar NU maupun pesantren, termasuk pengajian, khataman, haul sampai ajang muktamar. Orang bisa berangkat ke ajang itu tidak semata-mata untuk acaranya, namun untuk hawa atau suasana dari acara tersebut.
Namun kiranya, kemajuan zaman relatif menggeser kecenderungan itu. Hiburan yang bisa didapat di genggaman tangan, membuat orang tak begitu tertarik lagi mencari hiburan dari keramaian. Singkatnya, saya menduga jumlah penggembira di ajang muktamar NU kini tidak lagi sebanyak dulu. Kalau jumlah rombongan baik yang ‘teratur’ maupun yang ‘liar’ makin banyak atau makin sedikit, saya tidak tahu.
***
Saya punya pengalaman di waktu kecil, saat momen Muktamar Ke-28 NU di Yogyakarta, yaitu menjadi penggembira, bukan menjadi rombongan baik ‘teratur’ maupun ‘liar’. Waktu itu, saya yang kira-kira masih kelas 3 SD berangkat bersama keluarga dari tempat tinggal kami di Purworejo, Jawa Tengah.
Bersama anggota dari dua keluarga lain, kami berangkat dalam satu mobil carteran jenis station wagon (kami bilang stesen) yang kalau tidak salah adalah Mitsubishi Colt T120. Hari sudah petang saat saya melihat baliho harian Kedaulatan Rakyat yang sudah menyala lampunya di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan DIY.
Kami pun berhenti sejenak untuk shalat maghrib di Masjid Agung Wates. Setelah itu perjalanan dilanjut kembali dan saya melihat ramainya lampu kendaraan di jalan Wates - Yogyakarta sambil membatin “ini sudah bau-bau ramainya Yogya”. Bagi orang Purworejo macam saya waktu itu, pergi ke Yogyakarta yang jarak perjalanaannya sekitar 70-an kilometer adalah sesuatu yang ‘wow’.
Singkat cerita, sampailah kami di Krapyak, lokasi pesantren Al Munawwir menjadi tuan rumah muktamar. Di sana mobil kami diparkir di satu tempat, lalu kami memesan bakso dan memakannya di dalam mobil. Acara selanjutnya adalah jalan-jalan ke arena bazar, yang seingat saya diadakan di lapangan, tapi entah itu lapangan bagian mana.
Di Krapyak kami bertemu adik dari ibu saya yang waktu itu sedang kuliah di Yogyakarta dan ikut dalam kepanitiaan muktamar. Bangga sekali rasanya punya paman di kota Yogyakarta, yang kalau pulang kampung tampak keren sekali. Paman ini jugalah yang cerita ke saya kalau Kiai MA Sahal Mahfudh dilarang anggota Banser masuk ke arena muktamar. Ia adalah saksi kejadian itu.
Dari Krapyak, perjalanan kami lanjut ke Kaliurang yang juga menjadi bagian dari arena muktamar. Di sana kami sejenak menonton hiburan kasidah putri. Selebihnya saya tidak punya memori lagi tentang perjalanan itu. Namun yang pasti, kami pulang ke Purworejo malam itu juga.
***
Jika mengingat perjalanan itu, saya berpikir betapa sederhananya peran kami sebagai Nahdliyin dalam muktamar; hanya penggembira. Di sana kami sekadar datang, makan bakso, jalan ke sini dan ke situ, lalu nonton kasidah dan pulang. Namun justru bagi saya, penggembira itulah yang meneduhkan muktamar dari segala kasak-kusuk yang tak jarang penuh intrik. Mereka tidak paham seperti apa pertarungan di ajang muktamar, namun mereka gembira dengan adanya muktamar.
Tidak hanya penggembira muktamar, bagi saya terdapat juga golongan penggembira NU. Mereka, para penggembira NU, mungkin tidak tahu siapa ketua tanfidziyah atau rais ‘aam NU, tidak tahu isu-isu politis apa yang sedang menerpa NU, namun mereka menjadi orang NU dengan gembira.
Mereka yang ada di kampung-kampung, yang dengan begitu bersemangat berkegiatan atas nama NU. Mereka tidak tahu bagaimana bagan struktur NU, namun mereka bagi saya adalah para penjaga NU, satu organisasi yang tak jarang terseret pusaran politik tertentu. Mereka bahkan mungkin tidak tahu perbedaan seragam NU maupun Muslimat, sampai seorang bapak-bapak berangkat acara NU dengan mengenakan seragam Muslimat. Namun bagi saya, keikhlasan mereka memiliki peran besar bagi tegaknya NU sampai saat ini.
***
Kiranya dari orang-orang yang saya sebut sebagai para penggembira ini, kita dapat belajar tentang ketulusan dalam berjam’iyyah, meski ini juga bukan perkara gampang. Soal keberangkatan ke muktamar, sampai saat tulisan ini ditulis, saya masih pikir-pikir. Ini karena ongkos perjanalan dari Yogyakarta (tempat tinggal saya kini) ke Lampung tentu tak sebanding dengan ongkos sewa station wagon dari Purworejo ke Yogyakarta.
Muhyidin Basroni, penggembira di UNU Yogyakarta dan IKANU Training Center Yogyakarta