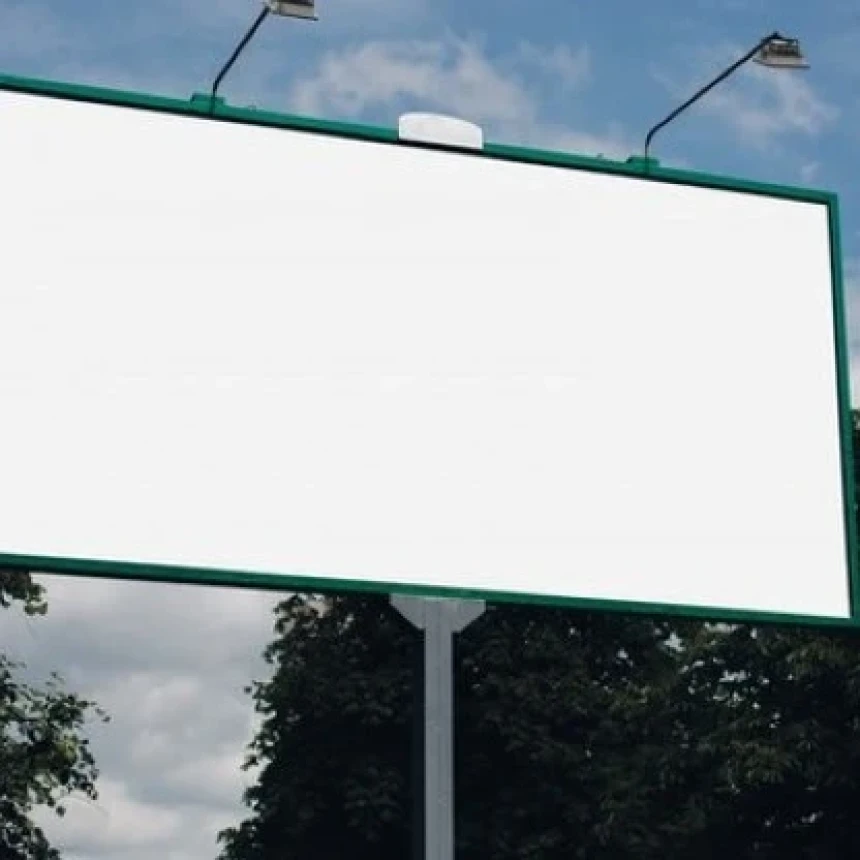Aku berdiri tegak di pantai pasir yang lembut. Tanganku terikat borgol. Suasana terasa sepi dan hening. Matahari pun telah kembali ke peraduannya. Di depanku kini berdiri 1 regu tembak dengan senapan Gewehr 98 yang siap memuntahkan pelurunya kapan saja.
Di tengah mereka, seorang pemimpin regu berdiri gagah, dengan pistol terselip di pinggang kirinya. Tentu saja aku mengenal siapa dia. Sudharmo namanya, mantan Kepala Staf Resimen XVII TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di Pekalongan semasa Peristiwa Tiga Daerah, tempat dia memainkan peranan penting dalam operasi penghancurannya.
Dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya, ia berjalan ke arahku dengan langkah pasti, sambil menghapus pasir yang menempel di unfiorm hijau kebanggannya. Keringat masih mengkilat di pelipisnya dan matanya berbinar penuh semangat. Aku bisa merasakan kegembiraan dalam dirinya, sebab sudah pasti ia akan mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan mentereng.
Baca Juga
Si Pemalu Menang Pemilu
"Apa permintaan terakhirmu?" tanyanya penuh antusias.
"Tidak ada," jawabku tersenyum.
Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, rupanya selembar sapu tangan berwarna merah. Ia hendak mengikatkannya pada mataku. Namun, aku dengan tegas menolaknya. Aku ingin melihat dunia terakhir yang akan kulihat sebelum segalanya berakhir. Mungkin, dari sebagian nyaliku adalah agar aku bisa merasakan apa yang akan datang lebih mendalam.
Setelah itu Sudharmo kembali ke tempatnya, berdiri di samping kiri regu yang sudah siap sedia menembak. Dengan suara lantang, ia memberikan aba-aba. Dan dalam sekejap, peluru melesat melalui udara. Ketika peluru itu menghantam dadaku, dunia seakan berhenti berputar. Rasa nyeri yang tajam menyelimuti seluruh tubuhku. Aku merasa seolah-olah waktu akan berhenti.
Baca Juga
Temon dan Cungkup Dukuh Pekowen
Semua bergerak dalam lambat, dan aku merenungkan tentang masa lalu, tentang kenangan yang tak akan pernah kunikmati lagi. Dalam detik itulah, aku merasa begitu rapuh dan kuat, dan aku tetap pada pendirianku bahwa apa yang kulakukan adalah benar. Sementara tubuhku menikmati rasa sakit, aku lihat ada tiga lubang peluru bersarang di dadaku, ingatanku membawa aku kembali ke masa lalu.
Kutil, begitulah orang-orang memanggil namaku, sementara nama asliku adalah Sakhyani. Kutil sendiri dalam Bahasa Jawa memiliki dua makna; bisa bermakna bintil kecil, bisa juga bermakna pencopet. Nah, sewaktu kecil memang mukaku berbintil-bintil. Meskipun setelah dewasa bintil-bintil itu hilang nama Kutil tetap melekat pada diriku. Selain itu juga sewaktu kecil aku dikenal sebagai anak bangor, alias anak nakal, ayam tetangga hingga mangga tak luput dari incaranku.
Aku bukan asli Tegal, aku anak kedua seorang pedagang emas di Taman dekat Pemalang. Sewaktu umurku 7 tahun kami sekeluarga pindah ke Tegal, pindah ke sebuah rumah yang telah dibeli oleh ayah di Dukuh Pesayangan. Di sini aku mendapatkan banyak teman. Mereka bukan hanya dari Dukuh Pesayangan, tetapi juga dari Desa Talang, Desa Kajen, oleh mereka aku diangkat menjadi pemimpin.
Para orang tua di Desa Talang melarang anak mereka berteman dengan diriku, takut ketularan bangor. Meskipun begitu, diam-diam anak mereka tetap bermain denganku.
Baca Juga
Pernikahan Rasmin
"Akin ingat ya kamu jangan bermain dengan orang seberang itu," ujar Kepala Desa Talang sewaktu aku lewat di depan rumahnya. Memang benar aku ini orang seberang. Karena selain tinggal di Dukuh Pesayangan yang letaknya di seberang Kali Gung (Sungai Gung), aku berasal dari Madura.
Aku hanya duduk sampai kelas dua Sekolah Rakyat, sekadar bisa membaca dan menulis. Meskipun tulisan tanganku jelek, dan hampir tidak terbaca, tetapi untungnya bacaanku lebih luas dibandingkan dengan kawan-kawan seusiaku. Aku sering membaca tulisan-tulisan Semaun, sampai-sampai aku ingin seperti dirinya, membela kaum kecil. Bahkan aku sampai membayangkan suatu saat bisa mengorganisir massa dalam jumlah besar, sama seperti yang dilakukan oleh Semaun, mengorganisir buruh kereta untuk melakukan pemogokan.
Memasuki usia 20 tahun pergaulanku semakin luas, bertemu dengan beberapa orang dari daerah lain yang memiliki kegelisahan serupa. Di usia itu pula aku menikah dan menempati rumah peninggalan ayahku. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aku tempat pangkas rambut di Desa Kajen, yang terletak di pinggir jalan raya selatan Tegal. Selain itu, aku juga meneruskan pekerjaan ayahku sebagai tukang emas, meskipun hanya kecil-kecilan.
Di masa-masa itulah aku semakin muak dengan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kajen. Ia sibuk memperkaya diri, sementara warga desa tetap dalam garis kemiskinan. Pada tahun 1937, aku memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai dalam pemilihan Kepala Desa Kajen. Tetapi sayangnya aku kalah selisih satu suara. Dalam pemilihan tersebut aku menyaksikan sendiri kecurangan yang dilakukan oleh lawanku.
Baca Juga
Seraut Wajah Perempuan Baliho
Ketika masa pendudukan Jepang, kebencianku terhadap para pangrah praja semakin memuncak. Rakyat banyak yang kelaparan, bahkan sampai harus memakan ubi beracun, sementara mereka masih bisa makan nasi. Mereka masih bisa mengenakan pakaian layak, sementara rakyat hanya mengenakan karung goni. Belum lagi banyak rakyat desa yang dijadikan Romusha, dikirim hingga ke Burma, dan tak pernah kembali lagi. Lalu banyak juga perempuan yang dijadikan jugun ianfu.
Aku dan beberapa pemuda di Tegal pun kini harus lebih hati-hati, sebab mata-mata kampetai ada di mana-mana. Kami satu bulan tiga kali mengadakan pertemuan bawah tanah, membicarakan situasi terkini. Dalam rapat bawah tanah Bulan Agustus 1945, diketahuilah bahwa Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, dan kami yakin Indonesia akan merdeka dalam waktu dekat. Dugaan kami tidaklah salah, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. 1945.
Permasalahan datang tatkala Jepang tak mau menyerahkan senjata mereka kepada para pemuda, mereka hanya mau menyerahkan senjata kepada Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II. Maka terjadilah perebutan senjata di mana-mana, tak terkecuali di Tegal. Dalam penyerbuan di markas kempetai di Tegal aku ikut serta, aku pun mendapatkan 5 pucuk senapan Lie Enfield dan 1 pucuk pistol Luger P08.
Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi jabatan wedana, kepala desa masih diduduki oleh orang-orang lama, orang korup. Itulah yang membuat kami para pemuda merasa muak, ditambah lagi mereka seperti masih mengharapkan kedatangan Belanda. Pada Bulan Oktober 1945 aku membentuk organisasi bernama Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dan menjadikan Bank Rakyat Talang sebagai markas.
Baca Juga
Peci Hitam Kiai
Di bulan-bulan itulah kekacauan terjadi di mana-mana, para pangrah praja di Karesidenan Pekalongan diganti oleh rakyat, banyak kepala desa yang didombreng, terjadi antara Oktober-November, yang dikenal dengan Peristiwa Tiga Daerah. AMRI yang aku pimpin juga terlibat dalam revolusi sosial itu, kami melakukan penjarahan ke Pabrik Gula Talang, merampas kuningan, lalu menjualnya ke Jakarta. Hasilnya dibagikan ke rakyat. Selain itu juga kami memburu orang-orang yang diduga mata-mata NICA.
Pada akhirnya kekacauan yang terjadi di Karesidenan Pekalongan berhasil diredakan pada bulan Desember 1945. Aku pun ditangkap dengan tuduhan penyebab kekacauan itu, sebuah tuduhan yang bagiku tidak berdasar. Tentu saja aku mendapatkan penyiksaan di dalam Tahanan Pekalongan. Pada tanggal 21 Oktober 1946 aku dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Suprapto dan menjadikan aku orang pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman mati.
Sewaktu Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947, para tahanan di Penjara Pekalongan diungsikan ke selatan Pekalongan. Dalam pengungsian tersebut aku berhasil kabur dan lari ke Jakarta. Di sana aku tinggal di Kebun Kacang Gang II, dan bekerja sebagai tukang cucur, pekerjaan yang digeluti dulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, penyamaranku hanya bertahan 2 tahun, aku dikenali oleh orang Slawi, dan aku pun ditahan oleh polisi Belanda.
Pada Januari 1950 seiring dengan penyerahan kedaulatan, aku diserahkan ke pihak Republik Indonesia. Dari Jakarta aku dibawa ke Semarang, lalu ke Pekalongan. Pada 8 April 1950 kembali menegaskan hukuman mati terhadap diriku, setelah pada 13 Februari Hakim Suprapto yang kini menjadi jaksa agung datang ke Pekalongan menjadi saksi atas putusan yang ia jatuhkan kepadaku beberapa tahun yang lalu.
Baca Juga
Kubu Langgar dan Kubu Masjid
Lalu pada 1 Agustus 1950 aku mengajukan grasi kepada Presiden Soekarno. Tetapi grasiku ditolak pada 21 April 1950. Dua minggu kemudian kini aku terbaring di Pantai Pekalongan bersimbah darah di hadapan regu penembak. Kini aku pun tersentak, kembali ke dalam kesadaran, bayang-bayang masa lalu pun menghilang, seiring dengan nyawaku yang melayang. Aku ikhlas dengan apa yang terjadi, aku tidak pernah menyesal dengan apa yang aku lakukan, biarlah sejarah yang kelak akan menilai apakah namaku harum atau bangkai.
Malik Ibnu Zaman, kelahiran Tegal Jawa Tengah, kontributor NU Online. Malik menulis sejumlah cerpen dan esai yang tersebar di beberapa media online.