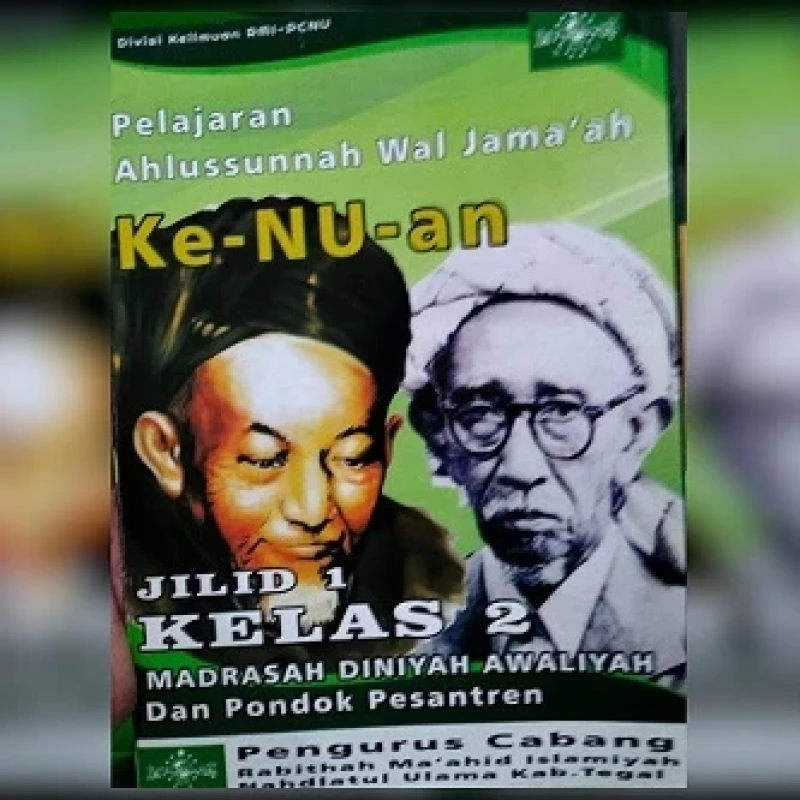Sejarawan Nilai Historiografi Indonesia Masih Maskulin dan Jawa-Sentris, Kontribusi Perempuan Terpinggirkan
Senin, 10 November 2025 | 13:00 WIB

Sejarawan UGM Mutiah Amini dalam Diskusi Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 bertema Meneguhkan dan Melanjutkan Juang Pahlawan Perempuan yang diselenggarakan Komnas Perempuan secara daring, pada Senin (10/11/2025). (Foto: tangkapan layar zoom)
Jakarta, NU Online
Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Mutiah Amini menilai historiografi atau penulisan sejarah di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh cara pandang maskulin dan Jawa-Sentris.
Hal itu menyebabkan kontribusi perempuan, khususnya yang berasal dari luar Jawa, terpinggirkan atau tidak banyak muncul dalam narasi sejarah nasional.
“Kalau kita bicara sejarah Indonesia, yang muncul di benak kita adalah Jawa. Dan kalau bicara sejarah, seolah ruang itu hanya milik laki-laki. Padahal masa lalu adalah milik laki-laki dan perempuan bersama-sama,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Mutiah dalam Diskusi Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 bertema Meneguhkan dan Melanjutkan Juang Pahlawan Perempuan yang diselenggarakan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara daring, pada Senin (10/11/2025).
Ia mencontohkan tokoh Siti Manggopoh, pejuang perempuan asal Agam, Sumatra Barat, yang memimpin perlawanan terhadap kebijakan pajak kolonial Belanda (Belasting Oorlog). Menurut Mutiah, perjuangan tersebut bukan hanya perlawanan bersenjata, tetapi juga bentuk kesadaran atas ketidakadilan sosial.
Mutiah menjelaskan bahwa dalam sistem matrilineal Minangkabau, tanah merupakan hak dan identitas perempuan. Dengan demikian, kebijakan pajak yang diterapkan pada lahan dan sumber daya tersebut dipandang sebagai bentuk perampasan hak-hak perempuan.
“Ketika tanah dikenakan pajak, itu sama saja dengan merampas hak perempuan. Maka perlawanan Siti Manggopoh menjadi sangat besar dan bermakna,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mutiah menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap pemaknaan pahlawan nasional. Berdasarkan data Komnas Perempuan, hingga 2023 hanya sekitar 8 persen tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah perempuan. Kondisi ini menunjukkan narasi kepahlawanan masih lebih banyak disematkan pada laki-laki dan perlawanan bersenjata.
“Kita perlu melihat kembali siapa yang disebut pahlawan? Apakah hanya mereka yang melawan kolonialisme, atau juga yang memperjuangkan keadilan sosial di lingkungannya?” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pengalaman dan perjuangan perempuan tidak tunggal. Perempuan hadir dalam beragam kondisi sosial, usia, kelas, dan wilayah, termasuk perempuan Papua, Natuna, serta daerah-daerah lain yang menghadapi ketidakadilan dengan konteks masing-masing.
“Perempuan itu variabel yang banyak ada. Perempuan tua, muda, ibu, buruh, dan semua punya ruang perjuangan masing-masing. Termasuk perempuan di Papua, Natuna, atau daerah-daerah lain yang harus bertahan menghadapi ketidakadilan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komnas Perempuan periode 2020-2024 Mariana Amirudin mengangkat perjuangan Sri Mangoensarkoro sebagai contoh tokoh perempuan yang berkiprah melalui jalur intelektual dan politik pada masa pasca kemerdekaan.
“Beliau (Sri Mangoensarkoro) memimpin Kongres Perempuan Indonesia Kedua dan menegaskan bahwa perempuan harus menjadi subjek sejarah dan pembangunan bangsa,” kata Mariana.
Sebagai Ketua Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), Sri Mangunsarkoro memperjuangkan regulasi terkait monogami, hak waris, usia minimal pernikahan, serta kesetaraan dalam perceraian. Mariana menilai peran tersebut menjadi jembatan antara gerakan emansipasi ala Kartini dan feminisme kebangsaan modern.
“Kepemimpinan Sri Mangoensarkoro menjadi jembatan antara gerakan emansipasi ala Kartini dan feminisme kebangsaan modern, yang menekankan keseimbangan antara peran keluarga, masyarakat, dan negara,” jelasnya.