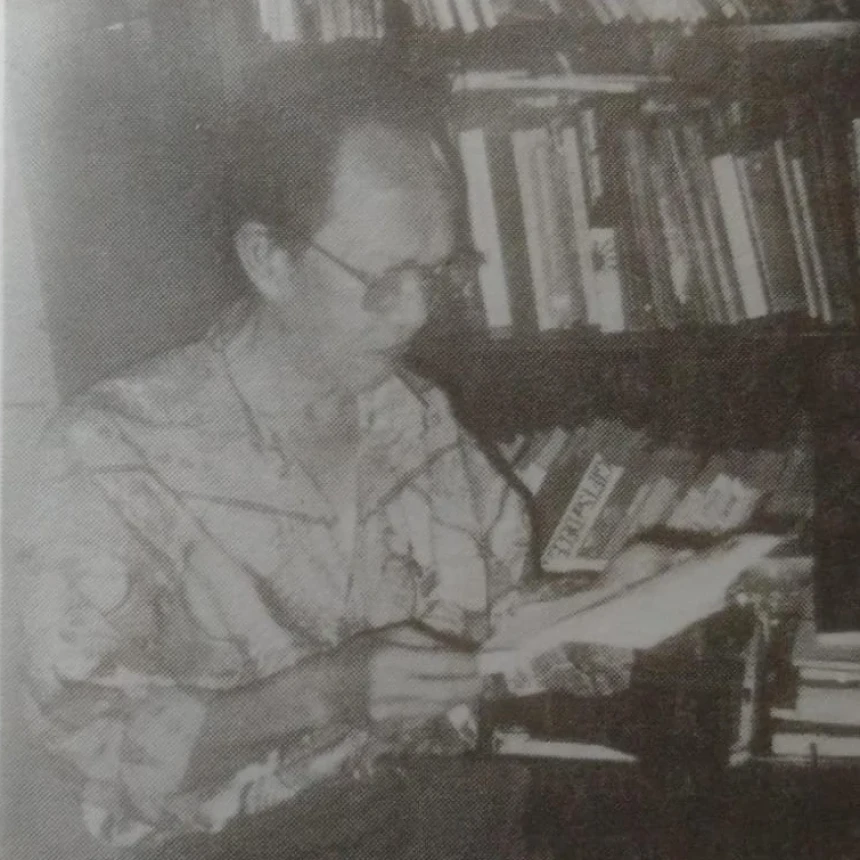Mahbub Djunaidi, Nahdlatul Ulama, dan Perpolitikan Indonesia
Selasa, 30 September 2025 | 13:52 WIB
Nama Mahbub Djunaidi (1933-1995) menempati posisi unik dalam sejarah intelektual dan politik Indonesia. Selain wartawan dan kolumnis ulung, ia juga seorang organisator, politisi, dan budayawan yang berakar pada Nahdlatul Ulama (NU). Sosoknya sering disebut sebagai “si jenius jenaka” yang mampu menembus batas ideologi, menyapa semua kalangan, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Islam tradisional.
Sejarah perpolitikan Indonesia pasca-kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari peran NU, baik sebagai organisasi sosial-keagamaan maupun kekuatan politik. Mahbub Djunaidi adalah salah satu figur yang menjembatani dunia pesantren, dunia politik, dan dunia jurnalistik modern. Ia lahir dan besar dalam orbit NU, namun cara berpikirnya yang tajam membuatnya bisa hadir sebagai intelektual publik lintas batas.
Membaca Mahbub Djunaidi mewakili cara kita melihat salah satu sudut wajah NU dalam politik Indonesia, serta bagaimana kiprahnya menggambarkan dialektika antara Islam, tradisionalisme, nasionalisme, dan demokrasi.
NU dan Dinamika Politik Indonesia
Untuk memahami Mahbub, kita perlu melihat lanskap NU dalam politik Indonesia. NU lahir pada 1926 sebagai reaksi ulama pesantren terhadap arus modernisme Islam yang dipelopori Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam) dan juga sebagai respons atas kebijakan Wahabi di Hijaz. Namun, pasca-kemerdekaan, NU tidak hanya bergerak di bidang sosial-keagamaan, melainkan juga ikut aktif dalam politik.
NU mula-mula bagian dari Masyumi (1945–1952), tetapi kemudian memisahkan diri pada 1952 dan mendirikan Partai NU. Sejak saat itu, NU menjadi salah satu kekuatan politik utama pada masa demokrasi parlementer. Dalam Pemilu 1955, Partai NU berhasil menempati posisi keempat dengan suara signifikan, menunjukkan kekuatan politik umat pesantren (Bruinesen, 1994).
Namun, hubungan NU dengan kekuasaan tidak pernah linear. Dalam Demokrasi Terpimpin (1959–1965), NU harus menyesuaikan diri dengan tekanan Sukarno yang menguatkan PNI dan PKI. Dalam masa Orde Baru, NU pun harus berhadapan dengan kooptasi politik Soeharto, hingga pada 1984 di bawah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), NU memutuskan kembali ke khittah 1926 dan meninggalkan politik praktis (Barton, 2002).
Dalam kerangka ini, Mahbub Djunaidi muncul sebagai figur yang merepresentasikan wajah NU yang kritis, progresif, sekaligus akomodatif terhadap perubahan zaman.
Mahbub Djunaidi lahir di Jakarta pada 1933. Ia tumbuh dalam keluarga NU dan menempuh pendidikan di pesantren, sebelum melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari muda, Mahbub menunjukkan kecemerlangan intelektual dan bakat menulis yang luar biasa.
Karier jurnalistiknya dimulai sejak ia aktif di Harian Duta Masjarakat, media yang menjadi corong NU. Namun, Mahbub tidak berhenti di situ. Ia juga aktif mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 1960, sebuah organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan NU, dan menjadi ketua pertamanya. PMII kemudian melahirkan banyak kader intelektual Muslim yang berpengaruh di Indonesia.
Di dunia jurnalistik, Mahbub dikenal sebagai kolumnis tajam yang kerap menggunakan humor sebagai senjata. Kolom-kolomnya yang kemudian dibukukan dalam Kolom Demi Kolom memperlihatkan gaya tulis yang lugas, penuh ironi, namun tetap membumi.
Mahbub juga aktif dalam politik praktis. Ia menjadi anggota DPR mewakili Partai NU, dan pada masa Orde Baru, ia tetap bertahan di jalur politik meski sering bersikap kritis terhadap kekuasaan.
Mahbub, NU, dan Identitas Islam
Salah satu kekuatan Mahbub adalah kemampuan mengartikulasikan identitas NU sebagai bagian dari wajah Islam ala Indonesia. NU selama ini dikenal sebagai penyangga tradisi, menjaga amaliah keagamaan yang berakar pada tasawuf, fiqih, dan budaya lokal. Dalam kolom-kolomnya, Mahbub seringkali menyuarakan kritik terhadap kecenderungan puritanisme atau radikalisme yang mencoba menghapus tradisi keislaman lokal.
Mahbub memahami bahwa kekuatan NU terletak pada kemampuannya merangkul kebangsaan. Ia melihat nasionalisme bukan ancaman, tetapi sebagai perekat Islam. Hal ini sejalan dengan gagasan Bung Karno tentang Nasakom dan pemikiran Gus Dur tentang “pribumisasi Islam.”
Melalui tulisannya, Mahbub menegaskan bahwa NU bukanlah kekuatan yang semata-mata ingin memperjuangkan formalisasi syariat Islam, melainkan kekuatan moral dan kultural yang berkontribusi pada demokrasi dan kebangsaan.
Mahbub dikenal sebagai politisi NU yang kritis terhadap kekuasaan, baik pada masa Sukarno maupun Soeharto. Ia memahami bahwa politik Indonesia seringkali penuh intrik dan kooptasi, namun ia tidak terjebak dalam sikap hitam-putih.
Pada masa Sukarno, Mahbub menyaksikan bagaimana NU harus berkompromi dengan Nasakom. Di satu sisi, NU mendapat ruang politik, tetapi di sisi lain harus berhadapan dengan dominasi PKI. Mahbub menilai bahwa kompromi ini perlu, tetapi juga berbahaya jika membuat NU kehilangan jati diri.
Pada masa Orde Baru, Mahbub berhadapan dengan politik represif Soeharto. NU dan partai-partai Islam dipaksa bergabung ke dalam PPP pada 1973. Mahbub tetap aktif dalam jalur politik ini, namun ia juga menyadari bahwa ruang gerak sangat terbatas. Dengan kecerdikannya, Mahbub menggunakan tulisan-tulisan satir untuk melancarkan kritik terhadap rezim (Deliar, 1987).
Humor adalah senjatanya. Ia sering melontarkan kritik tajam dengan gaya santai, sehingga tidak langsung dianggap subversif, meski pernah dipenjara Suharto di Nirbaya bersama Mochtar Lubis. Dalam sebuah kolom ia menulis, “Politik kita ini seperti main catur, tapi bidaknya sudah diatur sebelum permainan dimulai” (Mahbub Djunaidi, Kolom Demi Kolom, 1986).
Warisan Mahbub, Dunia Jurnalistik dan PMII
Di luar politik, Mahbub memberi warisan besar pada dunia jurnalistik Indonesia. Sebagai wartawan, ia dikenal jujur, kritis, dan penuh integritas. Gaya menulisnya menggabungkan kecerdasan analisis dengan humor khas NU.
Banyak menyebut Mahbub sebagai “Mark Twain-nya Indonesia” karena gaya satirnya yang khas. Namun, berbeda dengan satiris Barat yang cenderung individualis, humor Mahbub berakar pada tradisi pesantren. Jenaka, sederhana, namun mengandung makna filosofis.
Ia menegaskan bahwa menulis bukan menyampaikan informasi semata, tetapi juga membentuk kesadaran politik. Baginya, wartawan adalah guru bangsa yang bertugas menyampaikan kebenaran kepada rakyat. Dalam kumpulan tulisan, Kolom Demi Kolom, ia menyampaikan, “Kolom itu bukan tempat marah-marah, melainkan tempat mendidik orang banyak agar mengerti ke mana arah bangsa ini.”
Salah satu kontribusi terbesar Mahbub bagi NU adalah perannya dalam mendirikan dan memimpin PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) pada 1960. PMII lahir dari kebutuhan mahasiswa NU untuk memiliki organisasi yang mandiri, terpisah dari HMI yang dianggap lebih dekat dengan modernis.
Sebagai ketua pertama PMII, Mahbub menanamkan semangat kebangsaan, keterbukaan intelektual, dan komitmen sosial. Begitu juga lirik Mars GP Ansor yang dibuatnya menggelorakan semangat kebangsaan yang begitu kuat. Ia tidak mengajarkan kadernya untuk menjadi fanatik, tetapi untuk menjadi kritis.
Hingga kini, PMII menjadi salah satu kawah candradimuka kader NU, melahirkan banyak pemimpin nasional yang tumbuh di PMII.
Perlu dicatat, warisan nilai yang utamakan Mahbub sebagai berikut:
Pertama, warisan paling mendasar dari Mahbub adalah pandangannya tentang Islam dan kebangsaan. Ia hidup dalam era ketika perdebatan tentang hubungan agama dan negara masih sangat kuat. Apakah Islam harus menjadi dasar negara ataukah cukup sebagai etika moral dalam kehidupan berbangsa. Mahbub menegaskan bahwa Islam dan nasionalisme bukanlah musuh, melainkan mitra yang saling menguatkan. Ia sejalan dengan arus pemikiran para tokoh NU sejak KH Wahid Hasyim hingga KH Abdul Wahab Chasbullah yang menekankan pentingnya menerima Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Pandangan ini relevan hingga kini, ketika relasi antara agama dan politik kerap ditarik ke arah polarisasi yang tajam (Baso, 2017).
Kedua, Mahbub menempatkan humor sebagai instrumen kritik sosial-politik. Di tengah situasi politik yang penuh represi, terutama pada masa Orde Baru, ia memilih jalur satir ketimbang frontal. Baginya, sindiran yang dikemas dalam kelucuan jauh lebih efektif daripada makian yang cuma menimbulkan perlawanan tanpa hasil. Kolom-kolomnya kerap memancing tawa sekaligus renungan. Misalnya, ketika ia menulis tentang pejabat yang sibuk dengan seremoni, ia menggambarkan mereka seperti “wayang yang kehilangan dalang, sibuk bergerak tapi tak tahu arah.” Kritik semacam ini membuatnya tetap aman dari represi, sekaligus mampu menggugah kesadaran publik.
Ketiga, Mahbub meyakini bahwa NU adalah penjaga demokrasi. Meski NU sempat terjun dalam politik praktis, ia percaya bahwa kekuatan terbesar NU justru sebagai penyangga moral dan sosial masyarakat. NU berfungsi sebagai benteng tradisi, tetapi juga sekaligus kekuatan rakyat yang mampu menyeimbangkan jalannya kekuasaan oleh pemerintah. Ia mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak akan kokoh tanpa partisipasi masyarakat sipil yang berakar pada tradisi lokal. Dalam perspektif Mahbub, NU adalah “pohon rindang” yang menaungi masyarakat kecil sekaligus menjaga keseimbangan politik nasional.
Keempat, dalam dunia media, Mahbub menekankan bahwa jurnalisme bukan bisnis informasi, tetapi misi pendidikan politik. Wartawan, menurutnya, tidak boleh melaporkan fakta kering, tetapi harus berani memberikan makna, arah, dan kritik. Bagi Mahbub, kolom adalah ruang untuk membangun kesadaran politik rakyat, agar mereka tidak terjebak dalam narasi elite semata. Prinsip ini membuatnya berbeda dari banyak jurnalis lain pada zamannya yang cenderung bermain aman. Ia memilih jadi “guru bangsa,” bukan “tukang catat peristiwa.”
Baca Juga
Ketika Mahbub Djunaidi Membela Subhan ZE
Kelima, warisan Mahbub ini memperlihatkan bagaimana seorang intelektual NU bisa memadukan akar tradisi dengan modernitas. Ia lahir dari rahim pesantren, tetapi berpikir dan menulis dengan gaya modern. Ia bisa berbicara dengan bahasa rakyat kecil, tetapi juga mampu berdialog dengan wacana global. Perpaduan ini membuat warisannya melintasi zaman. NU yang berakar kuat pada tradisi, tetapi sekaligus terbuka terhadap demokrasi, nasionalisme, dan modernitas. Dalam hal ini, Mahbub menjadi teladan bagaimana seorang kader NU bisa tetap setia pada akar sambil terlibat aktif dalam dunia yang terus berubah.
Keenam, yang paling penting dari warisan Mahbub adalah keberanian intelektual. Ia tidak terjebak pada sikap fanatisme buta, baik terhadap NU maupun partai politik. Ia berani mengkritik elite NU sendiri ketika dirasa terlalu pragmatis, tetapi tetap melakukannya dengan cara yang elegan dan penuh kepedulian. Keberanian intelektual ini adalah teladan langka di tengah kultur politik Indonesia yang sering terjebak dalam patronase. Dari Mahbub kita belajar menjadi bagian dari NU bukan berarti harus menutup mata terhadap kesalahan NU, melainkan justru menjadi pengingat yang jujur agar organisasi tetap berada di jalur moralitas dan demokrasi.
Mahbub, NU, dan Politik Indonesia Kontemporer
Jika kita melihat politik Indonesia hari ini, warisan Mahbub masih terasa relevan. Politik seringkali jatuh ke dalam pragmatisme, sementara nilai-nilai kebangsaan dan moralitas terpinggirkan. NU sebagai ormas Islam terbesar tetap memainkan peran penting, namun sering juga ditarik-tarik ke dalam kepentingan praktis.
Dalam konteks ini, Mahbub mengajarkan pentingnya humor, kejujuran, dan intelektualitas dalam politik. Ia mengingatkan bahwa politik tanpa etika hanya akan menjadi perebutan kekuasaan belaka.
Sebagai figur NU, Mahbub juga menunjukkan bahwa Islam tradisional bisa tampil modern, progresif, dan kritis. NU tidak harus inferior di hadapan modernisme, melainkan bisa menjadi penyeimbang dalam membangun demokrasi.
Mahbub Djunaidi adalah wajah dialektika antara NU, politik, dan intelektualisme di Indonesia. Ia lahir dari tradisi pesantren, tumbuh dalam dunia jurnalistik, dan berkiprah dalam politik nasional.
Dalam dirinya, kita melihat wajah NU yang humanis, kritis, dan humoris. Ia menunjukkan bahwa politik tidak harus kaku, bahwa Islam tidak harus eksklusif, dan bahwa demokrasi membutuhkan suara moral dari rakyat kecil.
Warisan gagasan Mahbub selain melalui tulisan dan jabatan yang diembannya, melampaui semua itu, dia adalah teladan tentang bagaimana menjadi cerdas tanpa kehilangan akar, kritis tanpa kehilangan humor, dan religius tanpa kehilangan spirit kebangsaan.
Abi S Nugroho, pengurus Lakpesdam PBNU