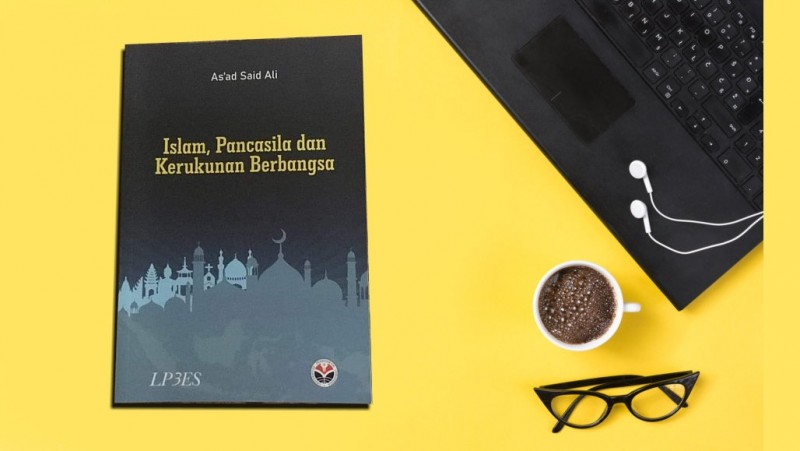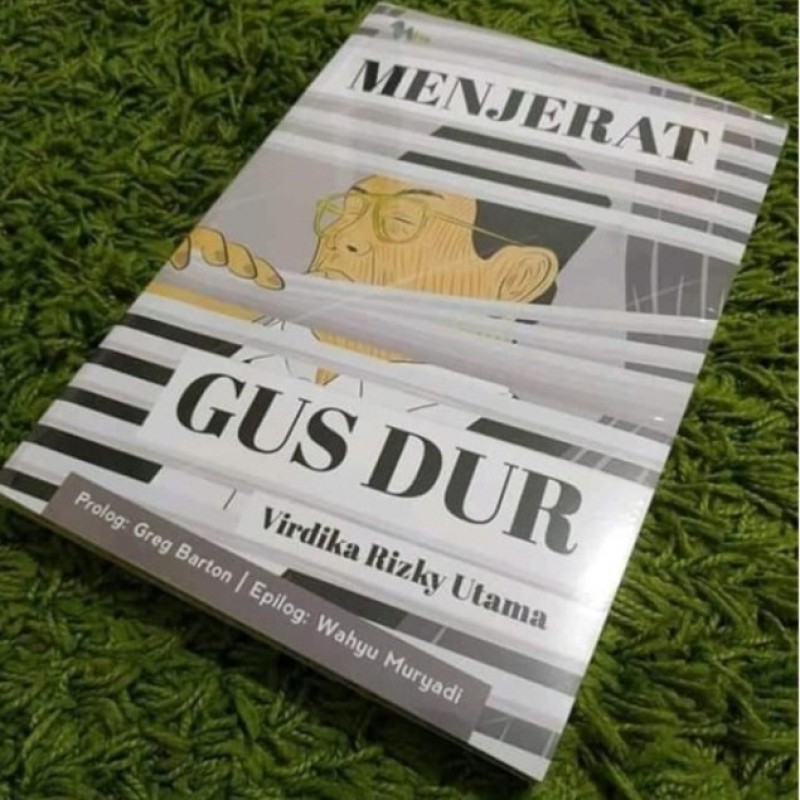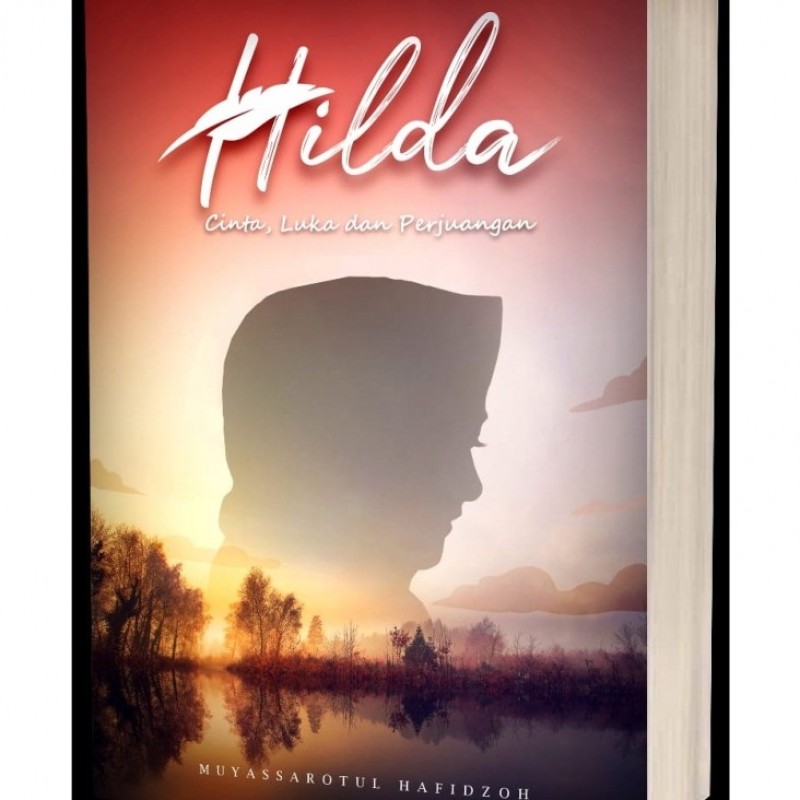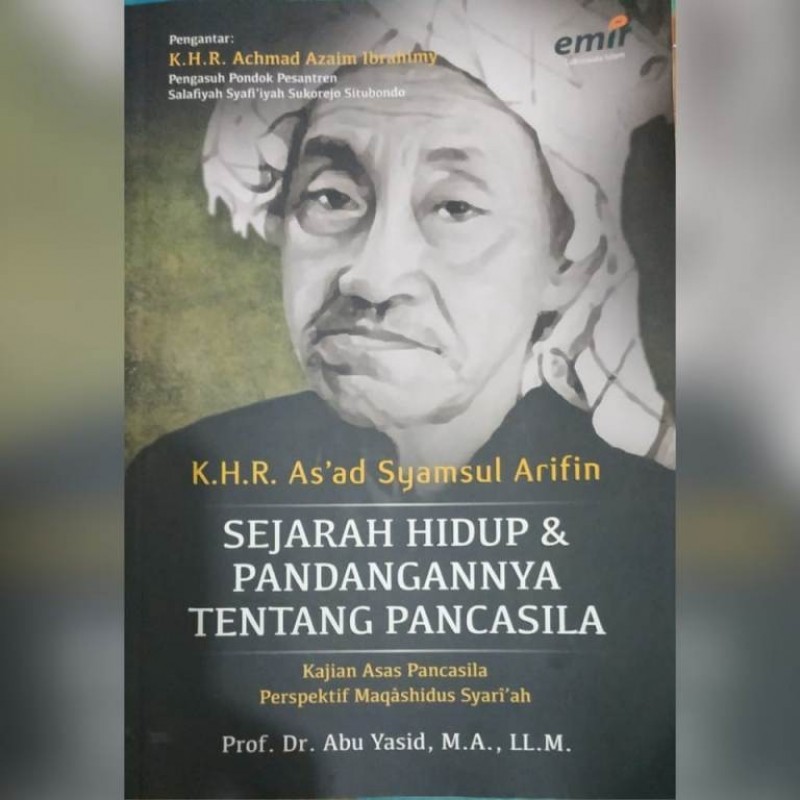Akibat “kampanye hitam” yang dikembangkan oleh gerakan trans-nasional Islam, sebagian umat kita tidak lagi mencintai Pancasila. Alasannya, Pancasila bukan ideologi Islam sehingga status normatifnya dianggap sebagai ideologi kafir. Diperlukan rumusan argumentasi Islam atas ideologi bangsa untuk mengonter “kampanye hitam” ini.
Yang terpapar tidak bisa dianggap remeh. Menurut survei LSI Denny JA, selama 13 tahun (2005-2018) terjadi penurunan dukungan terhadap Pancasila sebanyak 10% (dari 85,2% pada 2005 menjadi 75,3% pada 2018). Sedangkan terhadap ide NKRI Bersyariah, publik menaikkan dukungannya sebanyak 9%, dari 4,6% 2005 menjadi 13,2% pada 2018. Memang dukungan terhadap Pancasila masih lebih besar. Namun tren naik dan turunnya dukungan menunjukkan mana ide yang berkembang dan mana yang stagnan.
Survei Alvara Research Center pada 2017 menunjukkan hal serupa. Terdapat 15,5% kaum profesional yang sepakat Islam sebagai dasar negara, 16,8% di kalangan mahasiswa, 18,6% di pelajar dan 19,4% Aparatur Sipil Negara yang tidak mendukung Pancasila dasar negara. Semua populasi itu merindukan Islam sebagai dasar negara serta Khilafah sebagai bentuk negara. Tidak hanya mendukung, mereka juga siap berjihad untuk mewujudkan pandangan tersebut.
Apakah yang terjadi? Mengapa keselarasan Islam dan Pancasila yang lama terbina kini mulai runtuh? Argumen apa yang harus dibangun kembali, agar umat tidak salah dalam memahami ideologi bangsa yang sebenarnya mencerminkan nilai-nilai Ilahiah?
Diferensiasi, Bukan Separasi
Buku terbaru dari Kiai As’ad Said Ali, mantan Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) telah menjawab persoalan krusial ini. Di dalam buku bertajuk, Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa ini, Kiai As’ad menghadirkan kembali berbagai argumentasi Islam bagi peneguhan Pancasila sebagai ideologi terbaik bangsa. Tentu argumentasi yang dibangun khas kaum tradisionalis, berlandaskan khasanah fiqih dengan metodologi yang rumit.
Menurut beliau, hubungan antara Islam dan Pancasila berada pada ranah hubungan antara agama dan negara. Inilah mengapa pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo, 1983, para kiai menempatkan Pancasila sebagai “landasan konstitusi negara”, sedangkan Islam sebagai akidah. Dengan penempatan seperti ini, maka Pancasila bukanlah agama, tidak ingin menjadi agama dan tidak akan menggantikan agama.
Dengan mengutip pandangan Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa agama dan negara merupakan saudara kembar, dimana agama menjadi pondasi masyarakat, sedangkan negara menjadi penjaga. Maka hubungan Pancasila dan Islam juga seperti itu. Islam merupakan pondasi kehidupan masyarakat secara luas, sedangkan Pancasila menjadi dasar pengaturan masyarakat. Dalam rangka fungsi pengaturan ini, Pancasila menjaga nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat (hlm. 23).
Pandangan seperti ini sempat hadir di sidang perumusan Pancasila di Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) 1945. Adalah Bung Hatta yang mengajukan pandangan tersebut untuk mengritik dikotomi agama dan negara yang berkembang di dalam sidang. Menurut Bung Hatta, pembenturan agama dan negara memiliki bias persoalan Eropa. Sebab di Eropa menjelang Abad Pencerahan, terjadi pergulatan antara otoritas agama dan otoritas negara. Keduanya berkontestasi karena masing-masing memiliki otoritas politik.
Di dalam Islam, kontestasi seperti itu tidak terjadi. Islam bukan lembaga politik. Ia merupakan nilai-nilai religius yang hidup di masyarakat, tanpa tergantung dengan negara. Jika merujuk pada konsep Sunni, penegakan syariah berada di ruang publik di bawah otoritas ulama. Sedangkan negara menjadi wewenang Sultan. Keabsahan pelaksanaan syariah berada di tangan keilmuan ulama, meskipun pra-kondisi legitimasinya di tangan Sultan. Inilah mengapa pada 1954, para ulama kita melegitimasi Sukarno dan seluruh Presiden Indonesia sebagai waly al-amri al-dlaruri bi al-syaukah. Pemimpin Islam (dalam keadaan darurat) namun berwenang melegalkan syariah. Meskipun syariah membutuhkan legalisasi Presiden, namun pelaksanannya tetap di tangan ulama, bukan Presiden.
Hal ini yang membuat hubungan agama dan negara menganut pola diferensiasi, bukan separasi atau integrasi. Pinjam istilah Bung Hatta, Indonesia menganut pola pembedaan antara “urusan agama” dan “urusan negara”. Bukan pemisahan maupun penyatuan agama dan negara.
Argumentasi Fiqih
Dalam kerangka pola diferensiatif ini, Kiai As’ad lalu membangun argumentasi keselarasan Islam dan Pancasila melalui metode fiqih. Hal ini ia lakukan dalam beberapa langkah.
Pertama, meletakkan persoalan Pancasila di wilayah hukum, bukan akidah. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (Grundnorm), letaknya di dalam Islam tidak berada di ranah teologis, melainkan yuridis. Inilah yang membuatnya mengkaji Pancasila melalui fiqih, bukan teologi sebagaimana kaum Islamis yang membenturkan dasar negara dengan akidah.
Pada ranah hukum Islam ini, letak Pancasila berada di ranah filsafat hukum (ushul fiqh) yang lalu melahirkan kaidah hukum (qawa’idul fiqh). Mengapa? Karena Pancasila merupakan filsafat (meta) hukum, pengkajiannya juga harus melalui filsafat hukum Islam. Dalam konteks ushul fiqh, pengkajian Pancasila masuk pada wilayah ijtihad penerapan hukum (ijtihad tathbiqi). Penerapan ini berangkat dari penafsiran atas al-Qur’an dan hadist, lalu ijma’ dan qiyas, disempurnakan dengan penggunaan prinsip kemaslahatan (al-maslahah), kebaikan (istihsan) dan tradisi (‘urf). Artinya selain mengacu pada al-Qur’an dan hadist, penerapan syariah haruslah melibatkan prinsip kemaslahatan, kebaikan di masyarakat serta tradisi yang berkembang (hlm. 7-10).
Beberapa kaidah fiqih menjadi pijakan. Misalnya, “Dimana ada maslahat di situ ada syariat, dan dimana ada syariat di situ ada maslahat” (haitsuma kanat al-mashlahah fatsamma syar’u Allah, wa haitsuma kana syar’u Allah fatsamma al-mashlahah). Atau kaidah, “Adat bisa menjadi landasan hukum” (al-‘adah muhakkamah). Ini artinya, kemaslahatan dan adat yang berkembang di masyarakat harus pula menjadi pijakan penerapan hukum. Salah satu bentuk kemaslahatan, kebaikan dan adat kebangsaan kita ialah Pancasila. Dengan demikian, penerapan syariah justru bisa dilakukan melalui prinsip kemaslahatan di dalam Pancasila.
Kedua, persoalan Pancasila berada di ranah hukum ijtihadi (ahkam ijtihadiyah) yang berada di rumpun hukum praktis (ahkam ‘amaliyah). Bukan di rumpun hukum pasti (ahkam qat’iyah) yang berisi prinsip-prinsip teologis seperti termaktub dalam Rukun Iman. Membandingkan persoalan hukum praktis ijtihadiyah dengan hukum teologis qath’iyah tentu tidak apple to apple. Hal ini terjadi karena persoalan bentuk dan sistem kenegaraan merupakan wilayah yang dibuka Islam untuk dieksplorasi oleh rasionalitas. Dalam konteks ini, Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip politiknya saja seperti; kesetaraan (al-musawah), keadilan (al-‘adalah), musyawarah (al-syura), kebebasan (al-hurriyyah) dan pengawasan rakyat (riqabah al-ummah) (hlm. 83-85).
Berdasarkan argumentasi fiqhiyah ini, pembenturan antara Islam dan Pancasila menjadi gugur. Sebab bukannya berbenturan, Pancasila justru menjadi saluran terbaik bagi nilai-nilai Islam untuk membumi di masyarakat bangsa. Pembenturan Islam dan Pancasila bukan hanya bertentangan dengan kerahmatan Islam. Lebih dari itu, ia menunjukkan sifat anti-metodologi di dalam beragama. Kekuatan metodologi inilah yang menjadi kekayaan khasanah pesantren sebagaimana dielaborasi dengan baik oleh buku ini.
Oleh karena itu, buku ini menjadi salah satu buku terbaik tentang Islam dan Pancasila yang lahir dari khasanah “orang pesantren”. Sebelumnya (2009), Kiai As’ad menerbitkan buku, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Sebuah buku yang mengupas “pengalaman-pengamalan Pancasila” baik oleh Orde Lama maupun Orde Baru. Dengan menulis buku Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa ini, Kiai As’ad menyempurnakan diri sebagai seorang Nahdliyin Pancasilais, yang menghayati Pancasila tidak hanya sebagai ideologi bangsa, melainkan sebagai panggilan iman.
Peresensi adalah Syaiful Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila. Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017-2018).
Identitas Buku
Judul Buku: Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa
Penulis: As’ad Said Ali
Tebal: 265 halaman
Terbit: September 2019 (cetakan pertama)
Penerbit: LP3ES