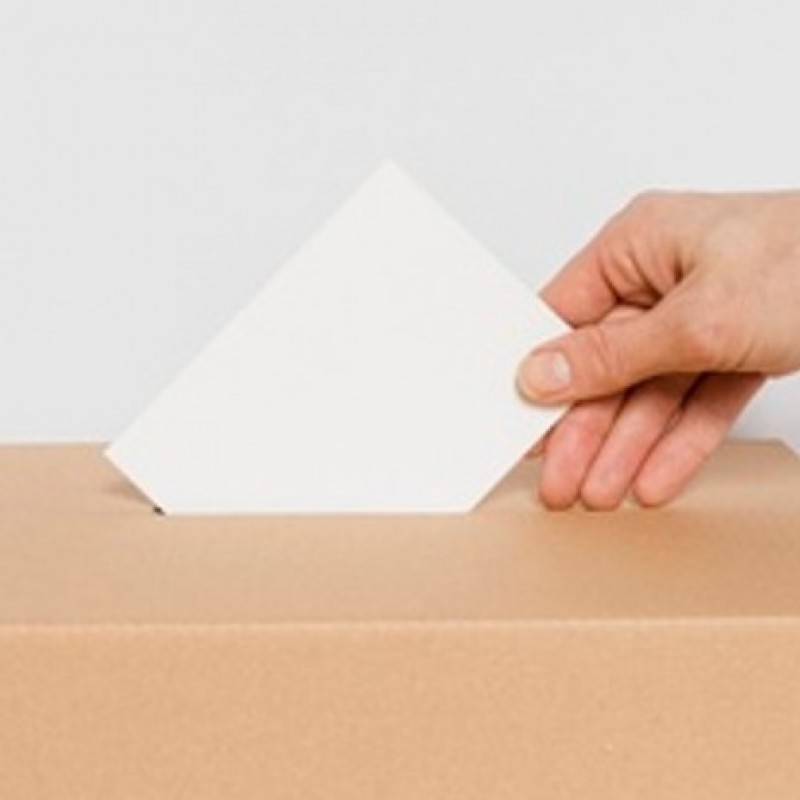Maraknya Calon Tunggal dan Turunnya Kualitas Demokrasi Kita
NU Online · Ahad, 13 Desember 2020 | 13:00 WIB

Fenomena calon tunggal sangat terkait dengan dinasti politik, yang membuat "demokrasi" terpusat pada jaringan politik keluarga.
Achmad Mukafi Niam
Penulis
Pilkada 2020 diikuti oleh 25 calon tunggal yang bertarung melawan kotak kosong. Terdapat tren peningkatan calon tunggal dari waktu ke waktu. Pada pilkada 2015, hanya ada 3 calon tunggal, lalu naik menjadi 9 daerah pada 2017, selanjutnya menjadi 16 pada 2018, dan 25 daerah pada 2020. Data sirekap KPU 2020 menunjukkan 24 dari 25 calon tunggal menang, sementara satu calon tunggal di Pegunungan Arfak belum masuk data sirekap KPU. Dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi ini, strategi calon tunggal besar kemungkinan akan semakin banyak digunakan dalam ajang pilkada di masa mendatang.
Calon tunggal dapat terjadi karena dua faktor, pertama karena profil yang populer sehingga calon lain merasa peluangnya untuk menang dalam pertarungan menjadi rendah. Calon populer ini biasanya petahana yang sukses membangun daerahnya. Akhirnya tidak ada calon lain yang siap maju. Kedua, faktor kesengajaan dengan memborong dukungan dari partai politik sehingga menutup peluang calon lain maju dari jalur partai politik. Di sisi lain, untuk maju dari jalur independen juga cukup berat karena adanya persyaratan dukungan antara 6,5-10 persen dari jumlah pemilih.
Fenomena calon tunggal yang dengan sengaja direkayasa berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Rakyat diminta untuk memilih calon yang ada atau kotak kosong. Dalam mekanisme seperti ini, seolah-olah rakyat memiliki pilihan, tetapi sesungguhnya pilihan yang ada bersifat semu karena calon yang disodorkan merupakan hasil rekayasa. Calon yang ada belum tentu figur yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin dan dengan kampanye masif, maka kemenangan mudah diraih.
Fenomena calon tunggal sangat terkait dengan dinasti politik, yaitu praktik politik dengan cara menguasai jabatan politik kepada keluarga dan kerabat dekat. Politik dinasti sangat terkait dengan dinasti partai di mana partai-partai tertentu dikuasai oleh keluarga. Dari situlah, elit partai menentukan calon-calon yang akan menduduki jabatan politik, dari bupati, walikota, gubernur sampai dengan anggota parlemen.
Dalam situasi seperti ini, maka kader partai yang sudah mengabdi puluhan tahun dan tidak memiliki modal finansial sulit untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan. Tokoh masyarakat yang tidak berpartai, lebih kecil lagi peluangnya untuk menjadi pemimpin. Dalam pilkada 2020 ini, sejumlah calon tunggal yang memiliki koneksi politik merupakan anak muda yang sama sekali belum memiliki pengalaman politik. Memimpin sebuah daerah bukanlah tempat untuk sekedar coba-coba atau tahap belajar karena menyangkut nasib ratusan ribu, bahkan jutaan rakyat.
Dinasti politik menyebabkan sulitnya mekanisme kontrol pemerintahan. Jika dalam satu keluarga besar ada yang menjadi bupati atau walikota sementara kerabatnya menjadi anggota DPRD, maka sulit untuk mengharapkan anggota DPRD tersebut bersikap kritis terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh keluarganya. Atau ketika pemimpin daerah terpilih memiliki koneksi dengan orang kuat di pusat kekuasaan di Jakarta, maka DPRD akan segan untuk melakukan kontrol dengan baik karena bagaimanapun juga, kebijakan partai di tingkat daerah akan mengikuti perintah pusat.
Dinasti politik bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, negara yang menjadi kampium demokrasi, dikenal dinasti Kennedy dan dinasti Bush. Banyak anggota keluarga tersebut yang sukses berkarier politik. Di India dikenal dinasti Nehru Gandhi.Fenomena serupa banyak terjadi di negara lainnya. Jika terjadi di negara maju, hal bisa saja hal tersebut karena para anggota keluarga memiliki kualifikasi yang memadai, namun di negara-negara berkembang, mungkin fenomenanya tak jauh berbeda dengan Indonesia.
Politik dinasti sebagai salah satu penyebab maraknya calon tunggal pernah diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang melarang adanya hubungan kekerabatan dengan petahana. Namun, mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut karena melanggar hak konstitusi, yaitu hak untuk dipilih. Pelarangan ini menimbulkan diskriminasi karena adanya perbedaan perlakuan akibat kelahiran dan kekerabatan.
Upaya mengatur cengkeraman politik dinasti perlu terus diupayakan, namun tentunya dalam bentuk UU yang tidak melanggar hak lainnya. Misalnya dengan menerapkan aturan minimal 60 atau 70 persen kemenangan sebagai syarat minimal terpilih. Umumnya, calon populer yang biasanya merupakan petahana yang berhasil membangun daerahnya akan mendapatkan dukungan yang tinggi, bisa 80-90 persen. Namun untuk calon-calon tunggal hasil rekayasa, lebih sulit untuk mendapat dukungan yang tinggi karena sebagian dari mereka bahkan belum mengenal dunia politik. Jika batasannya hanya 50 persen plus satu suara, hal tersebut mudah dicapai.
Hal lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi politik. Dalam masyarakat yang memiliki literasi politik yang rendah, mereka mudah dimanipulasi dengan ketokohan dari pemimpin dinasti seolah-olah anggota keluarga lain memiliki kualifikasi yang sama. Masyarakat perlu didorong untuk memperhatikan kapasitas pribadi seorang calon. Pada daerah-daerah yang cukup maju di mana literasi politik lebih tinggi, dinamika politik lebih hidup sehingga upaya untuk memunculkan calon tunggal lebih kecil peluangnya.
Demokrasi merupakan proses pencarian pemimpin terbaik. Jangan sampai kita sebagai rakyat lengah terhadap upaya manipulasi proses-proses perekrutan pemimpin tersebut karena rakyat juga yang akhirnya menanggung akibatnya. (Achmad Mukafi Niam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
4
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua