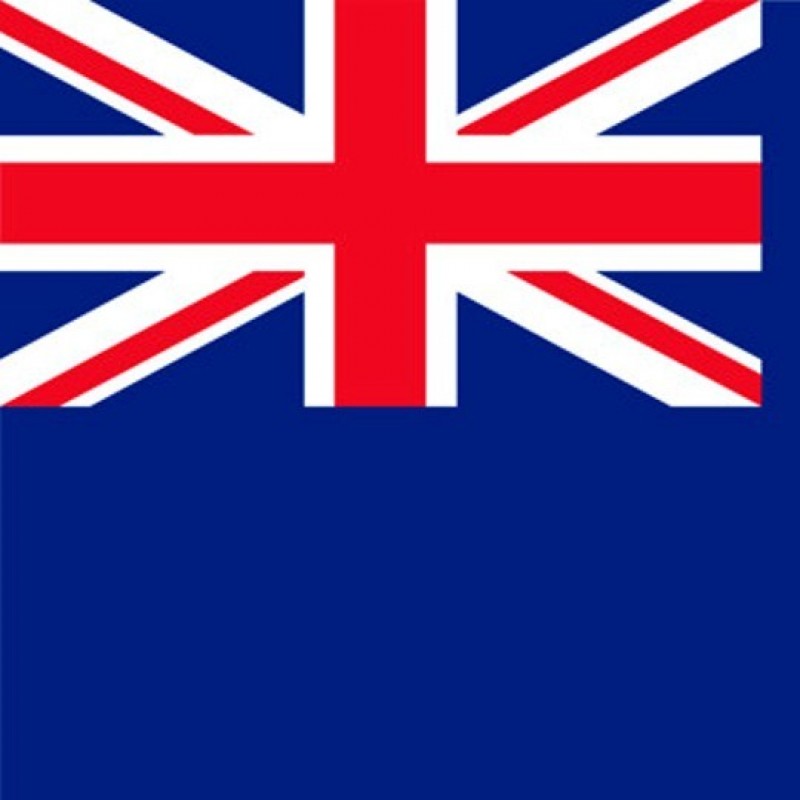Oleh Syihabuddin Qalyubi
KHA Wahab Muhsin (1924 M – 2000 M) kiai karismatik dari Sukahideng Tasikmalaya, memimpin Pondok Pesantren Sukahideng Sukarame Tasikmalaya sejak tahun 1945 hingga tahun 2000. Pesantren yang didirikan ayahandanya KHZ Muhsin pada tahun 1922. Pesantren ini sekarang dipimpin putra sulungnya, Prof. Dr. KH Fuad Wahab.
Keilmuan KHA Wahab Muhsin sangat diakui para ajengan di tatar Tasikmalaya, terutama dalam bidang balāgah dan usul fiqih. Beliau pernah memberi kuliah di Perguruan Tinggi Islam Pondok Pesantren Al-Musadaddiyah Garut dan Institut Agama Islam Cipasung Tasikmlaya dalam kedua bidang keilmuan di atas.
Tidak ada satu informasi pun dalam buku sejarah yang menceritakan keterlibatan almaghfurlah dalam perjuangan revolusi, karena ketawadluan yang melandasi kehidupannya, beliau tidak mau dikultus dan dipuja sebagai seorang pahlawan.
Hanya saja, almarhumah Hj Siti Sofiyah (isteri almaghfurlah) pernah bercerita di depan putra-putri dan cucu-cucunya, bahwa abah (panggilan untuk KHA Wahab Muhsin) pada zaman perlawanan KHZ Musthafa beserta para santrinya di pesantren Sukamanah terhadap tirani Jepang — (dan abah adalah salah seorang santrinya yang telah dimukimkan ke Sukahideng)–, abah pergi ke medan tempur bersama KH Ma’mur (Pimpinan Ponpes Al-Ma’mur Rancabolang yang masih termasuk murid KHZ Musthafa).
KH Ma'mur gugur sebagai salah seorang syuhada, sedangkan abah tertangkap tentara Jepang dan dijebloskan ke penjara Kota Tasikmalaya, dan diperlakukan sebagai seorang yang berontak kepada Jepang. Selama di dalam penjara beliau sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, antara lain, kepala abah pernah dipakai untuk memadamkan api rokok salah seorang sipir penjara, mata beliau dikucuri air kencing yang dicampur dengan kapur, bahkan di punggung beliau masih ada bekas luka penyiksaan di penjara Jepang tersebut. Kisah ini tidak pernah keluar langsung dari ucapan beliau baik sewaktu pengajian, perkuliahan ataupun di tempat lainnya.
Ibu Hj Ai Maemunah, putri kedua almaghfurlah, mengisahkan pengalamannya sewaktu kecil, ia sering disuruh beliau memijitnya. Sewaktu memijit terlihat di punggung abah ada dua bentuk lebam seperti bekas pukulan benda keras. Ia pun bertanya:
“Abah bekas apa di punggung ini?”
“Itu, sewaktu abah di Sukamiskin.” Demikian jawaban almaghfurlah singkat. tanpa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di Sukamiskin itu.
Dalam bidang organisasi, beliau pernah menduduki jabatan Rais Syuriah NU Cabang Tasikmalaya dan Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya. Di antara fatwanya yang monumental adalah tentang KB (Keluarga Berencana) yang pada waktu itu dilaksanakan secara paksa. Jika ada warga Tasik yang enggan melaksanakan KB maka yang bersangkutan harus berhadapan dengan yang berwajib. Sehingga muncullah kegelisahan umat Islam terutama di pedesaan.
Dalam kondisi seperti itu, muncullah fatwa tentang KB. Bahwa KB itu bi manzalah al-dawā (sama kedudukannya dengan obat). Hanya orang sakitlah yang memerlukan obat, sedangkan orang sehat tidak membutuhkannya. Orang miskin dalam ekonomi dan dalam pendidikan digolongkan sebagai “orang sakit”, bagi mereka dianjurkan ikut program KB, sedangkan orang kaya, alim, terpandang dan terpelajar tidak dianjurkan untuk ikut program KB, karena kelompok ini termasuk golongan “orang sehat”. Fatwa ini sangat memukul kebijakan pemerintahan Orde Baru yang kala itu tampaknya sedang mengejar target.
Relasi dengan santrinya sangat akrab sekali, sehingga beliau memosisikan diri di depan para santrinya sebagai kakak mereka, beliau biasa dipanggil akang (artinya kakak atau abang), bukan mama atau pak ajengan sebagaimana panggilan yang lazim dipakai di tatar Priangan Timur. Namun lambat laun, sesuai dengan pekembangan jaman para santri akhirnya memanggilnya bapak atau pak ajengan.
Dalam proses pembelajaran di pesantren beliau sering mengajarkan nadhoman-nadhoman (lagu-lagu religius) yang berupa bait-bait terjemahan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Sunda, agar mudah dipahami oleh santri terutama masyarakat yang membutuhkan bimbingan sambil dinyanyikan, supaya disenangi dan mudah dihafal. Tampaknya beliau mempunyai aliran darah seni. Konon lagu Indonesia Raya pun pernah diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab.
Di samping itu, beliau sering memberikan nasihat dan doa-doa yang seyogyanya diamalkan oleh para santrinya, terutama setelah melaksanakan shalat wajib. Kumpulan doa atau wirid ini saya namai pusaka. Dinamai pusaka karena termasuk peninggalan yang harus dipelihara keberadaannya dan dilestarikan. Setelah dipelajari secara mendalam ternyata pusaka ini mengandung informasi yang sangat luas, bisa dijadikan pedoman dan motivasi untuk menghadapi berbagai keadaan termasuk dalam menghadapi virus korona yang sedang mewabah sekarang ini. (Bersambung)
Penulis adalah Guru Besar Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta