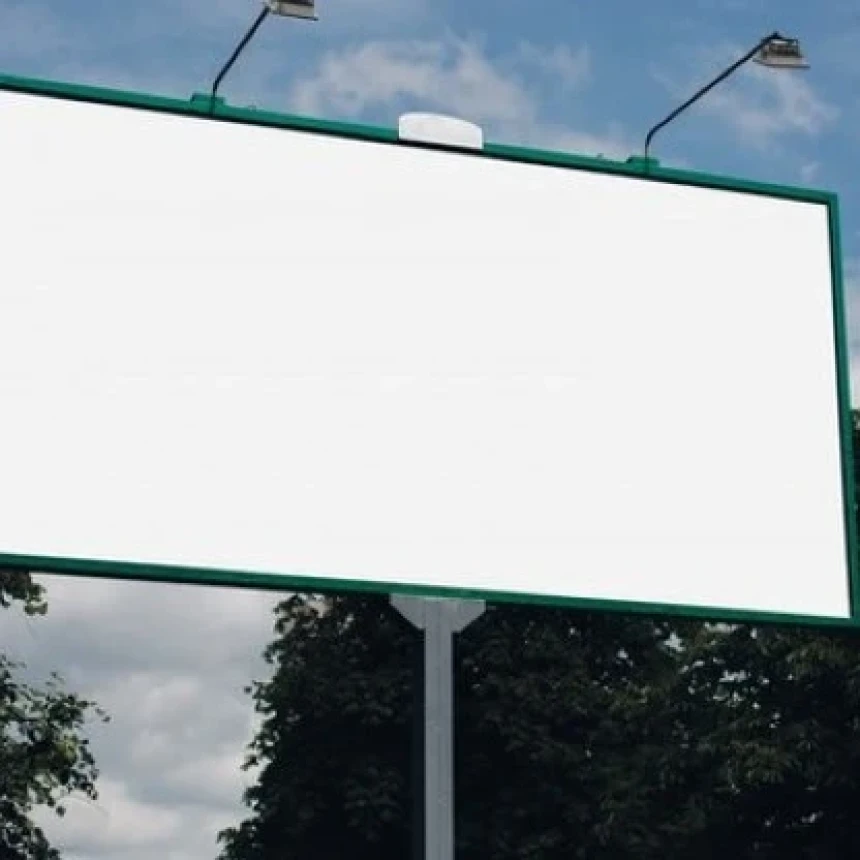Cerpen: Indah Noviariesta
Gadis remaja itu duduk termenung di bangku panjang di serambi kantor kelurahan. Beberapa orang yang memerhatikannya mendekat. Di pelipis kirinya tergores luka dengan darah yang sudah mengering. Ia melepas jam tangan yang sudah mati, lalu menyimpannya dalam genggaman.
Mukanya memelas, rambutnya kusut masai, dan kakinya masih bersimbah lumpur basah hingga lutut. Tak seorang pun berani bertanya di manakah keluarganya, atau sekadar bertanya siapakah orang tuanya.
Ibu petugas kelurahan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Adik ke sini sendirian?"
Gadis remaja itu mengangkat kepalanya pelan, “Ya, semuanya terendam lumpur ketika longsor itu datang tadi malam.”
Baca Juga
Cerpen: Perempuan Kedua
“Semuanya?” tanya petugas kelurahan.
“Ya, semua keluarga saya, termasuk ibu dan ayah saya.”
"Kejadiannya jam berapa?”
Ia terdiam seraya melepas jam tangan di genggamannya yang sudah mati menunjukkan pukul 03.00 pagi. "Mula-mula terdengar ledakan dan gemuruh dari atas bukit, lalu tiba-tiba longsor itu datang bersama air sungai yang meluap menjebol tanggul. Tak lama kemudian, tiba-tiba longsor itu menghantam dan menenggelamkan puluhan rumah di kampung kami."
Jam tangan hitam itu ditatapnya erat-erat. Jarum jamnya berhenti di angka 03.00 tepat. Berarti sekitar jam itulah si gadis terseret banjir dan lumpur, sampai kemudian berhasil diselamatkan oleh regu penolong. “Jam ini pemberian ayah saya, ketika saya naik ke kelas dua SMP. Ibu yang menyuruh ayah membelikan jam ini untuk saya, tapi sekarang keduanya sudah tidak ada,” katanya dengan nada memelas.
Beberapa orang mendekatinya, lalu gadis itu melanjutkan, "Setelah beberapa hari memilikinya, saya menganggap jam tangan ini biasa saja. Jarang saya pakai, bahkan saya menganggapnya tak beda jauh dengan benda-benda lain di kamar saya. Tapi, setelah peristiwa longsor ini, barangkali inilah satu-satunya peninggalan orang tua saya yang paling berharga."
Beberapa petugas kelurahan mendekat, seraya ikut mendengarkan gadis remaja itu menggumam, "Minggu lalu, saya menganggapnya sama dengan pinsil atau bolpoin yang saya sukai, atau seperti piring atau gelas kesukaan saya untuk minum susu. Tapi coba lihat, angka-angkanya berwarna biru, terlihat dengan jelas seperti menyala. Jarum penunjuknya mungkin terbuat dari besi, meski kelihatan sudah aus dan rusak. Tapi ia tetap menempel kokoh di tempatnya semula, meskipun ia sudah tak bergerak lagi.”
Dengan gerak memutar, perlahan ia mengusap bagian kaca jam dengan ujung bajunya yang kumal. “Biasanya kalau malam hari tak pernah saya pakai, tapi entah mengapa, tadi malam saya lupa melepasnya hingga terbawa tidur?”
Orang-orang yang duduk di bangku panjang, mulai disinari matahari pagi, ikut memperhatikan jam tangan yang digenggam gadis itu. Seseorang memberanikan diri bertanya, “Apakah benar Adik sudah enggak punya siapa-siapa lagi, kecuali jam tangan itu?”
“Ya, ya,” jawab gadis remaja itu, “semuanya sudah musnah. Tak ada yang tersisa. Sekarang saya hanya sendirian bersama jam tangan dan pakaian lusuh yang menempel di tubuh saya ini."
"Tapi untuk apa jam tangan yang sudah rusak itu,” seloroh salah seorang dari mereka.
“Ya, memang dia sudah rusak, tak berfungsi lagi, tetapi jam ini terlihat masih baru, tetap utuh, hanya jarum jamnya yang sudah berhenti.”
“Tapi, untuk apa?”
Gadis itu memakai jam tangan di pergelangan kiri, lalu menunjukkannya pada orang-orang, “Lihat, lihat… saya harus menjelaskan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, sejak pagi tadi orang-orang bertanya, termasuk para wartawan yang datang masih bertanya-tanya, jam berapakah kejadian banjir dan longsor itu datang, lihat… jarum jam ini menunjukkan angka yang tak mungkin membohongi kita semua….”
“Apakah ada hubungannya jarum jam yang berhenti itu, dengan peristiwa longsor semalam?” tanya seorang kakek tua. “Jika ada bom atau dinamit yang meledak di sekitar kita, saya percaya kalau jam tangan akan berhenti karena tekanan dari ledakan itu, tapi kalau kejadian itu berupa longsor?”
“Tapi kenapa sampai terjadi adanya ledakan di atas bukit, sebelum terjadinya longsor?” protes sang gadis seketika. “Ataukah jam saya terhenti tepat ketika terjadinya ledakan itu?”
Semuanya terdiam dengan tatapan bertanya-tanya.
Kakek tua itu menatap jam tangan yang dikenakan sang gadis bagaikan menatap batu jimat yang mengandung kesaktian.
“Mungkin saja tak ada hubungannya, Kakek,” tambah gadis itu, “atau mungkin juga ada hubungannya. Mengapa tepat jam 03.00 peristiwa ini terjadi, bukan jam tiga lewat sembilan menit atau kurang tujuh menit misalnya? Saya tidak bermaksud menghubung-hubungkan sesuatu, tapi yang saya herankan mengapa tepat sekali jam 03.00? Ada apa dengan semuanya ini?”
Kakek tua itu menatap kepada yang lainnya, namun mereka telah mengalihkan pandangan darinya.
“Biasanya, sekitar jam 03.00, meskipun tidak tepat, bisa kurang atau lebih, perut saya merasa lapar lalu melangkah menuju kulkas di dapur untuk menghabiskan susu yang baru setengahnya saya minum. Kadang saya berjumpa dengan ayah yang juga mengambil seiris roti untuk didorong ke lambungnya dengan air putih. Selalu saja sekitar jam tiga, bisa kurang bisa lebih, tapi kenapa kejadian longsor ini persis jam 03.00, apakah ada di antara kalian yang bisa menjawab ini?”
Semuanya diam terpaku, sebagian lain bersitatap dan menggelengkan kepalanya. Kemudian lanjut si gadis, “Sesekali saya mendengar Ibu melangkah pelan menuju kulkas untuk meminum air mineral yang disimpannya di bagian bawah kulkas. Biarpun suara pintu kulkas terdengar berderit pelan, biasanya saya segera menyusul ke dapur, karena merasa nyaman untuk meminum susu ditemani Ibu. Ketika kami menatap jam dinding, selalu saja antara jam tiga kurang ataupun lebih. Hampir tak pernah saya melihat jam tiga tepat seperti pada kejadian ledakan ini,” gadis itu kembali menatap jam tangannya.
“Ayo, kembali tidur ke kamar. Nanti kamu kesiangan berangkat sekolah’, kata-kata seperti itu yang selalu Ibu ucapkan. Tidak kurang tidak lebih. Kadang ia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya karena merasa dingin. Kadang juga membunyikan setiap jari kakinya satu persatu, seperti suara saklar yang dipencet. Ketika saya sudah menuju kamar, ia akan kembali mematikan lampu dapur sebelum kembali tidur bersama Ayah.
Selalu saja seperti itu sekitar jam tiga malam. Bagi saya, hal itu seperti rutinitas kebiasaan keluarga kami. Sesekali saya merengek lapar, karena malam harinya malas untuk makan. Lalu, Ibu pun memasakkan mie rebus dicampur telor, kemudian disodorkan ke meja, lalu menyuruh saya sabar menunggu sampai mie itu tidak lagi panas. Ibu akan duduk bersama saya, menyuruh makan hingga habis, hingga saya merasa kenyang. Setelah itu, Ibu mengembalikan mangkuk mie, dan saya mendengar suara mendenting pelan, seperti suara mangkuk yang beradu dengan gelas atau piring. Selalu saja seperti itu setiap hari. Dan seperti biasanya, selalu saja sekitar jam tiga pagi, bisa kurang dan bisa juga lebih.”
Semuanya masih mendengar dalam sunyi. Untuk beberapa saat, kesunyian itu menyelimuti suasana di sekitar teras kelurahan desa. Kemudian seseorang menegur si gadis dengan suara berbisik, “Lalu, jam tangan itu mau kamu apakan, Dik?”
Gadis remaja itu tidak menjawab, masih duduk terkesima menatap jarum jamnya. "Saya tidak tahu, apa yang dilakukan keluarga-keluarga lainnya sekitar jam tiga pagi. Tapi ayah saya, kadang terbangun sendirian sekitar jam tiga pada malam Jumat, seperti melangkah mengendap-endap, tanpa alas kaki. Sesekali saya mengintipnya ketika menuju pintu kamar mandi untuk kembali ke ruang tengah. Nampaknya, Ayah mengambil sejadah dan melakukan solat tahajud sendirian sekitar jam tiga pagi, bisa kurang atau lebih. Kadang ia duduk dengan khusuk sambil berdoa hingga jam empat pagi. Kadang saya mencoba untuk menguping apa-apa yang beliau doakan, tapi lamat-lamat suaranya terdengar pelan, agar Tuhan memberikan keselamatan bagi kami, baik di dunia maupun di akhirat. Saya yakin, sekarang ia sudah merasa damai dan bahagia di negeri akhirat, meski kadang saya bertanya-tanya, bisakah dia merasa bahagia di akhirat sana, tanpa kehadiran saya sebagai anak satu-satunya.”
Gadis itu kembali menatap jam tangannya. Sebagian masih memandang dengan rasa iba. Kata-kata terakhir yang disampaikan gadis remaja itu memecah kesunyian di ruangan teras kelurahan itu. Ia menyatakan dirinya melihat bulatan putih di sekitar jam tangannya, hingga menutupi jarum-jarumnya. Bulatan putih itu menyiratkan suasana sejuk, asri dan rindang. Dihiasi sungai yang mengalir jernih, dengan rumput-rumput dan pohon-pohon bunga yang indah semerbak.
Sambil menatap jam tangannya itu, tiba-tiba ia tersenyum lembut.
“Saya melihat kedua orang tua saya sedang duduk di balai-balai dengan pemandangannya yang indah. Saya melihat Ibu sedang memetik buah dan memberikannya pada Ayah, tapi… buah apakah itu… seperti buah mangga? Bukankah ia sering melarang saya memakan mangga mentah di pagi hari? Tapi jam berapakah mereka menyantap buah mangga itu? Apakah masih mengkal, ataukah sudah matang? Jam berapakah itu? Kenapa Ayah tak lagi memakai jam tangan yang selalu ia kenakan di lengan kanannya sebelum berangkat kerja? Tapi, kenapa di tempat yang indah itu, tak ada seorang pun yang mengenakan jam tangan?”
Sebagian orang berpaling dan menganggap si gadis sedang mengigau dan menggumam. Tapi, seorang nenek berusia 60-an mendekat dan melingkarkan tangan kanannya ke bahu si gadis, “Tenanglah, Nak, suatu saat nanti kamu akan kembali berkumpul bersama kedua orang tuamu di surga. Semua yang kamu butuhkan akan disediakan oleh Tuhan. Di tempat itu, kamu akan berkumpul dengan semua orang yang kamu cintai di dunia ini.”
“Tapi, kenapa tidak seorang pun yang mengenakan jam tangan, Nek?”
Nenek itu menerawang ke langit, “Saya kira, sudah tidak ada lagi jam tangan di tempat itu.”
Bulatan putih pada jam tangannya seakan memudar pelan-pelan. Ia kembali menatap jarum jamnya yang terhenti di pukul 03.00. Nenek tua itu kembali menenangkannya, sambil tersenyum lembut, “Tenang saja, Nak, Allah Maha Penyayang. Sekarang kamu tinggal bersama Nenek, tenang saja, nanti jam tanganmu bisa diperbaiki… atau nanti Nenek akan belikan jam tangan yang baru….”
Indah Noviariesta, cerpenis dan peneliti sastra milenial Indonesia, alumnus Untirta Banten, menulis prosa dan esai di berbagai media nasional luring dan daring.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua