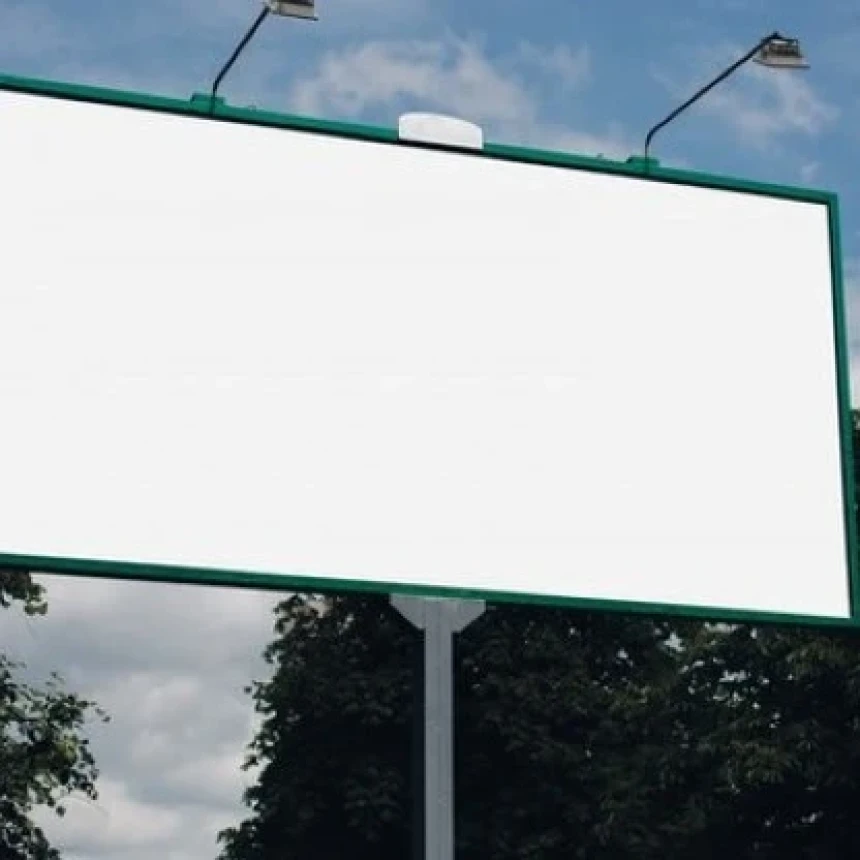Malik Ibnu Zaman
Kontributor
Selepas tamat Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Pekalongan, aku merantau ke Batavia. Tujuannya untuk melanjutkan pendidikan di Algemeene Middelbare School (AMS). Namun, hanya setahun saja, sebab kedatangan Jepang. Mereka menutup semua jenis dan jenjang sekolah. Ketika Jepang akhirnya membuka kembali sekolah setelah berbulan-bulan lamanya, aku tidak semangat lagi untuk melanjutkan sekolah. Selama sekolah tutup aku lebih banyak menghabiskan waktuku membantu paman berdagang buah di Pasar Senen.
Lalu ketika ada pengumuman seleksi pasukan Pembela Tanah Air (PETA), aku ikut mendaftar. Agak aneh memang, seorang pemuda yang penakut dalam segala hal mendaftar PETA. Secara tidak langsung mengapa aku mendaftar PETA itu karena Saroh, temanku di AMS yang rumahnya di Kebon Kosong, Kemayoran. Bapaknya mantan prajurit KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger). Ya, aku menyukai Saroh. Pikirku saat itu dengan masuk PETA dapat dengan mudah mendapatkan Saroh.
Meskipun dengan niat yang bisa dikatakan tidak seratus persen, aku berhasil lolos seleksi, dan aku melakukan pendidikan di Bogor. Di pendidikan aku menjadi murid kesayangan Letnan Tanaka Shoici. Ketika suatu hari aku mengobrol dengannya, barulah aku tahu kalau ia memiliki adik yang seumuran denganku. Katanya wajah dan perawakannya mirip denganku. Ia sendiri tak tahu bagaimana kabar adiknya. Terakhir kali ia mendengar adiknya berada di Burma.
Kedekatanku dengan Letnan Tanaka membuat beberapa siswa memusuhiku. Mereka yang secara terang-terangan memusuhiku adalah Sastro dan Wignyo. Karena selalu bersama-sama, mereka mendapat julukan kiwa-tengen. Sekali mereka mengeroyokku di kamar mandi. Sebenarnya bisa saja melaporkan hal ini kepada instruktur. Namun, aku tidak melakukannya. Dua minggu setelah pendidikan, Sastro dan Wignyo ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi umum di Jatinegara dengan luka tebasan samurai pada perut. Kawan-kawannya mencurigai aku yang melakukannya. Hal ini membuat aku dijemput oleh Kempetai untuk diinterogasi. Aku pun dibebaskan, sebab tidak ada bukti jika aku pelakunya.
Baca Juga
Ibu Tak Mau Jadi Tuhan
Setelah menempuh pendidikan selama tiga bulan di Bogor, aku menjadi Shodanco (Komandan Peleton) di Jatinegara. Seminggu sekali aku menyempatkan untuk pulang ke rumah pamanku di Kebon Kosong, berjarak beberapa rumah saja dari rumah Saroh. Praktis setiap aku juga berkunjung ke rumah Saroh. Tetapi lebih sering ayahnya yang menemui diriku. Sebagai pensiunan KNIL dengan pangkat Sersan ia selalu membanggakan kesatuannya. Tampak jelas di matanya bendera merah putih biru.
“Kamu jangan main ke sana,” ujar pamanku.
"Kenapa?" tanyaku.
"Kamu suka Saroh?" tanya paman. Aku pun hanya diam.
Baca Juga
Ihwal Kejadian Longsor
"Sebaiknya kamu pendam perasaan itu jauh-jauh. Kamu tahu kalau keluarga mereka lebih Belanda dari Belanda itu sendiri. Sekarang saja mereka tidak menunjukkan itu karena ada Jepang," ungkap paman.
"Saroh sudah memiliki kekasih, sama-sama anak kolong. Dengar-dengar kekasihnya anak dari komandan ayahnya. Mereka sekarang mengungsi di Australia," timpal istri pamanku. Sejak mendengar omongan dari paman dan bibiku aku tak lagi mengunjungi rumah Saroh.
Beberapa bulan kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari kemudian, PETA dibubarkan. Pada 19 Agustus prajurit PETA melapor ke markas Jepang terdekat dan menyerahkan senjata mereka. Sebenarnya aku tidak masalah menyerahkan senjata, sebab tak sebutir peluru pun aku gunakan, dan tak setetes darah pun menempel di samuraiku. Tetapi aku merasa berat hati menyerahkan samurai pemberian Letnan Tanaka. Untungnya ketika aku menyerahkan senjata bersama dengan pletonku di markas Jepang Jatinegara, mereka mengembalikan samuraiku.
Tak lagi menjadi prajurit PETA, aku pun kembali membantu pamanku berjualan buah di Pasar Senen. Sebenarnya beberapa hari setelah proklamasi dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan banyak bekas prajurit PETA yang bergabung. "Kamu tidak mendaftar BKR?” tanya pamanku. "Enggak, BKR bukan tentara. Nanti sajalah kalau ada pendaftaran tentara,” jawabku.
Baca Juga
Gula, Teh dan Lingkaran Sesat
"Agak aneh memang, masa negara enggak punya tentara? Aku lihat kemarin di Tanjung Priok ramai orang-orang asing bersenjata turun dari kapal. Macam-macam orangnya, ada yang pakai semacam sorban di kepala. Lalu ada orang Inggris entah Belanda, atau barangkali keduanya," timpal Mang Sastro penjual ikan di samping lapak pamanku.
Barulah ketika ada maklumat pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) aku mendaftar. Aku mendapatkan pangkat Letnan dan ditempatkan di bagian Staf Umum TKR Jakarta Raya. Tetapi situasi di Jakarta tak menentu, rentetan tembakan, dentuman suara mortir terjadi siang dan malam. Setiap harinya ada saja mayat pejuang Indonesia, tentara Gurkha yang bergelimpangan di jalan-jalan. Situasi ini bukan hanya membuat pusing pihak Sekutu saja, tetapi juga republik. Sekutu mendesak pemerintah untuk mengatasi kekacauan itu.
“Yang di atas seperti tidak tahu saja bagaimana situasinya. Tidak semudah itu untuk menghentikan tembak-menembak, tentara, laskar kita belum terorganisir dengan baik. Masih sering bertindak sendiri-sendiri,” ujar Komandan TKR Jakarta Raya Mayor Moefreni pada rapat di markas dekat Pasar Senen.
Aku masih tinggal di rumah paman di Kebon Kosong. Setiap tengah malam selalu ada jeep-jeep parkir di depan rumah Saroh. Mereka baru pulang ketika menjelang Subuh. "Apa paman bilang, benar kan kalau Suro itu Londo Ireng?" ujar paman kepadaku ketika aku mengintip dari balik jendela. Pernah sekali aku bertemu dengan Saroh di Cikini, ia naik jeep bersama dengan seorang tentara berseragam Sekutu. Sore harinya ketika aku sedang berada di teras rumah, Saroh menghampiriku bersama dengan lelaki yang aku lihat bersamanya tadi siang.
Baca Juga
Cerita Pendek: Perjanjian Kedua Iblis
"Lama aku tak melihat engkau," sapa Saroh.
"Ya, sering pulang malam," aku menjawab singkat.
"Perkenalkan ini temanku, Brouwer."
"Wijaya," jawabku sambil mengayunkan tangan mengajaknya bersalaman. Ia menyambut tanganku, "Brouwer.”
Baca Juga
Kosongnya Langgar
"Belanda dan tentara?" tanyaku. Belum sempat Saroh menjawab Brouwer langsung memotong: "Sudah menjadi rahasia umum kalau Sekutu juga membonceng kami. Ya, saya berteman dengan Saroh sejak kecil, kedua orang tua kami berteman baik." Ingin saat itu aku berlari ke kamar, mengambil samuraiku, lalu menebas Brouwer. Tetapi aku berusaha untuk menenangkan diriku, jika aku nekat, maka keluarga pamanku yang akan menjadi korbannya. Melihat muka dan mataku yang merah padam, Saroh bergegas pamit.
Situasi di Jakarta semakin tidak menentu. Pemerintah menginstruksikan pejuang untuk menyingkir ke luar Jakarta. Markas TKR Jakarta Raya berpindah ke Cikampek. Aku merasa agak bosan berdiam di markas, sementara teman-temanku berjuang di Front Timur Jakarta. Bisa saja sebenarnya aku mengajukan ke markas untuk berangkat ke front, tetapi aku masih takut untuk mati, aku selalu pusing ketika mendengar dentuman bom, mortir. Kuping dan kepalaku serasa mau pecah. Atau barangkali aku takut untuk tidak bisa bertemu lagi dengan Saroh.
Di penghujung Desember, Mayor Moefreni memanggilku ke ruangannya. Ia menugaskan untuk masuk ke Jakarta dengan misi menghabisi nama-nama yang ada dalam sebuah daftar yang ia sodorkan di atas meja. Aku pun langsung mengernyitkan dahi. "Kamu tak perlu khawatir, akan ada satu orang yang menemani. Kamu pasti mengenalnya,” ujarnya.
"Masuk!" teriaknya. Dari pintu muncul seorang pria dengan langkah tegas dan tatapan tajam dengan muka putih. Ilyas, ia kawanku semasa pendidikan PETA di Bogor.
"Letnan Ilyas banyak menceritakan tentang kamu. Tak kusangka kalau kamu adalah murid kesayangan Letnan Tanaka. Dan kau pernah diajak olehnya untuk menghabisi mata-mata Sekutu yang menyamar menjadi prajurit PETA."
"Besok malam kalian akan berangkat masuk ke Jakarta lewat Cilincing. Sekarang kalian bisa istirahat dulu."
"Siap Mayor," sahut kami serempak.
Di luar aku mencecar pertanyaan kepada Ilyas, mengapa ia bisa tahu peristiwa beberapa tahun lalu. Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan cerita ini langsung dari Letnan Tanaka. "Aku bertemunya di Surabaya, ia menyampaikan salam kepadamu."
Baca Juga
Kutukan Sunan Amangkurat
"Sekarang ia di mana?" tanyaku. "Barangkali sudah sampai di Jepang."
Menjelang Subuh kami sudah berada di pusat Jakarta, kami bersembunyi di salah satu rumah yang menjadi mata-mata Republik di dekat Stasiun Kemayoran. "Kau sudah membaca nama-nama dalam daftar ini?" tanya Ilyas. "Belum," jawabku.
"Malam ini kita ke Kebon Kosong, Suro, seorang bekas KNIL berpangkat sersan," ujar Ilyas. Aku tercengang dengan hal tersebut. Tak salah lagi, Suro ayah Saroh, gadis yang aku cintai. Melihat perubahan mimik wajahku, Ilyas langsung bertanya penasaran. "Kau mengenalnya?"
"Dia tetangga pamanku, memang setiap malam rumahnya ramai oleh jeep-jeep Sekutu."
Baca Juga
Lembaran Cinta Kanjeng Nabi
"Terus apa yang membuatmu ragu? Jangan bilang dia punya anak gadis, lalu kau jatuh cinta kepada anaknya," kata Ilyas penuh selidik.
"Ya dia punya anak gadis, tetapi sudah punya pacar, Letnan Brouwer namanya. Aku dan Saroh hanya sebatas teman," jawabku singkat.
"Ouh Saroh namanya. Revolusi memang menumbalkan banyak orang, Bung. Dibunuh atau membunuh. Untuk kali ini biar aku saja yang melakukannya. Kau cukup mengawasi dari kejauhan saja."
Malam itu pada dini hari Suro masih berada di ruang tamu sehabis menerima kunjungan beberapa perwira KNIL Batalyon Anjing NICA. Ia merasa akan ada hal buruk yang datang. Suro pun memanggil istrinya lalu mengatakan jika terjadi suatu hal agar meminta bantuan kepada Brouwer.
Ilyas berjalan dengan santai mendekat ke arah rumah Suro dengan menggunakan seragam KNIL. Katanya ia mendapatkan seragam itu di dekat Stasiun Senen tadi siang. Sementara itu, aku dari kejauhan dengan penutup wajah dan kepala berwarna hitam, bersembunyi di balik pohon. Tangan kananku menggenggam samurai dengan erat.
Ilyas mengetuk pintu dengan nada keras tapi teratur, lalu menunggu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan sosok Suro muncul di ambang pintu, mengenakan sarung dan kaos oblong. Belum sempat Ilyas mengungkapkan maksud dan tujuannya, Suro langsung menghantaman wajah Ilyas.
Ilyas terjatuh ke belakang, dan Suro terus memukulnya dengan tinju penuh kemarahan. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, aku langsung bergegas maju, samurai di tanganku terangkat tinggi. Aku menebas di depan Suro dengan gerakan cepat dan tegas, membuat dirinya seketika roboh dengan luka menganga di leher. Keributan ini membuat Istri Suro dan Saroh yang baru memejamkan mata bangun dan berlari ke depan.
Aku berdiri di tempatku, samurai di tangan masih meneteskan darah. Dadaku naik turun karena nafas yang memburu, tapi pikiranku kosong. Istri Suro dan Saroh pun pingsan melihat orang yang mereka cintai tewas mengenaskan. Sebelum pingsan, Saroh sempat melihat cukup lama samuraiku. Ya, aku baru ingat bahwa pernah sekali sehabis pendidikan PETA di Bogor, aku memamerkan kepadanya samurai pemberian Letnan Tanaka ini.
Bergegas aku dan Ilyas lari di kegelapan malam Jakarta dan kembali ke rumah di dekat Stasiun Kemayoran.
Malik Ibnu Zaman, penulis kelahiran Tegal Jawa Tengah. Ia menulis sejumlah cerpen, puisi, resensi, dan esai yang tersebar di beberapa media online.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua