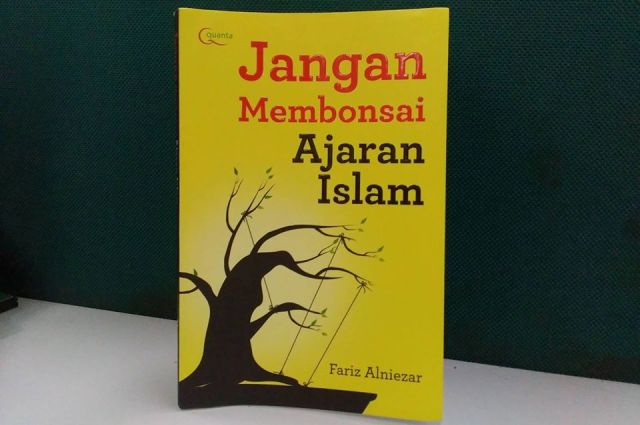Agama merupakan jalan hidup (the way of life) setiap manusia yang menginginkan koneksi dengan Tuhan. Koneksi di sini bukan konotasi pragmatis, melainkan sadar bahwa Tuhan dengan segala “Maha”-Nya turun melalui ayat-ayat Qauliyah maupun Kauniyah-Nya. Di sinilah manusia harus memahami bahwa ayat-ayat Tuhan diperuntukan bagi kebaikan segenap manusia di jagat raya, bukan semata-mata untuk kebaikan Tuhan sendiri.
Paradigma agama untuk kebaikan manusia inilah yang sering disalahartikan manusia dari berbagai golongan sehingga membuat diri dan kelompoknya merasa berhak mewakili Tuhan. Akhirnya mereka memahami agama hanya sebagai simbol, bahkan untuk melegitimasi setiap gerakannya yang tak jarang merugikan manusia secara materi maupun imateri melalui perilaku-perilaku anarkis.
Mereka terjebak dengan pemahaman simbolik yang berdampak pada pengerdilan ajaran agama yang mulia dan adiluhung. Buku gubahan Fariz Alniezar, anak muda NU berjudul Jangan Membonsai Ajaran Islam ini merupakan potret gamblang yang memberikan argumentasi lugas terkait pemahaman agama yang kontraproduktif di atas.
Penulis buku ini berupaya memberikan pemahaman agama dari sisi lain yang ditulis secara apik dengan tidak lari dari kompleksitas kehidupan beragama yang selama berjalan, baik di lingkungan sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Di titik ini, buku setebal 156 yang terdiri dari 35 artikel renyah namun substansial ini menemukan public interest-nya. Artinya, setiap pembaca langsung mencapai rasa karena kemungkinan besar terjadi di dalam pikiran dan laku setiap harinya. Atau minimal melihat dan menyaksikan kejadian nyata yang diulas secara lugas dalam buku tersebut.
Penulis buku ini juga jernih dalam membaca kontekstualitas dengan tetap berangkat dari dinamisasi tradisi, budaya, dan pemahaman agama yang berkembang di tengah masyarakat. Substansi dalam buku ini banyak memotret sekaligus mengkritisi laku yang berkembang dari umat beragama dengan menawarkan solusi yang dibalut dengan argumen kuat.
Dalam salah satu artikelnya berjudul ‘Berislam tanpa Menjadi Teroris’ (halaman 137), penulis buku mengawali coretan panjangnya dengan menukil Bernard Lewis yang berbunyi: Most Muslims are not fundamentalist, and most fundamentalist are not terrorist, but most present-day terrorist are muslims and proudly identify themselves as such. Dari kutipan Berbard Lewis tersebut, penulis buku ingin menunjukkan bahwa berislam tidak harus menjadi teroris. Bahkan sangat tidak manusiawi membawa panji-panji Islam sebagai legitimasi menyakiti dan membunuh orang lain.
Dari Bernard Lewis itu juga sesungguhnya menjadi pukulan telak bagi umat muslim karena kenyataannya tindakan teroris banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam, namun tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam berislam yang merupakan bagian integral dalam beragama. Narasi besar yang tersirat dalam kutipan tersebut adalah fundamentalisme sebagai akar dari tindakan terorisme, tetapi fundamentalis sendiri belum tentu teroris. Artinya, akar dari segala akar terorisme adalah paham fundamentalisme yang menumbuhkan radikalisme sehingga kristalisasinya adalah terorisme.
Di titik inilah penulis buku menemukan konteksnya dalam menggubah argumentasi sehingga pembaca dapat langsung memahami kondisi yang sedang berkembang dan terjadi di tengah masyarakat. Tetapi betapa sangat memilukannya karena agama Islam sendiri terstigma teroris sehingga gerakan kultural yang dilakukan oleh sebagian besar warga Nahdlatul Ulama (NU) patut didukung oleh seluruh masyarakat dalam menangkal akar-akar tindakan terorisme.
Penulis buku juga dengan apik menjelaskan istilah jihad secara filosofis yang selama ini memang banyak disalahpahami oleh sebagian kelompok agama. Penulis buku seperti yang telah ditulis dalam artikelnya (halaman 146) mengajak kepada masyarakat untuk merumuskan kembali makna jihad yang lebih tajam dan aktual untuk konteks masa dan juga konteks masyarakat plural di Indonesia.
Jika ditelaah lebih jauh, tulisnya, kata jihad merupakan satu rumpun (derivasi) dari kata jahada yang berarti berusaha (fisik). Dekat juga artinya dengan kata ijtihad, segala upaya yang lebih mengandalkan kerja otak dan intelegensia serta mujahadah, yakni usaha yang lebih menekankan pada dimansi intuitif (bathiniyah). Artinya, di titik ini bisa ditarik benang merah bahwa ideal seorang muslim (bahkan mansuai secara umum) yaitu orang yang mendayagunakan keseluruhan dimensi-dimensi spiritual tersebut.
Pendayagunaan dimensi-dimensi tersebut secara anakronis (separuh-separuh, setengah-setengah, sepenggal-sepenggal), berdampak pada pemahaman Islam yang juga setengah-setengah. Perilaku ini tentu akan berdampak pada tereduksinya kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan keyakinan sehingga seorang tersebut menjelma menjadi manusia yang anti-budaya, anti-tradisi bahkan sampai pada titik anti-perbedaan. Dalam hal ini, muncul diktum Birds born in a cage think flying is an illness, burung yang lahir di sangkar akan berpikir bahwa terbang adalah sebuah kejahatan. Untuk itulah keterbukaan akses pemikiran dalam beragama tidak hanya teks, tetapi juga konteks yang melingkupi sehingga beragama tidak melulu simbol namun bagaimana melihat substansi nilai.
Dalam semua artikelnya, penulis buku juga berusaha ingin menyampaikan revitaliasi spiritualitas dengan tetap berpegang pada tradisi yang berkembang di masyarakat. Antara lain memaknai tradisi mudik yang dikorelasikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian nilai kesabaran dalam berpuasa secara substantif di mana selama ini ritus-ritus tersebut hanya dipahami secara retoris bahkan munafik, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan ‘kriuk’ lainnya yang dapat memberi pemahaman kepada pembaca terkait ajaran Islam yang substantif dan inspiratif, bukan aspiratif yang hanya menggembar-gemborkan Islam secara simbolik untuk kepentingan diri dan kelompoknya.***
Identitas buku:
Judul: Jangan Membonsai Ajaran Islam
Penulis: Fariz Alniezar
Penerbit: Quanta PT Elex Media Komputindo
Tebal: x + 156 halaman
Cetakan: I, Maret 2015
Peresensi: Fathoni Ahmad, Pengajar di STAINU Jakarta.