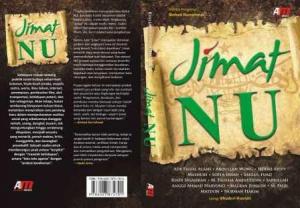Jimat adalah sebuah benda yang diyakini memiliki manfaat tertentu bagi yang membawanya. Berbeda dengan benda pusaka seperti keris, cincin, tombak dan semacamnya, jimat biasanya terbuat dari kertas yang di dalamnya bertuliskan mantra-mantra, angka-angka, atau rajah yang dianggap mempunyai tuah. Penulis rajah atau mantra pada kertas tersebut tidak bisa orang sembarangan. <>Mereka haruslah orang yang ahli dan mendalami dunia kegaiban, semisal kiai tertentu atau dukun.
Kata “jimat” sendiri konon berasal dari ungkapan Jawa siji dirumat yang berarti “satu dipelihara” lantas diakronimkan menjadi kata “jimat”. Manfaat yang dihasilkan dari para pengguna jimat bermacam-macam kerena jenis jimat juga bermacam-macam, bisa sebagai keselamatan, kekebalan, kewibawaan, pengasihan, dan sebagainya.
Buku berjudul Jimat NU ini ditulis oleh enam belas penulis yang masing-masing menyumbang satu tulisan. Semua tulisan mengangkat tema tentang perilaku keseharian masyarakat tradisional, khususnya hal-hal gaib yang kerapkali mewarnai kehidupan warga Nahdlatul Ulama (NU) dan masyarakat pesantren.
Lazim diketahui jika praktik keagamaan dan perilaku keseharian masyarakat Nadliyyin seringkali oleh sebagian kalangan dipandang tidak rasional, klenik, bid’ah, bahkan sesat. Praktik seperti ziarah kubur, memercayai jimat, dan membaca amalan-amalan tertentu sebelum atau sesudah sholat dianggap menyimpang dari akidah Islam.
Beberapa tulisan dalam buku ini hendak “memberi legitimasi kebenaran” pada keberadaan jimat dan berbagai praktik lain yang dianggap tidak rasional dan sesat. Menariknya, perspektif yang digunakan dalam usaha tersebut bukan hanya dari perspektif agama namun juga dari perspektif logis-rasional.
Kita dapat membaca bagaimana penyair Binhad Nurrohmat dalam tulisannya berjudul Jurnal Kuburan menyoroti praktik ziarah kubur dalam perspektif sosio-antropologis. Ia dengan jeli melihat bahwa praktik ziarah kubur merupakan suatu penghargaan dari yang hidup kepada yang telah mati. “Kuburan bukanlah tempat membuang bangkai manusia. Kuburan merupakan artefak otentik terakhir manusia yang pernah hidup di planet ini” (hal. 17).
Ritual ziarah kubur merupakan usaha untuk mengenang biografi sang penghuni kubur. Agar supaya kesadaran kita di masa sekarang tidak terputus dengan sejarah manusia yang hidup di masa lalu. Selain itu, ziarah kubur merupakan ikhtiar kita untuk selalu sadar, bahwa hidup kita tidak kekal. Dengan demikian kuburan memiliki makna kultural-simbolik dalam relasinya dengan manusia yang hidup. Oleh karenanya kita tidak bisa serta-merta menganggap bahwa praktik ziarah kubur merupakan sebuah perilaku tidak rasional.
Kemudian Ade Faizal Alami dalam tulisannya Nalar Perdukunan melacak secara runtut asal-muasal ilmu perdukunan, jimat, dan mantra-mantra yang diyakini mengandung tuah kekuatan. Keberadaan jimat dan mantra sudah ada dan berkembang di Babilonia Kuno. Masyarakat Babilonia Kuno menganut sistem kepercayaan Sabean (Saba’) yakni mengultuskan planet-planet dan bintang-bintang. Mereka percaya bahwasanya alam semesta memiliki energi yang besar sehingga dengan rumus tertentu, mereka bisa menciptakan hal-hal ajaib laiknya ilmu magis dengan memanfaatkan energi gerakan planet. Rumus-rumus tertentu itu bisa berupa rajah, angka-angka atau huruf yang dituliskan, bisa juga berupa mantra yang dirapal pada waktu tertentu. Kemudian praktik tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada anak-cucu mereka.
Di Nusantara sendiri praktik perdukunan telah terjadi berabad-abad silam. Dukun sendiri awalnya merupakan julukan bagi seseorang yang bisa menyembuhkan orang sakit dengan cara memberi racikan ramuan sebagai obat serta merapalkan beberapa mantra untuk menambah khasiat obat tersebut. Juga para leluhur kita dulu memahami bumi dan gejalanya dengan cara melihat pergerakan bintang dan planet. Nelayan lampau memutuskan kapan melaut dengan melihat posisi bintang di langit. Para petani memutuskan kapan mulai menebar benih juga dengan cara melihat posisi bintang. Dengan demikian, jelas sekali, ilmu perbintangan sudah sangat dikuasai oleh leluhur kita.
Lantas lewat masuknya Islam ke Nusantara yang berarti masuknya juga “praktik perdukunan” dari Timur Tengah, beberapa mantra khas Nusantara dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mantra tersebut merupakan percampuran bahasa-bahasa Nusantara dan Arab. Ada mantra berbahasa Sunda-Arab, Melayu-Arab, Jawa-Arab, dan sebagainya. Tidak semua mantra Nusantara dimodifikasi. “Hibriditas” mantra hanya terjadi pada mantra-mantra tertentu saja. “Hibriditas” mantra ini juga merupakan salah satu bukti berbaurnya nilai budaya lokal dengan budaya lain. Hal ini juga bukti bahwa para leluhur kita sangat lentur/fleksibel dalam memegang nilai-nilai budaya lokal
Kemudian mengapa doa-mantra dan jimat bisa bertuah? Ade menulis, “huruf bukan goresan tanpa makna. Huruf terhubung dengan alam semesta” (hal. 25). Karena huruf dan angka terhubung dengan alam semesta maka ilmu merangkai huruf, angka, dan rajah agar dapat memiliki tuah berkaitan dengan ilmu perbintangan. Dengan demikian “penulisan rajah atau azimat misalnya, harus memenuhi syarat waktu penulisan” (hal. 29).
Sebenarnya, rajah, angka maupun mantra, baik yang ditulis pada kertas (berbentuk jimat) atau yang dibaca dengan lisan adalah sebuah doa. Oleh karenanya, keyakinan terhadap rajah maupun mantra adalah keyakinan terhadap kekuatan doa. Dan keyakinan terhadap doa adalah keyakinan pada kekuatan kata. Keyakinan jika kata dapat membentuk realitas.
Dalam karyanya berjudul Syams al Ma’arif al-Kubro, Syeikh Ahmad bin Ali al-Buni (w. 1225 M) menjelaskan berbagai macam rajah, ilmu simbol, doa-mantra, ilmu huruf, ilmu angka, wafaq, serta fungsi dan kegunaannya bagi yang memakainya. Karya tersebut masih dijadikan rujukan dan diajarkan di pesantren-pesantren tradisional di Jawa hingga kini. Di Nusantara juga ada beberapa manuskrip primbon dan mantra yang sayangnya jarang sekali diketemukan karena minim dokumentasi.
Jika kita lihat saat ini, kekuatan angka dan huruf menemukan bentuknya dalam teknologi modern yang berkembang di masyarakat. Bukankah telepon genggam dan komputer tercipta dari bahasa pemprograman yang tersusun dari gugusan kode-kode huruf dan angka. Dengan demikian, jimat dan mantra adalah teknologi dalam bentuk lain.
Demikianlah asal-muasal serta logika jimat dan mantra. Dari penjelasan tersebut menjadi terang bahwa sebenarnya sebuah laku yang dianggap tidak rasional dan takhayul, ternyata memiliki akar kesejarahan yang panjang serta alasan logis dan rasional. Rasionalitas yang untuk saat ini tidak bisa dibuktikan dengan metode verifikasi ilmiah positivisme Auguste Comte. Namun, bukan berarti apa yang belum bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah lantas menjadi tidak benar.
Oleh karena itu, sudah saatnya metodologi ilmu pengetahuan dengan rendah hati mengakui keterbatasan dirinya. Kenyataan sehari-hari lebih kompleks dan kaya akan variabel. Mengalami dan menghayati sendiri peristiwa sehari-hari terkadang lebih bisa membuat kita memahami kenyataan daripada harus menjaga jarak dengannya untuk kemudian menyimpulkan peristiwa yang terjadi.
Buku ini tidak mengutuk metodologi ilmu pengetahuan modern. Tidak juga memaksa kita agar memercayai jimat dan mantra. Namun mengingatkan kita agar tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan saat melihat peristiwa sehari-hari yang dianggap klenik, mistis, dan takhayul. Oleh karena itu buku ini layak dibaca siapapun, baik dari kalangan Nahdliyyin maupun kalangan yang ingin mengetahui praktik mistik sehari-hari di sekitar kehidupan kita.
Kita seringkali mencemooh praktik perdukunan tradisional, tetapi menanti dan memercayai rubrik zodiak yang berseliweran di koran, majalah, hingga twitter. Kita mencela rajah, simbol, dan mantra yang terdapat dalam jimat namun sembari pergi ke tukang tarot untuk meminta diramal nasibnya. Bukankah zodiak, jimat, tarot memiliki alur logika yang sama, yakni logika huruf, angka, simbol dan relasinya dengan alam semesta.
Masyarakat kita masih dihinggapi perasaan minder (inferior) untuk mengakui kebenaran khazanah pengetahuan tradisional. Katrin Bandel berpendapat bahwa hal tersebut dampak dari penjajahan yang dialami bangsa kita di masa lalu. Karya-karya pengarang Eropa diajarkan sebagai kanon yang berlaku “universal”, sedang sastra dan budaya lokal diacuhkan, sehingga anak didik mendapat kesan bahwa hanya Eropalah yang berbudaya dan “beradab” (Sastra, Perempuan, Seks 2009:120). Perasaan serta pikiran tersebut terwariskan (baik sengaja atau tidak) secara turun-temurun hingga saat ini.
Terlebih mengingat sistem pendidikan dan kurikulum sekolah kita masih menganut serta mengacu pada Barat, maka tidak mengherankan bahwa masyarakat kita merasa hanya pengetahuan dari Barat yang “ilmiah”, maju, dan modern. Sedangkan pengetahuan lokal dianggap terbelakang, primitif, dan irasional.
Tulisan dalam buku ini tidak melulu serius. Penyair Mashuri justru menulis tentang lelucon-lelucon supranatural di lingkungannya, Riadi Ngasiran menulis tentang masa kecilnya di desa saat menimba ilmu agama. Juga beberapa tulisan lain yang mengingatkan kita akan keberagaman kejadian dalam hidup manusia. Terkadang terkesan remeh dan sederhana, saking remehnya sampai-sampai kita lupa merenungkan maknanya bagi kita.
Semua penulis dalam buku ini berlatarbelakang santri, atau setidaknya hidup dalam lingkungan pesantren, maka membaca tulisan dalam buku ini terasa renyah karena penulisnya berkisah tentang pengalaman yang terjadi di lingkungan sekitar mereka sendiri. Wallahu a’lam.
Judul Buku: Jimat NU
Penulis: Binhad Nurrohmat, dkk
Penerbit: Arruz-Media
Cetakan: Pertama, 2014
Tebal: 300 halaman
Peresensi : Tufail Muhammad, alumnus Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, alumnus pesantren Tebuireng Jombang
Terpopuler
1
KH Said Aqil Siroj Usul PBNU Kembalikan Konsesi Tambang kepada Pemerintah
2
Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah PBNU Hadir Silaturahim di Tebuireng
3
Silaturahim PBNU Sesi Pertama di Tebuireng Selesai, Prof Nuh: Cari Solusi Terbaik untuk NU
4
Kiai Sepuh Respons Persoalan PBNU: Soroti Pelanggaran Pemakzulan dan Dugaan Kekeliruan Keputusan Ketum
5
KH Ma’ruf Amin Ikuti Forum Sesepuh NU, Sampaikan 4 Sikap untuk Redam Persoalan di PBNU
6
Hasil Lengkap Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng
Terkini
Lihat Semua