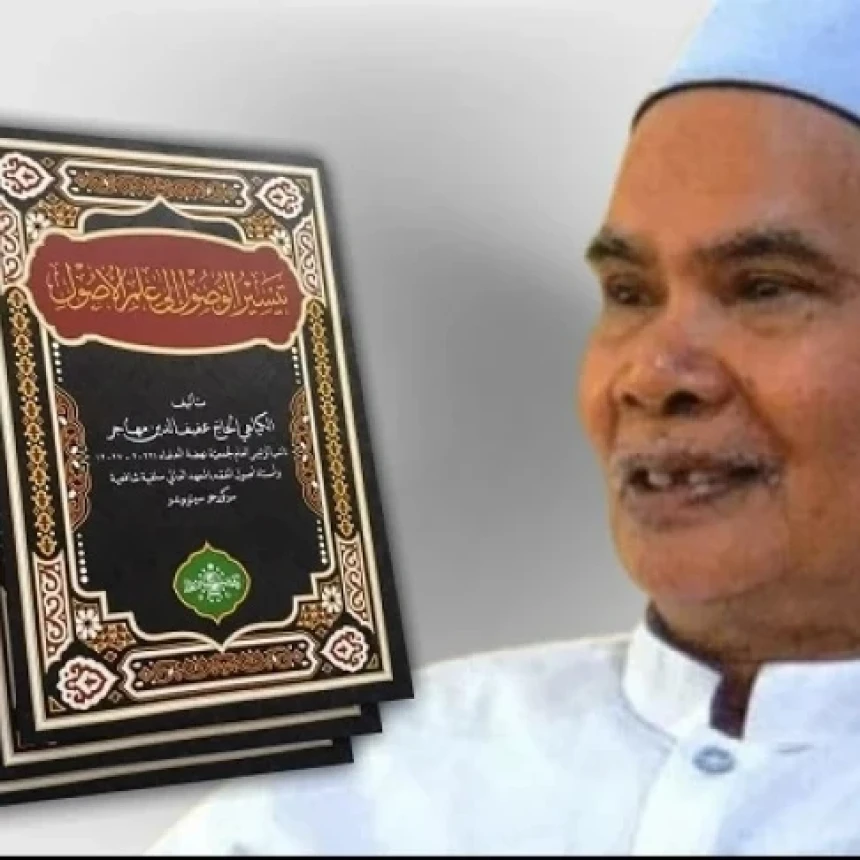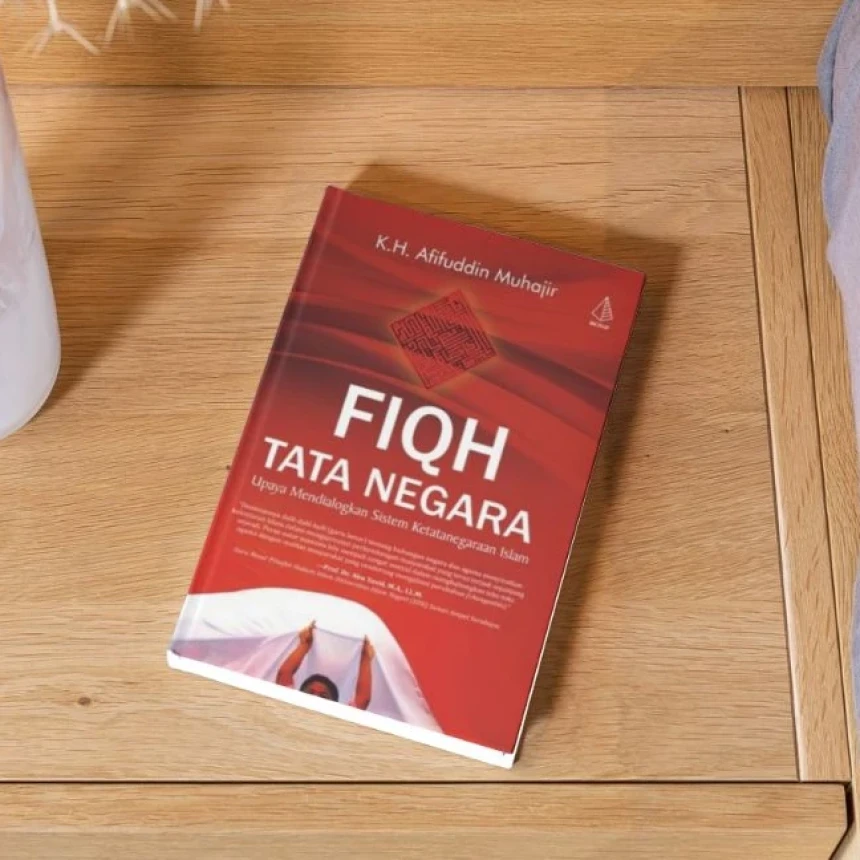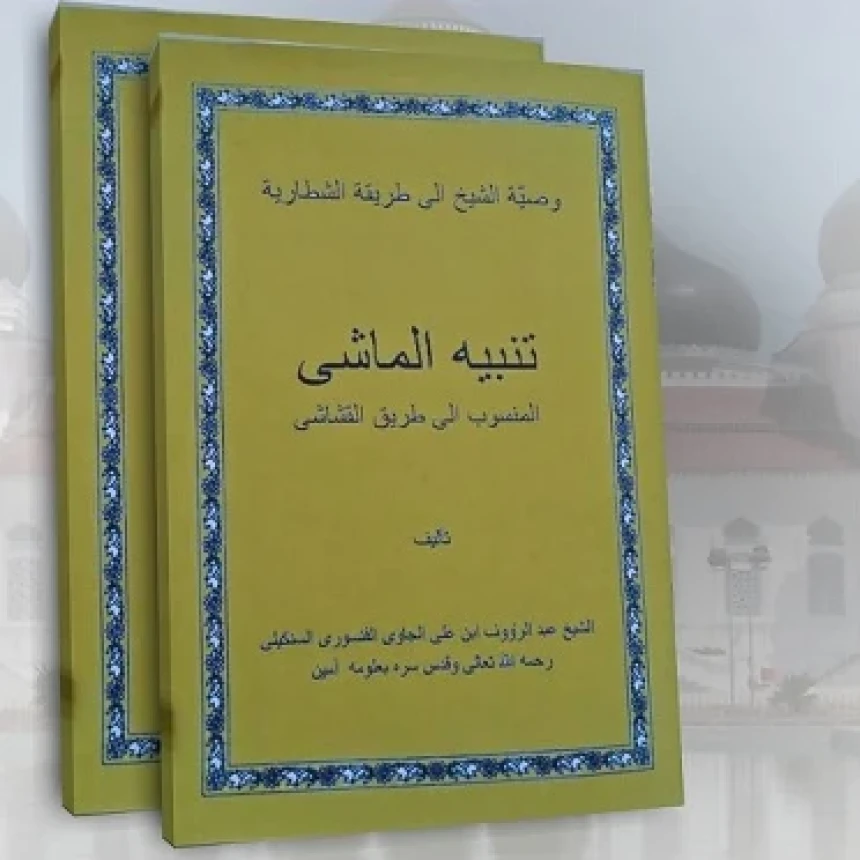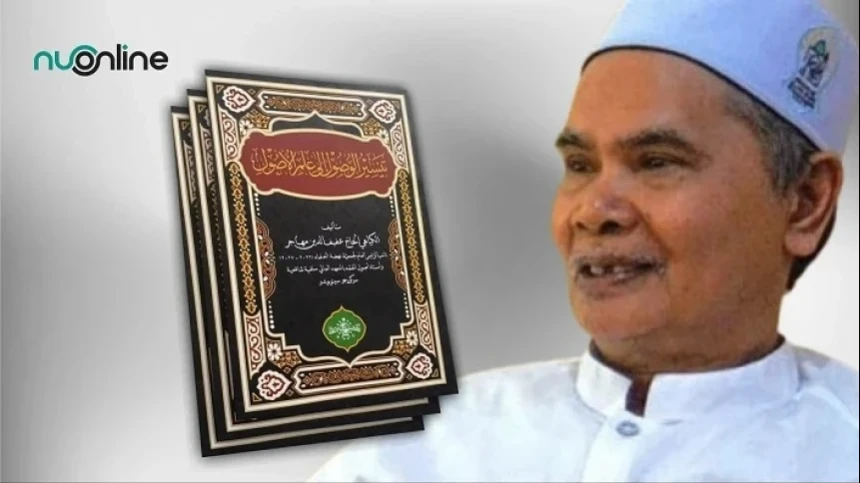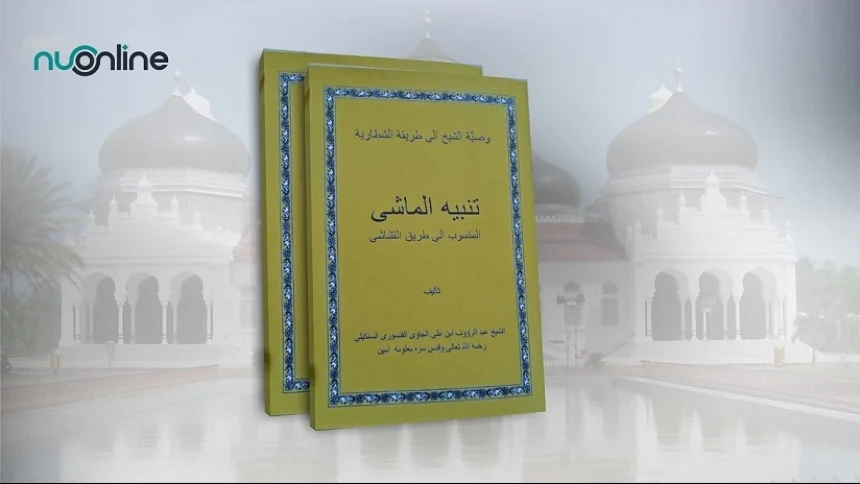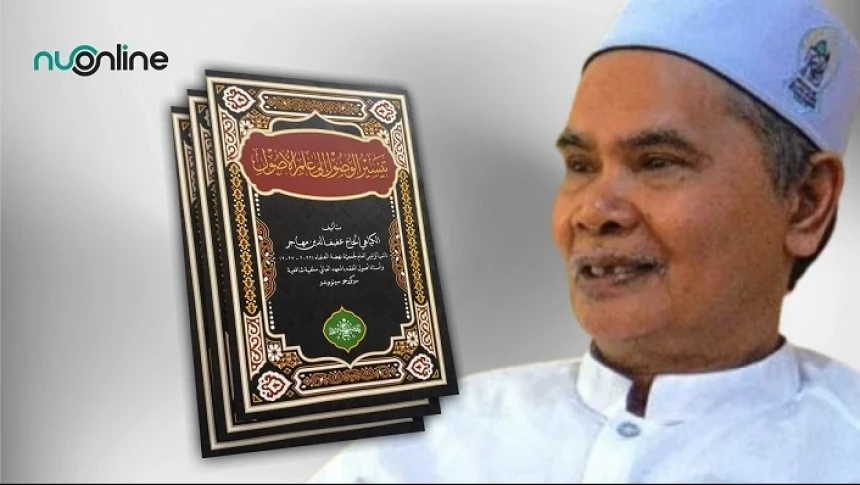Judul: Ramadan di Jawa: Pandangan dari Luar
Penulis: Andre Moller
Tahun terbit: September, 2005
Halaman: xi+309
Penerbit: Nalar, Jakarta
Peresensi: Abu Khaer
‘Bapak Antropolog’ Indonesia, Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip oleh Ceprudin (2010), pernah melukiskan mengenai kegiatan Ramadhan di Jawa dengan menyatakan “orang Jawa senang mencari kesusahan dan menderita ketaknyamanan dengan sengaja untuk tujuan agama.”
<>
Dalam pandangan Guru Besar Antropologi salah satu universitas negeri tersebut, memandang bahwa kesusahan dan penderitaan menjalankan ‘adat’ religius bagi masyarakat Jawa, justru dipandang sebagai kesenangan pribadi, bahkan sebenarnya lebih tepat lagi jika ia mengatakan sebagai suatu kebahagiaan tersendiri, termasuk ketika menyambut, melaksanakan, dan meneruskan tradisi agung umat Islam, shaum Ramadhan. Istilah shiyam ataupun shaum, bukan ‘barang’ atau ‘wacana’ baru bagi orang Jawa. Terlepas dari perbedaan makna shiyam atau shaum dan puasa, orang Jawa lebih memilih istilah sendiri dengan menggunakan istilah wulan puasa.
Bagi umat Islam, tak terkecuali di Jawa, percaya bahwa dengan menahan lapar selama satu bulan, ia akan mendapatkan ridho Allah. bagi orang Jawa, puasa, tirakat, bertapa, sudah menjadi adat tradisi yang berlangsung turun-temurun sejak nenek-moyang dulu. Salah satu contoh, bagaimana puasa telah mengakar dalam kehidupan orang Jawa seperti tercantum dalam Serat Wulang Reh, “Dadiyo lakunireku, cegah dhahar lawan guling, lan aja asukan-sukan, anganggowa sawatawis, ala watake wong suka, nyuda prayitnaning batin.” Orang Jawa sangat menjaga dan terus berusaha meningkatkan kualitas rohani. Seluruh nasihat dalam peribahasa Jawa yang ribuan itu pun, posisinya lebih sebagai ‘’fatwa rohani’’. Bukan rumus perhitungan untuk menyelesaikan persoalan praktis keduniawian, melainkan ajakan untuk menjalankan puasa dan tirakat setiap hari, sepanjang hayat. Jika direnungkan, makna dari cegah dhahar lawan guling, ana sethithik dipangan sethithik, ya jangane ya segane, adalah upaya untuk mengolah dan menata dunia batin manusia.
Puasa dan tirakat di Jawa memang berat, karena cenderung dilakukan setiap hari, setiap saat. Namun, seperti halnya orang yang telah terbiasa memikul beban berat, manakala benar-benar mendapat cobaan (beban kehidupan nyata) tentu akan lebih kokoh, tawakal, dan ikhlas menerimanya. Dengan demikian, beban hidup itu jadi terasa ringan.
Maka tidak mengherankan jika puasa yang dimaknai sebagai upaya pembersihan diri banyak diamalkan orang Jawa sebelum ajaran shiyam Ramadhan diperkenalkan oleh ajaran Islam. umat Islam di Jawa jauh-jauh hari menjelang bulan Ramadhan sudah melakukan ritus-ritus. biasanya diawali sejak bulan Ruwah atau roa (Syakban). Di bulan Ruwah, umat Islam menyibukkan dengan kegiatan atau pekerjaan yang memungkinkan diselesaikan (dipadatkan) pada bulan itu. Di Semarang ada Dugderan yang sangat terkenal dan erat kaitannya dengan Ramadhan di Jawa. Bahkan, dihampir seluruh wilayah pulau Jawa, terutama pedesaannya, pada pertengahan bulan roa, di malam harinya ramai-ramai mengadakan acara nisfu sya’banan, suatu ritus untuk berupaya semoga buku amal perbuatan manusia selama satu tahun di tutup dengan indeks prestasi ke-sholeh-an sebelum menghadapi ‘bulan panen’ amal kebajikan Ramadhan.
Lebih jauh lagi, seiring dengan perkembangan budaya Jawa aksesoris menjelang Ramadhan ada yang menggunakan secara simbol “politis”. Tujuan politis pada bulan Ramadhan dapat dipahami dalam konteks pemikiran yang menganggap Ramadhan sebagai sebuah “momentum”-nya umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah kontroversi hisab-rukyat dalam menentukan satu syawal pun ikut mewarnai. Meskipun tidak terjadi kontras begitu serius.
Hal yang masih kontroversi dalam ritus menjelang Ramadhan yaitu nyekar. Nyekar adalah kegiatan berkunjung dan membersihkan makam-makam orang tua atau sanak saudara yang telah terlebih dahulu menghadap kehadirat Illahi biasanya dengan membawa bunga tujuh rupa (umba rampe) untuk ditaburkan di makam dan pembacaan do’a tahlil. Pro-kontra ini terjadi antara Islam tradisional (pro) dan modernisme (kontra). Bagaimana pun juga umat Islam Jawa mayoritas percaya dan yakin terhadap nyekar sebagai bentuk lain dari perwujudan ziarah kubur, yang bertujuan ketika memasuki bulan Ramadhan diri dalam keadaan suci dan untuk ‘sekedar berusaha’ meringankan beban ukhrowi keluarganya yang telah wafat.
Memasuki bulan Ramadhan menurut orang Jawa harus benar-benar suci secara komprehensif, baik lahir maupun bathin. Dimulai dengan bebersih diri, beranjak sampai skup bebersih lingkungan, dimana ada tradisi bersih lingkungan. Di bulan Ramadhan, lingkungan harus bersih dari kotoran sampah dan juga dipahami bersih dari perbuatan amoral. Karena dianggap dalam bulan ramadhan lebih mengganggu aktifitas berpuasa.
Sebelum berpuasa, umat Islam pada malam hari disunnahkan untuk makan sahur. Alunan ‘musik’ ensambel perkakas dapur yang dimainkan anak-anak atau ta’mir mesjid yang mengumandangkan agar menyegerakan bersahur mengakibatkan suasana menjadi riang dan saling bergotong royong meski ala kadarnya menjadi semakin kuat, tak seperti malam-malam biasa. Pada siang harinya segala lapisan strata sosial, mulai anak-anak sampai dewasa, menyibukkan diri dengan membaca al-Qur’an (Tadarusan). Menjelang sore, sebagian ibu-ibu sibuk mempersiapkan menu untuk berbuka puasa, kaum remaja dan anak muda jalan-jalan sore (JJS) dengan berbagai ragam niatnya, dengan tertib menunggu waktu ifthor tiba.
Di malam hari selesai sholat Isya’ dilanjut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan ritus paling penting sepanjang bulan Ramadhan. Dalam penentuan jumlah raka’at pun disini terjadi perbedaan antara Islam tradisional dan modernis. Meski akhir-akhir ini perdebatan itu sudah mulai mencair.
Malam-malam khusus yang diperingati pada bulan Ramadhan juga ikut meramaikan belantika wulan puasa Jawa. Di antaranya malam Lailatul Qodar dan Nuzulul Qur’an. Bisanya diisi dengan pengajian-pengajian yang berkaitan dengan turunnya al-Qur’an. Umat Islam dan Orang Jawa khususnya, percaya bahwa malam itu penuh dengan berkah dan kemuliaan dibanding dengan seribu bulan.
Ritus yang tidak kalah penting menurut orang Jawa yaitu I’tikaf. I’tikaf tidak begitu populer, biasanya kegiatan i’tikaf dilakukan pada hari-hari ganjil sepuluh hari akhir bulan Ramadhan. Ritus ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sebagai sarana untuk introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah.
Pada hari terakhir menjelang bergantinya bulan Ramadhan ke bulan Syawal (Idul Fitri) untuk menyempurnakan ibadah puasanya umat islam diwajibkan untuk berzakat fitrah (kesucian). Datangnya hari raya Idul Fitri itu diakhiri dengan berbuka puasa hari terakhir bulan Ramadhan dengan ditandai pemukulan beduk di musholla dan masjid setelah ada pengumuman resmi dari Pemerintah.
Pada malam hari ini umat muslim merayakan dengan sangat meriah. Paling banyak dilakukan adalah Takbiran. Ada yang melakukannya dengan sambil keliling kampung dengan menggemakan koor Takbir dengan berulang-ulang sambil membawa lampu ‘oncor’ yang terbuat dari bambu. Tua, muda, perempuan, laki-laki tumpah-ruah sama-sama memeriahkan malam hari ‘kemenangan’ Hari Raya Idul Fitri ini. Pagi harinya umat muslim berbondong-bondong menuju ke mesjid untuk melaksanakan Shalat Id. Tepatnya hari ini tanggal 1 syawal.
Selesai Sholat Id, umat Islam Jawa bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Tujuannya agar dosa sesama manusia selama berinteraksi pada hari itu bisa diampuni Allah. Setelah merasa lega dan puas bermaaf-maafan serta silaturahmi pada hari itu juga dilanjutkan dengan kumpul bareng keluarga sambil menyantap opor ayam dan ketupat bersama-sama keluarga. Acara Hari kemenangan lumrahnya diakhiri dengan kembali nyekar ke pekuburan keluarga. Nyekar disini substansinya sama dengan nyekar menjelang Ramadhan. Hanya bedanya ini dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan tentunya dengan busana pakaian yang baru dibeli.
Demikian gambaran Ramadhan berikut dengan aksesoris ritus yang dilakukan orang Jawa. Meskipun dari sisi materiil orang Jawa harus menyediakan lebih dibanding bulan biasanya, tapi semua itu tertutupi dengan senangnya kedatangan bulan suci Ramadhan.
Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, karya penulis Swedia, Andre Moller ini menarik untuk kita renungkan terutama dalam momen-momen Ramadhan. Buku ini tidak melihat puasa semata-mata dari aspek teologis-normatif, tetapi lebih dari itu, pelaksanaan ibadah puasa dalam buku ini dilihat dari aspek aksesoris yang mengitarinya dan membuat ramadhan menjadi lebih meriah dari bulan-bulan lainnya.
*Koordinator social Karang Taruna PelitaIndonesia Banyuputih Wringin Bondowoso Jatim
Terpopuler
1
Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN 12%
2
Kronologi Santri di Bantaeng Meninggal dengan Leher Tergantung, Polisi Temukan Tanda-Tanda Kekerasan
3
Bahtsul Masail Kubra Internasional, Eratkan PCINU dengan Darul Ifta’ Mesir untuk Ijtihad Bersama
4
Bisakah Tetap Mencoblos di Pilkada 2024 meski Tak Dapat Undangan?
5
Fikih Perempuan: Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam
6
Pencak Silat Pagar Nusa Jadi Mata Kuliah Ko-Kurikuler di Universitas Islam Makassar
Terkini
Lihat Semua