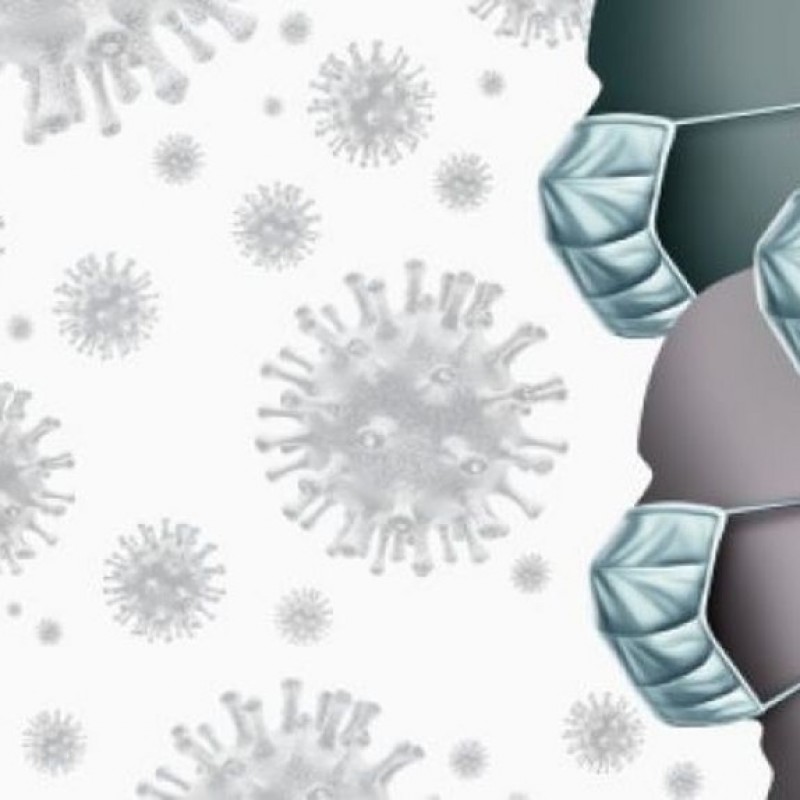Sebetulnya, sebelum aku masuk, pesantrenku tak mengenal tunil sama sekali. Akulah yang jadi pelopornya. Artinya, akulah yang memulai memperkenalkannya. Sebelum masuk pesantren itu, aku sering bermain tunil di kampungku ketika mengaji di Ajengan Enoh. Dari rumah, aku sering membawa sarung sebagai layar untuk tunil selepas mengaji.
Kebetulan aku mengaji ke pesantren dengan ajengan yang "moderen". Ajengan yang menyukai kesenian.
Pernah ajengan mejelaskan pentingyna kasenian. Menurut dia, tetabuhan saperti gamelan, kendang pencak dan sejenisnya tidak haram.
"Ana mah sering merasa heran kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang mendengarkan gamelan itu haram, sementara mendengarkan terebang (semacam rebana) tidak. Ana tidak mengerti, padahal dua-duanya sama sejenis tetabuhan. Coba dengarkan gamelan dengan khusuk. Suara gongnya ngungkungan. Gung... gung... itu pertanda mengajak memuji kepada Yang Maha Agung. Coba perhatikan sarengkak saparipolahna (gerakan-gerakan) orang yang ngibing (menari). Gerakannya mengandung ketertiban, mendahulukan yang harus lebih dahulu dan mengakhirkan yang memang harus terakhir. Jangan sampai terbalik. Demikianlah hidup kita juga, harus tertib,” begitu penjelasan ajenganku.
“Coba perhatikan dalam permainan tunil. Ada raksasa gagah perkasa, ada ksatria yang yang kebal. Semua hanyalah di pentas. Setelah layar ditutup, ksatria tidak kebal dan gagah lagi. Begitulah hidup. Tiada beda dengan mengatur dalam seni peran. Kalau kita sudah pulang ke tempat asal, sama saja. Tak ada yang gagah. Tak ada yang kebal. Semuanya tunduk kepada takdir Yang Maha Kuasa. Manusia ibarat anak wayang yang menjalani alur naskah peran, seperti dalam tunil, menjalankan apa yang diinginkan yang membuat cerita,” kata ajengan.
“Yang haram itu, yang termasuk ke dalam maksiatm kalau seni untuk ujub takabur atawa menjadi lantaran lupa kepada segala hal. Saking asiknya, lupa shalat, lupa kepada Allah.”
Begitulah penjelasan ajenganku terkait kesenian. Makanya kataku, ajenganku modern.
Ajengan berpandangan seperti itu tidak hanya dalam pembicaraan, tapi juga praktik. Ia sering meminta santri memainkan kacapi atau kendang pencak. Bahkan ajengan kadang ngengklak (menari). Lagu Buah Kawung favoritnya. Aku tak akan lupa.
Makanya tak heran ketika aku memperkenalkan tunil di pesantren, ajengan tak melarangnya. Meski demikian, tunil di pesantren berbeda dengan di kota. Pertama, alur ceritanya tak bisa sembarangan, melainkan harus selaras dengan ajaran agama. Kedua, para pemainnya hanya santri laki-laki, tak boleh ada pemain perempuan.
Aku akui, selama menjadi santri, aku tak menonjol dalam mengaji, tapi dalam hal lain. Pertama dalam kesenian, terutama dalam tunil. Akulah yang menjadi sutradara. Kadang aku ikut berperan menjadi pemeran utama.
Pementasan biasanya berlangsung di balai. Tiga sampai empat bangu dijajar berdempetan menjadi pentas sementara layar pentas, gorden pangwedonan.
Jika pentas tunil, penontonnya tidak hanya laki-laki, santri putri juga ikut. Juga tak hanya para santri dan keluarga ajengan, tapi penduduk sekitar pesantren. Mereka hadir seperti mau mendengarkan ceramah dari seorang dai. Menurutku, sebetulnya tunil tak ada bedanya dengan ceramah sebab naskah ceritanya diambil dari ajaran agama.
Orang-orang begitu tertarik ketika si Atok menyampaikan kabar akan ada pementasan Yaumul Qiyamah. Aku menyusun naskahnya dari ayat-ayat Al-Qur’an yang dibimbing Kang Engkus, santri yang dikenal sebagai raja lughah.
Setelah naskah itu selesai, aku memperlihatkannya kepada ajengan supaya diperiksa. Ajengan manggut-manggut. Ia menambahkan beberapa hal dalam naskah itu. Dan perlu diketahui, naskah tunil itu ditulis dengan huruf Arab.
(Belakangan, pada tahun 1959, aku menyempurnakan naskah sandiwara "Yaumul Qiyamah" dan mementaskannya kembali di beberapa tempat di Priangan).
Dalam pementsan itu, aku iktu berperan menjadi orang yang banyak dosa. Di saat yaumul qiyamah, aku sempoyongan sembari meratap-ratap menahan panasnya pada Mahsyar.
Sebelumnya, sandiwara itu dimulai dengan ayat-ayat Al-Qur’an surat "Zalzalah" yang dibacaka si Usup. Setelah itu layar terbuka. Ahli-ahli kubur terbangun. Mereka meratap-ratap sambil berkata, "Ya wailana, man baatsana min markodina..." (Wahai siapa gerangan yang membangunkaku — tuqilan dari surat Yasin). Kemudian ada suara, "... hadza ma wa adarrahman, wa shadaqal mursalun... " (itulah yang dijanjikan- diambil dari surat Yasin juga).
Kemudian dalam pentas itu menggambarkan siksaan yang luar biasa pedihnya. Tempat yang panas tanpa ada pelindung apa pun. Tak ada air pengobat haus. Tak ada makanan pengobat lapar. Semuanya yang terlihat cucuk-cucuk tajam dan nanah-nanah yang mendidih. Gambaran itu merupakan kutipan dari Al-Qur’an. Tentu saja pada praktiknya, dalam pentas itu tak bisa menggambarkan secara detil. Maka diceritakanlah suasananya dengan narator.
Aku masih ingat, sebagai yang berperan calon ahli neraka, aku diharudum sarung, meratap-ratap, menengadahkan tangan ke langit meminta pertolongan kepada calon-calon ahli surga.
Kemudian ada nyanyian:
Aduh indung, aduh bapa geuning bet kieu jadina (alok: kuring sangsara) teungteuingeun anu mu'min di dunya henteu ngingetan (alok: henteu ngelingan)
Kemudian calon-calon ahli surga menjawab sembari menunjuka calon ahli neraka. Digambarkan dengan nyanyian:
Trong kohkol andika anggur morongkol dur bedug andika anggur murungkut diadanan beuki tibra pajar maneh teu ngelingan (alok: henteu ngelingan) dasar jelema doraka kudu asup ka naraka
Ahli naraka deui:
Aduh indung, aduh bapa geuning bet kieu jadina jst., jst.,
Para penonton meneteskan air mata sambil mengucapkan "... aaudzubillahi min dzalik, audzubillahi min dzalik".
Keesokan harinya, ibu ajengan membanggilku. Ketika aku menemuinya, Nyi Halimah langsung masuk ke dalam. Sepertinya dia tahu apa yang akan diceritakan ibunya kepadaku.
"Ana (aku) mah suka sekali tunil tadi malam,” kata Bu Ajengan. “Tapi lain kali kalau dipentaskan lagi anta (kamu) kamu jangan jadi ahli neraka. Tak tega aku melihatnya. Kamu jadi ahli surga saja. Bagian yang menjadi ahli neraka mah biar saja Si Atok atawa Si Umar," ungkapnya.