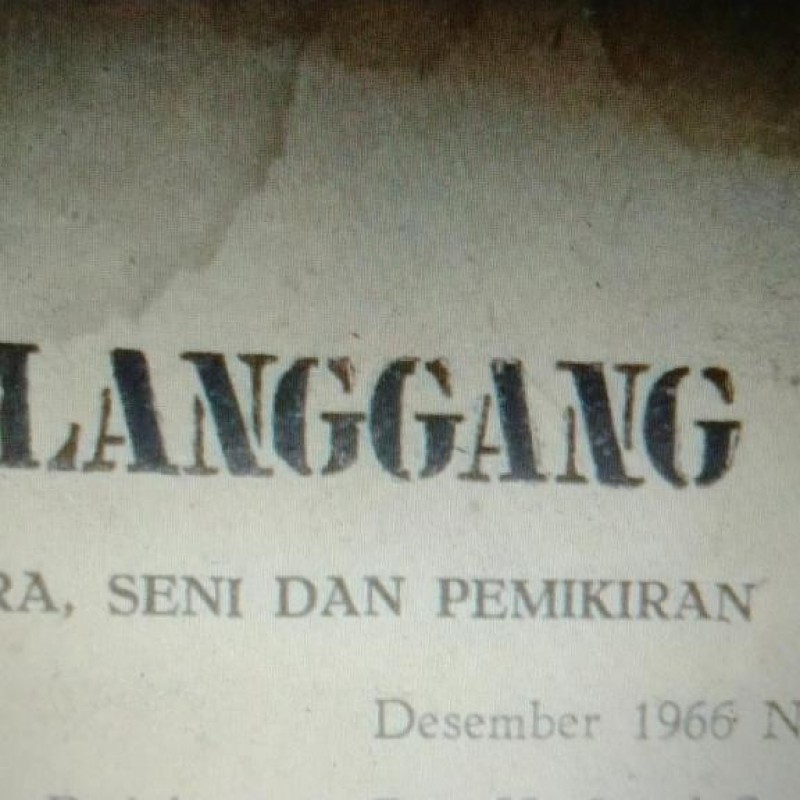Santri Sunda Pentaskan Legenda Minang, Malin Kundang Tak Jadi Batu
Ahad, 23 Februari 2020 | 10:15 WIB

Salah satu adegan Drama Malin Kundang yang dipentaskan SMA Manggala (Foto: NU Online/Nelly Nurul Azizah)
Kemudian, seorang perempuan tua mengenali pria muda itu sebagai anaknya bernama Malin Kundang. Dengan penuh haru dan bahagia ia mendekatinya. Namun, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak perempuan tua, karena si pria muda tak mengakuinya. Padahal ia telah menunggu Malin Kundang ratusan malam digempur angin jahat. Perempuan tua itu gelap mata. Terjadilah pengutukan.
Di dalam legenda Minang, Malin Kundang menjadi batu. Abadi. Namun, dalam pementasan murid-murid Ilmu Pengetahuan Sosial I kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA) Manggala, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Sabtu (22/2) malam, lain dari cerita biasanya. Dalam naskah Drama Malin Kundang itu, ia tak jadi batu. Dia insyaf.
“Maafkan Malin, Bundo,” kata Malin sembari mencium kaki ibunya.
Dan tentu saja sang ibu mengampuninya. Ibu mana yang tak pernah memaafkan anaknya? Demikianlah, cerita yang disutradarai Meri Maryamah itu berakhir dengan happy ending. Ratusan penonton pun bernapas lega.
Selain pementasan Drama Malin Kundang, kelas IPS II menampilkan lakon Tanah Air Mata karya Sutardji Calzum Bahri dan Ridwan Ch Madris dengan sutradara Eneng Hilda Fahira, sementara kelas Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mementaskan naskah Mau Dibawa Kemana Negeri Ini karya Ridwan Ch Madris dengan sutradara Laila Niswatu Akmalia dan Farid Nuralim.
SMA Manggala dan Pondok Pesantren Al-Istiqomah
Menurut salah seorang putra KH Ali Imron yang juga Kepala Sekolah SMA Manggala Ahmad Fuad Ruhiat, sang ayah sangat mengapresiasi kesenian. Sang ayah, saat memimpin Pondok Pesantren Baitul Arqom pernah mengizinkan pameran seni rupa di pesantren yang menghadirkan Acep Zamzam Noor, Tisna Sanjaya, Isa Perkasa, dan lain-lain.
“Ayah saya sangat mendukung kesenian di pesantren, pembacaan Al-Barzanji sudah tidak asing dengan pesantren, dan itu karya sastra, karya seni. Seni justru sangat akrab dengan pesantren. Dari dulu pesantren tidak lepas dari budaya dan seni,” ungkap ajengan muda yang terampil bermain gitar ini.
Dukungan pesantren itulah membuat anak seperti Iqbal dan teman-temannya berperan total dan menghayati watak yang dimainkannya. Ia menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Minang dengan terampil. Begitu juga Debi Amal Amaliyah yang berperan sebagai ibu Malin Kundang. Iqbal berani tampil sebagai pemuda sombong yang menendang ibunya. Sementara Debi berani tersungkur ke lantai yang becek dan meratap dengan kalimat-kalimat panjang dengan tubuh terseok-seok.
Mereka Belajar dari Nol
Menurut dia, proses kreatif anak didiknya itu hanya berlangsung tiga bulan termasuk mulai pengenalan dan bedah naskah. Baru kemudian diperkenalkan aplikasinya dalam seni peran. Mereka diperkenalakan olah vokal, olah tubuh, dan pelemasan.
“Olah vokal misalnya artikulasi, intonasi, misalnya lafal Indonesia harus jelas jangan endonesia, olah tubuh dengan keringanan badan untuk peran seperti jatuh terguling-guling. Teu hariwang karena mereka sudah dilatih. Olah rasa paling sulit karena terkait imajinasi. Peran sedih harus sampai nangis, lucu harus membuat ketawa. Setelah kelihatan, mereka baru dikasih naskah dan bagaimana cara mengemas teater,” jelas aktivis Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia ini.
Untuk pementasan kali ini, lanjutnya, mereka berlatih seni peran hanya berlangsung dua bulan. Itu pun berlangsung seminggu sekali. Tentu saja durasi berlatih yang jauh dari standar.
Untuk cerita Malin Kundang misalnya, kelas IPS II harus belajar memahami budaya minang mulai pakaian, logat bahasa, dan musik. Kelas IPS I, misalnya Melza Triana Restu yang berperan sebagai Marsinah, buruh pabrik Arloji sedikit banyak harus membaca siapa sosok yang disebut sebagai pahlawan buruh itu di masa Orde Baru.
Jika Santri Dapat Waktu Lebih Luas
Sebab, sebagaimana dikatakan Abdullah Wong, seniman Lesbumi PBNU, dalam kesehariannya, para santri mempraktikkan teater. Seorang santri saat bertemu kiai akan memainkan seni peran berbeda saat bertemu temannya.
Namun, tentu saja para santri tak mendapat waktu longgar dalam berlatih tetaer sebab waktu untuk mengakji kitab kuning lebiih banyak.
Editor: Alhafiz Kurniawan