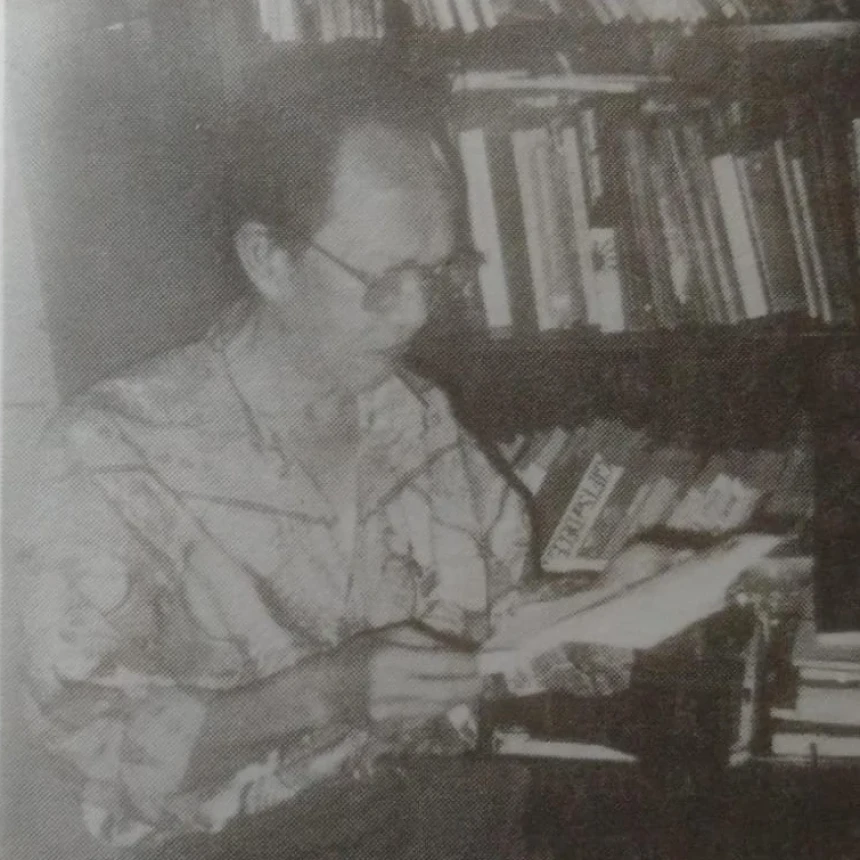Suatu sore pada 1987, Sudarman, seorang remaja, bergegas mendirikan sembahyang Ashar ketika kemudian ia bergabung dalam serombongan warga di desa yang hendak menghadiri suatu rapat akbar di Lapangan Mojosari, Mojokerto. Lokasi yang berjauhan sekitar 40 kilometer dari desa remaja culun itu di belahan utara Kali Brantas.
Ketika itu, menjadi figur panutan anak baru gede adalah Kiai Muhammad Arief Hasan dan Kiai Akhyat Chalimy, almaghfurlahum. Tokoh-tokoh itu tak selalu tampak, tapi memberikan semangat tersendiri bagi orang-orang santri untuk hadir dalam perhelatan yang menghadirkan keteduhan karena gema Shalawat Badar dengan alunan indah di telinga. Sangat berbeda ketika setiap kali menjelang sembahyang Maghrib atau Isya' dalam nyanyian pujian di langgar, yang terkesan monoton.
Remaja itu pun tersadar kini betapa di dekat lokasi rapat akbar itu ada Dusun Pekukuhan, tempat tinggal Kiai Moenasir Ali, sekretaris jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi sahibul bait. Saya terhentak ketika pembawa acara (MC) menyampaikan bahwa selain KH Muhammad Yusuf Hasyim, akan menyampaikan pidato adalah H. Mahbub Djunaidi dari Jakarta. "Lho, bukankah ini orang yang kerap kali muncul menulis di majalah Tempo?" Si remaja membatin.
Ada yang aneh dalam gaya ucapan pidato Tokoh Kita ini. Berbeda dengan kiai dan tokoh lainnya, yang perlahan menyampaikan pesan. Mahbub Djunaidi bicara seperti ayam yang mau lewat dikejar seseorang bersepeda di jalan. Kencang sekali dalam bertutur, tak mudah dikejar pemahamannya karena dialek Betawi.
Beberapa tahun kemudian, di pasar di kota kecil itu si remaja menemukan kesan mengagumkan suatu jembatan pemahaman akan tokoh-tokoh terdepan dunia, melalui terjemahan Mahbub Djunaidi. Ya, itulah karya Michael H. Hart, Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah (dari judul The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History) yang menempatkan Nabi Muhammad s.a.w. dalam urutan pertama atau "manusia paling jempolan".
Mencermati nama Mahbub Djunaidi bagi si remaja, ia teringat satu buku saku berjudul Di Kaki Langit Gurun Sinai (dari judul asli Road to Ramadhan), karya Hassanein Heikal (edisi 1979 terbitan PT Almaarif, Bandung). Ternyata, Tokoh Kita inilah yang menerjemahkannya ketika dalam penjara di masa rezim tirani Orde Baru. Seiring itu pula dilahapnya suatu memoir sastrawi, Guruku Orang-Orang dari Pesantren karya KH Saifuddin Zuhri. Sebagai remaja, Sudarman begitu terusik akan jati-dirinya sebagai santri desa setelah memahami sederet tokoh dalam masyarakat santri -- istilah Gus Dur, “pesantren sebagai subkultur”.
Tapi perlahan Sudarman, remaja itu, cermati dalam teks-teks tulisan di kolom-kolomnya kemudian, baik di Tempo maupun Kompas, gaya ucap berbahasa Mahbub Djunaidi tetap khas. Ini tipikal kiai modern, desahku. Istilah "modern" semasa itu adalah berpikiran lebih maju ketimbang sebagian besar tokoh yang terkesan berpikiran kolot dan khas orang desa. Juga dilahapnya pula tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid di Majalah Tempo, yang membuatnya semakin gandrung terhadap orang-orang pesantren yang mampu mengaktualisasikan diri, mengartikulasikan kegelisahan intelektual kepada publik secara luas.
Ketika itu telah terbit Kolom Demi Kolom-nya. Juga, Dari Hari ke Hari dan Angin Musim, dua prosa karya Mahbub Djunaidi yang memosisikan dirinya yang cerpen-cerpennya termasuk dalam pembicaraan kritikus sastra legendaris H.B. Jassin dalam Analisa: Sorotan atas Cerita Pendek (1986). Kisah tentang "Tanah Mati", Mahbub Djunaidi menghadirkan suasana romantik: suasana yang timbul karena jalinan percakapan dan lukisan alam berselang-seling, tingkah meningkah, terkesan seperti ilustrasi musik dalam pertunjukan sandiwara. Seperti suasana di hamparan alam semesta, demikian jiwa manusia di dalam, berganti-ganti dengan sewajarnya, suasana yang satu memperkuat suasana lain. Mahbub Djunaidi berkisah tentang sepasang suami istri yang rindu kehadiran seorang anak, dihadirkan begitu mesra. Kesentimentalan yang, dalam istilah Budi Darma, cenderung "melodramatis" (hyperromantis).
Dalam rapat akbar di lapangan kota kecil itu, Sudarman menyaksikan betapa luapan manusia memerhatikan dengan serius tokoh-tokoh mereka berbicara. Para tokoh itu, ulama dan kiai pesantren yang sedang memberikan penjelasan, sebagai bagian dari proses pencerahan, akan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang tengah dihadapi bersama.
Baca Juga
Ketika Mahbub Djunaidi Membela Subhan ZE
Dari rapat akbar itulah, Sudarman kemudian mencoba mengidentifikasikan dirinya: ternyata ia bagian dari kaum santri. Ia menyaksikan kehadiran para ulama di tengah masyarakat, para kiai pesantren, tokoh-tokoh agama yang peduli akan kehidupan masyarakat. Mereka berperan sebagai "agen perubahan" (agen of change) dan “makelar kebudayaan” (cultural brocker) mengajarkan kaum awam akan kesadaran beragama secara sederhana dan mudah dipahami.
Sudarman memahami telah terjadi transformasi kultural yang perlahan menjadikan kondisi masyarakat ke arah perbaikan yang nyata. Ke arah kemajuan, ke arah "modernisasi" dalam arti kerohanian memperbaiki kepribadian yang lebih menjawa sekaligus islami. Kehadiran para ulama pesantren di tengah masyarakat membawa perubahan akan sikap terhadap persoalan politik dan kemampuan menjadi keseimbangan agar masyarakat tak mudah dibodohi para penguasa yang, saat itu, cenderung mulai menampakkan kuku-kuku tajamnya akan sikap tiraninya.
Sudarman menyaksikan secara jelas, dalam suatu kampanye pemilihan umum, yang mewajibkan memilih gambar tertentu sebagai simbol tanda gambar penguasa. Syukurlah, dengan hadirnya para ulama dan kiai pesantren, memberikan arah jelas bagi sikap dan pilihan politik yang benar-benar mengarahkan pada pilihan yang lebih rasional, dengan nada-nada kekritisan kepada penguasa.
Para ulama dan kiai pesantren, memiliki jalinan erat dengan para santrinya. Mereka kemudian mengajarkan Islam di langgar-langgar, dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami. Tentang persoalan sederhana, dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tata cara sembahyang lima waktu, hingga masalah-masalah kehidupan di kalangan masyarakat perdesaan yang ditilik dari sudut pandang keagamaan.
Para ulama dan kiai pesantren itulah yang tersambung ilmu dari guru ke guru, dan seterusnya (sanad atau geneaologi keilmuan) dengan guru-gurunya terdahulu hingga para Rasulullah s.a.w. Mereka itulah ulama’ warasatul anbiya’ (pewaris para nabi). Segera si remaja teringat guru-gurunya, yang mengajar di langgar dan ruang kelas di pesantren. Si remaja pun teringat akan suatu pidato, dalam suasana haru di hatinya:
Ayyuhal 'ulama ul-atqiya'! Antum khazanatul islam wa abwabu hu. Wa laa tu'tul buyuta illaa min abwaabiha. Faman ataaha min ghairi abwaabihaa summiya saariqan! (“Wahai para ulama yang ahli takwa! Saudara-saudara adalah perbendaharaan Islam dan pintu-pintunya. Jagalah, jangan hendaknya orang memasuki rumah kecuali melalui pintu-pintunya. Hanya pencurilah memasuki rumah tanpa melalui pintu...!”)
Pesan sangat memesona bagi Sudarman, terucap dari Hadlratussyaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Para ulama dan kiai pesantren adalah pintu-pintu ilmu bagi pemahaman keagamaan Islam bagi para santri, juga si remaja culun yang berusaha memahami diri pribadinya.
Begitulah kesadaran, pemahaman Sudarman terhadap eksistensi para ulama dan kiai pesantren, melalui kehadiran Mahbub Djunaidi. Melalui Tokoh Kita ini, juga pemikiran Abdurrahman Wahid. Khusus kiai dari Pesantren Ciganjur, yang dikenalnya sebagai Gus Dur, menjadi cerita dari mulut ke mulut para santri saat itu, sebentuk kekaguman akan kemampuannya menghafal buku, bahkan mengetahui persis tentang topik permasalahan yang dibacanya hingga pada halaman buku yang dibacanya itu.
Mahbub Djunaidi dan Gus Dur menjadi inspirasi Sudarman, dalam menyongsong masa depannya. Kedua Tokoh Kita membuktikan eksistensi orang-orang pesantren yang meskipun diperolok sebagai udik dan kampungan, tapi berpikiran kosmopolit dan lebih maju -- tanpa meninggalkan identitas dan performa sederhana berbusana khas dalam sehari-harinya.
Mahbub Djunaidi dan Gus Dur adalah inspirasi setiap santri yang mencita-citakan kemajuan. Cita-cita yang memberikan harapan hari depan, dengan kemampuan mengartikulasikan gagasan dan mengambil bagian dari proses pencerahan di tengah masyarakat yang terus berubah. Juga bagi Sudarman, sebagai bagian pengalaman perjalanan hidupnya kemudian mengenal Muchtar Lubis, Goenawan Mohamad, Yosar Anwar, Y.B. Mangunwijaya, Onghokham, dan mereka yang tampil sebagai intelektual publik. Mereka mengajak bersikap kritis dalam memahami setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan perspektif masing-masing.
Begitulah sosok Mahbub Djunaidi di mata Sudarman. Mata seorang remaja yang segera berproses mengukir hari-hari depannya.
Politik Keadaban, Partisipative Society
Dalam kolomnya yang memikat, "Andaikata" ia membayangkan mengajak masyarakat ikut berperan dalam derajat yang sama dengan pemerintah (Asal Usul, Kompas 30 Juli 1989). Ia mengetengahkan pandangan Charles de-Gaulle yang menghendaki negerinya menjadi suatu masyarakat partisipative society dan bukan masyarakat bengong dan dalam keadaan serba was-was. Dalam partisipative society, tercipta suatu timbal balik yang berimbang, antara pemerintah di satu pihak dan rakyat di pihak lain, bekerja atas dasar sukarela dan saling menguntungkan atau dalam bahasa yang mudah dipahami awam "besar sama dipikul ringan sama dijinjing".
Dalam situasi saat ini di Indonesia, ketika setiap orang bebas berbicara dan mengemukakan pendapat. Reformasi bergerak sejak Mei 1998, sejak itu memberikan jejak yang terkadang tak sedap karena orang-orang bicara tanpa kendali: adab dan keadaban tak lagi menjadi perhitungan di depan publik. Berbeda ketika masyarakat di bawah rezim tiran, seperti pada masa rezim Orde Baru, pemerintah bersikap gertak menekan (represif). Mahbub Djunaidi mengajak kritis, pada zaman itu.
Dalam partisipative society, diingatkan Tokoh Kita, bersama-sama mencari titik keseimbangan antara pemerintah dan rakyat, segala sesuatu diputuskan menurut pertimbangan suara. Penguasa berusaha senantiasa mencari persesuaian dengan rakyat dan tak menggunakan tangan kekuasaan untuk menindas. "Tak ada untung terlalu untung sebagaimana tak ada yang merugi berlebihan," tutur Mahbub Djunaidi. Partisipative society, memelihara keseimbangan sewajarnya: antara memberi dan menerima berada dalam keadaan menyenangkan pihak bersangkutan.
Memerhatikan pemikiran ini, di masa ketika reformasi pemerintahan berlangsung lebih dari 27 tahun (sejak Mei 1998) kita menyaksikan panggung kebebasan begitu terbuka. Siapa saja bisa berbicara. Siapa saja boleh mengungkapkan pendapatnya. Sayangnya, ada yang tak substansial dalam mengungkapkan pendapatnya atau bahkan lebih cenderung mengedepankan kebencian pribadi dan bukan mencari penyelesaian bersama.
Kesadaran Artikulasi Gagasan
Di antara tokoh NU, Mahbub Djunaidi telah memberi harga lebih terhadap eksistensi dan ketokohannya. Penulis yang prolifik, dan menorehkan monumen pemikirannya dalam buku. Saya membayangkan, andaikata Tokoh Kita masih berkesempatan menghirup udara segar tentu akan menyampaikan sikapnya dengan jenaka. Ketika seorang wapres mulai bertugas, menyusul saat-saat pelantikannya, berkemas-kemas memasukkan barang-barang mainnya seperti kanak-kanak yang tak lepas dari mobil-mobilan dan boneka mainan. Berbanding terbalik dengan Bung Hatta, yang selalu bergulat dengan ilmu, bernapas di tengah tumpukan buku, sebagai bagian dari hidupnya. Buku-buku itulah “pacarnya”.
Mohammad Hatta pada masa pendidikan di negeri Belanda, menulis tentang masa depan negerinya, Republik Indonesia yang dicita-citakan, sekaligus memublikasikan artikulasi pemikiran di media-media, baik di Belanda maupun di Indonesia. Saat dipenjara di Bandaneira bersama Sutan Sjahrir, dkk, Bung Hatta pun rela "asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas".
Dalam menyampaikan artikulasi pemikiran, sifat dan kejujuran menjadi taruhan. Ada pesan Bung Hatta yang selalu aktual, "Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki".
Demikian pula bagi founding father kita yang lain. Sutan Sjahrir sejak remaja telah memiliki kesadaran menulis pada buku harian. Ketika dalam masa pengasingan, sebagai konsekuensi perjuangan untuk bangsanya, di Bandaneira dan Boven Digul, ia menuangkan renungan-renungannya demi Indonesia. Bung Karno telah mendokumentasikan pemikirannya saat muda dalam bukunya, Di Bawah Bendera Revolusi -- merupakan gagasan yang menyangkut ideologi-ideologi besar dunia yang akan ditanam di bumi Indonesia.
Di kalangan pesantren, KH Abdul Wahid Hasyim dikenal sebagai persona yang melahap habis suratkabar dan majalah, baik berbahasa Indonesia maupun Arab, semasa di masa perkembangan pribadinya di Pesantren Tebuireng Jombang. Ia pun menghadirkan dirinya dalam artikulasi pemikirannya di media-media umum sebagai ikhtiar untuk kemajuan Indonesia di masa depan.
Mahbub Djunaidi, mengambil bagian dari proses panjang bersama KH Saifuddin Zuhri, saat memimpin surat kabar Duta Masjarakat, menghadirkan pemikiran-pemikiran segar para intelektual publik pada zamannya. Mahbub Djunaidi kemudian dikenal sebagai kolomnis dan KH Saifuddin Zuhri dikenal sebagai penulis prolifik tentang politik dan sejarah Islam di Indonesia.
Berkembangnya teknologi informasi mendorong terjadinya perubahan dalam konteks literasi. Literasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kesadaran melek aksara, kemampuan dan kecakapan baca tulis guna didalami setiap permasalahan, mengartikulasikan gagasan itu, dan disosialisasikan kepada masyarakat. Literasi media menjadi salah satu bentuk di literasi yang secara tak langsung tak terlepas dari informasi. Informasi menjadi hal paling penting dalam kehidupan manusia. Dengan informasi manusia dapat melakukan pelbagai macam hal dan tindakan.
Memang, pada masa Mahbub Djunaidi tak mengenal istilah literasi yang dijejalkan di forum-forum publik. Kini ada istilah literasi media, ketika media sosial menguasai setiap ruang-ruang pribadi kehidupan kita. Awal literasi media berisi kajian tulisan dan diskusi di kalangan para pakar atau ahli komunikasi semata. Namun, seiring perkembangan waktu menjadi suatu gerakan yang dilakukan para aktivis dan organisasi media guna secara nyata memberikan pendidikan untuk memahamkan pentingnya kemampuan literasi media dalam menghadapi konten-konten yang disajikan media sosial.
Mahbub Djunaidi membukakan mata kita akan pentingnya artikulasi gagasan. Pemikiran yang ditorehkan, renungan yang dihikmati dalam setiap persoalan kehidupan, dimonumenkan dalam buku. Tokoh Kita mengingatkan akan kepribadian para Pendiri Negeri RI, yang sejak muda mencitrakan dirinya sebagai intelektual dan pemikir bebas, yang berorientasi pokok demi kemajuan dan kebaikan bangsanya. Pada ujungnya, pemikiran founding father kita, menjadikan Pancasila sebagai puncak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. "Pancasila lebih sublim dari Declaration of Independence-nya Thomas Jefferson dan Manifesto Komunis-nya Karl Mark," pesan Mahbub Djunaidi.
Dari Kitab Mein Kampf ke Banser
Tokoh Kita berperan penting bukan sekadar ketika kader-kader muda NU dipinggirkan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan kemudian membentuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tempat Mahbub Djunaidi tampil sebagai ketua umum pertama. Mahbub Djunaidi pun berperan atas terbentuknya barisan khusus dari Gerakan Pemuda Ansor. Kiai Muhammad Yusuf Hasyim menuturkan bahwa ide pembentukan Banser (Barisan Ansor Serbaguna), sebagai barisan paramiliter yang eksis hingga kini, tak lepas dari referensi sahabat karibnya, Mahbub Djunaidi. Tokoh asal Betawi ini mengambil spirit Adolf Hitler melalui kitab Mein Kampf. Saat mengumpulkan data-data perjuangan para kiai untuk Museum Nahdlatul Ulama sebelum diresmikan KH Abdurrahman Wahid pada Desember 2004, saya pun sempat mendapat kisah soal pasukan paramiliter ini dari Kiai Yusuf Hasyim di Pesantren Tebuireng, Jombang.
Dalam Mein Kampf, disadari Mahbub Djunaidi bahwa Hitler menulis tentang ideologinya dan menampilkan dirinya sebagai pemimpin sayap kanan ekstrem. Sang Fuhrer bercerita tentang kehidupan dan masa mudanya, "pertobatannya" menjadi antisemitisme (kebencian terhadap orang Yahudi) dan waktunya sebagai seorang prajurit dalam Perang Dunia I. Terasa sikap Hitler marah besar terhadap Perjanjian Versailles (1919) dan ganti rugi yang harus dibayarkan Jerman karena Perjanjian tersebut. Memang, berdasar perjanjian itu, negara-negara besar penjajah seperti Perancis dan Inggris, menjadi mandataris dari Liga Bangsa-Bangsa. Mereka mempunyai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Liga Bangsa-Bangsa setiap tahun atas mandat yang dimilikinya. Hitler akhirnya pun tak percaya pada demokrasi parlementer.
Mein Kampf penuh dengan ide-ide rasis dan kebencian terhadap kaum Yahudi dan komunis. Dalam Mein Kampf, Hitler pun menulis tentang masa depan Jerman. Ia ingin memperluas wilayah Jerman di Eropa Timur dan mengusir orang-orang Yahudi dari Jerman, karena ia yakin mereka mengancam kelangsungan hidup rakyat Jerman. Meskipun Mein Kampf tidak merujuk pada pembunuhan massal orang-orang Yahudi di kemudian hari selama Perang Dunia Kedua (holocaust). Namun, kitab inilah menunjukkan bahwa ia telah mengembangkan kebencian terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu.
Lepas dari isi kitab peninggalan Adolf Hitler yang isinya mengerikan itu, Mahbub Djunaidi mengambil inspirasi bagi kemaslahatan negerinya, mengoptimalkan peran kaum santri dalam menjaga tokoh-tokohnya, pemuka masyarakat dan kecintaan pada negerinya. Banser bukan paramiliter yang ditakuti karena menindas dan berkarakter preman, melainkan justru memberi rasa aman dan keteduhan di tengah masyarakat majemuk di negeri ini.
Kehormatan ulama dan kiai pesantren adalah utama bagi Banser -- tertanam sejak awal berdirinya -- dan menjaga keselamatan para tokohnya. Pada saat para kiai dan NU mendapat gangguan, Banser hadir membela dan mengamankannya. Lebih dari itu, di tengah suasana gejolak dan gejala intoleransi, radikalisme dan terorisme, Banser hadir untuk mengambil langkah penting agar setiap umat beragama tenang dalam menjalankan ibadahnya.
Meskipun mengambil inspirasi dari kitab Mein Kampf yang cenderung rasis, Banser justru menolak sikap rasis dan menindas. Bahkan, justru Banser akan membela mereka yang minoritas dan cenderung disisihkan dari tata pergaulan bersama. Banser, sebagaimana nilai-nilai ajaran Ahlussunnah wal-Jamaah bersikap toleran (tasamuh), moderat (tawasuth), proporsional (tawazun), dan tegak lurus (i’tidal) serta berlomba-lomba untuk mengajak kebaikan dan mencegah munculnya kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar).
Mahbub Djunaidi mengambil spirit dari kitab Mein Kampf agar kaum santri tegak dalam jalur perjuangannya. Perjuangan selaras yang digariskan para muassis, generasi founding father NU, dan ulama yang jelas tergolong dalam waratsatul anbiya’.
Kesadaran Sejarah
Pada diri Mahbub Djunaidi, juga Gus Dur, KH Saifuddin Zuhri dan KH Achmad Sjaichu, terdapat kesadaran sejarah dalam pergumulan hidupnya. Bagi Tokoh-Tokoh Kita, sejarah bukanlah sekadar masa lalu yang diam melainkan guru kehidupan yang bijaksana. Sejarah bukan hanya mengajarkan tentang perjuangan, jerih payah dan kejayaan, melainkan juga kegagalan-kegagalannya. Sejarah pula memahamkan dengan tuturan kisah tentang kebijaksanaan dan kebodohan, tentang cinta kasih dan kebencian. Setiap sejarah bukanlah milik suatu bangsa atau kelompok semata, tetap sejarah umat manusia dan berhak dimiliki setiap warga bangsa di mana pun berada.
Tokoh-tokoh yang lain, KH Hasyim Muzadi, begitu gandrung dengan sejarah hidup Napoleon Bonaparte, meskipun tetap menempatkan Sirah Nabawiyah dan Qishashul Anbiya’, pada deretan teratas yang dipahaminya. Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama, Pendiri Pesantren Al-Hikam (Malang dan Depok), duduk setara dengan George W. Bush, Presiden Amerika Serikat (zaman terorisme melanda dunia), saat menyampaikan pemikiran-pemikiran Islamnya. Juga kefasihannya berbicara soal perdamaian dunia bersama Pangeran Charles dari Britania Raya.
Dengan mempelajari sejarah, juga tokoh-tokoh sejarah, kita dapat memahami diri kita sendiri, masyarakat kita, dan dunia di sekitar kita. Sejarah sebagai sumber inspirasi yang selalu menyegarkan. Kisah-kisah tentang para pahlawan, pemimpin, dan pemikir besar, aktor-aktor protagonis dalam sejarah, dapat membangkitkan semangat dan memotivasi untuk mencapai cita-cita. Memahami sejarah, sekaligus mengetahui karakter antagonis pada aktor sejarah, pengkhianatan dan pewaris kebencian dan dendam.
Peristiwa-peristiwa sejarah, yang besar maupun yang kecil, memberikan percikan hikmah dan pelajaran berharga. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat belajar dari kesalahan orang-orang terdahulu, menghindari terulangnya tragedi serupa, merancang harapan baru bagi masa depan yang lebih baik. Mahbub Djunaidi mengenal dekat aktor-aktor sejarah kita, mulai Bung Karno, Inggit Ganarsih, Adam Malik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Moamad Roem hingga Singgih yang PETA.
Mencermati setiap tulisan Mahbub Djunaidi, yang kritis dan jenaka, saya merasakan seperti membuka dialog-dialog Plato dalam Republik-nya. Seperti mencermati Niccolo Machiavelli dalam Diskursus-nya.
Setiap hari, kita semua adalah bagian dari sejarah yang sedang ditulis. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak di kanvas waktu. Oleh karena itu, marilah kita menulis sejarah kita sendiri dengan tinta emas, dengan berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban manusia.
Ketika ada informasi suatu dokumen awal pendirian NU, organisasi yang dicintai hingga akhir hayatnya, ditemukan data kehadiran seorang pejabat Hindia Belanda, Mahbub Djunaidi menghadapi dengan kritis. “Buka semua, sampaikan sejarah dengan kejujuran. Sejujur-jujurnya,” respon Mahbub Djunaidi, dalam suatu seminar di Universitas Nusantara, Bandung. Ia menekankan sikapnya: Sejarah adalah cermin yang memantulkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan ke mana kita akan melangkah. Sejarah adalah kompas; ia membimbing menuju masa depan yang lebih cerah.
Akhirul kalam. Mahbub Djunaidi menjejakkan eksistensinya hingga kita. Eksistensi keilmuan yang terus bisa digali dari karya-karya pemikirannya. Ia adalah pejuang pena, lewat tulisan-tulisannya kritis bersikap pada zamannya. Pena adalah pedang yang selalu diasah, guna menghadapi situasi sulit akibat sikap para penguasa. Mahbub Djunaidi mengasah pedang pena demi menyadarkan masyarakat akan pentingnya politik keadaban.
Di luar perbincangan ini, ada pesan lirih terdengar. Dengan perlahan Hadlratussyaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, membisikkan pesan: Ayyuhal 'ulama ul-atqiya'! Antum khazanatul islam wa abwabu hu. Wa laa tu'tul buyuta illaa min abwaabiha. Faman ataaha min ghairi abwaabihaa summiya saariqan! (“Wahai para ulama yang ahli takwa! Saudara-saudara adalah perbendaharaan Islam dan pintu-pintunya. Jagalah, jangan hendaknya orang memasuki rumah kecuali melalui pintu-pintunya. Hanya pencurilah memasuki rumah tanpa melalui pintu...!”)
Oh, ya. Pesan yang ini sepertinya tak terkait langsung dengan Mahbub Djunaidi. Tapi indah dalam memahami ilmu keagamaan dan jalur kerohanian di kalangan pesantren dan kaum santri.
Riadi Ngasiran, Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) PWNU Jawa Timur, Ketua Tim Kerja Monumen Resolusi Jihad NU Surabaya