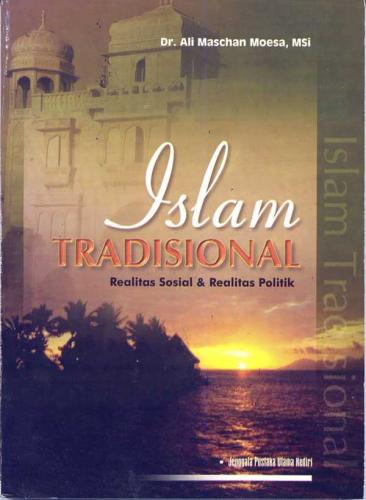Penulis: Dr Ali Maschan Moesa
Penerbit: Jenggala Pustaka Utama
Cetakan: I, September 2008
Tebal: vii, 199 hlm.
Peresensi: Ahmad Shiddiq Rokib
Khittah NU 1926 yang diputuskan pada Muktamar di Situbondo, Jawa Timur, adalah upaya ulama untuk memosisikan NU pada jalan yang benar dalam relasi negara dan agama. Meski pada pra-wacana, bersinggungan dengan situasi politik di tubuh NU yang kurang menguntungkan dan selalu dinomerduakan dalam pengambilan keputusan strategis. Sehingga wajar kalau politik yang dimainkan selalu berubah-ubah wajah dari satu ideologi ke ideologi lain, puncaknya ditandai keputusan NU kembali Khittah pada Muktamar Situbundo.<>
Posisi yang seperti itu, sangatlah menguntungkan saat NU yang mulai kehilangan jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan dan menjadi kekuatan oposisi kerakyatan dalam upaya membangun gerakan moral dalam membendung kekuatan pemerintahan diktator, sehingga saat itu hubungan NU dan pemerintah agak renggang, kemudian kegiatan yang dilakukan NU selalu dicurigai dan diawasi pemerintah.
Nah, pada Muktamar 30 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, ditegaskan bahwa warga NU memilih partai secara bebas, kritis, rasional, dan berdasarkan nilai-nilai Khittah 1926, etika politik. Kemudian tepat saat Muktamar ke-31 Bayolali, Jawa Tengah, merekomendasikan 10 program dasar lima tahun yaitu institusional building, pemikiran keagamaan, pemberdayaan sumber daya manusia dakwah, pengembangan ekonomi, pemberdayaan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan jaringan kerja, pelayanan sosial, dan mobilisasi dana.
Dari dua Muktamar, berlangsung kelembagaan NU menjadi ikon polemik bagi penikmat politik antara pelibatan NU dalam politik dan menjaga netralitas sebagai wujud Khittah 1926.
Sehingga, Muktamar menjadi ajang perebutan tiket kekuasan oleh elit-elit berkepentingan. Dan, tidak heran, meski di Muktamar Boyolali memutuskan bahwa organisasi ini perlu menegaskan kembali etika berpolitik warga NU yang diputuskan saat Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta, yaitu, pertama, NU melepaskan diri ikatan semua politik yang ada dan sekaligus menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Kedua, bagi warga NU, baik yang berada di dalam struktur kepengurusan di semua tingkatan, maupun yang berada di luar struktur, diperbolehkan memilih partai poltik sesuai aspirasinya masing-masing dengan selalu menjaga keutuhan jamiyah dari segala bentuk perpecahan.
Tetap saja, NU terseret politik untuk meraup suara banyak dan lebih terasa intensitasnya bagi NU sejak dideklarasikannya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sekaligus menjadi pesaing berat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terlebih dahulu lahir yang dibidani ulama (halaman 124).
Dari hegemoni politik tesebut, berimbas pada pola pikir kiai pesantren dalam mengembangkan umat meski tidak semua pesantren terpengaruh keruh politik. Seharusnya pesantren tetap pada komitmen awal bahwa sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi peminpin umat dan menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya, tentu menjadi mempunyai dasar pijakan keagamaan dalam melakukan tindakan, terutama hal yang dianggap oleh masyarakat.
Kalaupun demikian, kiai pesantren dalam pemberdayaan umat tak seharusnya menjadikan kedudukan tersebut disalahgunakan, apalagi menjadikannya sebagai legiteiasi politik kekuasaan.
Karena kedudukan yang mulia dari kiai menyebabkan masyarakat memandang mereka bukan semata-mata pemuka agama, melainkan juga pemimpin masyarakat. Dari hal itu, masyarakat membutuhkan bimbingannya (irsyad), ketauladan (uswatun hasanah), pengarahan (taujihat) seoarang ulama. Walhasil, para kiai memegang kendali legitimasi dan pandangan serta keputusannya mudah diterima dan dikuti masyarkat (halaman 116).
Buku yang ditulis Dr KH Ali Maschan Moesa ini tidak hanya berbincang tentang NU dan pesantren, tapi juga bagaimana membangun tatanan masyarakat yang prulalis, religius, kesehatan serta problem masyarakat sehari-hari.
Judul buku “Islam Tradisional, Realitas Sosial dan Realitas Politik” hendak mengetengahkan sekaligus pembacaan mantan ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu terhadap perubahan-perubahan politik dan sosial yang tengah terjadi akhir-akhir ini. Tentunya perubahan tersebut tidak lepas dari cara pandang yang kian mengarah pada keabsurdan dalan melihat realitas hidup dan perjuangan. Pandangan cerdas yang tertuang dalam buku ini akan menjadi tidak bermakna, jika tidak dibarengi implementasi yang baik oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap realitas sosial dan politik tersebut.
Sehingga, amatlah tepat kalau para penikmat dinamika politik dan pesantren menjadikan buku ini sebagai bacaan sumber informasi, apalagi penulisnya bisa dikata sudah menjadi ikon dalam NU, politik dan pesantren.
Setiap manusia, baik pribadi atau kelompok, jika menghadapi suatu keputusan dalam konteks kesejarahan, maka sikap arif adalah diam sejenak, menarik napas, lalu berkata dengan tenang, ”Kami termasuk orang yang tidak berandai-andai dengan sejarah yang sudah berjalan dengan perubahannya, dan kita harus menghadapinya dengan realistis. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pilihan lain, tetapi, kita dapat belajar dari sejarah, dengan kata lain ’yang senantiasa berubah adalah perubahan itu sendiri’.”
Peresensi adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya