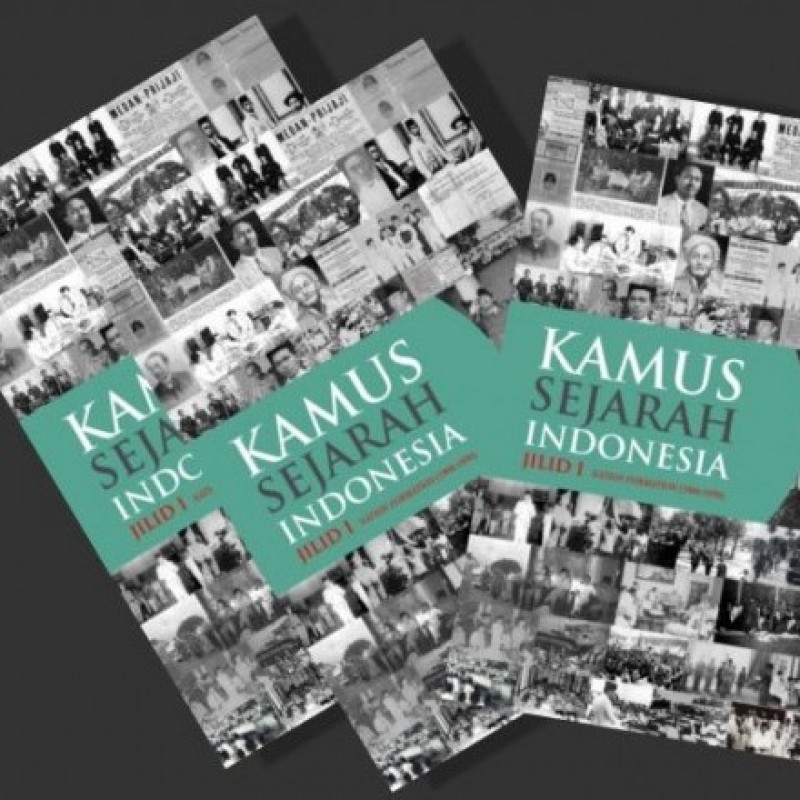Oleh Adhi Ayoe Yanthy
Sindroma menjadi rezim bisa menimpa siapa saja, bahkan pada orang orang yg katanya khatam membaca epistemologi paling kritis sekalipun. Bekerja dengan memahami ada yang liyan di antara kita, justru harus dibuktikan ketika kita berkuasa. Bukannya sekadar berbalik menjalin kerja sama dengan orang orang yang posisinya pernah ada secara marginal.
Sederhana saja, sejarah keindonesiaan dan pendokumentasiannya dalam bentuk apapun bukan sebatas mengubah pihak yang kalah jadi menang dan yang menang dikalahkan.
Kita ini sedang bekerja membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mampu mengapresiasi peran setiap warga dalam kesejarahannya untuk menguatkan konsensus pilihan founding fathers republik ini.
Kita bekerja untuk menihilkan tradisi tidak sehat, "sejarah milik penguasa". Di mana dokumentasi sejarah tersebut bisa dipakai sebagai pijakan untuk memudahkan generasi mendatang melangkah bersama, menjauhi luka masa lalu yang mungkin saja kita korbannya bahkan tidak mustahil sebagai pelakunya.
Kasus penyusunan item Kamus Sejarah Indonesia oleh Kemendikbud berkembang menjadi gesekan di antara kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana tesis Sukarno tentang Indonesia di tahun 1927, yaitu kelompok Nasionalisme-Islamisme-Marxisme.
Kesemuanya saat proklamasi secara hukum dikonstruksi dengan berbasis pada gerak komunitas lokal di Nusantara menjadi Indonesian, yang satu sama lain tidak menihilkan peran kesejarahannya dalam kerja untuk kedaulatan Indonesia.
Di masa Orde Baru, Harsja W. Bachtiar mempertanyakan logika penulisan sejarah perempuan Indonesia di masa itu, yang menempatkan Kartini sebagai ikon. Padahal di masa pra Republik Indonesia Kartini dengan feodalisme Jawanya dianggap segaris dengan kebijakan politik etis pemerintahan kolonial.
Polemik itu bisa dijadikan rujukan, penulisan sejarah yang sekadar membolak balik posisi dan status pemihakan politis seseorang, pada akhirnya membuat perspektif emansipasi dan partisipasi aktif di masyarakat tidak berkembang secara substansial.
Masa reformasi, membuka ruang bagi semua kelompok masyarakat berperan di ruang publik. Namun rezim berkuasa tetap harus berkomitmen mewujudkan kebinekaan yang ada sebagai satu kesatuan ideologi untuk menatap Indonesia ke depan.
Kesadaran dan kerja rezim sangat diperlukan untuk mengembangkan kebinekaan menjadi satu solidaritas. Karena Pancasila sebagai sistem nilai harus menjelma dalam praktik pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Pancasila tidak semata menjadi statuta dogmatisme bagi kepentingan rezim untuk meneguhkan 'status quo' kekuasaannya.
Pada praktiknya, kita sering melupakan pemikiran Sukarno tentang 'Pancasila sebagai bintang penuntun yang dinamis' yang membuka ruang dialektika historis dari semua kelompok dalam penguatan rasa kepemilikan NKRI tanpa diskriminasi. Di dalamnya ada kerja membangun kesadaran menjadi kita Indonesia, bukan sekadar aku yang berkuasa. Emansipasi itu ada pada tindakan, bukan saat berorasi.
Penulis adalah Sekretaris Jenderal Pergerakan Sarinah
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
4
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua