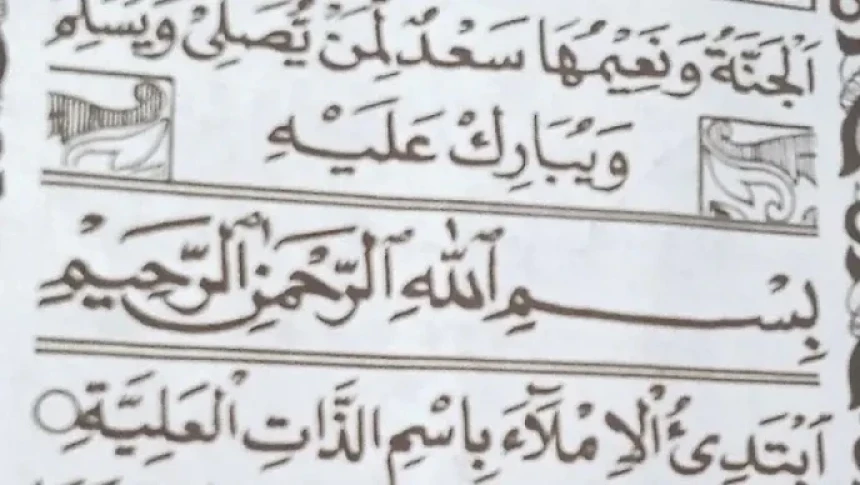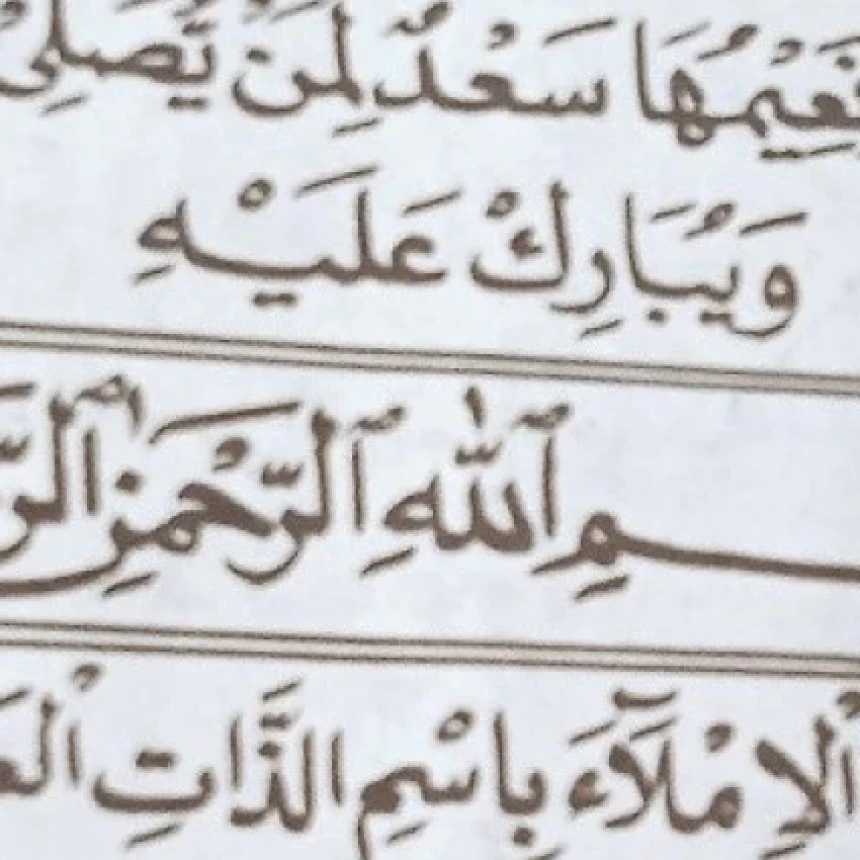Pujian Puitis dalam Kitab-Kitab Maulid dan Mimpi Bertemu Nabi sebagai Transformasi Ilmu
NU Online · Kamis, 28 September 2023 | 22:30 WIB
M. Faizi
Kolomnis
Acara peringatan Maulid Nabi erat hubungannya dengan kitab Maulid. Apa itu? Sebuah buku syair/puisi yang berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad serta sekelumit kisah kelahirannya. Ada banyak buku seperti ini, bahkan ulama-ulama besar dahulu banyak pula yang menyusun kitab Maulid. Yang masyhur di Indonesia tentu saja adalah Barzanji karya Sayyid Jakfar al-Barzanji dan Dayba’i atau Diba’i/Diba’ karya Imam Abdurrahman al-Dayba’i.
Di luar itu, terdapat kitab Burdah karya Imam al-Bushiri. Kitab ini cenderung dibaca terpisah dan tidak secara khusus dibacakan di bulan Maulid—mungkin karena lebih banyak mengandung semata madah (sebetulnya al-Bushiri juga memiliki karya yang berjudul Hamziyah, yaitu buku puisi yang menghimpun 456 larik dan rimanya berakhiran huruf hamzah. Kitab ini dibuatkan syarah oleh Ibnu Hajar al-Haitami dengan judul Al-Minahul Makkiyah).
Secara umum, buku-buku atau kitab-kitab tersebut mengandung puji-pujian (madah) dan kisah kelahiran Nabi Muhammad. Bentuknya pun nyaris sama, yaitu kombinasi antara puisi bersajak dan diselingi narasi berbentuk prosa (lirik). Penerbit-penerbit di Indonesia kerap mengumpulkan semua itu dalam satu paket buku.
Salah satu kitab Maulid lokal adalah Maulidul Mahmud yang berasal dari Madura. Kitab ini disusun oleh Habib Alwi bin Abu Bakar Bilfaqih (Sumenep). Sebuah majelis shalawat di Yogyakarta, Muhyin Nufus, membacakan shalawat dari kitab ini dalam rutinannya di seputaran DIY dan eks-Karesidenan Kedu serta sebagian Jawa Tengah bagian utara. Yang unik, Maulidul Mahmud tidak populer di Sumenep dan hanya dibacakan di kalangan sangat terbatas, terutama saat perayaan haul pengarangnya. Satu lagi yang muncul adalah Sintong, yang merupakan seni tradisi lama yang nyaris punah dan kini kembali bergeliat di kota ujung timur pulau Madura tersebut. Isinya adalah pujian untuk Allah dan madah nabawi.
Sementara itu, Simtud Duror, sebuah buku Maulid karangan Al-Habib Ali al-Habsyi, kira-kira dalam 10-15 tahun belakangan mulai dikenal luas di Madura. Sejauh ini jarang sekali yang membacakannya kecuali di beberapa kota di Jawa dan Kalimantan. Hal itu—menurut sementara perkiraan—adalah seiring dengan popularitas bentuk tabuhan pengiring yang disebut Banjari, sebagaimana populer di Sekumpul, Martapura, berkat Guru Ijai dan munculnya Habib Syekh di Solo dan Habib Ali Zainal Abidin dan Azzahari di Pekalongan.
Di Madura dan area Tapal Kuda, umumnya masyarakat mempunyai cara sendiri dalam bermaulid. Biasanya, mereka menggunakan bacaan dari Dayba’i untuk posisi duduk (julus) dan menggunakan Syaraful Anam atau Barzanji atau Simtud Duror saat posisi berdiri (qiyam) atau sebaliknya. Adapun madah maupun salawat yang dibacakan menggunakan hadrah (5 terbang tanpa darbuka dan tanpa marawis) di luar acara Maulid biasanya dicuplik dari kitab Diwan Hadrah, sebuah antologi madah yang lazim digunakan untuk pementasan hadrah dan tari rodad.
Di balik kisah mimpi bertemu Nabi
Mimpi bertemu Nabi dikisahkan dalam kitab Roaitun Nabi bahwa Sa’ad al-Asadi bertemu Nabi dalam mimpi dan ditanya asal usulnya. Nabi juga menanyakan apakah Sa’ad kenal dengan seseorang bernama Kumait bin Zaid. Sa’ad kaget karena Kumait adalah seorang penyair dan kebetulan memang pamannya sendiri. Lalu, Nabi meminta Sa’ad membacakan puisi karya Kumait dan ia pun membacakannya. Di akhir mimpi, Nabi berkata, “Besok pagi, sampaikan salamku untuknya, lalu katakan kepadanya bahwa ‘Allah mengampunimu karena kasidahmu ini!’”
Tak terbayangkan, betapa bahagia sang paman dan keponakannya itu. Sa’ad bahagia karena bermimpi dan Kumait lebih bahagia karena mendapatkan salam istimewa dari orang paling istimewa yang perantaranya tak lain adalah kasidah—puisi sanjungan yang ia tulis untuk Sang Junjungan, Nabi Muhammad SAW.
Sebagaimana kita tahu, tidak banyak orang yang berani menceritakan bahwa dirinya telah bermimpi bertemu Nabi. Padahal hampir semua Muslim mendambakannya. Mengapa? Karena memang ada larangan untuk menceritakannya dengan beberapa perkecualian (seperti kepada orang-orang tertentu yang sekiranya dapat dipercaya).
Aturan main seperti itu agaknya sudah masyhur di kalangan umat Islam. Dalam Islam, mimpi bukanlah sekadar bunga tidur, lebih-lebih jika ia berhubungan dengan orang saleh, apalagi Nabi. Ia lebih dari sekadar pandangan sains yang menganggapnya sebagai aktivitas otak yang sedang berfungsi sama dengan di saat terjaga serta sebagai proyeksi ide-ide seseorang di kala bangun lalu mengendap dan “terlahir kembali” di luar kendalinya. Sementara kisah Saat dan Kumait itu bukanlah sekadar tentang mimpi, melainkan dengan salawat dalam bentuk puisi/kasidah.
Apa yang tergambar di atas juga terjadi pada al-Bushiri dan Habib Ali al-Habsyi serta ulama lain yang juga menulis madah/kasih atau puisi-puisi pujian untuk Nabi. Konon, al-Bushiri suatu saat mandek saat ia menulis selarik puisi Burdahnya, tepatnya pada larik berikut.
فمبلغُ العلمِ فيهِ أنهُ بشرٌ
Artinya, : “Puncak pengetahuan menyatakan bahwa dia hanyalah manusia”
Kemudian—melalui mimpi—diteruskan sendiri oleh Nabi, dilengkapi dengan kalimat berikut.
وأنهُ خيرُ خلقِ اللهِ كلهمِ
Artinya, “Namun dialah yang terbaik di antara semua ciptaan sarwa-semesta.”
Dengan demikian, bait yang semula rumpang itu menjadi sempurna.
Selain Burdah, ada pula kisah bagaimana Nabi membacakan Simtud Duror. Hal ini terjadi dalam mimpinya seorang murid dari sang pengarang, yakni Habib Ali al-Habsyi. Sementara Habib Ali sendiri malah sering bertemu dalam keadaan terjaga (yaqazatan). Begitu juga dengan kisah kontemporer tentang salam dari Nabi kepada Ahmad Syauqi, penyair besar Mesir yang lirik-lirik puisinya banyak dinyanyikan oleh Ummu Kultsum, seperti Saalu Qalbi dan Wulidal Huda. Sementara yang paling masyhur di antara itu semua adalah yang dialami oleh Syekh Ahmad al-Marzuqi al-'Asy'ari saat menyusun Aqidatul Awam dan semuanya terjadi melalui mimpi.
Begitu berharganya shalawat dan madah nabawi hingga Nabi sendiri yang menyapa sang pengarang, baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan terjaga. Itulah mengapa diyakini bahwa mimpi (yang benar) adalah bagian dari kenabian. Sebab itu pula, berdusta atau mendustakan mimpi (apa pun) adalah dosa besar karena luhurnya mimpi sebagai bagian dari transformasi hikmah dan ilmu pengetahuan.
M Faizi, pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
4
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
5
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua