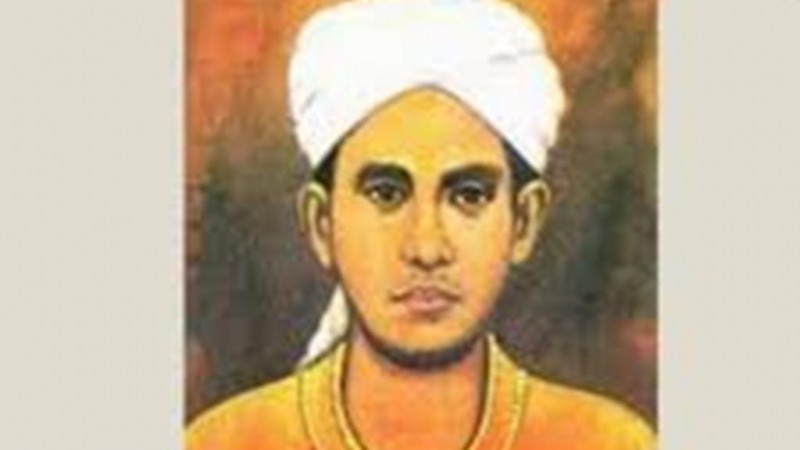Relasi Ajengan dan Santri pada “Dongeng Enteng ti Pesantren”
NU Online · Kamis, 30 April 2020 | 16:15 WIB
Di dalam tulisan Pusaka KH A. Wahab Muhsin dalam Konteks Covid-19, karya Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Syihabuddin Qalyubi yang dimuat di NU Online, menceritakan bahwa pengasuh pesantren Sukahideng Tasikmalaya almaghfurlah Kiai Wahab Muhsin kepada santri-santrinya bersikap seperti kakak kepada adik-adiknya.
“Relasi dengan santrinya sangat akrab sekali, sehingga beliau memosisikan diri di depan para santrinya sebagai kakak mereka, beliau biasa dipanggil akang (artinya kakak atau abang), bukan mama atau pak ajengan sebagaimana panggilan yang lazim dipakai di tatar Priangan Timur. Namun lambat laun, sesuai dengan pekembangan jaman para santri akhirnya memanggilnya bapak atau pak ajengan,” ungkap penulis.
Saya pernah ke Pesantren Sukahideng saat peringatan 90 tahun usia pesantren. Tapi Kiai Wahab sudah tiada. Waktu itu saya diantar salah seorang alumnusnya untuk sowan kepada Kiai Ii Abdul Basith. Saat sowan, kiai duduk di kursi, si alumnus dan saya juga berada di kursi masing-masing. Tidak duduk di lantai. Dan tampak dari obrolan kiai dan alumnus itu sangat akrab. Memang, menurut alumnus, di pesantren itu hubungan kiai dan santri sangat akrab.
Saya sendiri, saat di kampung, belajar kepada kiai yang oleh para santrinya disapa akang. Sang kiai dalam moment tertentu berkenan memakan nasi liwet bersama santri di atas daun pisang. Tak hanya itu, karena dia senang bermain dan menonton sepak bola, sang kiai juga kerap menonton dan bermain bola bersama santri. Saat Persib melawan Petrokimia Putra di final Liga Dunhil 30 Juli 1995, mengaji pun libur karena ajengan berada di hadapan televisi milikinya. Televisi merk Fujitec 14 inch. Di hadapan tivi itu pula ajengan kerap pertandingan-pertandingan penting piala dunia 1994.
Keakraban kiai dan santri saya temukan pula saat membaca Dongeng Enteng ti Pasantren karya Rahmatullah Ading Afandie. Dongeng itu seperti kumpulan cerpen, seperti terpisah dengan bab selanjutnya. Namun, sebetulnya ada tali penghubung yang membentuk autobiografi pada masa kanak-kanak penulisnya.
Dongeng Enteng ti Pasantren terbit pertama kali tahun 1961 oleh penerbit Tarate Bandung. Kemudian buku setebal 108 halaman ini diterbitkan kembali oleh pemerintah melalui Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Di tahun yang sama buku itu memperoleh hadiah dari LBBS.
Menurut Adun Subarsa, kumpulan cerpen tersebut digolongkan ke dalam kesusastraan Sunda modern sesudah perang.
Di dalam buku itu, menceritakan seorang anak masuk pesantren setelah berhenti sekolah di lembaga pendidikan formal. Saat Jepang mulai menjajah, pendidikan formal ala Belanda dilarang. Latar waktu cerita sekitar tahun 1942-1943. Latar tempatnya terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis. Sementara penulisannya dilakukan tahun 1960-an, ketika penulis sudah dewasa. Jadi, buku itu mengenang masa kanak-kanaknya.
Nah, dalam buku saya mendapatkan relasi ajengan dan santri yang sangat akrab sekali. Bahkan dalam konteks tertentu agak kurang sopan meskipun itu dilakukan di belakang atau dengan tidak sengaja. Namun, secara umum memang seluruh santri, termasuk penulisnya sangat hormat kepada ajengan.
Tapi sebelum itu, kita periksa dulu profil ajengan berdasarkan buku berbahasa Sunda itu:
Sarebu kali anjeunna teu sakola, teu meunang didikan universitas, tapi kuring yakin, yen Ajengan urang kampung teh bener-bener jelema pinter, jelema ngulik. Carana ngajar, najan teu make padika beunangna maca tina buku, tapi babari kaharti. Najan remen haok hamprong, tapi dipikaserab ku santri-santri. Malah dianggap papayung ku jalma sakampung. Pamanggihna estu asli, lain beunang nyutat tina buku batur. Najan kitu, jero sarta ngandung bebeneran. Jembar panalarna, luhur panemuna. Cindekna, lain jalma atah-atah. Teu loba ayeuna oge kuring manggihan jalma nu jembar kawas Ajengan. Loba kanyaho, barí beunang tapakur sorangan. Padoman anjeunna, "Tapakur sajam, leuwih gede gunana, batan salat jungkel-jumpalik genep puluh poe teu make tapakur".
Dalam dongeng enteng di pesantren ada bagian fragmen yang menceritakan bahwa ajengan sangat menyukai sepak bola. Tak hanya menonton, tapi juga turut bermain, sama sebangun dengan ajengan saya di kampung.
“Dalah Ajengan pisan ari dina lebah maen-bal mah nurut ka kuring. Mun cek kuring jadi bek, jadi bek. Mun cek kuring tong maen, atawa eureun maen, tara make kadenge gegelendeng.”
Terjemahan bebasnya:
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
4
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua