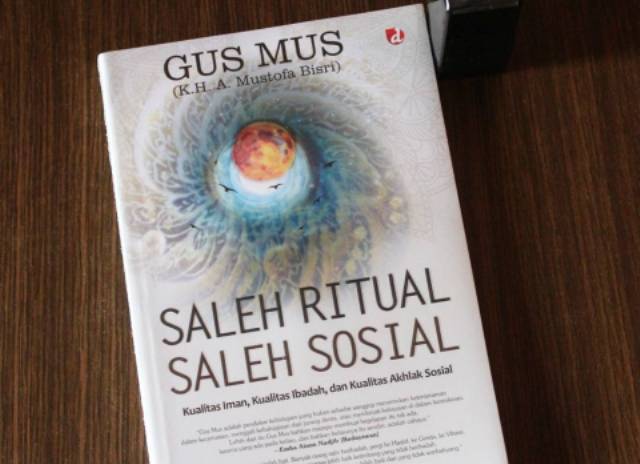Membaca kata-kata Gus Mus, dalam Saleh Ritual dan Saleh Sosial, seperti menari; ada keluwesan dan kebernasan kalimat yang tak kita dapati dalam pada aspek “di luar kata-kata tulis Gus Mus”. Kebijaksanaan kiai sepuh dan ritmisitas kepenyairannya melebur menjadi satu dan membuat kita lena, bahkan sejak awal pengantar, bagaimana kesederhanaan, dengan anehnya, dapat berpadu dengan “kemewahan” sebuah nasehat.
Gus Mus, dalam pengantarnya berjudul Takdim, mengesankan beliau telah melampaui yangfana; tentang bagaimana beliau menegaskan bukan sekadar tidak sempat, tetapi tidak bisa membikin artikel yang panjang dan “serius”; maka kebanyakan tulisan di Saleh Ritual dan Saleh Sosial pun hanya berupa catatan-catatan pendek tentang perjalanan hidup. Beliau lebih berharap buku tersebut bisa menjadi amal ibadah. Sebuah espektasi yang tidak neko-neko.
Tetapi, yang pendek-pendek itu tidak selalu pas diasosiasikan dengan tidak dalam, jelentreh, rigid. Justru, oleh Gus Mus, sesuatu yang pendek itu pas dan akan malah berasa berlebihan bila dipanjang-panjangkan. Seolah tak ada pretensi menasehati, menulis artikel untuk “mengejar sesuatu”—semisal pengakuan, honor, atau popularitas. Beliau menulis sekadar berbagi, laiknya nuturicucunya, tetapi semua seakan bermula dari keresahan yang dalam.
Kesederhanaan itulah yang kemudian rasanya akan lebih mudah diterima pembaca.Tidak ada berondongan dalil, yang kadang-kadang membuat pembaca-sambil-lalu jengah seakan “digurui”. Gus Mus bercerita, dengan kepiawaian seorang cerpenis, ihwal perumpamaan Al-Ghazali tentang posisi hati nurani, akal, anggota tubuh manusia, serta aturan agama dalam menjalankan fungsi hidup. Apakah kita sudah benar memposisikan semuanya.
Gus Mus juga lebih menggunakan tamsil-tamsil sederhana yang dilandasi atau dipungkasi satu-dua dalil, sehingga kita merasa ringan dan teredukasi (baca: terhibur) ketika membacanya. Seperti perumpamaan olahan tanah liat—dan keliatannya—sebagai representasi manusia dan api sebagai analogi setan. Juga, pada tulisan berjudul Pakaian, Gus Mus menunjukkan pengetahuannya tentang dunia mode, selaras dengan pakaian Gus Mus yang nyaris selalu modis.
Saleh Ritual dan Saleh Sosial,rasa-rasanya, pada beberapa tulisan juga begitu ensiklopedis. Contohnya tulisan berjudul Nabi yang Manusia. Gus Mus mampu menjelaskan sisi-kemanusiaan-nabi (humornya, jengkelnya, moderasinya) dengan begitu lancar, sebab boleh jadi pengetahuan yang kemudian diungkapkannya itu merupakan kristalisasi khazanah yang sudah mengendap lama di dalam pikir, sehingga sajiannya pun ringkas tetapi mantab.
Metode kritiknya pun menunjukkan kesepuhan dan barangkali sulit ditiru. Seperti dalam tulisan Kurban dan Korban. Ada kritik terselubung, yang membuat pembaca tidak berasa ditunjuk, tetapi kesadaran bahwa kita dikritik, uniknya, justru datang dari diri kita sendiri. Gus Mus menulis, Nabi Ibrahim rela mengorbankan apa yang menurut semua manusia bakal sulit dikorbankan: nyawa putranya. Berbeda dengan kita yang meski cuma mengurbankan kambing saja masih sering menyisakan pamrih.
Banguna kritik yang bertebaran di buku ini, seperti ketika Gus Mus membandingkan Rab’iah al-Adawiyah yang tidak takut neraka tetapi begitu takut bila tidak dicintai Allah dengan betapa kita takut pada kematian dalam tulisan berjudul Apabila Allah Mencintai Hambanya, membuat kita berpikir—alih-alih menentang;“itu-kan-nabi”, “itu-kan-sufi”—betapa kita, sebab kadar keimanan dan ketakwaan yang hari ini masih begini-begini saja, harus bisa mencontoh beliau-beliau itu.
Dalam kadar tertentu, beberapa tulisan bahkan terasa sangat instropektif, membuat kita merenung lama, bepikir, dan boleh jadi sampai menitikkan air mata. Seperti ketika membaca Dosa Besar, kita berpikir apakah selama ini kita adalah orang yang takabur—dengan keluasan makna sebagaimana disampaikan Gus Mus. “Orang yang berbuat dosa karena meremehkan dosa adalah orang yang takabur,” tulisnya di halaman 66. Sedang takabur adalah “dosa pertama” yang tak termaafkan.
Beberapa tulisan dalam buku ini juga menunjukkan semacam pemberontakan terhadap kemapanan, kritis konstruktif yang, “khas anak muda”. Paradigmanya masih sama: kemanusiaan. Atau, betapa Islam adalah agama yang mudah dan sangat manusiawi. Selain memotret sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW dalam Nabi yang Manusia, Gus Mus juga membongkar anggapan puasa-lebih-utama dengan tanpa mengurangi pengakuan akan keagungan ibadah tersebut.
Dalam tulisan Selamat Makan, Gus Mus mengatakan, “…di Al-Qur’an sendiri, ‘perintah’ makan lebih dari tiga puluh kali difirmankan Allah. Bandingkan dengan ‘perintah’ puasa yang tidak sampai lima kali (bahkan yang menggunakan bentuk amar cuma dua kali),” tulisnya di halaman 86.Paradoks. Pasalnya, di awal tulisan, Gus Mus membeberkan stigma yang terbangun yang terangkum dalam ujaran: kau ini, makan saja yang kau pikirkan—seolah makan identik dengan aib.
Pula di dua tulisanDalih dan Dalil dan Ghairah yang relevan dengan kondisi kekinian, di mana banyak orang yang melegitimasi (mendalihkan) perspektifnya atau lebih mencenderungi dalil yang “menguntungkan” diri dan “merugikan” liyan. Meski, kita tahu, tentu saja tidak ada yang salah dari sebuah dalil. Kemudian Gus Mus mengusulkan jalan tengah; bagaimana kalau dalil yang biasanya dijadikan legitimasi tersebut dibalik.
“Misalnya, dalil tentang keharusan taat kepada pimpinan, biar rakyat saja yang me-‘wirid’-kannya, para pemimpin dan penguasa biar me-‘wirid’-kan dalil tentang kewajiban pemimpin dan penguasa untuk jujur dan adil. Dalil kehebatan lelaki biar dipegangi kaum wanita saja; dalil keagungan wanita biar dipegang kaum lelaki,” tulis Gus Mus di halaman 103. Dengan begitu maka akan terwujud suasana saling memperbaiki diri, guyub, dan bukannya saling menuntut.
Dalam Ghairah, Gus Mus mengumpamakan agama adalah istri. Kepada agama, sebagaimana kepada istri, kita mempunyai ghairah yang kuat, sebab adanya cinta yang begitu dalam. Tetapi, ghairah tersebut bisa juga lebih dekat kepada nafsu dan menegasikan akal sehat manakala kita tidak bisa menguasainya. Fanatisme yang tidak dilandasi dengan logika-aqli, objektivitas, dan cenderung fobia terhadap “mereka” yang tidak sama dengan “kita” adalah biangnya.
Maka Gus Mus menutup tulisan tersebut dengan firman Allah, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, saksi-saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum (menurut kebanyakan mufasir, “kaum” di sini artinya malah orang-orang kafir) mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS 5:8)
Data buku:
Judul buku : Saleh Ritual Saleh Sosial
Penulis : KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus)
Penerbit : DIVA Press
Cetakan : 2016
Tebal : 204 halaman
Peresensi: Syamsul Badri Islamy, Ketua LTN NU Kota Bekasi.