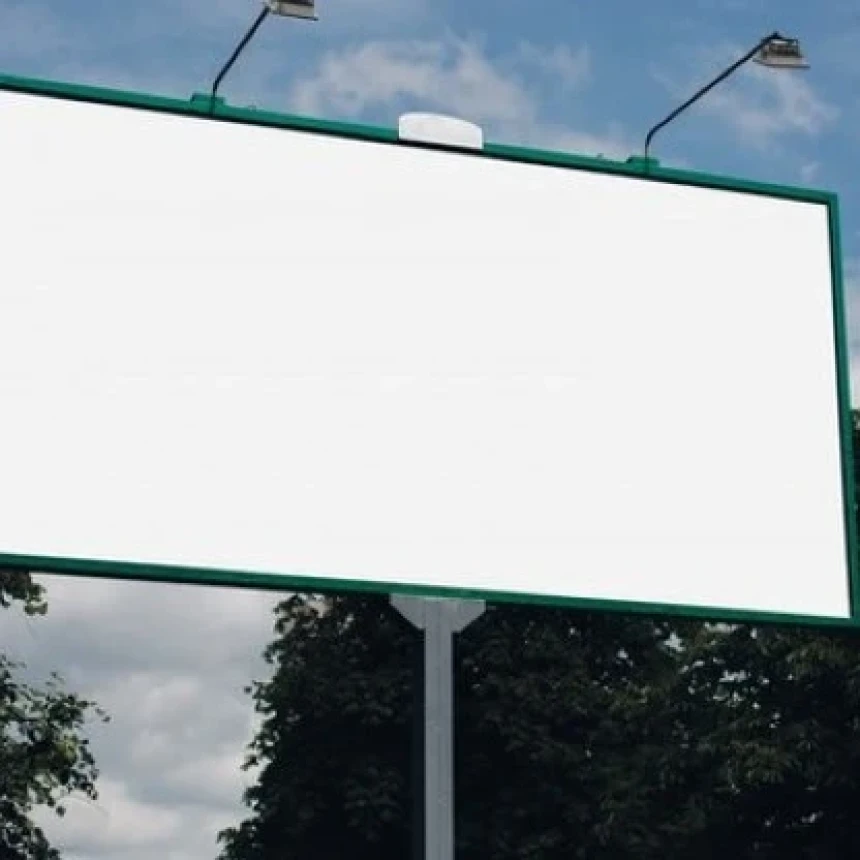Cerpen Endang S. Sulistiya
Dahulu, aku membenci Ibu. Aku mengumpat untuk sikap pelitnya. Bagaimana bisa putri dari seorang kepala desa, uang sakunya lebih rendah dari anak-anak lainnya? Rupiah yang Ibu berikan hanya cukup untuk membeli permen dan es kucir. Tiada sisa untuk membeli mainan.
Menunggu lonceng berdentang tanda istirahat, aku akan mendudukkan dagu di antara dua telapak tangan. Termangu, menyaksikan teman-teman perempuanku bersiap main bongkar pasang. Iri serta-merta merambat cepat di hatiku.
Teman-teman perempuanku kemudian berlomba membangun rumah mewah dari tanah. Kamar tidurnya ada tiga, dengan masing-masing kamar mandi. Tiap kamar dilengkapi meja rias dan lemari pakaian besar. Tumpukan baju tidur, gaun pesta, pakaian kantor dipisah-pisahkan. Tiap hari mereka membelinya, wajar bila koleksinya bertambah.
Baca Juga
Ihwal Kejadian Longsor
Sementara aku? Bongkar pasang yang aku beli dua minggu lalu, hanya akan menjadi ejekan teman-teman bila kuikutsertakan. Nona Marina, kepalanya sudah terlepas. Itu karena baju-bajunya tidak pas pola guntingannya dari awal. Karena terus menerus dipaksakan, kepalanya terpenggal dengan sendirinya. Nona Anita, kakinya sudah layu. Tidak kokoh berdiri lagi. Bahkan sepatu merahnya telah lama memudar. Ya, mau bagaimana lagi, mereka terbuat dari kertas.
Permasalahan tersebut telah kuadukan pada Ibu. “ Masih bisa disambung dengan lem, atau dengan ini!” enteng Ibu menjawab. Lalu Ibu menghampiriku dengan bulir nasi di ujung telunjuknya.
Melengos. Kutinggalkan Ibu dengan omelan tinggi rendah.
Andai Bapak segera pulang dari Balai Desa. Tentu Bapak akan mengakhiri masalah ini dengan selembar uang. Lalu semua akan baik-baik saja. Bapak memang pahlawanku. Meski Bapak tidak selalu ada, keberadaannya senantiasa menghapus kesedihan yang ditimbulkan oleh Ibu.
Baca Juga
Gula, Teh dan Lingkaran Sesat
Bapak memang keren. Aku selalu kagum dengannya. Pakaian dinas harian khaki dengan segala atributnya membuat bapak semakin tampan dan gagah.
Terheran-heran, aku tidak mengerti mengapa antara Bapak dan Ibu sanggatlah timpang? Penampilan Bapak penuh kharisma dan membuat kagum siapa saja. Dari ujung kepala hingga kaki tampak sempurna.
Sementara Ibu selayak Cinderella yang dipungut bapak dari tempat kumuh. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, belum lagi perangainya yang tidak kusukai.
Tiap kali mampir ke rumah sebelum pergi lagi, Bapak memberiku selembar uang yang seketika membuatku terlonjak riang. Sayangnya, hal itu menjadi sia-sia ketika Ibu memergoki. Ibu merampas uang itu dariku. Setelah itu, aku tidak tahu di kemanakan uang itu oleh Ibu. Dipakai belanja oleh Ibu pun kurasa tidak mungkin. Pasalnya Ibu hampir-hampir tidak pernah membeli telur, ayam apalagi daging untuk lauk makan.
Baca Juga
Cerita Pendek: Perjanjian Kedua Iblis
***
Gemuruh ricuh terdengar mendekat. Derap gesa gerombolan orang disusul teriakan serta sahutan menerobos gendang telinga. Terbangun dari tidur siang, aku linglung. Campuran rasa penasaran dan cemas menyeruak.
Ibu mendekapku dari belakang ketika aku hendak menuju ruang tengah. “Jangan mendekat!” Ibu menarik wajahku dan mendorongnya ke gundukan dadanya yang kenyal.
"Keluar kau Kades serakah!”
Baca Juga
Kosongnya Langgar
"Kembalikan uang kami!” Kalimat itu diteriakkan berulang-ulang dengan kemarahan.
“Pyar!” Kaca jendela pecah.
“Duar!” Daun pintu goyah.
Ibu memelukku erat. Siang mencekam itu akan selalu terekam dalam ingatanku. Untuk pertama kalinya, segala indraku mulai bekerja. Melihat, mendengar, mencium, meraba dan mencerna sebuah peristiwa.
Akhirnya aku tercerahkan. Hal yang kukira terang ternyata menyimpan sisi gelap. Dan hal yang kukira gelap ternyata menyimpan sisi terang.
Sejak hari itu, bertubi-tubi kekacauan datang. Pernah satu malam, wanita berperut buncit menggedor-gedor pintu rumah. Ibu bangun untuk membukakan pintu setelah memastikan aku tak terjaga. Padahal sewaktu ibu menemui tamu asing itu, aku yang pura-pura tidur gegas mengintip dari balik tirai kamar.
“Di mana Pak Kades? Aku ingin minta pertanggungjawabannya!” seru wanita yang mengenakan daster motif bunga sembari mengelus perutnya.
“Pak Kades sedang dinas ke luar kota,” jawab Ibu tenang.
“Bohong! Pasti sekarang laki-laki pengecut itu sedang bersembunyi!” teriak wanita yang tidak kukenal itu histeris.
Baca Juga
Kutukan Sunan Amangkurat
Berikutnya secara membabi buta wanita bersandal jepit itu mengamuk. Membanting segala pigura foto, vas bunga, dan suvenir hiasan. Untungnya wanita yang mengamuk itu tidak melukai Ibu. Bapak yang ternyata bersembunyi di dalam peti gabah sama sekali tidak berani keluar hingga wanita itu pergi.
***
Sungguh waktu-waktu berikutnya caraku memandang sesuatu kuusahakan lebih menyeluruh. Pun bertumbuhnya usia, membuatku tak lagi berpikir dangkal. Kini dapat aku nilai dari ujung ke ujung seperti apa Bapak yang selama ini kubanggakan. Sungguh aku tak mengenalinya lagi sebagai sebuah kekaguman.
Baca Juga
Jemari Ternoda
Di awal periode kedua kepemimpinannya sebagai kepala desa, Bapak menjadi tersangka kasus penyelewengan dana desa. Bapak didakwa merampas uang rakyat. Menggelembungkan dana proyek. Juga mengingkari ganti rugi. Namun kala itu Bapak masih lihai menghindar berkat sendok emas yang disuapkannya kepada pegawai kejaksaan.
Dari sini, aku mulai menduga-duga akan sikap pelit Ibu. Di mana Ibu akan sangat marah bila mendapatiku membelanjakan uang yang diberi oleh Bapak. Lalu terkait pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, Ibu memilih mencukupinya dari hasil menjahit pakaian. Kadang Ibu ikut serta merias pengantin. Bahkan Ibu tak jarang memanfaatkan apa yang ada di kebun belakang rumah untuk makan sehari-hari. Tak mengherankan, berkat keaktifannya di PKK, ibu mengusai banyak keterampilan.
Tentang Bapak yang gemar main wanita, usut punya usut, Ibu bukannya tak tahu. Kasak-kusuk perselingkuhan Bapak sudah kerap Ibu dengar dari ibu-ibu tetangga yang doyan bergosip. Hanya saja Ibu memilih menyimpannya seorang diri. Luka demi luka itu terus-menerus Ibu balut dalam keterdiaman. Entahlah, mungkin Ibu mendapatkan keterampilan menyimpan rahasia dan kesedihan juga dari kegiatannya di PKK.
Baca Juga
Lembaran Cinta Kanjeng Nabi
Waktu tidak pernah keliru. Bapak segera dicopot dari jabatannya setelah terbukti bersalah di pengadilan. Demi mendapatkan keringanan hukuman, semua harta ludes dikorbankan.
Tak berselang lama sejak kehilangan harta dan takhta, Bapak mengidap sakit kulit yang menjijikkan. Lima tahun lamanya Ibu setia merawat Bapak yang sakit-sakitan.
Tanpa keluh dan kesah, Ibu berada di samping Bapak. Meskipun tetangga sebelah bergibah kalau Bapak mengidap AIDS, Ibu tak ambil peduli. Pula ketika tetangga sebelahnya lagi bergunjing bapak suka jajan, Ibu tak ambil pusing. Bahkan saat ada nyinyiran mengatakan, “tidak ada janda di kampung yang belum dicicip oleh Bapak”, ketulusan Ibu tetap tak berubah.
Kini aku telah mampu mengenali hakikat dari kehidupan yang bagai permainan bongkar pasang. Kita bisa mengoleksi segala jenis pakaian. Juga mudah bagi kita untuk mengubah penampilan. Hingga semua itu dapat memperdayai siapa saja. Namun ada masanya permainan akan berakhir.
Ketika Bapak akhirnya meninggal. Tidak ada yang mau mengubur dan melayat. Hingga Ibu mengeluarkan simpanan yang ditabungnya dengan susah payah untuk membayar penggali kubur dan pemanggul jenazah.
Usai jasad Bapak terkubur, Ibu menabur bunga di permukaan tanah merah. Ibu mengusap nisan yang tertulis nama Bapak di sana. Seuntai doa bergetar dari bibir kering Ibu. Tak ada raut wajah marah atau dendam.
Banyak orang protes dengan sikap Ibu, termasuk aku putri satu-satunya. Lantas Ibu menjawabku, “Ibu hanya berlaku sebatas sebagai manusia seharusnya. Ibu merasa tidak berhak menghakimi. Ibu tak mau seolah-olah menjadi Tuhan.”
Plak! Aku tertampar.
Endang S. Sulistiya, menetap di Boyolali. Alumnus FISIP UNS. Tergabung dalam Grup “Diskusi Sahabat Inspirasi”.