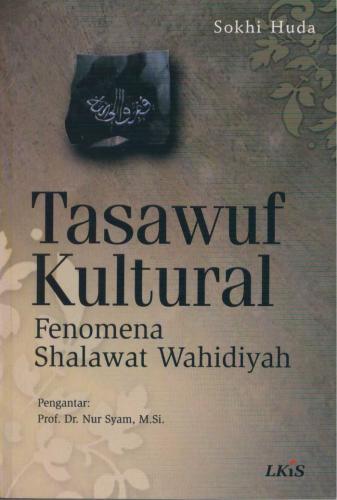Penulis: Sokhi Huda
Penerbit: LKiS, Yogyakarta
Cetakan: I, Juli 2008
Tebal: xxviii + 372 halaman
Peresensi: Akhmad Kusairi
Dampak modernitas terhadap sendi-sendi kehidupan memang hampir mendekati sempurna. Harus diakui hampir segala dimensi kehidupan sudah dimasuki modernitas, termasuk agama. Di tengah kondisi demikian, banyak orang beranggapan bahwa Tuhan tak lagi dibutuhkan mengingat segala macam keperluan manusia sudah disediakan di dalam kehidupan modern. Namun, benarkah demikian? Tumbuh suburnya majelis-majelis pengajian tasawuf mana merupakan bukti bahwa hal itu tidaklah benar. Dengan kata lain, masyarakat merasa terbelenggu kecenderungan materialisme. Mereka membutuhkan sesuatu yang dapat menenteramkan jiwanya serta memulihkan kepercayaan mereka yang nyaris punah karena dorongan kehidupan materialis-konsumtif. Salah satunya adalah tasawuf.<>
Tasawuf di Indonesia sekarang ini tidak hanya menarik perhatian para peneliti muslim, tetapi juga menarik perhatian masyarakat awam. Di Barat pun terjadi hal serupa. Akhir-akhir ini juga muncul perhatian besar terhadap tasawuf. Hal demikian tampaknya dipicu beberapa faktor, seperti adanya perasaan tidak aman menghadapi masa depan, di samping juga karena adanya kerinduan masyarakat Barat untuk bisa menyelami ajaran-ajaran rohani dari agama-agama di Timur.
Realitas di atas, tidak heran jika banyak pakar meramalkan bahwa tasawuf akan menjadi tren abad 21 ini. Ramalan ini cukup beralasan karena sejak akhir abad 20 mulai terjadi kebangkitan spiritual di berbagai kawasan. Munculnya gerakan spiritual merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap dunia modern yang terlalu menekankan hal-hal yang bersifat material-profan sehingga menyebabkan manusia mengalami keterasingan jiwa.
Kebangkitan spiritual ini terjadi di mana-mana, baik di Barat maupun di Timur, termasuk Islam. Di Barat, kecenderungan untuk kembali pada spiritualitas ditandai dengan semakin merebaknya gerakan fundamentalisme agama. Sedangkan di dunia Islam ditandai dengan banyaknya artikulasi keagamaan, seperti fundamentalisme Islam yang ekstrim dan menakutkan, di samping juga bentuk artikulasi keagamaan esoterik lainnya yang akhir-akhir ini menggejala, seperti gerakan sufisme dan tarekat.
Dalam konteks Indonesia, tasawuf berkembang sangat pesat. Bahkan, disinyalir ia muncul sejak awal datangnya Islam ke negeri ini. Dalam buku Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara, misalnya, M. Solihin menulis bahwa Islam datang pertama kali ke wilayah Aceh.
Karena itu, Aceh sekaligus berperan penting bagi penyebaran tasawuf ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk juga ke semenanjung Melayu. Tasawuf yang singgah pertama kali di Aceh tersebut memiliki corak falsafi. Tasawuf falsafi ini begitu kuat tersebar dan dianut sebagian masyarakat Aceh, dengan tokoh utamanya adalah Hamzah al-Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrarri.
Dua tokoh sufi-falsafi ini mempunyai pengaruh cukup besar hingga corak tasawuf yang diajarkannya tersebar ke daerah-daerah lain di Nusantara.
Munculnya dua tokoh tasawuf dari Aceh yang bercorak falsafi tersebut kemudian disusul para tokoh tasawuf berikutnya, yakni Nuruddin ar-Raniri, Abd Shamad al-Palimbani, dan Walisongo. Munculnya tokoh-tokoh sufi pasca-Hamzah al-Fansuri dan as-Sumatrani ini lebih menampakkan ajaran tasawuf tipikal al-Ghazali. Bahkan, tasawuf ini kemudian menjadi begitu dominan di Nusantara.
Pada sisi lain, patut diperhatikan juga bahwa ada dua tokoh lain yang ikut memperkaya khazanah tasawuf di Indonesia, yakni Ronggowarsito yang bernuansa "Kejawen" dan Haji Hasan Musthafa yang bernuansa "Pasundan". Kedua tokoh ini mempunyai pemahaman spiritual yang berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya. Mereka memperlihatkan adanya dialektika antara pemikiran tasawuf secara umum dengan budaya lokal setempat.
Berdasarkan data-data yang ada, para sufi Nusantara cukup memahami ajaran-ajaran wihdatul wujud milik Ibn Arabi dan ajaran insan kamil milik al-Jili. Teori-teori itu masuk ke Nusantara melalui dua tokoh Aceh, yakni Hamzah al-Fansuri dan as-Sumatrani yang ditopang pemikiran Muhammad Fadhlullah al-Burhanpuri (India). Konsep wahdah al-wujud karya dan insan kamil kemudian berpadu dengan Tuhjah milik al-Burhanpuri sehingga melahirkan teori ”martabat tujuh”. Teori ini terlihat mewarnai wacana pemikiran sufi Indonesia.
Teori martabat tujuh ini berhubungan erat dengan paham tanazzul dan tajalli, dan ia menjadi fenomena yang banyak dijumpai di Indonesia. Konsep martabat tujuh merupakan tingkatan-tingkatan perwujudan melalui tujuh martabat, yaitu: (1) ahadiyah, (2) wahdah, (3) wadhidiyah, (4) 'alam arwah, (5) 'alam mitsal, (6) 'alam ajsam, dan (7) 'alam insan.
Pemahaman seperti itu kelihatannya lebih tegas dipahami Walisongo di pulau Jawa, yang kental dengan nuansa Sunni. Gaya-gaya penafsiran mereka ini kelihatan tetap cenderung pada tasawuf Sunni. Dan, tasawuf Sunni inilah yang banyak dianut masyarakat Islam Indonesia hingga sekarang.
Di sisi lain, dalam realitas kultural yang ada, di Indonesia juga muncul dua aliran tasawuf/tarekat yang cukup populer, yakni Shiddiqiyah dan Wahidiyah. Dua aliran tasawuf ini lahir di Jawa Timur. Kedua aliran ini ternyata berkembang cukup pesat di tengah masyarakat dan memiliki sistem organisasi yang cukup bagus dan solid. Menurut buku Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidyah ini kedua aliran ini merupakan aliran tasawuf produk Indonesia asli karena mempresentasikan formula amalan dan ajaran yang khas Indonesia dibanding dengan aliran-aliran tasawuf/tarekat lainnya.
Buku ini mencoba mengkaji secara komprehensif fenomena Wahidiyah sebagai sebuah aliran tasawuf kultural. Dalam hal ini, Sokhi Huda sebagai penulis, mencoba melacak kelahiran shalawat Wahidiyah sebagai aliran tasawuf serta dinamika yang terjadi di dalamnya, respons para ulama terhadapnya, juga sistem ajaran sekaligus pengorganisasiannya. Tak pelak, tema kajian buku ini sangat menarik untuk dicermati dan didiskusikan, terutama di tengah masyarakat yang sering mengklaim diri dan kelompoknya sebagai yang paling benar.
Sebagai sebuah penelitian, tentunya berhasil dan tidaknya buku ini ditentukan respons peneliti-peneliti lain sehingga tertarik untuk melakukan kajian terhadap tema serupa. Tasawuf kultural untuk kalangan Indonesia sepertinya sesuatu yang harus ada, sebab selama ini kelompok-kelompok tasawuf didominasi kalangan Sunni yang notabene sangat jauh dari tradisi ke-lokalan Indonesia. Karena itu, sebagai kaum muslim Indonesia sudah sepatutnya berterima kasih terhadap penulis buku ini, yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya mampu menghadirkan buku ini.
Peresensi adalah Peneliti pada The Alfalah Institut Yogyakarta