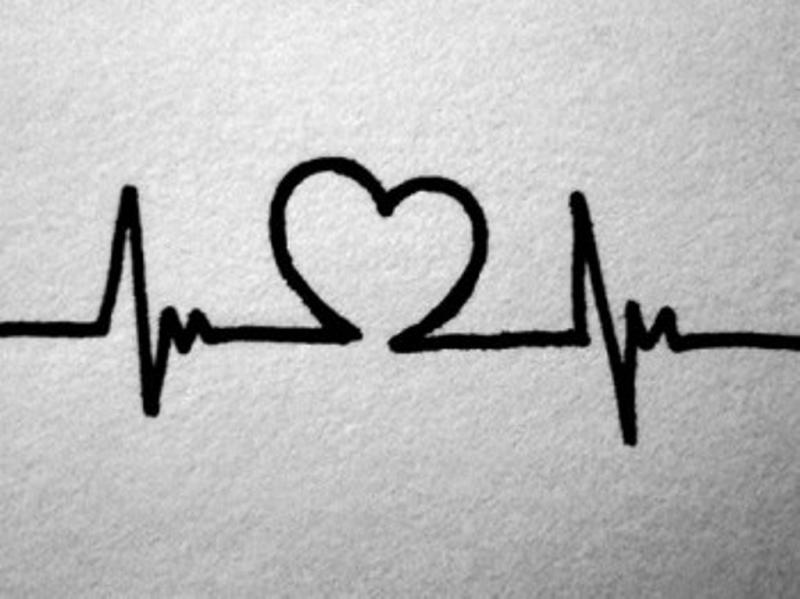RINA menyeka air matanya. Ia keluar kantor dengan muka sembap. Langkahnya begitu pelan. Beberapa orang yang semula berjalan di belakangnya sudah mendahuluinya. Ia masih lemas. Syok akibat kejadian yang baru saja menimpanya.
Lanskap kota mencoba menghiburnya. Cahaya senja memantul dari gedung-gedung tinggi. Burung-burung walet beterbangan. Pepohonan bergoyang menyambut datangnya malam. Rina masih saja muram.
“Minuman dingin, Mbak?”
“Tahu hangat, Kak?”
“Ih, si Neng diam aja.”
Beberapa penjual yang menyapanya tidak digubris. Ia tetap melangkah. Lalu berhenti di pangkalan ojek langganannya. Terletak di Jalan KH Hasyim Asy’ari. Seorang tukang ojek menghampirinya sambil memberikan helm. Rina merapikan rambutnya. Helm membungkus kepalanya kemudian terdengar bunyi, “ceklek”.
“Biasa ya, Bang. Ke Menteng.”
“Siap, Mbak Rina.”
Motor langsung melaju kencang, menerobos kepadatan lalu lintas. Suara bising klakson terdengar tanpa henti. Saling bersahutan, bagaikan teriakan kera di kebun binatang. Hilir mudik kaum urban memadati trotoar. Wajah-wajah letih menolak untuk dipandang. Mereka berdiri, berjalan, duduk, dan diam. Ada yang menunggu jemputan, memilih kendaraan, berjualan tanpa modal, mengamen dengan kasar, dan bahkan mencari kesempatan kriminal.
Rina berlalu meninggalkan senja yang getir.
***
TEH pahit hangat baru saja dibuat Lestari. Asapnya keluar dari gelas, lalu ruangan menelannya. Ia meletakkan teh itu di atas meja antara suaminya dan televisi yang sedang menyala. Suaminya sudah duduk sedari tadi. Menikmati hiburan malam sambil mengupas kacang. Lestari duduk. Ikut menjumput kacang.
“Yah, kapan kita menikahkan anak kita?”
“Apa harus buru-buru, Mah?”
“Tidak sih, tapi bukankah lebih cepat lebih baik?”
“Pilih lebih cepat, atau lebih cermat?”
“Maksud Ayah?”
Darmawan membenarkan posisi duduknya. Giginya masih mengunyah kacang. “Mereka kan baru saja kenal toh, Mah. Lha mbokyo dijalani dulu hubungan mereka. Biar saling kenal.”
“Mau mamah juga gitu, Yah. Takutnya kalau kelamaan malah nggak jodoh. Lagi pula, kan si Andi sudah mapan, bahkan punya mobil sendiri.”
“Hus, Mamah ini ngomong apa toh.”
Tumpukan kulit kacang sudah menggunung. Lebih banyak daripada kacang yang belum dikupas. Asap teh keluar malu-malu. Suasana hening. Hanya gelak tawa siaran televisi yang menguasai ruangan dan malam.
***
“Ba’ fathah ba, ta’ kasrah ti, tsa’ dlammah tsu, batitsu”
“Dal fathah da, dal kasrah…”
“Eit, hayo.”
“Yang ini apa namanya, Ustadz?”
“Kalau dal ada titiknya, kan dzal. Ingat ya, pintar.”
“Oh iya, Ustadz,” sang murid menyedot ingusnya, “Dzal kasrah, dzi.”
Khaliel, guru ngaji di sebuah musala kecil di daerah Cikini. Awalnya, ia hanya seorang jamaah biasa pada umumnya. Suatu ketika, Ji Ruslan, imam tetap musala itu tidak datang. Khaliel ditunjuk para jamaah untuk menggantikan. Mereka terpukau dengan kemerduan dan kefasihannya membaca Alquran. Lambat laun, beberapa jamaah menyerahkan anaknya kepada Khaliel untuk diajari mengaji setiap bakda asar.
Melihat ada pemuda berpotensi, Ji Ruslan bangga. Musala yang didirikan almarhum abahnya akhirnya membuka Taman Pendidikan Alquran (TPQ). Adapun gurunya hanya Khaliel.
Dari kegiatan tersebut, Khaliel mendapat pemasukan tiap bulan. Uang itu cukup untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Namun ia merasa gelisah. Tidak sepantasnya mengajarkan ilmu agama menjadi profesi utama, pikirnya. Ia ingin menjadikannya side job, dan mencari pekerjaan lain yang kelak digunakan untuk hidup berkeluarga.
“Nak Khaliel, sudahlah tak perlu bekerja di luar,” Ji Ruslan menasihati, “Kalau kelelahan bagaimana?”
“Tidak apa-apa, Pak Haji. Justru mumpung masih bujang saya harus bekerja keras.”
“Kalau butuh makan, tak usah sungkan-sungkan main ke rumah.”
“Makasih, Pak Haji.”
“Atau kalau uang bulanannya kurang bilang saja.”
“Alhamdulillah, cukup kok Pak Haji,” jawab Khaliel penuh rendah hati, “Oh ya, katanya, Pak Zaini orangtua Ahmad mau haji ya, Pak Haji?”
“Iya betul. Kamu datang walimatus safar ya besok bakda isya. Nanti kalau saya berhalangan, sekalian kamu pimpin baca Yasin dan Tahlil ya, Liel.”
“Insya Allah, Pak Haji. Besok saya akan pulang lebih cepat.”
***
DARMAWAN dan Lestari menikmati sarapan pagi. Jika tidak masak, mereka biasa menyantap bubur ayam yang dibeli tak jauh dari rumahnya. Pagi itu, mereka tidak masak. Tiga mangkuk bubur ayam telah tersaji. Tinggal satu mangkuk yang belum terjamah.
“Rina, sarapan!” teriak Lestari.
Lestari menyudahi sarapannya. Ia bergegas ke kantor setelah mengecup tangan suaminya. Melangkah dengan tergesa-gesa menghampiri kamar putrinya, “Sayang, sarapan dulu gih.” Tak ada jawaban dari dalam kamar, kecuali rapalan tak jelas yang tertahan bantal.
Darmawan mencangking segelas kopi ke taman belakang. Setiap usai sarapan, ia menikmati pagi dengan kopi hitamnya. Ia tak begitu suka menonton berita politik. Baginya, mengonsumsi berita hanya membuat kopinya semakin pahit. Ia lebih memilih membaca buku. Seperti pagi ini, ia sedang menggenggam buku mutiara hikmah terjemah kitab Al-Hikam mahakarya Imam Ibnu Atha’illah al-Sakandari.
Rina keluar dari kamar. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak dijumpai seorang pun. Mukanya masih sembap. Dengan tertatih-tatih, ia menuju taman sambil menenteng handuk pingnya.
“Ayah…”
“Lho, kamu kenapa? Mata kamu kok bengkak.”
“Aku sedih dan kecewa, Yah. Andi jalan dengan perempuan lain. Pakai gandengan tangan dan pegang-pegangan segala. Yang membuat hatiku tercabik-cabik lagi, foto mereka diunggah di media sosial. Huuu…”
Darmawan menaruh kopi yang baru diseruputnya. Membersihkan ampas kopi yang tersangkut di gusinya. Lalu menggelontorkannya dengan ludah. Pandangannya ke atas menerawang langit yang bisu. Belum ada kata-kata. Rina masih terus sesenggukan.
“Sudah, sudah. Kamu belum sarapan kan? Sana isi dulu perutmu, nanti malah sakit.”
“Biarin Rina sakit. Mati sekalian nggak apa-apa.”
“Hus, nggak boleh gitu. Kamu harus bersyukur dikasih tahu Tuhan sosok Andi yang sebenarnya. Untung kalian belum menikah. Coba kalau tahunya setelah menikah, atau ketika pesta pernikahan, pasti akan lebih hancur. Berarti Allah masih mencintai kamu. Apa mamah sudah tahu?”
“Belum.”
“Biar Ayah yang cerita. Sabar Rina, pasti Allah memberi yang terbaik. Ayah mau berangkat.”
***
PONSEL Rina berdering berkali-kali. Bukan hanya belasan panggilan telepon, melainkan hampir seluruh akun media sosialnya memberikan notifikasi. Mulai WhatsApp, BBM, Facebook messenger, Twitter inbox, Path, dan Instagram. Semua pemberitahuan itu bersumber dari satu biang keladi, Andi.
“Sayang, dengarin aku dulu. Aku lebih mencintaimu daripada dia. Perkara gandengan tangan, dia yang memulai dan memintanya bukan aku. Aku akan meminta dia menghapus foto-foto kemarin di medsos-nya. Aku janji. Sayang, please dibalas.”
Rina tidak meresponsnya sama sekali. Andi terus menghubungi. Rina semakin jengkel. Akhirnya ia putuskan untuk memblokir semua akun pacarnya itu. Dengan kejengkelan tingkat dewa, ia menekan satu tombol OK sambil mengibaratkan menjatuhkan palu godam ribuan ton ke kepala Andi. Korban pun gepeng bagai kaleng minuman yang terlindas ban truk.
Kurang puas dengan imajinasi buasnya, Rina beranjak naik kursi, menanggalkan seluruh foto kenangan yang terpajang di dinding, meja belajarnya, dan menyobek foto boks di dompetnya. Ia kumpulkan semua kemudian dibawa ke dapur. Ia membakarnya dengan api emosi. Andi pun lebur dalam kehidupan Rina.
Hampir saja ia menyayat pergelangan tangannya dengan pisau. Namun diurungkannya setelah Rina melihat kaligrafi indah Ayat Kursi di dinding rumahnya.
***
SEPERTI sore biasanya, Khaliel mengajar ngaji anak-anak di musala. Selama mengajar, tak sekalipun Khaliel memarahi muridnya. Jika ada salah satu murid yang tidak masuk karena sakit, ia membacakan Surat Alfatihah bersama anak-anak. Dan tak lupa, di setiap Salat Tahajud malam, Khaliel senantiasa mencantumkan nama mereka dalam daftar doanya.
Semua yang ia praktikkan tak lain meniru gurunya dahulu di pesantren. Sang kiai mengajarkan ilmu dengan penuh hati, teladan, dan juga doa yang tulus. Hidupnya juga sangat sederhana, masih tinggal di rumah yang beranyaman bambu bukan tembok. Hampir seluruh murid-muridnya menjadi tokoh panutan di berbagai elemen masyarakat.
Sampai kapan pun, ia tak kan pernah lupa petuah guru sepuhnya, Kiai Harun, “Kalian boleh menjadi apa saja selepas lulus dari pesantren, menjadi dokter, polisi, hakim, direktur, guru, atau kuli bangunan sekalipun. Asalkan ingat, kalian harus tetap ‘berjiwa santri’ yang senantiasa tawaduk dan ikhlas. Allah tidak melihat fisik seseorang, nasab emas leluhurnya, harta yang melimpah ruah, profesi yang mulia, amal yang menggunung, ilmu dan buku seluas lautan, gelar akademik yang menumpuk, tetapi Allah hanya melihat hati kalian. Maka teruslah berendah hati dan tulus, karena itu adalah akhlak yang paling terpuji”.
***
“APA?! Rina putus sama Andi? Nggak, nggak bisa. Pokoknya Andi harus jadi menantu kita.”
“Mah, dengar, Mah. Rina sudah sakit hati ama pria nggak jelas itu.”
“Nggak jelas gimana? Ayah tuh yang nggak jelas. Seandainya kemarin, uhuk, uhuk…”
“Mah, sabar, Mah.”
“Uhuk, uhuk. Yah, obatnya, Yah.”
“Rina, carikan obat mamah. Cepat!” teriak Darmawan.
Rina segera mencarikan obat mamahnya. Nahas, obat yang dimaksud hanya tinggal botolnya saja. Lestari langsung dilarikan ke rumah sakit. Darmawan menyetir mobil dengan panik. Rina belum bisa tenang. Dengan dibantu pak satpam kompleks mobil bisa menerobos kemacetan. Untung saja di rumah sakit tidak terlalu banyak pasien. Lestari segera ditangani oleh dokter ahlinya. Semalaman suntuk Darmawan menunggu istrinya tercinta.
***
“KAMU berapa tahun nyantri di Kiai Harun?
Darmawan baru saja pulang dari walimatus safar di kediaman Zaini, di Cikini. Sebagai kepala pembimbing haji, ia selalu menyempatkan diri hadir. Jarak Cikini-Menteng tidak terlalu jauh, Darmawan lebih memilih naik ojek. Khaliel memimpin tahlil menggantikan Ji Ruslan, ia juga yang mengantarkan Darmawan pulang.
Selama perjalanan, keduanya ngobrol banyak, bahkan semakin akrab ketika tahu bahwa mereka sama-ama alumnus pesantren Kiai Harun. Khaliel diajak masuk ke rumah Darmawan dan dilanjutkan cengkrama gayeng senior dan junior itu.
“Hanya lima tahun, Pak Haji.”
“Berarti belum tamat madrasah aliyah?”
“Belum, Pak Haji,” tutur Khaliel malu-malu, “Kalau Pak Haji?”
“Alhamdulillah, saya sampai lulus aliyah. Tapi dulu saya rada nakal,” Darmawan tertawa lepas, “Meski begitu, saya merasakan berkahnya menjadi santri. Cuma nyantri saja sudah bisa punya bimbingan haji dan umrah, coba dulu sampai menyandang gelar ustadz di pesantren, mungkin sekarang saya jadi menteri agama”.
Kelakar kembali pecah.
“Oh iya, katanya menteri agama yang baru juga alumnus pesantren ya, Pak Haji?”
“Iya betul. Memang banyak alumni pesantren yang kemudian berkontribusi besar untuk negeri ini, baik di pemerintahan, dunia bisnis, akademik, sampai semua lapisan masyarakat. Bahkan, presiden kita saja ada kan yang alumnus pesantren? Kalau menteri banyak sekali yang jebolan pesantren.”
“Iya ya, Pak Haji. Kira-kira apa faktornya?”
“Banyak. Tapi satu yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya di negeri ini, yaitu keberkahan. Kiai Harun mendidik para santri dengan ikhlas, sikapnya kepada semua orang juga tawaduk, ditambah doa-doa beliau setiap malam. Belum lagi kehidupan sehari-hari yang sederhana, mungkin sampai sekarang rumah beliau masih gedhek. Bagaimana tidak berkah?”
“Pak Haji punya pengalaman pribadi dengan Kiai Harun?”
Darmawan menggeser tempat duduknya. Wajahnya semakin ceria. “Dulu setiap hari, saya menata dan membersihkan sandal beliau di ndalem dan masjid. Nah, ketika pamit boyong, ternyata Kiai Harun kenal saya. Lalu saya diberi kenangan peci putih. Waktu itu saya tidak paham untuk apa, saya juga punya banyak dan bisa beli di toko. Tapi saya simpan terus. Dan akhirnya kini terjawab. Peci putih sebagai tanda saya bisa bolak-balik ke Tanah Suci bahkan bisa mengajak banyak jamaah, membimbing, dan membuka travel di mana-mana. Alhamdulillah, dapat berkah Kiai Harun.”
Khaliel tercengang kagum. Ia merasa malam ini adalah lailatul qadr kedua.
“Sebentar, ini kok tidak ada minumnya.”
“Tidak perlu repot-repot, Pak Haji.”
Darmawan masuk ke dalam. Terdengar suara percakapan tak begitu jelas. Dia kembali dengan membawa peci pemberian Kiai Harun yang baru saja diceritakan.
“Ini dia, pecinya. Sampai hari ini, saya selalu pakai ketika Salat Tahajud.”
“Subhanallah,” Khaliel meraih peci itu.
Tiba-tiba gorden terbuka. Ada sosok yang masuk dengan membawa dua gelas teh hangat. Rina melangkahkan kakinya hati-hati, tidak memperhatikan siapa tamunya. Khaliel pun tak berani macam-macam. Ia hanya merunduk dan sesekali memandang wajah teduh seniornya.
Suasana menjadi berbeda ketika Rina mulai angkat bicara.
“Bang Ibra?”
“Mbak Rina?”
“Lho, kalian saling kenal?” Darmawan agak terkejut, “Kamu kok memanggilnya Ibra? Jangan-jangan salah orang?”
“Bang Ibra ini yang biasanya narik ojek nganter Rina pulang kerja, Yah.”
“Iya, Pak Haji. Nama lengkap saya Ibrahim Khaliel, sebagian ada yang memanggil Ibra dan Khaliel.”
“Oh, tapi kok ngojek segala?”
“Iya Pak Haji, awalnya saya hanya mengajar tapi kemudian saya ditawari teman ikut ngojek. Tekad saya semakin bulat melihat nama jalannya, ‘KH Hasyim Asy’ari’, yang kalau tidak salah beliau termasuk gurunya Kiai Harun.”
“Iya, betul itu. Hampir semua kiai-kiai besar punya nasab keilmuan yang bersambung kepada beliau yang juga pahlawan nasional itu. Rahimahullahu ta’ala.”
Rina mendengarkan obrolan mereka, lalu mengangkat tema baru, “Ayah dan Bang Ibra, Rina mau tanya, mengapa sih banyak alumnus pesantren memakai peci?”
Darmawan menoleh ke Khaliel, memberi kode untuk mewakili menjawabnya.
“Ya, banyak hal. Salah satunya sebagai identitas, bahwa si pemakai harus sadar dia mengenakan atribut keagamaan, maka peci bisa memproteksi dirinya dari perbuatan yang tidak baik.”
“Oh, berarti hampir sama dengan tradisi masyarakat Bali ya?”
“Memangnya di sana bagaimana?”
“Bulan lalu, Rina dapat tugas ke Bali. Di sana, Rina melihat banyak sekali pengendara pria yang mengenakan udeng tanpa helm. Kata orang sana, polisi Bali selalu berbaik sangka kepada mereka yang mengenakan atribut keagamaan, seperti udeng, bisa dipastikan mereka akan beribadah atau sepulang dari ibadah, jadi tidak mungkin berbuat kriminal.”
“Kalau guyonan Ayah dulu, pakai peci biar tidak dikencingi setan,” Darmawan berkelakar lagi.
Peci bersejarah itu membentuk lekukan mesem. Suasana menjadi semakin hangat. Bahkan Lestari yang baru beberapa hari sembuh dari rumah sakit ikut menuju ke ruang tamu. Rina mengenalkan Ibra kepada ibunya. Lestari dan Darmawan merasa kembali muda.
Udara malam semakin dingin. Menembus kulit, darah, tulang, dan juga hati. Ada bunga yang memekar di relung hati Rina. Mulai malam itu, dan malam-malam selanjutnya, keberkahan menyelimuti mereka. []
Rumah Karya, 2016
Atunk Oman, lahir di Rembang 1990. Berdomisili dan berkarier di Jakarta. Suka membaca, menulis, menggambar, dan traveling. Twitter dan Instagram @Atunk_Oman.
Terpopuler
1
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
2
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
5
Kultum Ramadhan: Keutamaan Tarawih dan Witir
6
Khutbah Jumat: 4 Cara Menghidupkan Malam Ramadhan dengan Ibadah
Terkini
Lihat Semua