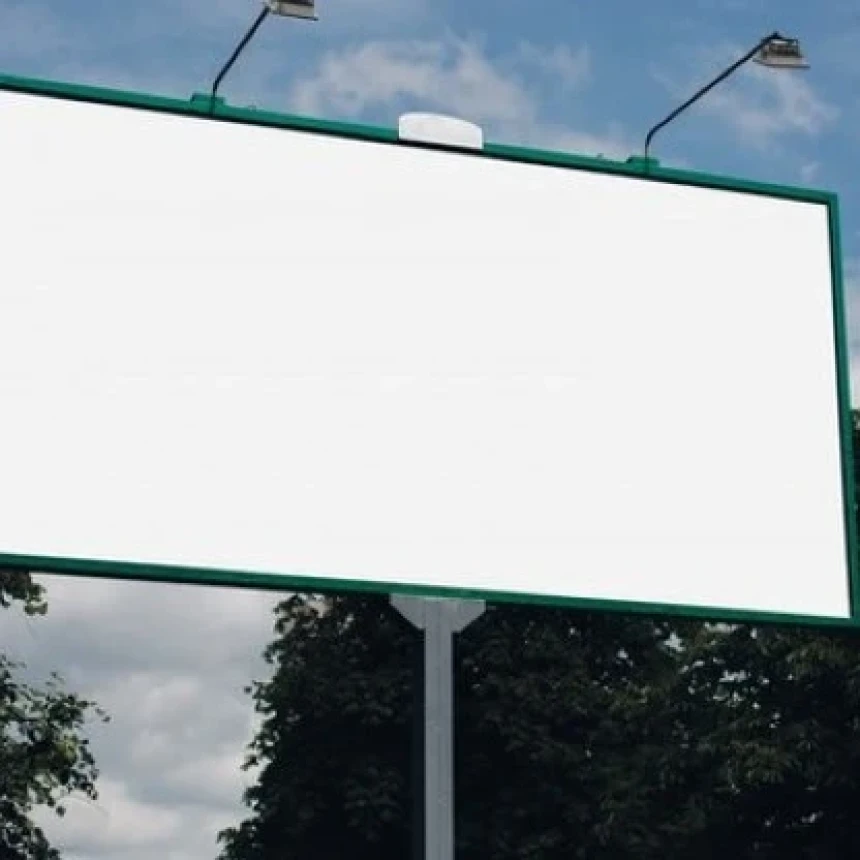Malik Ibnu Zaman
Kontributor
Matanya tak kunjung terlelap, bukan karena deru truk tronton yang menggetarkan lantai dan dinding kamar kosnya. Lagian, ia sudah terbiasa dengan getaran yang ditimbulkan dari truk pembawa peti kemas yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok.
Dilihatnya jam yang berdetak di dinding, jam sudah menunjukkan pukul 2 malam tepat. Ia menggumamkan sesuatu, “Sudah jam segini belum pulang.”
Ina sebenarnya sudah mengingatkan suaminya agar jam 12 malam sudah berada di kosan, meskipun siomay yang dijualnya masih banyak. Sebagai seorang istri tentu saja ia khawatir apabila suaminya pulang terlalu larut malam. Sebab kejahatan di kota Jakarta lebih banyak terjadi di malam hari.
Hubungan dengan suaminya bisa dibilang tak harmonis. Hal ini terjadi setelah anak pertamanya hilang tak ada jejak. Ina selalu menyalahkan bahwa hilangnya Ali, 5 tahun yang lalu, secara tidak langsung ada andil suaminya.
Baca Juga
Kepergian Seorang Kenalan
Ina bukanlah tipe orang yang bisa jauh dari kampung halaman. Dari lahir hingga umur 45 tahun tak pernah sekalipun keluar dari kampungnya di kaki Gunung Slamet. Tetapi hilangnya anak sulung, memaksanya pergi ke Jakarta. Tentu saja dengan satu harapan, ia bisa menyambut anaknya langsung dengan pelukan. Dan kosan yang ia tinggali sekarang adalah kosan yang dulu ditinggali anaknya.
Ali adalah satu dari sekian banyak orang yang dihilangkan secara paksa oleh rezim. Ia menjadi tumbal reformasi. Ina sering mendengar dari orang-orang, bahwa percuma ia menunggu anaknya yang diculik, sebab tak akan pernah mungkin kembali.
Ditatapnya anak bungsunya yang kini berumur 5 tahun, lalu ia usap rambutnya. Ia bersyukur dengan kelahirannya ke dunia. Ina menganggapnya sebagai obat yang diberikan Tuhan sebagai pelipur lara atas yang namanya kehilangan. Ditambah lagi wajah, perawakan, dan kelakuannya makin hari makin mirip dengan kakaknya. Dulu saat bayi merah hingga berumur 1 tahun wajahnya berbeda sekali, matanya sipit, kulitnya putih. Sehingga Ina sempat mengira anaknya tertukar di rumah sakit.
Akhir-akhir ini pikirannya sedang gamang, antara tetap menetap di Jakarta atau kembali ke kampung halaman. Azi sebentar lagi sudah waktunya masuk sekolah dasar, dan Ina sudah bertanya ke sana ke mari tentang biaya sekolah di Jakarta. Semua jawaban yang ia peroleh sama, yaitu mahal. Sehingga jalan realistisnya memang hanya satu, kembali ke kampung halaman.
Baca Juga
Selembar Memoar Aji
Tetapi sebab Ali masih hilang, hatinya enggan meninggalkan kota yang bernama Jakarta. Bisa saja sebenarnya ia bekerja, entah menjadi buruh cuci atau buruh masak, tetapi ia bingung menitipkan Azi ke siapa. Ditambah lagi ada perasaan takut kalau terjadi apa-apa dengan Azi. Ia tak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya.
Dulu saat masih di kampung, Ina punya penghasilan sendiri, tak bergantung pada uang dari suami. Selain menjadi buruh tani, kemampuannya meracik obat-obatan dari tanaman membuatnya benar-benar menjadi wanita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kemampuannya ini adalah warisan turun temurun dari mendiang ayahnya. Di Jakarta, sempat terpikirkan untuk membuka semacam rumah pengobatan alternatif, namun mendiang ayahnya mendatanginya dalam mimpi dan mengatakan tidak boleh. Praktis di Jakarta, kemampuannya meracik obat-obatan dari tanaman hanya digunakan ketika suami atau anaknya sakit, lalu tetangga kanan kiri saja yang hanya dibayar dengan ucapan terima kasih.
Suara roda gerobak berhenti terdengar di luar rumah, sudah pasti itu adalah suaminya. Tak, berselang lama suaminya masuk, lalu duduk di lantai, menyandarkan badan ke dinding. Meskipun ia tak mengeluh capai, tetapi tarikan nafasnya mengatakan capai.
“Sepi, masih sisa banyak,” keluh Ilman.
Baca Juga
Kehilangan Sandal Jepit
“Iza sebentar lagi masuk sekolah dasar, butuh yang namanya modal,” kata Ina membuka topik.
“Iya, iya aku juga mikir.”
“Dari dulu juga selalu bilang begitu,” ucap Ina. “Sudahlah, tak usah kamu biayai kuliah anak kakakmu yang kedua. Di mana-mana tak ada yang namanya keponakan bakal balas budi.”
“Tetapi Ira lain, anaknya tahu diri,” jawabnya sambil berusaha berdiri hendak keluar.
Baca Juga
Hitam dan Hijau
“Mau ke mana? Aku belum selesai ngomong.”
“Gerah, mau mandi.”
“Kamu tuh kebiasaan dari awal kita rumah tangga, aku belum selesai ngomong milih pergi.”
Ilman pun duduk kembali, lalu berucap, “Umur kita kan nggak muda lagi, Azi itu anak kita satu-satunya. Ketika dia kuliah, kalau kita masih hidup, umur kita sudah tua. Jadi dengan aku membiayai Ira, itu sama saja aku menitipkan Azi kepadanya kelak.”
Baca Juga
Warisan Api dari Tangan Ibu
“Kamu juga dulu membiayai kuliah Ima anak kakakmu yang pertama. Jangan pikir aku tidak tahu, Ali yang dulu menceritakannya. Tetapi lihat sekarang? Ima yang sudah jadi PNS di kementerian, nggak ingat sama pamannya yang telah membiayainya kuliah. Sikapnya malah sombong. Seharusnya ia tengok pamannya, bisa makan tidak.”
“Seandainya Ali masih hidup, barangkali sekarang ia jadi dosen, atau jadi PNS,” bisiknya pelan. Tetapi suara itu terdengar oleh Ina, dengan wajah mendadak merah ia meluapkan kekesalannya, “Ali hilang gara-gara kamu. Kalau saja kamu membiayai kuliahnya dengan benar, ia tak perlu mencari uang tambahan dengan menulis puisi, esai, cerpen yang mengusik rezim. Seharusnya saat itu kamu fokus membiayai Ali, tak perlu memikirkan biaya Ima.”
“Bu, Ali menulis bukan karena uang, melainkan panggilan hati,” kata suaminya sambil berusaha tangannya memeluk Ina, namun ia menangkis tangan Ilman.
Selanjutnya, Ina menangis sesenggukan. Meskipun tak meraung-raung, tetapi tetap saja suara tangsinya yang lirih membangungkan Azi, segera ia memeluk ibunya.
Baca Juga
Rindu yang Tak Berwujud
“Dan ingat ya, Ali itu masih hidup, dia belum mati.”
“Sudahlah, kamu ikhlaskan dia, agar jalan menuju Tuhannya lapang. Jika Ali melihat keadaanmu sekarang, pasti ia sedih. Ia pasti tak ingin ibunya hidup dalam kesedihan.”
“Ibu mana yang tak sedih kehilangan anaknya, kalau anaknya mati ada jasadnya masih mending. Lah ini, tak jelas keberadaannya,” timpal Ina. “Aku yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, tentu saja rasa kehilanganku jauh lebih besar dari pada kamu.”
Ilman pun hanya diam tertunduk lesu. Ia berpikir tak ada gunanya saling berargumen, yang perlu ia lakukan hanya diam. Di pertengkaran yang selama ini terjadi sebelum-sebelumnya, guna mendinginkan suasana Ilman harus menyingkir, agar api berubah jadi air. Ilman bangkit, lalu keluar. Kali ini Ina tak mencegahnya. Ilman terus berjalan, tujuannya adalah tepi Kali Lagoa Kanal guna menenangkan diri sejenak.
Baca Juga
Cerpen: Peci Miring
Esoknya, panas di dalam rumah tangga mereka sudah mereda, meskipun masih tercipta kekakuan di antara mereka. Ina seperti biasanya tetap menyiapkan sarapan untuk suaminya. Seusai makan, Ilman dengan hati-hati mengatakan agar Ina dan Azi kembali ke kampung.
Baca Juga
Matematika Tuhan
"Di kampung Azi jauh lebih aman dari segi apa pun, termasuk dari segi pergaulan,” dalihnya. "Di kampung, kamu bisa berkegiatan seperti dulu lagi. Dan di kampung, kamu bisa menenangkan diri, melupakan kesedihan.”
“Aku akan tetap di sini.”
“Kamu yakin?”
Baca Juga
Gadis di Derap Sunyi
“Tentu saja yakin,” ucapnya sambil membereskan piring yang tergeletak. “Aku akan membuka pengobatan alternatif.”
“Terserah kamulah, aku nggak mau ribut,” kata Ilman, lalu ia bangun dari duduk dan pergi ke pasar untuk belanja bahan membuat siomay.
Tak berselang lama, pintu kamar kosan diketuk. Rupanya ada tamu. Tampaknya suami istri dengan dua anaknya, satu berumur 4 tahun, satunya lagi 1 tahun. Dipersilakannya mereka masuk.
"Maaf, tempatnya sempit, maklum kamar kosan.”
Baca Juga
Mbah Samah
“Ya, nggak papa,” jawab si istri. “Kukira yang namanya Ina sudah nenek-nenek, ternyata tidak. Jadi begini nih, kami sudah ke mana-mana tetapi hasilnya nihil. Terus, ada orang yang menunjukan agar kami datang ke sini.”
"Maksudnya?” tanya Ina heran.
“Aku minta dibuatkan obat penggugur janin. Mbak tahu obatnya kan?”
Ina tercekat bukan main, baru kali ini ia dimintai obat untuk menggugurkan bayi. “Ngapian digugurkan, anak sudah diatur rezekinya oleh Tuhan.”
"Bukan begitu. Bagaimana ya aku menjelaskannya?" katanya kebingungan. “Ini tuh bukan suamiku. Suamiku merantau ke Kalimantan, sudah satu tahun lalu. Tolong, berapa pun Mbak minta, akan aku penuhi.”
"Tidak mau, jika aku menuruti itu, maka akan ada karma yang juga menimpaku. Aku bisa ketiban sial. Pokoknya aku tidak mau.”
Mereka kemudian pamit, wajah keduanya menjadi sedih. Di ambang pintu Ina mengatakan, “Lebih baik jujur saja, ya meskipun pahit.” Cukup lama keduanya ribut di depan kosan, sebelum akhirnya Ina menengahi, “Sudah, kalau ribut jangan di sini."
Sepeninggal mereka, Ina bergumam, “Mungkin hari ini aku menolak, tetapi aku tak yakin apakah ke depannya idealisku akan tetap sama. Katanya, Jakarta dapat dengan gampang membolak-balikkan hati, dan membuat putih jadi hitam. Sepertinya aku memang harus pulang kampung."
Malik Ibnu Zaman lahir di Tegal Jawa Tengah. Menulis cerpen, puisi, esai, dan resensi yang tersebar di beberapa media online. Buku pertamanya sebuah kumpulan cerpen berjudul Pengemis yang Kelima (2024).
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua