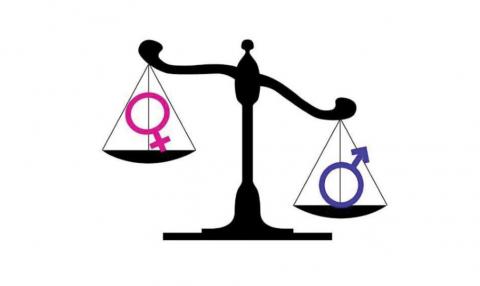Kapan Kita Bicara Keragaman di Wilayah Gender?
NU Online · Selasa, 24 Desember 2019 | 04:00 WIB

Perjuangan kesetaraan adalah tentang adanya ketertindasan, dan tak selalu terkait dengan dikotomi minoritas-mayoritas.
Fahri Hilmi
Kolomnis
Menyebut Indonesia sebagai negeri yang multikultural adalah benar. Mengatakan bahwa di dalamnya terdapat banyak kelompok masyarakat yang beragam juga benar. Pun kalau kita meyakini bahwa menjaga keragaman itu adalah berarti menjaga Indonesia, itu juga benar.
Seperti bumi, langit, dan segala keteraturannya, keragaman negeri ini adalah sunnatullah, tak bisa diganggu gugat. Barangkali ini dapat menjadi argumen, mengapa menjaga kemajemukan adalah bagian dari ibadah. Seperti itu pulalah, mengapa menjaga kesatuan negeri ini sering kita sebut bagian dari hubbul wathan (cinta tanah air)--yang juga bagian dari iman (minal iman).
Dalam sebuah pertemuan, Lukman Hakim Saifuddin, yang saat itu menjabat menteri agama, mengatakan bahwa keberagaman adalah sunnatullah. Menolak keberagaman, artinya melawan sunnatullah.
Baik. Jika kita menjaga keragaman itu karena berdasar pada sifatnya yang niscaya, maka memahami adanya perbedaan adalah juga pekerjaan yang niscaya. Sayangnya, wacana mengenai keberagaman ini cenderung terbatas pada pengelompokkan agama, ras, dan suku saja. Padahal, heterogenitas Indonesia itu lebih jauh dan luas daripada ketiganya.
Salah satu yang menjadi bagian dari keberagaman adalah perbedaan gender. Mengapa perbedaan gender menjadi bagian dari wacana keberagaman? Seperti kita tahu, pertemuan antar-gender juga tak luput dari pertentangan. Pertentangan kepentingan antara laki-laki dengan perempuan telah lama dimenangkan oleh laki-laki dan mengakibatkan perempuan berada pada posisi tertindas. Kepada laki-laki, perempuan seakan sekunder dan tak memiliki daya tawar yang sama. Keduanya dianggap tak setara.
Boleh saya beri contoh. Seorang perempuan bernama Khotimah bekerja sebagai kasir di sebuah kedai kopi. Suatu hari, ia mesti pulang larut malam karena kebetulan ia mendapatkan shift malam.
Di lain posisi, Abdullah, suami Khotimah, sudah menunggu kepulangan Khotimah dengan akumulasi kemarahan. Abdullah sudah lama marah karena Khotimah tak mengindahkan kemauannya untuk tak memilih pekerjaan tersebut. Ia menilai, perempuan tak baik jika pulang terlalu malam. Abdullah bahkan bilang bahwa tak apa kalau harus kekurangan uang asal istrinya tetap fokus pada “kodratnya” sebagai perempuan: mengurus urusan rumah. Singkat cerita, mereka bertengkar dan berujung pisah ranjang.
Pertentangan antara Abdullah dan Khotimah ini bagi saya juga bagian dari persoalan kebinekaan. Mengapa demikian? Jika kita merunut pada pengelompokkan manusia berdasarkan agama, maka Abdullah dan Khotimah sama-sama Muslim. Namun, patahan lain mesti mempertentangkan keduanya. Patahan tersebut adalah patahan gender.
Khotimah yang kerja larut malam berpikir bahwa ia bekerja demi keuangan keluarga. Namun, Abdullah lain hemat. Baginya, perempuan tak berkodrat demikian. Kendati Abdullah belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari segi finansial, Abdullah mau Khotimah fokus di rumah, sedangkan ia fokus bekerja. Kedua kepentingan ini bertemu di medan realitas. Sebagaimana menjadi bahasan dalam tulisan ini, pertentangan tersebut mestilah didamaikan melalui apa yang kita sebut sebagai perjuangan keberagaman.
Persoalan ini belum sampai pada persoalan pemerkosaan, kekerasan seksual, pembungkaman, objektifikasi perempuan, eksploitasi, pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, juga persoalan-persoalan lain yang merugikan perempuan.
Belum lagi nisbinya pemenuhan hak cuti haid, cuti hamil, atau kebutuhan-kebutuhan perempuan yang selalu luput dari perhatian. Persoalan-persoalan keberagaman macam itu masih tak menjadi pembahasan. Apakah kemudian wacana kebinekaan tak berhak menyentuh wilayah itu? Jika memang iya, tentu menyedihkan, mengingat perempuan adalah ibu dan asal dari mana kita lahir.
Jika kita meyakini bahwa perempuan adalah juga manusia, maka semestinya kita menaruh diri duduk setara dengan mereka. Mengapa demikian? Boleh kita membaca Gus Dur. Gus Dur betul-betul yakin bahwa memperjuangkan keberagaman berarti berjuang bagi kemanusiaan. Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah mengatakan, “Memuliakan manusia, berarti memuliakan penciptanya.”
Dalam hemat saya, apa yang Gus Dur sebut sebagai manusia adalah benar-benar manusia. Maksud saya begini, selama ini kita menangkap pesan kemanusiaan itu dengan bekerja memperjuangkan kesetaraan bagi kaum minoritas. Namun, kita tak menangkap, bahwa manusia yang mesti disetarakan adalah manusia yang “tidak setara”, tidak melulu terkait kuantitas mereka.
Memperjuangkan kesetaraan bagi minoritas adalah berjuang pada konteks ketertindasannya, bukan pada konteks jumlahnya. Artinya, walaupun perempuan berjumlah lebih banyak ketimbang laki-laki, selama mereka diperlakukan tidak adil, maka kita wajib memperjuangkan kesetaraannya.
Perempuan dan laki-laki adalah kelompok sosial yang kepentingannya berbeda. Kepentingan itulah mesti didamaikan. Dalam konteks pertentangan antara keduanya, perempuan yang ditekan dan ditindas. Untuk itu, bagi saya, memperjuangkan keberagaman, berarti juga memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
Melalui pemetaan di atas, saya ingin mengatakan, bahwa Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya berlaku pada pertentangan kelompok agama, ras, dan etnis saja, melainkan juga pertentangan gender. Ragam gender adalah juga ragam Indonesia. Menolak kesetaraan gender, berarti menolak kebinekaan. Memperjuangkan kesetaraan gender, berarti memperjuangkan kebinekaan.
Lalu, kapan kita bicara keragaman pada wilayah gender?
Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
4
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua