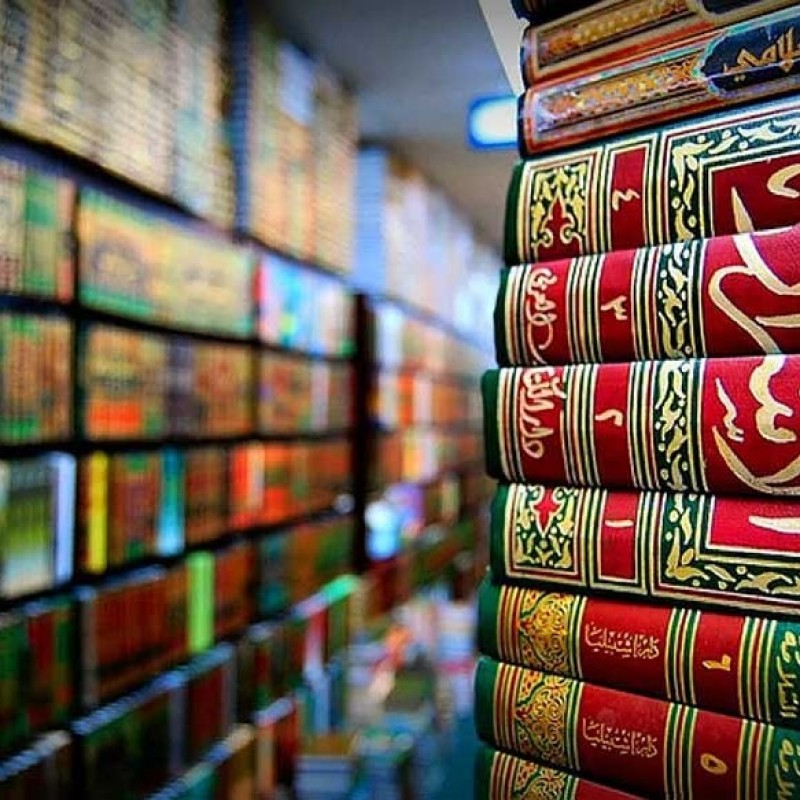Risiko Ekonomi bagi Kelas Bawah saat Pasar Ditutup
NU Online · Kamis, 2 April 2020 | 10:15 WIB
Muhammad Syamsudin
Kolomnis
Wabah Coronavirus disease (Covid-19) yang tengah melanda negeri ini telah menjadi konsumsi informasi dan perbincangan masyarakat di semua lini kehidupan. Tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah perkotaan yang terdampak, melainkan juga mereka yang tinggal di perdesaan turut serta terkena imbasnya. Sudah barang tentu, imbas ini tidak hanya dari sektor kesehatan, melainkan juga sektor ekonomi masyarakat. Roda perekonomian terganggu sebagai ekses besar dari kebijakan dan kondisi.
Ketergangguan ekonomi khususnya terjadi pada sektor distribusi. Pemberlakuan lockdown dan social distancing secara tidak langsung menghambat cepat sampainya barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Terputusnya beberapa mata rantai jaring ekonomi menjadikan harga jual produk pertanian menjadi sektor yang paling riskan mengalami terjun bebas, namun sampai di tangan konsumen dengan harga meroket.
Sebenarnya stok barang di pasaran konsumen tidaklah begitu banyak. Masyarakat konsumen juga tengah gencar mencarinya, bahkan berapa pun harganya, mereka siap menebusnya asalkan barang kebutuhan itu ada. Tapi, sektor pendistribusian hasil produk pertanian dari hulu ke hilir ini yang mengalami keterguncangan.
Imbasnya, hasil produksi para petani yang berhasil diserap oleh pasar menjadi semakin sedikit. Membludaknya hasil produksi, dan tersumbatnya jalur distribusi barang, sementara kebutuhan konsumen di pasaran yang meningkat, mengakibatkan timbulnya jurang harga. Yang diuntungkan adalah pengusaha tengkulak yang menjadi mak comblang antara kedua pihak (produsen-konsumen). Mereka dengan cakap dapat memainkan harga dengan alasan keterbatasan sarana distribusi barang.
Jika peningkatan harga oleh pengusaha yang menguasai sektor produksi terus menerus terjadi, sementara masyarakat harus lockdown dari aktivitas mata pencariannya, dapat berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Terhentinya sumber mata pencarian ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya beli mereka ini, jika berlangsung lama, dan bila dikaitkan dengan harga jual barang kebutuhan, dapat memunculkan krisis baru yaitu miskin dadakan.
Kondisi ini akan semakin parah bila pasar dan pusat perbelanjaan masyarakat ditutup. Tidak hanya masyarakat konsumen saja yang menjadi korban, melainkan juga masyarakat produsen. Dan masyarakat produsen ini sebagian besar justru tinggalnya ada di wilayah-wilayah perdesaan yang bermatapencarian petani dan nelayan.
Aktivitas penutupan pasar oleh aparat setempat, justru semakin mempersempit ruang distribusi dan daya serap produk mereka. Untuk para petani yang memproduksi bahan pokok kebutuhan tahan simpan sih tidak banyak berpengaruh. Tidak bisa dijual hari ini, bahan pokok kebutuhan bisa dijual kelak di kemudian hari. Namun, untuk para petani sayur-mayur yang barangnya harus cepat habis, hal itu dapat menjadi keprihatinan.
Bagaimana tidak? Hasil produksi mereka harus habis dalam waktu cepat. Jika tidak, maka barang itu akan rusak sehingga berbuntut penyusutan dan tidak laku di pasaran. Eksesnya, modal produksi mereka menjadi tidak bisa kembali. Sementara itu, durasi panen mereka yang berlangsung cepat, karena untuk kategori tanaman sayuran, umumnya hanya mampu mencapai 8-9 masa petik dalam satu kali tanam.
Bahkan untuk kategori tanaman bawang merah dan bawang putih, hanya memiliki waktu sekali panen saja dalam satu kali periode tanam dengan lama simpan yang tidak mampu mencapai 30 hari pasca panen. Semakin lama tertahan maka berat hasil panenan menjadi semakin susut bobotnya. Alhasil, jika “pasar produksi” mereka harus mengalami proses lockdown juga, maka itu berarti sama saja dengan telah menyumbat peluang cepat habisnya barang mereka. Dan pada akhirnya, kebijakan seperti ini menjadi tidak populis, meskipun berdasar data Badan Pusat Statitistik (BPS) Nasional, penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perdesaan hanya berkisar 46 persen saja.
Dengan demikian, mereka yang berjumlah 46 persen ini harus menjadi penyangga dari masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan dengan komposisi 54 persen. Sekilas saja, dapat dibayangkan, bahwa rusaknya hulu, dapat berakibat pada rusaknya hilir. Gangguan pada produsen di hulu (perdesaan), dapat membikin gejolak pada lapisan masyarakat yang tinggal di hilir (perkotaan). Dan itu semua kuncinya ada pada pasaran produk. Jika pasaran itu ditutup, maka penulis tidak sanggup membayangkan dengan apa yang terjadi kelak.
Bulan Maret dan April merupakan bulan di mana statistik produk pertanian yang terdiri atas sayuran adalah mencapai puncak produksi. Petani sedang panen raya, seiring keterlambatan datangnya musim penghujan pada tahun 2020 ini, menjadikan proses produksi mengalami molor hingga hampir memasuki tahun 2020, para petani baru bisa menggarap sawah dan ladangnya.
Rata-rata kebutuhan untuk melakukan produksi di bidang pertanian, adalah minimal 70 hari setelah tanam (70 HST), untuk pertanian cabai dan 60 HST untuk bawang merah. Jadi, jika awal musim tanam itu dimulai bulan Januari, maka semestinya bulan Maret, adalah kondisi di mana para petani mengalami awal musim panen. Atau maksimal pertengahan Maret.
Sementara itu, status wabah Covid-19 dinyatakan sebagai Bencana Nasional Non-Alam oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tanggal 14 Maret 2020. Jadi, penerapan kebijakan ini bertepatan dengan kondisi petani mengalami panen raya. Padahal, ekses dari perubahan kebijakan Status Darurat Penanganan Covid-19 menjadi Bencana Nasional Non-Alam ini, berbuntut pembebanan tugas dan tanggung jawab siaga darurat Covid-19 tidak hanya terhenti pada Pemerintah Pusat, melainkan pemerintah daerah juga memiliki kewajiban meresponsnya berbasis kedaerahan.
Jika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan lockdown, sehingga berbuah menutup pasar, maka itu sama artinya dengan telah berbuat kezaliman kepada para petani di wilayah perdesaan. Hasil produksi sayur-mayur dan berbagai panenan mereka mau diapakan?
Penting untuk dijadikan sebagai sebuah catatan, bahwa fungsi jaring sosial yang dimiliki oleh petani, adalah tidak sama dengan masyarakat perkotaan. Jika masyarakat perkotaan, tidak bisa berangkat ke pasar pun, mereka bisa saja belanja daring online. Tapi, ini berkaitan dengan produk yang harus cepat habis di petani dan nelayan tentunya.
Saat kondisi masyarakat sedang normal, mereka kerap dinikmati produknya, meski juga tidak jarang mereka juga dijatuhkan haknya dalam mendapat keuntungan yang besar akibat kebijakan pembatasan harga produk lewat operasi pasar. Namun, dalam kondisi bencana seperti ini, masak kita juga akan tega menjadikan mereka sebagai korban hidup dan kebijakan akibat penutupan pasar?
Semestinya, harus ada perimbangan. Jika dalam situasi normal ada operasi pasar, maka dalam situasi wabah dan bencana nasional, para petani inilah yang semestinya pertama kali harus menerima kompensasi kebijakan. Bukannya justru para pengusaha-pengusaha sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 /PMK.03/2020 itu yang kerap diuntungkan dalam situasi normal dan abnormal. Tapi mengapa justru mereka yang mendapatkan pengampunan pajak. Daripada anggaran dipergunakan untuk mensubsidi tanggungan pajak mereka, alangkah lebih baik bila subsidi itu dialokasikan ke pemutihan tanggungan para petani di wilayah perdesaan. Merekalah korban virus Corona yang sebenarnya.
Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
4
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua