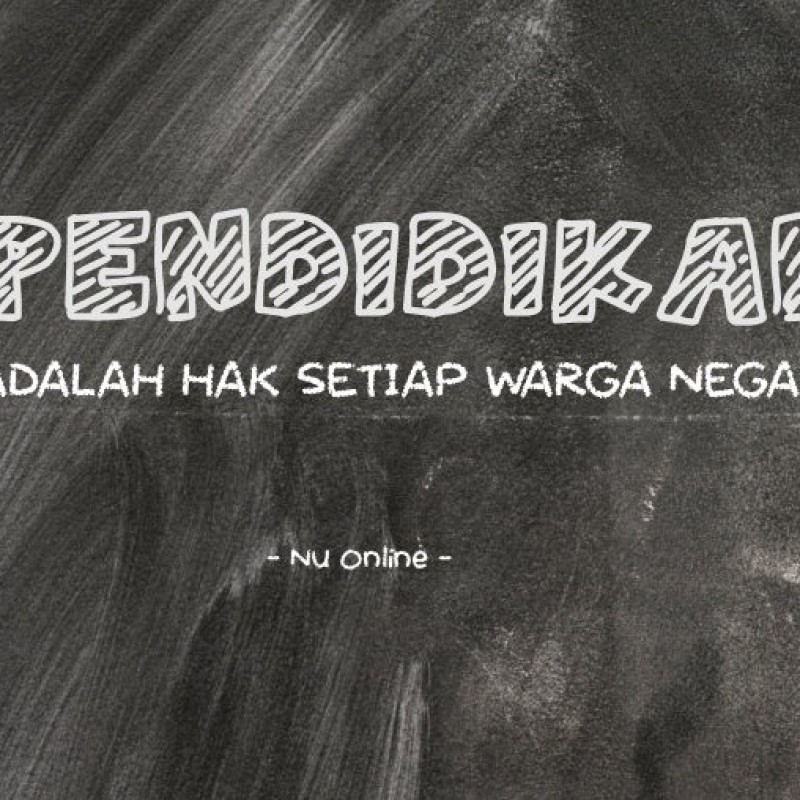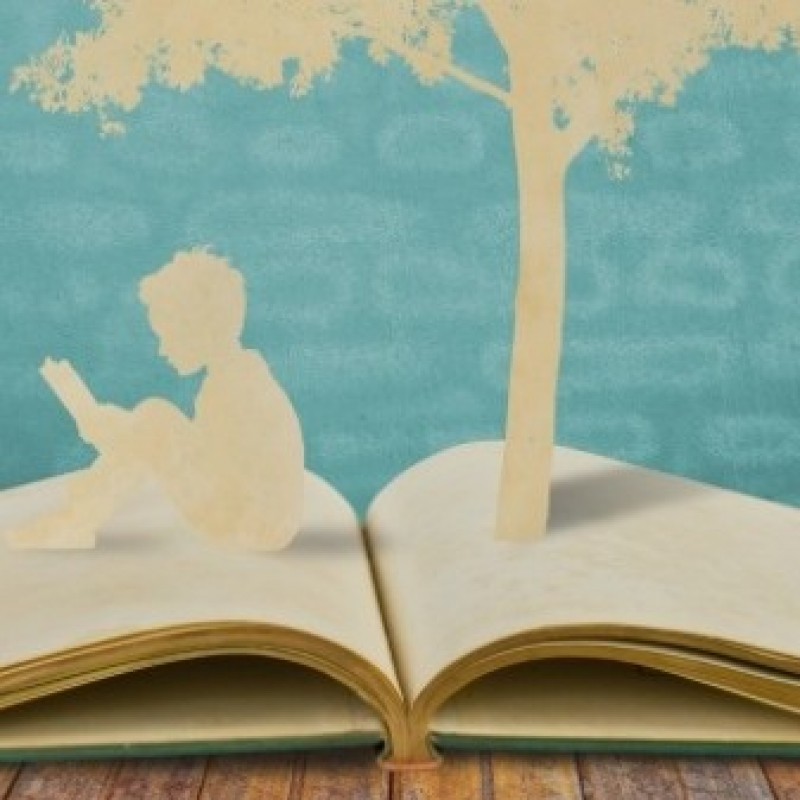Oleh Abdullah Wong
[Andai coronavirus adalah burung yang bicara, mereka terbang di angkasa seraya berteriak, "Diam!"]
Berdiam di Kediaman
Syahdan pandemi virus Corona menggiring kita untuk segera pulang. Virus Corona yang telah merenggut banyak korban itu seakan memaksa kita tidak punya pilihan kecuali berdiam di rumah. Atas nama nyawa dan penghentian laju penyebaran virus, pemerintah di setiap negara memerintahkan kepada rakyatnya untuk berdiam di rumah (stay at home). Keharusan tinggal, berdiam, atau "sembunyi" di suatu tempat sebagaimana rumah tentu bukan hal baru. Kita ingat zaman mesolithikum atau masa Batu Tengah ketika Abris Sous Roche menjadikan gua sebagai tempat berdiam, berlindung sekaligus persembunyian dari berbagai gangguan dan serangan binatang buas. Manusia gua berharap dengan berdiam di dalam gua, dirinya memeroleh keamanan, kenyamanan dan kedamaian.
Bicara gua, dalam khazanah sejarah Islam ditemukan sirah bahwa Muhammad bin Abdullah menjelang usia 40 tahun sering masuk dan berdiam di dalam gua. Gua Hira namanya. Berbagai riwayat menyebutkan, sebelum Muhammad diutus jadi nabi, ia sering uzlah (menjauh dari keramaian), khalwat (menyepi), dan tahannuts (kebaktian). Ahmad bin Faris dalam kitab Maqayis al-Lughat memaknai tahannuts sebagai ta’abbud atau peribadatan. Sedangkan dalam The New Encyclopedia of Islam: Revised Edition of The Concise Encyclopedia of Islam, Nicholas Drake dan Elizabeth Davis memahami tahannuts sebagai upaya pencarian Tuhan yang dilakukan seorang hamba dengan cara menghindari diri dari dunia ramai dan berbagai jenis gangguan yang ada dalam jiwa.
Muhammad melakukan tahannuts di gua Hira bukan tanpa alasan. Selain tradisi turun temurun dari leluhur Hunafa (jamak dari hanif), Muhammad menyepi demi menghindari perilaku bodoh masyarakat Mekah yang sedang terjangkit virus kemanusiaan. Dianggap wajar ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup oleh ayah kandung sendiri. Mereka malu punya bayi perempuan yang dianggap lemah dan tak berguna. Era yang disebut jahiliyah itu hanya menyajikan ketimpangan sosial, perbudakan, penindasan bahkan pembunuhan atas nama keyakinan dan kepercayaan. Padahal di bidang ekonomi, Mekah berkembang pesat. Di ranah sastra, masyarakat Mekah saat itu juga sangat kuat. Penghargaan estetik terhadap karya syair terbaik dilakukan dengan cara ditempelkan pada tembok Ka'bah sepanjang tahun, muallaqat namanya. Meski peradaban intelektual begitu hebat, tapi moral dan akhlak masyarakat Mekah mengalami dekadensi.
Satu hal yang menarik: Muhammad yang "gelisah" melihat situasi itu mencari solusi bukan dengan menyusun kekuatan tentara, membangun kekuasaan, apalagi menyiapkan peperangan. Muhammad memilih diam di gua Hira demi mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Laku Muhammad ini jadi makna: siapa yang hendak menyelesaikan permasalahan sosial bahkan kebangsaan, mesti dimulai dari menyelesaikan persoalan dirinya sendiri lahir batin. Faktanya, sebagaimana Ibrahim, Daud, Musa, atau Sidharta, mereka beroleh ketersingkapan ketika mereka dalam keberdiaman. Meski dalam konteks berbeda, ketersingkapan yang datang begitu saja tanpa upaya seperti "eureka" yang diteriakan Archimedes, ilmuwan dari Syracuse, Yunani itu.
Mengenai berdiam di dalam gua, khazanah Islam juga menyebut sekelompok pemuda yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang sembunyi di dalam gua demi menghindar kejaran raja yang tiran itu diabadikan dalam Kitab Suci Al-Quran (18: 9-13). Tak hanya dikisahkan, Al-Quran bahkan menjadikan Al-Kahfi yang bermakna 'gua' sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Begitu pentingnya gua, sampai Surat Al-Kahfi ditempatkan di tengah-tengah dari seluruh surat-surat dalam Al-Quran. Seakan Al-Quran berbisik, siapa yang hendak menemukan inti Al-Quran, maka ia harus masuk ke dalam gua.
Dalam gua atau tempat keberdiaman, terdapat keintiman yang kuat antara Keheningan dan Pemikiran. Pemikiran yang menyeluruh bila diendapkan dalam keheningan yang konsisten berbuah pada fokus yang kuat. Tapi untuk fokus kita harus berpikir mendalam. Sementara untuk mendalami relung pikiran, kita justru harus mengendapkan pikiran dalam keheningan. Dan keheningan dimulai dari diam.
Seperti garam di lautan. Meski laut yang selalu terpapar radiasi matahari tidak menjadikan laut jadi padang garam karena tidak berlangsung keheningan. Air laut selalu bergerak; di permukaan maupun di dalamnya. Sementara, garam itu terjadi melalui proses pengangkatan H2O demi meningkatkan konsentrasi mineral yang kemudian disebut air garam. Kepekatan larutan mineral itu sangat bergantung kepada seberapa banyak H2O yang terangkat atau terlepas. Dalam teknik tradisional, proses mengendapkan mineral sampai terbentuk kristal garam paling cepat membutuhkan waktu 9 minggu.
Hening dalam Kediaman
“Ketika kau sedang berbaring di kasurmu, carilah hatimu dan hening,” demikian kata Daud dalam Mazmur. Hening dalam kediaman menyimpan ribuan kesadaran. Kesadaran yang tak dapat didengar siapa pun yang tak bersedia hening dalam kediaman. Keheningan adalah Kidung Ilahi yang senantiasa membisikkan keagungan sekaligus pencerahan bagi siapa yang bersedia memerdekakan perang Bharatayudha dalam Kurusetra pikiran. Keheningan adalah anugerah untuk menyadari Kehadiran Tuhan.
Bagi Walter Benjamin, keheningan (silence) diyakini sebagai keadaan tidak ada kebisingan dan kata-kata. Falling silent, demikian kata Walter Benjamin. Falling silent meski mirip tapi tak sama dengan fall in love. Mirip karena siapapun yang falling silent, seperti berserah diri untuk hening sebagaimana fall in love itu menyerah untuk mencinta. Tapi bagi Benjamin, falling silence bukan suatu kondisi (state) tapi lebih sebagai peristiwa (event). Karena Falling tidak bisa dikondisikan melainkan kejadian yang mengalir, begitu saja hadir, ujug-ujug, yang mau tidak mau kita mengikuti harus peristiwa tersebut.
Lain lagi jika kita memahami Ludwig Wittgenstein, filsuf Matematika dari Austria. Dalam karyanya, Tractacus Logico-Philosophicus, terutama di proposisi ke-7, Wittgenstein menyebutkan, “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.” "Saat kita tak dapat bicara, maka kita harus diam.” Premis tersebut boleh diserap secara literal. Tapi bila kita lebih cermat lagi, esensi dari proposisi Wittgenstein justru sedang menyatakan bahwa sesungguhnya kita memang tidak akan pernah mampu membicarakan semuanya. Bahwa tidak semua hal mampu kita bicarakan, ceritakan, disampaikan dengan menggunakan kata dan makna. Dengan yakin Wittgenstein menegaskan, kita mesti diam, hening dan membiarkan kesadaran kita terekspresikan lewat gambar atau ungkapan non-verbal.
Fakta menarik, meskipun Wittgenstein merupakan salah satu tokoh penting dalam barısan positivistik di Lingkaran Wina--sebagaimana Rudolf Carnap, Friedrich Waismann, Bertrand Russell--malah menyatakan bahwa keheningan verbal dan bicara non-verbal dengan hanya menggunakan teori ‘The Picture Theory’ semata tidak akan pernah cukup menggambarkan "Diam". Untuk mencermati kebingungan Wittgenstein, penulis menyusuri disertasi Dr. Robert Eli Sanchez, Jr. yang berjudul The Virtue of Irony and Silence: An Ethical Reading of Socrates, Kierkegaard, and Wittgenstein. Untuk menggambar betapa sulitnya memahami Tractacus dari Wittgenstein, Dr. Eli Sanchez kemudian mengomparasi dua filsuf ternama, yaitu Sørén Aabye Kierkegaard dan Socrates. Eli Sanchez melakukan langkah ini lantaran kesulitan yang menyelimuti Tractacus mirip dengan Socratic Problem dan Kierkegaardian Problem. Keduanya sama-sama menggambarkan permasalahan bahwa suara Socrates yang asli itu sulit didengar, begitu pula dengan suara Kierkegaard. Keduanya sama-sama "diam" ketika mereka menulis filsafat. Sedangkan dalam kasus Tractacus, Wittgenstein memilih diam karena ketidakmampuan Wittgenstein menemukan keheningan di luar Non-Verbal. Singkat kata, Eli Sanchez seperti berkata, "Soren Kierkegaard diam karena tidak tahu apa yang hendak dikatakan, Socrates diam karena tahu dan tak perlu berkata apa-apa."
Mengulum Kehingan
Di muka disebutkan, siapa yang hendak memahami Al-Quran, maka ia harus masuk ke dalam "gua" (Al-Kahfi). Seakan gua (cave) adalah "ruang hampa" (void) untuk mengakses kandungan Al-Quran. Dalam Seni Sakral, urgensi kehampaan disimbolkan dengan realitas yang tidak dimanifestasikan (al-Ghayb). Orang yang baru kali pertama masuk ke dalam masjid, tentu takjub terhadap kehampaan ruang di dalamnya. Faktanya, realitas utama dari ruang masjid adalah kehampaan sehingga memberi pesan kepada siapapun yang memasuki dapat merasakan kekosongan dan kehampaan, ketidakberdayaan juga ketidakmampuan di hadapan Realitas Suci. Pengalaman kehampaan juga ditemukan di rumah-rumah tradisional. Hampir seluruh titik pusat dalam kesenian sakral, dekorasi yang ditunjukkan selalu menyajikan elemen kekosongan dan kehampaan. Tujuan kehampaan dalam kesenian sakral adalah untuk mengantar kita menyadari ketidakberadaan di hadapan Tuhan. Bahwa sejatinya kita tidak punya apapun, bahkan fana. Itu kenapa Nabi Muhammad berkata, “Kefakiran adalah Keindahanku.” Sementara Allah berfirman dalam Surat Muhammad ayat 38, "Dan Tuhan tak butuh apapun, sementara kalian selalu saja membutuhkan sesuatu."
Dalam teks Arab, kahfi (كهف) yang bermakna gua terdiri dari tiga huruf, yaitu k-h-f. Huruf yang berada di tengah-tengah k-h-f adalah huruf 'h'. Bila kita rasakan dalam mengartikulasikan, huruf 'h' adalah satu-satunya huruf dari seluruh peradaban manusia yang ketika diucapkan muncul dari dalam dada. Tak ada satu pun huruf yang keluar dari dalam dada manusia kecuali 'h'. Bila lebih dalam lagi kita susuri, huruf 'h' yang dalam literasi Arab ditulis dengan (ه) merupakan simbol kehampaan (void), yang tak lain adalah 'هو' yang bermakna Dia. 'H' adalah helaan nafas kesucian yang terdapat pada pusat wujud manusia. Kemana ia dibawa, kemana ia dicari, hela nafas suci itu senantiasa ada. Di sini kita insyaf, bahwa Dia begitu nyata terasa di kedalaman. Bukan dalam pikiran apalagi mulut yang rewel. Gua yang 'hampa' itu, sungguh 'wujud' di dalam diri kita.
Kesadaran gua adalah pengetahuan tentang kedalaman diri. Yakni ketika siapa pun istiqamah bersedia menemukan kembali apa yang telah diketahui tapi terlupakan, bukan apa yang sedang ditemukan. Karena logos yang pada awalnya memiliki prinsip-prinsip pengetahuan dan kekayaan pengetahuan berada tersembunyi di dalam ruhani manusia yang disadari melalui rekoleksi (iqra'). Bahwa yang diketahui itu bukan di luar sana atau di balik batas pengetahuan, tapi dalam pusat wujud manusia di sini dan sekarang, di keberdiaman. Dia tidak dikenal hanya karena sifat kelupaan kita terhadap kehadiran-Nya. Dia adalah matahari yang tak pernah padam secara sederhana, sementara kebutaan kita begitu keras membatu terhadap Cahaya-Nya lantaran virus berupa pikiran sendiri. Maka mengetahui adalah diselamatkan. Merujuk pada Gospel of John kita menemukan, "Dan bila engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran membebaskanmu."
Kemudian, jika kita lepas huruf demi huruf dalam 'كهف', ditemukan sejumlah isyarat. Isyarat itu dimulai dengan menyimpan huruf 'h' (ه) dari ketiga huruf tersebut maka yang terlihat adalah: Pertama, kata yang terbentuk dalam: كَفَّ - يكفّ عن; Kata ini memiliki sejumlah makna, yaitu menahan diri, menyangkal, menghentikan, menundukkan, meninggalkan, memutuskan, mencukupkan dan menyerah. Seluruh makna ini berkaitan dengan segenap sikap keberdiaman dalam gua. Yakni sikap melakukan penyangkalan demi penyangkalan dari setiap asumsi yang kita miliki. Bahkan Allah yang selama ini kita sembah sebatas Allah asumsi dalam pikiran kita sendiri. Semua mesti disangkal atau dinegasikan. Karena Allah tak dapat diserupakan dengan apapun bahkan yang mirip sekalipun. (Huwa laa huwa laa huwa). Segalanya bukan! Bahkan yang bukan pun bukan dan selalu bukan!
Kedua, jika kita balik hurufnya menjadi: فَكَّ - يفكّ, maka makna yang muncul adalah membongkar, mengambil terpisah, memisahkan, memutuskan, melepaskan, membebaskan, memerdekakan, menguraikan, membuka, mengurai (dechiper). Seluruh makna ini berisi tentang bagaimana keberdiaman dalam gua itu berkaitan dengan melepaskan dan memutus segala kemelekatan dalam diri kita. Bahkan kata ini dalam pembicaraan Arab bermakna memerdekakan. Ketiga, bila kita biarkan ketiga huruf itu berdiri sebagai huruf yang utuh, maka k-h-f (كهف) adalah kun (كن) untuk k (ك ); huwa (هو) untuk h (ه); dan fayakun (فَيَكُون) untuk f (ف).
Masih menyusuri gua bernama Surat Al-Kahfi, jika kita membaca ayat demi ayat di dalamnya, kita menemukan satu kata yang merupakan kata tengah-tengah (sentral) dari seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kata itu adalah walyatalatthaf (وَلْيَتَلَطَّف) yang artinya dan 'hendaklah dia bersikap lemah lembut.' Kata ini berakar dari kata 'l-th-f' (لَطَفَ - يلطف) yang bermakna 'lemah lembut dan ramah.' Tentu bukan kebetulan jika kata paling tengah dalam Al-Quran bermakna kelembutan dan keramahan, kecuali makna tersebut menjadi prinsip sekaligus pesan utama dalam penyelenggaraan segenap kebaktian kepada Tuhan maupun semesta. Dalam bahasa kotemporer, lathif kemudian maknai sebagai software. Karena secara substansial, software dari seluruh Al-Quran adalah kelembutan jiwa yang hanya dapat "ditemukan" di dalam gua "kehampaan" terdalam. Prinsip kelembutan sebenarnya sejalan dengan prinsip kepolosan atau kemurnian sebagaimana yang tampak pada anak-anak (طفل). Secara huruf, diksi طفل yang bermakna anak ini adalah pergeseran posisi huruf dari kata لطف yang bermakna kelembutan.
Robohnya Gua Keheningan
Coronavirus (Covid-19) hanya satu fakta. Suka atau tidak, keberadaannya menjadikan kita harus menemukan kembali gua-gua persembunyian. Tapi virus-virus lain yang juga mengharuskan kita pulang menemukan gua kehampaan di kedalaman diri kita juga fakta yang tak terbantah. Sebelum Covid-19, begitu banyak virus yang menghampiri kita secara laten. Virus kesenjangan sosial, virus koruptif, manipulatif, hingga virus hoax yang tak mampu dibendung oleh masker atau disinfektan apapun. Belum lagi virus bernama tafsir tunggal yang mengatasnamakan agama dan keyakinan. Virus kebenaran tunggal bahkan dapat menjadikan penganutnya sebagai mesin pembunuh sadis. Prinsipnya, virus apapun yang bermutasi dari ego kita secara laten mewabah di dalam diri kita.
Covid-19 membuat kita mengenakan masker, seakan mulut kita dipaksa bungkam. Selama ini kita terlalu bawel, berisik, chaos dan mengada-ada dalam memahami realitas. Kita mesti diam (سكن) dan tak perlu panik, demi mendapatkan ketenangan (سَكِيْنَة) yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Tapi bukankah diksi sakinah (سَكِيْنَة) itu berasal dari sikkin yang bermakna pisau? Artinya, stay at home jadi percuma jika kita tak bersedia memotong nafsu pikiran kita sendiri. Tubuh kita mungkin berdiam di rumah, tapi jiwa kita tak pernah dirumahkan dalam keheningan.
Jika demikian yang terjadi, maka seribu corona datang tak membuat kita menjalani kesempatan yang Dia berikan. Mestinya, stay at home menjadi momentum (ahwal) istimewa bagi kita dalam mengasingkan diri (seclusion) atau pengunduran diri (retirement) dari hiruk pikuk pikiran. Sehingga rumah-rumah kita dapat menjadi semacam zawiyah atau pesantren yang jauh dari keramaian selama beberapa hari demi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi mengapa tempat persembunyian sebagaimana karantina selalu dirasa menjenuhkan? Inilah perang yang sebenarnya terjadi. Siapa pun yang diasingkan pasti akan merasa kesepian. Jika kita tiba-tiba diasingkan di sebuah pulau kecil di tengah lautan tanpa penghuni, gangguan binatang buas atau makhluk tertentu mungkin masih dilawan. Tapi melawan kesepian, adalah penderitaan yang memilukan. Bahkan Chuck Noland dalam film Cast Away begitu terpukul dan menjerit ketika kehilangan Wilson.
Kenapa kesepian begitu mencekam dan menyakitkan? Karena dalam kesepian tak ada afirmasi tentang si aku. Keberadaan orang lain kemudian dianggap bermakna sebenarnya karena orang lain itulah yang dapat mengafirmasi aku-kita. Betapa sakitnya aku jika aku-kita tak diakui orang lain. Aku-kita akan selalu meronta apapun caranya untuk tampil (show off). Bahkan segenap kebaikan dan moralitas yang kita suguhkan ternyata emi meneguhkan keakuan kita. Kebaktian demi kebaktian yang kita lakukan tidak lain hanyalah upaya memupuk keakuan kita sendiri. Terlebih kini, ketika zaman memanjakan kita dengan segala fasilitasnya. Semua laten dilakukan atas nama keakuan. Maka yang terjadi adalah perayaan keakuan dimana-mana. Ketika festival keakuan dirayakan maka jagat makin bising lantaran dipenuhi oleh keakuan masing-masing. Itulah mengapa kesediaan mengendapkan aku untuk segera dikembalikan kepada Empunya aku menjadi laku tiada henti yang harus terus menerus dilangsungkan. Dan langkah awal sekaligus akhir dari pengembaraan si aku adalah keheningan.
Bagi Hossen Nasr, keheningan dapat berupa keheningan lisan dan keheningan hati. Keheningan lisan adalah tidak berkata apapun kecuali berkata Allah dan Muhammad. Karena hanya kalimat itulah yang Haq, yang lain batal. Bila seorang hening lisannya, meski belum hening hatinya, setidaknya ia akan bicara kebijaksanaan. Sementara Keheningan Hati adalah kesungguhan menahan diri dari semua pikiran yang muncul dalam/tentang jiwa yang berkaitan dengan makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Seorang yang hening lisan, meski belum sampai pada keheningan hati, bebannya telah diringankan. Tapi jika lisan dan hati telah hening, kesadaran dirinya dapat dimanifestasikan dan Tuannya Menunjukkan Diri-Nya kepada hamba. Hadrat Siddiq dalam Kitab Misbah al-Shari’ah kemudian berkata, “Keheningan adalah semboyan para pecinta. Dan di dalam keheningan bersemayam kenikmatan Tuhan. Itulah laku Nabi dan orang orang yang terpilih.” Wallahu a'lam.
Umah Suwung, 9 April 2020
Penulis adalah Pengurus Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) PBNU
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua