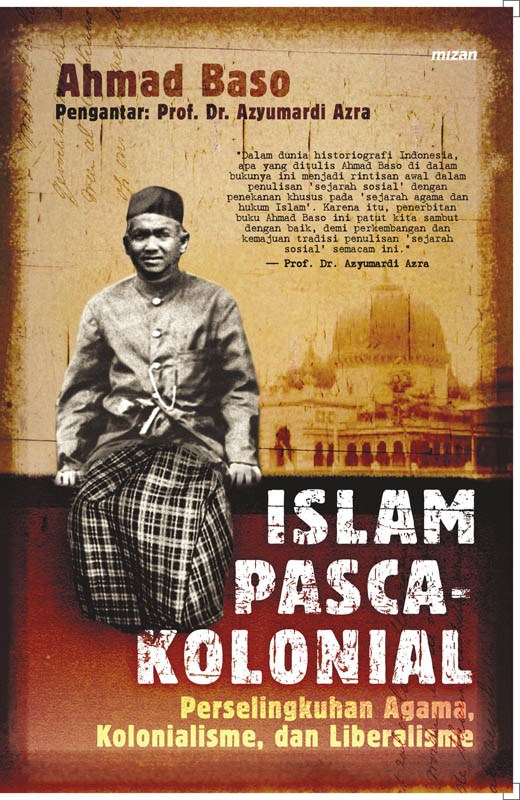Oleh Hasan Basri
Dalam literatur sejarah, ilmu sosial secara umum, disebutkan dengan gamblang bahwa usai Perang Jawa (1825-1830 M) ada suatu upaya intensif pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur Jawa dalam suatu bentuk diskursus yang sepenuhnya rigid. Menurut Peter Carey, pakar perang Jawa itu, berakhirnya Perang Jawa menjadi suatu penanda dari sempurnanya penakalukkan atas Jawa oleh Belanda. Hal senada disepakati oleh hampir seluruh pakar Indonesia, seperti Danis Lombard, dan beberapa spekulator tentang Jawa belakangan seperti Michael Laffan dan seterusnya.
Bakda Perang Jawa ada beberapa hal yang dilakukan dengan intensif oleh pemerintah kolonial Belanda: Mendirikan Kantor Urusan Islam dan Pribumi, Lembaga Kejawaan di Surakarta (1840, lima tahun setelah Perang Jawa), intensifikasi misi Katolik yang sebelumnya dinilai lambat, pembentukan sosial berupa kelas elit Jawa, dan tanam paksa. Semua bentuk imperialisme ini adalah serangkaian yang tidak terpisahkan untuk memastikan rigidnya kontrol atas perlawanan kalangan pesantren. Benarkah demikian?
Di dalam kajian pascakolonial, salah satu hal yang harus dipahami dengan baik adalah hubungan antara sejarah kolonial Barat dengan Islam. Jika ingin mendapatkan pengertian yang lebih terang benderang tentang kolonialisme dan imperialisme adalah dengan melihat garis singgung dan persaingan kaum kolonial dengan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Jadi tidak sekadar memungut pengertian kolonialisme dan imperialisme dari sudut pandang kalangan Marxis, walaupun hal ini adalah suatu yang dengan sendirinya tetap penting.
Jika berkukuh dengan poin persinggungan kolonial Barat sejak abad 16 Masehi di Nusantara, maka akan terlihat serangkaian perlawanan politis (perang fisik) yang nyata dari para penguasa Muslim di seluruh wilayah, tidak saja di Jawa. Seperti respons politik kesultanan Aceh atas kedatangan Portugis, perlawanan Demak di bawah pimpinan Sultan Akbar Kedua, Pati Unus, yang menyerang Malaka, perlawanan Sultan Agung, perlawanan Sultan Hasanuddin, Syaikh Yusuf dan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, perlawanan kolaboratif Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa, dan terakhir adalah perlawanan Pangeran Diponegoro. Tentu saja ada serangkaian perlawanan yang dilakukan oleh para bangsawan Aceh, Batak, Palembang, Sumateran Barat, Makassar, dan Nusa Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara secara umum tidak pernah menerima kenyataan dari ambisi kolonial dan imperial.
Salah satu aspek penting dalam kajian poskolonial menyebutkan, bahwa salah satu jalur penting untuk memahami sejarah negara pascakolonial adalah dengan menyusun kembali sejarah perlawanan yang di belakang hari disusun oleh pihak kolonial sebagai perlawanan sektoral agar para terjajah tidak memiliki ingatan berati mengenai pentingnya perlawanan. Semacam kontrol politik paling canggih agar hubungan yang terjajah sesuai dengan imagi para penjajahnya.
Salah satu bentuk jebakan narasi dekolonisasi modern adalah menghilangkan muatan dari ingatan akan perlawanan yang berkesinambungan tersebut. Di antara metode yang cukup efektif digunakan adalah dengan menulis sejarah nasional dari fase paling akhir dan krusial,yakni akhir abad 19 Masehi dan awal Abad -20. Dikatakan krusial karena fase ini disepakati sebagai fase matang dari imperialisme sehingga sepi dari perlawanan fisik. Sedangkan urusan sejarah sebelum abad-19 diserahkan kepada histriografi kolonial. Kedua, generasi yang tumbuh pada fase ini adalah generasi yang sudah beragam, antara mereka yang mencari persambungan semangat dengan generasi resisten pada masa sebelumnya dan mereka yang sudah mengalami erosi politik karena politik kolonial. Kalau meminjam istilah dari Eqbal Ahmad, intelektual brilian dari Bihar, Pakistan itu, generasi ini pada pertengahan abad 20 Masehi melahirkan bentuk “patologi sosial”, yakni mereka menjadi ujung tombak dari peralihan imperial ke dekolonisasi dengan segala penyakitnya. Salah satu penyakitnya, ketika mereka mencapai kemerdekaan, mereka menghadapi persoalan yang sangat kompleks secara internal. Tidak sedikit dari para penggagas negeri merdeka kemudian menjadi elite yang memiliki prilaku sama dengan para penjajah yang sebelumnya mereka lawan.
Lantas apa kaitan narasi ini dengan berdirinya organisasi seperti Nahdlatul Ulama? Jika di banyak negara jajahan, kaum pergerakan nasional rata-rata berubah menjadi partai politik dalam konteks politik negara baru merdeka, maka di Indonesia ada suatu fase krusial yang sangat kompleks dihadapi umat Islam dalam menyusun ulang nalar dan praktik politik mereka yang sesuai dengan kebutuhan dari trayek dekolonisasi. Persoalan sudah banyak dibahas oleh para pakar dengan segala muatan fabrikasinya.
Di sini hanya akan disinggung betapa pentingnya umat Islam, terutama kalangan pesantren, untuk menyusun ulang narasi perlawanan mereka, mengumpulkan serpihan dari ingatan perlawanan mereka sebagai salah satu modal untuk melihat postur kejamaahan mereka yang saat ini semakin kehilangan tali perekat kolektif karena dinamika internal dan eksternal yang mereka hadapi.
Ini salah satu contoh, agar tulisan mudah dipahami, ketika para orientalis dan Indonesianis menulis sejarah perjalanan haji pada akhir abad-19 dan awal abad 20 Masehi, mereka menggambarkan bahwa para haji dai Jawah (Nusantara) itu sedang menimba pengetahuan tentang agama mereka dari sumbernya, dari Arab sebagai muasal agama Islam guna memurnikan doktrin agama mereka. Keberadaan mereka di Makkah digambarkan sebagai awal dari tumbuhnya suatu entitas ilmiah yang nantinya membentuk jejaring ilmiah atau keulamaan di Nusantara. Hal ini ada benarnya, tapi tidak seluruhnya. Padahal tidak sedikit dari para ulama Jawa meninggalkan tanah air ke Haramain karena alasan-alasan politik, seperti direkam sendiri oleh Snouck Hurgronje dalam etnografinya yang terkenal, Ulama Jawa yang Ada di Mekkah pada Akhir Abad ke-19, terutama penggalan yang menyorot personal Syaikh Nawawi al-Bantani:
“...Orang Arab yang tidak mengenalnya mungkin mengabaikannya begitu saja, tanpa menyadari bahwa ia itu telah mengarang sekitar 20 karya ilmiah. Pengaruh moralnya sangat penting dan berjangkauan jauh, tetapi kepribadiannya sangat bersahaja. Berkat kemampuannya, semakin banyak orang Sunda, Jawa, dan Melayu yang mulai mengkaji Islam secara seksama, dan cita-cita politik-keagamaan Islam---dalam bentuknya yang paling maju—paling menyebar. Tetapi Nawawi bukanlah seorang bapak yang menerima pangakuan dosa. Wajarlah kalau orang ini bergembira melihat kesulitan Pemerintah (Hindia Belanda) yang ditimbulkan oleh orang Aceh, dan, dalam percakapan, ia tidak menyetujui para pejabat pensiunan yang berpendapat bahwa negeri Jawa harus diperintah oleh orang-orang Eropa. Pemberontakan Kesultanan Banten, atau pemberontakan dari sebuah negeri muslim yang independen, dalam bentuk apapun, akan disambutnya dengan gembira...”
Dari gambaran Hurgronje tersebut sangat terang benderang bahwa para ulama Jawah (Nusantara) di Mekkah adalah para eksil yang masih memendam semangat perlawanan terhadap kolonial. Ijtihad merawat harga diri dengan memendam bara perlawanan harus menjadi teladan generasi pelanjutnya agar tidak mudah lapuh oleh pranata laten penaklukkan hari ini dalam bentuk bentuknya yang lebih halus. Wal-Allahu yaqulul-haqqa wahywa yahdiis sabiil.
Penulis adalah Lurah Pesantren Kaliopak, Yogyakarta.
--------------
Artikel ini diterbitkan kerja sama antara NU Online dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI