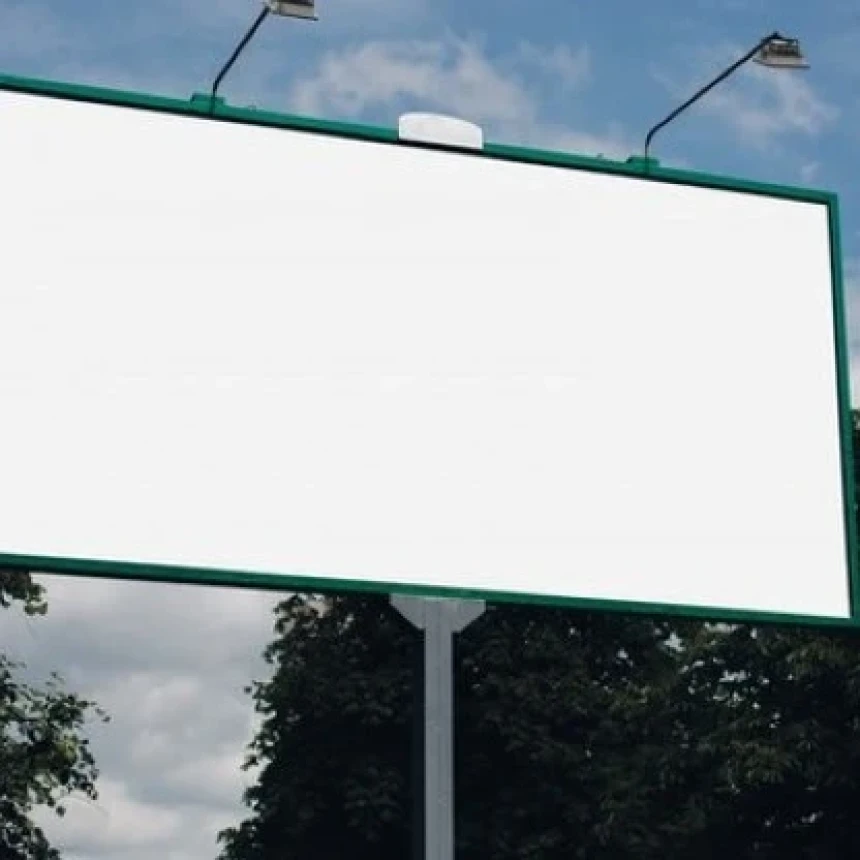Subhan tidak pernah pandai matematika. Setiap kali guru berdiri di depan papan tulis dan menulis angka-angka yang saling berkejaran seperti semut mabuk, kepala Subhan serasa dipenuhi suara lebah. Ia hanya mengangguk-angguk, mencatat, lalu menyerah. Bagi Subhan, angka hanyalah makhluk aneh yang suka menuntut hasil tapi tak pernah mau berbagi arti.
Namun, hidup tidak bisa dihindari hanya karena kita tak pandai menghitung. Maka Subhan tumbuh besar bersama kekeliruannya. Ia jadi orang yang selalu ingin mengerti dunia, tapi dunia selalu mengajaknya bermain teka-teki. Ia pernah jatuh cinta, dan mengira cinta punya rumus pasti: berbuat baik dikali setia sama dengan bahagia. Tapi nyatanya, hasilnya sering negatif. Ia juga pernah bekerja, mengira kerja keras ditambah kejujuran akan menghasilkan kesuksesan. Lagi-lagi, yang muncul di ujung tanda sama dengan hanyalah kelelahan.
Suatu hari, setelah bertahun-tahun gagal menjumlahkan kebahagiaan, Subhan berhenti.
Ia duduk di pinggir sungai yang airnya keruh oleh hujan semalam, lalu bergumam pelan: “Apakah Tuhan juga menghitung seperti manusia?”
Angin sore menjawab dengan menggigilkan daun-daun bambu.
*
Subhan membuka warung kecil di dekat pesantren tua. Warung itu menjual teh hangat, gorengan, dan kadang nasib baik bagi para santri yang kehabisan uang. Di dinding warungnya, tergantung jam tua yang jarumnya sering terlambat, dan papan tulis kecil bertuliskan harga yang selalu bisa ditawar. Ia tidak kaya, tapi hidupnya tenang seperti rumput yang tak iri pada bunga.
Suatu sore, datanglah seorang anak kecil membeli teh. Wajahnya kotor, bajunya robek, tapi matanya bening sekali—seperti belum pernah disentuh kesedihan. Setelah minum teh, anak itu berkata, “Pak, Bapak tahu matematika Tuhan?”
Subhan menatap anak itu lama. “Tidak. Tapi aku mau belajar.”
Anak itu tersenyum, seperti sudah menduga jawabannya. “Kalau manusia menghitung dengan tambah-kurang, Tuhan menghitung dengan niat. Kadang yang kelihatan rugi, di sisi Tuhan untung besar.”
Subhan diam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti batu kecil yang dilempar ke danau hatinya—menimbulkan riak panjang.
*
Malamnya, Subhan tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata anak kecil itu. Ia teringat bagaimana dulu ia pernah memberi makan pengemis di pasar, lalu uangnya hilang. Ia marah waktu itu, merasa dirugikan dua kali: kehilangan uang dan kehilangan kesabaran. Tapi jika matematika Tuhan memang dihitung dengan niat, mungkin saat itu ia sebenarnya sedang untung besar, hanya saja tak dicatat di buku bumi.
Keesokan harinya, anak kecil itu datang lagi. Membeli gorengan, duduk di pojok, lalu bertanya, “Pak, kenapa Bapak jual murah sekali? Santri-santri bilang, Bapak bisa saja naikkan harga.”
Subhan menjawab pelan, “Kalau aku naikkan harga, mereka tak bisa beli. Kalau mereka tak bisa beli, aku kehilangan pembeli dan kehilangan senyum mereka. Kalau keduanya hilang, apa yang tersisa?”
Anak itu tersenyum lagi. “Berarti Bapak sudah pandai matematika Tuhan.”
Subhan tertawa kecil. “Mungkin baru belajar menghitungnya.”
*
Hari-hari berlalu, dan Subhan mulai melihat kehidupan dengan rumus baru. Ketika seseorang mengambil hutang lalu lupa membayar, ia tidak langsung marah. Ia tulis di catatan kecil: semoga dilunasi Tuhan dalam bentuk lain. Ketika hujan membuat dagangannya sepi, ia menatap langit sambil berkata: Tuhan sedang mencuci udara agar besok lebih segar. Ia merasa ringan, seperti angka nol yang tidak punya beban tapi tetap penting di setiap hitungan.
Namun suatu malam, seseorang datang mencuri uang dari laci warungnya. Hasil penjualan seminggu lenyap begitu saja. Subhan duduk di kursi bambu, termenung. Untuk pertama kali sejak lama, ia ingin marah. Tapi entah mengapa, di sudut pikirannya muncul suara anak kecil itu:
“Kalau rugi di dunia, mungkin sedang ditambah di sisi Tuhan.”
Subhan tersenyum pahit. Ia tahu, belajar matematika Tuhan memang sulit—karena sering kali hasilnya tak terlihat.
*
Beberapa minggu kemudian, anak kecil itu tidak muncul lagi. Subhan mencarinya di sekitar pesantren, di jalan-jalan kampung, bahkan bertanya pada santri yang sering datang. Tak ada yang mengenal anak itu. Seolah ia hanya mampir seperti kabar langit yang lupa menutup pintu.
Malam itu, Subhan duduk sendiri di depan warung. Ia menatap bintang dan berbicara lirih, “Tuhan, mungkin Engkau mengirim anak itu untuk mengajariku berhitung. Tapi aku masih bodoh, masih suka menagih hasil, masih suka menghitung kebaikan.”
Angin malam menjawab dengan dingin yang lembut.
*
Beberapa bulan setelah kejadian itu, warung Subhan makin ramai. Santri-santri datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk mendengar obrolannya. Kadang mereka duduk berjam-jam mendengarkan Subhan berbicara hal-hal aneh tapi menenangkan.
“Kalau kamu ingin tahu hasil dari sabar,” katanya suatu hari, “tunggu saja. Tapi kalau kamu ingin hasilnya cepat, jangan sebut itu sabar.”
Atau, “Sedekah itu bukan soal uang keluar, tapi soal hati yang tak lagi takut kehilangan.”
Para santri menyebutnya Kiai Gorengan. Julukan itu membuat Subhan tertawa setiap kali mendengarnya. Ia tak pernah menganggap dirinya guru, apalagi kiai. Ia hanya seseorang yang sedang belajar berhitung dengan rumus yang tak pernah diajarkan sekolah.
*
Suatu sore, datanglah seorang santri membawa kabar, “Pak, anak yatim di ujung kampung itu sakit. Tak ada yang bawa ke klinik.”
Subhan menutup warung tanpa berpikir. Ia naik sepeda, menembus gerimis, membawa anak itu ke klinik. Setelah berjam-jam menunggu, dokter berkata, “Kalau terlambat sedikit, anak ini bisa tidak tertolong.”
Malamnya, Subhan duduk di luar klinik, menatap lampu jalan yang bergetar karena hujan. Dalam hati ia berkata, Mungkin beginilah Tuhan menambah, ketika kita mengira sudah habis.
Ia pulang dengan baju basah, tapi dadanya hangat.
*
Beberapa tahun berlalu. Warung Subhan tetap sederhana, tapi selalu penuh cerita. Orang-orang bilang, Subhan orang baik. Tapi Subhan selalu menjawab, “Aku hanya sedang menghitung ulang salahku.”
Suatu malam, seorang mahasiswa datang menemuinya. Katanya, sedang menulis skripsi tentang “Etika dan Kebahagiaan dalam Pandangan Masyarakat Pinggiran.” Ia mendengar banyak kisah tentang Subhan.
Mahasiswa itu bertanya, “Apa rumus kebahagiaan menurut Bapak?”
Subhan tertawa kecil. “Rumusnya berubah-ubah. Tapi sekarang aku rasa begini: kebahagiaan itu hasil dari pengurangan ego, penjumlahan sabar, dan pembagian kasih. Kalau masih ada sisa amarah, itulah tugas revisinya.”
Mahasiswa itu tersenyum dan menulis cepat di bukunya.
Lalu ia bertanya lagi, “Pak, kalau begitu apa rumus dosa?”
Subhan menatap jauh ke arah sungai, tempat dulu ia pernah merenung bertahun lalu.
“Dosa itu mungkin ketika kita merasa bisa menghitung lebih baik dari Tuhan.”
*
Suatu pagi, Subhan tak membuka warung.
Para santri menunggu, mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Mereka mendobrak masuk, dan mendapati Subhan tertidur di kursi bambu, dengan senyum tipis di bibirnya. Di meja, ada secangkir teh setengah habis, dan selembar kertas berisi tulisan tangan goyah:
"Segala sesuatu sudah genap di dalam perhitungan Tuhan. Aku cuma angka kecil yang sempat ikut menulis hasil.”
Di bawahnya, ada tanda tangan sederhana: Subhan.
*
Hari itu pesantren menjadi sunyi. Para santri saling diam, hanya memandang langit. Salah satu dari mereka berkata pelan, “Berarti rumus terakhir beliau sudah selesai.”
Tak lama setelah itu, seseorang menemukan catatan tua di laci warung. Isinya hanya daftar nama dan angka, tapi angka-angka itu tak berurutan, seperti kode rahasia. Setelah diteliti, ternyata setiap angka adalah jumlah gorengan yang Subhan pernah berikan gratis kepada orang yang lapar.
Tak ada tanda tangan. Tak ada catatan hutang.
Hanya satu kalimat di bawahnya: "Ini bukan sedekah. Ini latihan menghitung dengan hati.”
*
Bertahun-tahun kemudian, nama Subhan masih disebut di kampung itu. Anak-anak sering bermain di depan bekas warungnya sambil bercanda, “Kalau mau lulus ujian, hafalkan matematika Tuhan!”
Dan setiap kali hujan turun, orang-orang di kampung suka berkata, “Itu Tuhan sedang menambahkan air untuk menghitung keberkahan.”
Tak ada yang tahu ke mana anak kecil misterius itu pergi, atau siapa dia sebenarnya. Tapi bagi banyak orang, ia seperti bilangan tak diketahui dalam rumus besar kehidupan—tanpa dia, soal ini tak pernah lengkap.
Dan mungkin, kalau Tuhan benar-benar punya papan tulis, di sana tertulis nama Subhan kecil di pojok kanan bawah, di samping catatan kecil: "Lulus dengan nilai cukup.”
Namun entah kenapa, di bawah tulisan itu, Tuhan menambahkan satu tanda senyum kecil.
Sayyid Muhamad Abdulloh Almustofa, lahir di Banyumas, Jawa Tengah. Dewan Pengajar di Pondok Pesantren Al-Waasi' Purwokerto Wetan. Telah menulis beberapa kitab: Kun Waasi'an (2024), Sirajul Afham (2024), Suyukhi (2025)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua