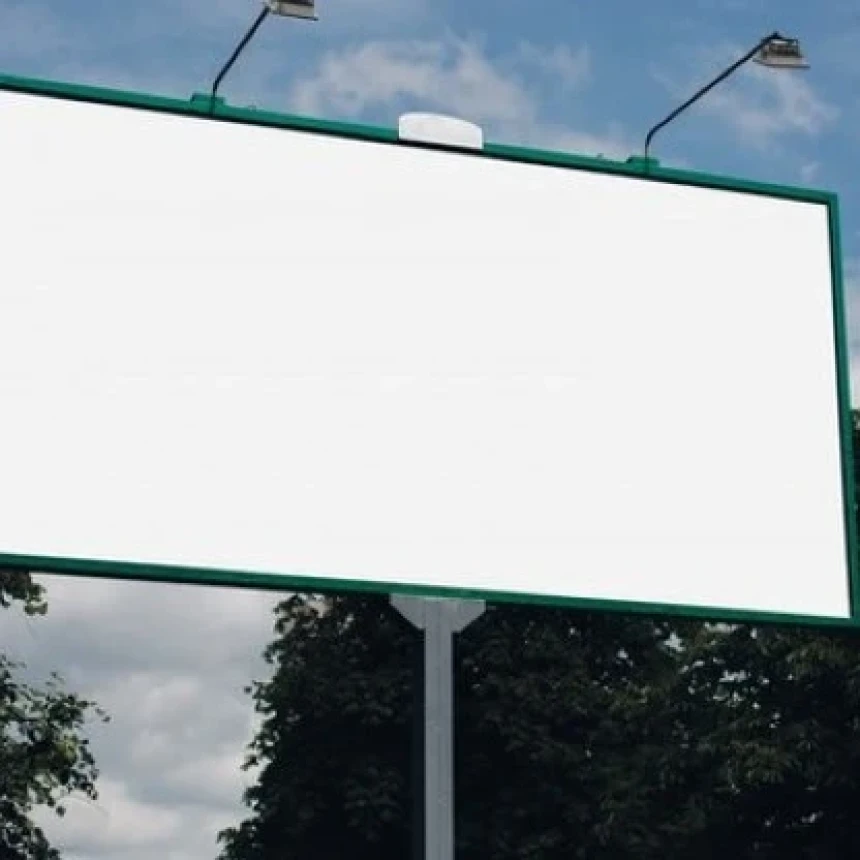Malik Ibnu Zaman
Kontributor
Sebagai orang yang tinggal di tanah orang, hal yang paling aku takutkan adalah dering panggilan WhatsApp dari kampung halaman. Keluargaku bukanlah tipe orang yang suka teleponan. Jadi ketika ada panggilan WhatsApp dari kampung, sudah barang tentu ada hal penting.
Hari itu karena saking capeknya lembur mengedit naskah, aku dibangunkan oleh cahaya matahari yang menembus jendela kosanku. Seketika itu juga yang aku raih pertama kali adalah gadget di samping kasur lantai. Tampak dalam layar terpampang jelas waktu menunjukkan tepat sebelas siang. Lalu ada notifikasi puluhan panggilan tak terjawab dari bibiku. Ia juga mengirimkan pesan, mengabarkan bahwa ibuku sakit terbaring di kasur.
"Tetapi anehnya setelah diperiksakan di rumah sakit, dokter mengatakan semuanya normal," lanjutnya. Aku hanya membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa aku akan pulang nanti sore dari Jakarta naik bus antarprovinsi.
Baca Juga
Loreng, Bintang, dan Merah
Terakhir kali ibu mengalami sakit demikian ialah 8 tahun lalu. Saat itu aku belum merantau. Jadi aku yang merawat dan menjaganya. Saat itu, sakit ibu juga sama anehnya. Setelah diperiksakan ke dokter, bahkan sampai cek darah, semuanya normal. Kemudian ibu dibawa ke tetua kampung yang dikenal memiliki ilmu suwuk, pengobatan dengan doa-doa, bernama Mbah Wahad. Ibu pun kembali sehat seperti sedia kala.
"Namanya manusia pasti ada sifat iri. Ya, namanya tangga itu tinggi,” itulah yang Mbah Wahad katakan kepadaku. Aku pun mengatakan bahwa apa yang diirikan dari keluarga kami, bisa dikatakan bahwa kami hidup pas-pasan. Ibu harus bekerja mati-matian dengan berdagang di pasar demi memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya dan tiga adik yang menjadi tanggungannya. Mbah Wahad hanya tersenyum, lalu mengatakan, "Kebanyakan orang ketika melihat orang lain, wah mereka enak ya hidupnya. Padahal mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mbah Wahad sendiri sudah meninggal lima tahun yang lalu.
Aku turun di pertigaan jalan lintas kecamatan jam tiga dini hari. Dari situ aku harus naik angkot untuk bisa sampai ke rumah. Berhubung sudah malam, satu-satunya mode transportasi yang ada adalah ojek. Setelah nego cukup alot perihal ongkos, akhirnya ia mau mengantarkanku dengan biaya 30 ribu.
“Sebenarnya saya takut kalau mengantarkan penumpang ke kampung, Mas. Jalanan sepi, kanan kiri sawah, kebun, sungai. Jalan minim lampu penerangan juga," ucap tukang ojek yang memperkenalkan diri bernama Ucup. “Agak aneh tahu kampung Mas dari dulu saya kecil, kalau siang hari itu ramai, kalau malam sepinya minta ampun,” imbuhnya. "Namanya juga daerah gunung, Mas," ucapku. Sepanjang perjalanan Ucup mengoceh, menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya.
Baca Juga
Tahun Wawu
Aku pun meminta turun di depan ruko Fahd. Dari situ aku harus berjalan kaki lagi sejauh 50 meter masuk ke jalan kecil yang ujungnya adalah buntu, sebab sawah. Di situlah rumahku berada. Sepeninggal Ucup, aku memilih untuk duduk di emperan toko. Melepas rasa pegal pada kaki akibat naik motor melewati jalanan yang rusak.
Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menepuk bahuku. Aku tersentak kaget bukan main. Ternyata nenek tua dengan mengenakan mukenah jadul. Warna putihnya sudah mulai pudar, berganti dengan warna coklat. Wajahnya terasa asing, aku tak pernah melihat sebelumnya. Sialan, aku pun jadi teringat akan cerita Ucup yang membonceng kuntilanak. Tetapi aku berusaha untuk menghilangkan perasaan takut itu dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa manusia derajatnya lebih tinggi dari hantu.
Aku pun berdiri, lalu saling berhadap-hadapan. Selanjutnya aku pun bertanya, "Mau ke mana, Mbah?” Ia pun menjawab, "Mau ke rumah cucuku. Sudah beberapa hari ini dia sakit. Setiap malam selalu menangis, merintih kesakitan. Kasihan dia.” Hanya itu yang ia katakan. Ia pun lalu berlalu meninggalkan aku seorang diri di emper toko. Dia berjalan ke jalan kecil yang menuju rumahku. Aku perhatikan kakinya menapak di tanah.
Baca Juga
Cerpen: Wong Nyupang
Sesampainya di rumah, aku disambut pamanku. Sementara ibu masih terbaring lemah di kasur. Aku pun menceritakan apa yang barusan aku alami. Paman hanya mengatakan, "Kamu hanya kelelahan, habis perjalanan jauh." Sementara itu ibu dari kamar mengatakan bahwa itu Mbah Samah. Paman pun menggelengkan kepala keheranan. Seketika ketakutan menghantui diriku. Aku masih ingat betul sebelum kakek pergi ia juga sering mengigau. Kalau kata orang-orang halusinasi.
Sudah seminggu aku di kampung. Dan hari berjalan seperti biasanya. Belum ada tanda-tanda ibu membaik. Malam itu selepas Maghrib aku diminta oleh ibu untuk mengantarkan kiriman uang ke adik bungsuku di pondok pesantren yang terletak di kecamatan sebelah.
Pada tanjakan ujung kampung di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Lingga, aku bertemu kembali dengan sosok nenek yang aku temui keluar dari pintu masuk makam. Aku pun menghentikan motorku. Lalu aku menanyakan. "Mbah habis dari mana?" “Habis mengunjungi kakakku. Ini saya mau mengunjungi cucuku. Tadi dia meminta agar cucuku dibawa ke cucunya." Ia pun pamit sebab cucunya sudah menunggu dan aku pun melanjutkan perjalanan.
Baca Juga
Kutukan Sunan Amangkurat
Sepulang dari mengunjungi adik bungsuku. Ibu meminta agar besok, habis Isya aku pergi ke rumah Kang Halim untuk menjemput obat. Ibu mengatakan rumahnya di samping kanan TPU Lingga. Katanya juga ia masih kerabat jauh ibu.
Ternyata ia sudah menunggu di teras dan ia mengajakku ke ruang tamu. Belum sempat aku mengungkapkan maksud dan tujuan, Kang Halim mengatakan bahwa Mbah Lingga sudah menceritakan semuanya bahwa cucu dari Mbah Samah yang merupakan adiknya akan datang ke sini. Aku pun heran tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Kang Halim. Lalu ia pun masuk ke ruang tengah sebentar dan kembali membawa satu botol air dalam kemasan. Kang Halim pun duduk kembali.
"Pasti kamu bertanya-tanya kan. Siapa itu Mbah Lingga, siapa itu Mbah Samah. Jadi begini mereka adalah penyebar agama Islam di daerah sini. Selain mereka ada yang namanya Mbah Bendera. Ketiganya kakak beradik,” ucapnya.
Baca Juga
Jejak Perjuangan Seorang Pemberontak
Aku hanya mengangguk-angguk. Ya, memang ibu pernah menceritakan bahwa leluhurnya bernama Mbah Bendera.
"Aku itu masih keturunan Mbah Lingga. Kalau ibumu itu keturunan Mbah Bendera. Sementara Mbah Samah tidak menikah,” imbuhnya. “Cucunya Mbah Bendera dan cucunya Mbah Lingga bisa dikategorikan sebagai cucunya Mbah Samah."
"Bagi kamu yang lama hidup di kota, tentu agak aneh. Aku tidak memintamu untuk percaya. Tetapi perlu kamu ingat penting bagi kita untuk terus mengingat leluhur. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang Jawa akan kehilangan keberuntungannya, manakala melupakan leluhur."
Baca Juga
Dul Abdal dan Dul Abdil
Aku pun bertanya ke Kang Halim di mana makam Mbah Samah. Ia pun menjawab “Kamu pasti paham kalau Islam diajarkan melalui berbagai media, ada yang melalui pengobatan, kanuragan. Itulah yang dilakukan oleh Mbah Bendera, Mbah Lingga Jaya dan Mbah Samah. Untuk makamnya sendiri Mbah Bendera berada di Taman Pemakaman Umum Kebon. Lalu Mbah Lingga Jaya berada di Taman Pemakaman Umum Lingga. Sementara Mbah Samah sudah tidak ada jejak makamnya, beralih menjadi ruko Fahd sekarang.”
Seketika ingatanku melayang ke kejadian seminggu yang lalu di toko Fahd dan kemarin di depan TPU. Dan aku jadi teringat ucapan dari kawan mainku dulu Imsal, "Kata almarhum nenekku, di ruko Fahd dulunya ada satu makam, nisannya hanya dari batu. Tetapi aku lupa siapa namanya, tetapi yang jelas makam tersebut adalah makam tokoh yang menyebarkan agama Islam di desa ini.
Kang Halim pun menceritakan bahwa ibuku mendapatkan kiriman santet dari tetangga. “Bukan sekali saja kan ibumu sakit seperti ini,” ujarnya. Aku pun mengangguk. "Kamu mau tahu nama jin yang ditugaskan untuk mengirimkan santet itu?" tanyanya. Ya, aku pun mengangguk. Bagaimanapun aku penasaran juga. “Namanya Ridah. Dia Jin Qorin. Jadi sandal ibumu ditaruh di makam orang yang bernama Ridah,” ucapnya.
Baca Juga
Kosongnya Langgar
Tentu saja aku terkejut aku mendengar penjelasan itu dari Kang Halim. Sebab, 8 tahun lalu sebelum ibu sakit, sandalnya hilang. Ridah sendiri adalah salah satu warga kampungku yang meninggal sudah lama. Ia terkena kanker, katanya organ dalamnya sampai rusak. "Apa orang yang mengirimkan santet itu berharap agar ibu bernasib sama seperti ridah?” tanyaku. Kang Halim pun menjawab "Iya."
Setelah itu aku pamit undur diri. Dalam hati jujur saja aku masih bertanya-tanya. Sesampainya di rumah aku serahkan botol minuman itu. Seketika wajah ibu yang lesu, pucat basi kembali segar bugar. Dua jam kemudian terdengar pengumuman di masjid bahwa Titah tetanggaku meninggal dunia.
Malik Ibnu Zaman lahir di Tegal Jawa Tengah. Menulis cerpen, puisi, esai, dan resensi yang tersebar di beberapa media online. Dapat ditemui di Instagram @malik_ibnu_zaman. Buku pertamanya sebuah kumpulan cerpen berjudul Pengemis yang Kelima (2024).
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua