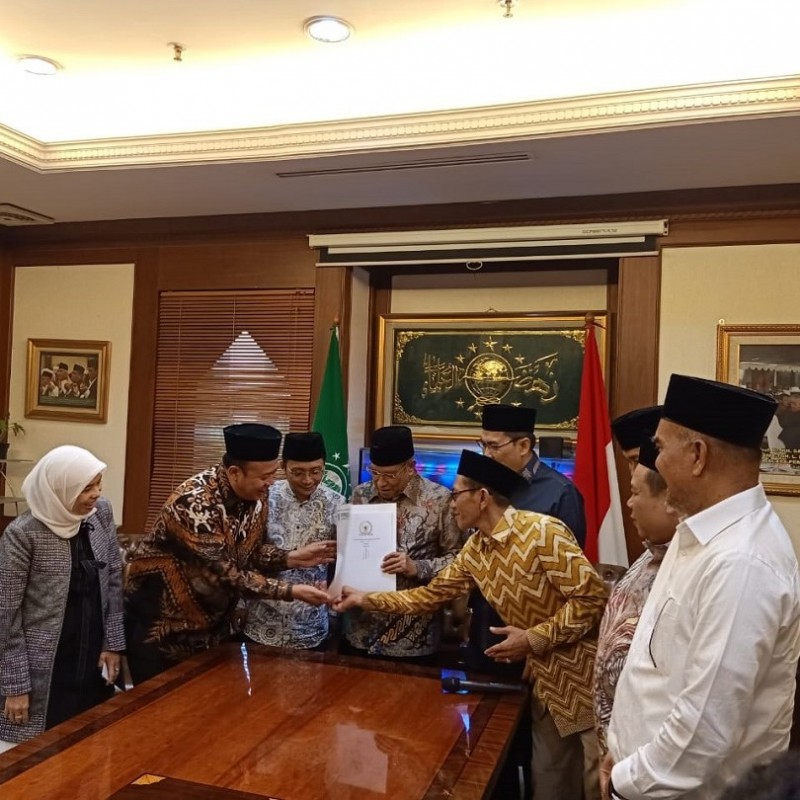Oleh A. Khoirul Anam
Undang-undang Pesantren yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 24 September 2019 lalu, bisa menjadi kado terindah dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun ini. Kita layak menyampaikan apresiasi kepada partai politik, Kementerian Agama, organisasi pesantren, para kiai-nyai dan santri-aktivis yang setia mengawal perjalanan RUU Pesantren. Berbeda dengan RUU KPK, RUU PKS, dan RKUHP, pembahasan RUU Pesantren memang tidak terlalu menyita perhatian publik. Namun tidak penting apakah viral atau tidak, faktanya RUU Pesantren ini telah disahkan. Ada yang menarik bagi saya sebagai pengkaji legislasi hukum Islam di Indonesia, beberapa RUU yang ditujukan khusus untuk umat Islam seperti terkait haji, zakat, wakaf dan halal serta RUU pesantren ini lebih mudah diketok dari pada RUU yang ditujukan untuk semua warga negara, tapi ini perbincangan lain.
Point paling penting dari Undang-undang Pesantren adalah rekognisi atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal maupun nonformal. Pesantren yang formal dalam UU ini terdiri dari pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma’had ali. Sementara jalur pendidikan nonformal berupa pengajian kitab kuning dengan beberapa metode pembelajarannya yang khas. Baik formal maupun nonformal, semua lulusan pesantren “diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja.”
Sebagaimana produk legislasi lain yang telah disahkan, UU Pesantren menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) bagi pihak-pihak terkait, bukan saja bagi pemerintah tetapi juga bagi pengelola pesantren sendiri. Saya mencatat ada sembilan (9) PR terkait pengesahan UU Pesantren. Angka 9 ini tentu bukan harga mati, tapi kalau kita menyusun PR sampai 212 tentu capek bukan?
Pertama, soal pendanaan pesantren. Beberapa pengasuh pesantren terkesan agak tersinggung ketika membahas soal dana pendidikan dari pemerintah untuk pesantren; seakan-akan urusan pesantren dengan pemerintah hanya soal bantuan dana, padahal pesantren sudah terbiasa mandiri soal pendanaan. Perlu ditegaskan bahwa kita sedang membahas mengenai regulasi dan penganggaran. Bahwa telah ditetapkan 20 persen APBN untuk pendidikan nasional yang tahun ini akan dinaikkan hingga menjadi Rp 487,9 triliun. Akan sangat tidak adil jika anggaran sebesar itu tidak bisa diserap oleh pesantren. Bahwa pihak pesantren kemudian menolak dana dari pemerintah karena sudah terbiasa mandiri, itu urusan lain.
Skema pendanaan dalam UU Pesantren ini hanya dibebankan kepada Kementerian Agama. Jelas bahwa “menteri” yang dimaksud dalam UU Pesantren adalah Menteri Agama. Pembahasan RUU ini juga “mengunci” di Komisi VIII DPR RI sehingga tidak bisa menjangkau dana pendidikan di luar mitra komisi VIII (komisi andalan lulusan sekolah tinggi Islam). Padahal Kementerian Agama hanya mengelola sekitar Rp 51,9 triliun dana pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia yang berada di bawah naungannya, itu pun sebagian sudah terserap dalam belanja rutin. Hampir Rp 400 triliun dana pendidikan ditransfer ke daerah. Nah dana ini dikelola oleh dinas pendidikan daerah, dan tidak bisa diperuntukkan pesantren. Dinas pendidikan daerah merupakan kepanjangan dari Kemendikbud yang secara nasional sudah mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 36 triliun. Silakan ditotal sendiri.
UU Pesantren memang tidak mengusik alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN. Namun pada pasal 48, ada peluang sumber pendanaan yang perlu dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelengaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu pasal (3) menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Kedua, masih terkait pendanaan pesantren, namun lebih spesifik soal Dana Abadi Pesantren (pasal 49) yang akan diambilkan dari dana abadi pendidikan. Jumlah dana ini akan mencapai Rp 56 triliun. Sejauh mana dana ini bisa diserap oleh pesantren, sangat tergantung dari Peraturan Presiden yang akan diterbitkan sebagai konsekwensi dari pengesahan RUU Pesantren (pasal 49 ayat 2). Peraturan Presiden yang akan terbit ini perlu dikawal.
Sekali lagi ini bukan soal ketergantungan pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Pesantren memang terbiasa mandiri. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan (tashorruful imam alar ra’iyyah manutun bil maslahah), pemerintah harus adil kepada semua lapisan masyarakat.
Ketiga, Undang-Undang Pesantren menitahkan kepada menteri agama untuk menerbitkan beberapa peraturan. Saya menghitung sedikitnya ada tujuh peraturan menteri agama yang harus segera diterbitkan: Peraturan menteri agama tentang pendirian pesantren (Pasal 6), tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren (pasal 24), tentang majelis masyayikh (pasal 28) dan tentunya tentang dewan masyaryikh, tentang penjaminan mutu pesantren (pasal 30), tentang kurikulum pendidikan umum di pesantren muadalah (pasal 18), tentang sistem informasi pesantren (pasal 47), serta tentang pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 34 dan 35). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan bunyi draft peraturannya harus tersosialisasikan kepada para santri dan masyarakat pesantren.
Keempat, terkait pengakuan negara terhadap lulusan pesantren. Dari sisi negara, pengakuan ini merupakan sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan pesantren secara apa adanya ke dalam pendidikan nasional, jauh lebih fair dibanding UU Sisdiknas 2003. Namun dari sisi pesantren, pengakuan negara bahwa pesantren sah sebagai lembaga pendidikan nasional sama dengan institusi pendidikan yang lain, ini sekaligus merupakan tantangan bagi pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam menciptakan generasi yang unggul. Ini tentu tidak melulu terkait dengan standar akademik dan kurikulum tertentu yang bisa kita diperdebatkan, namun terkait dengan kecakapan hidup yang perlu dimiliki oleh generasi bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain. Kalau soal pendidikan karakter, pesantren tidak perlu diragukan lagi.
Kelima, terkait kekhasan pesantren. Ketentuan mengenai masyayih di tingkat nasional (saya membayangkan ini seperti para komisioner) dan dewan masyayih di tingkat pesantren tidak perlu berorientasi menyeragamkan pesantren. Kekhasan pesantren ini berkaitan dengan kultur masyarakat di mana pesantren itu didirikan dan spesialisasi bidang kajian keilmuan pesantren. Kekhasan ini juga bisa berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pesantren, baik finansial maupun ketersediaan SDM. Jika negara tidak bisa memberikan timbal balik berupa afirmasi yang memadai kepada pesantren, maka semangat yang perlu ditekankan dari aturan turunan UU Pesantren ini adalah rekognisi atau pengakuan dan penghargaan terhadap pesantren di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan tugas negara yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan malah mengatur pesantren harus ini dan itu.
Keenam, fungsi dakwah pesantren. Selain memegang fungsi pendidikan, UU ini menyebutkan bahwa pesantren memegang fungsi dakwah atau penyebarluasan ajaran agama Islam. Pasal dan ayat dalam ketentuan ini sebenarnya bukan merupakan aturan, namun merupakan penegasan mengenai model dakwah yang selama ini dijalankan pesantren: Pesantren adalah pusat dakwah Islam yang moderat (tawassuth), menghargai tradisi masyarakat dan menggelorakan semangat cinta tanah air Indonesia.
Dari sisi pemerintah, pasal-pasal tentang dakwah pesantren ini sebenarnya mengandung pesan bahwa para pendakwah adalah orang-orang dengan standar keilmuan agama tertentu, dalam konteks ini telah menempuh jenjang pendidikan tertentu di pesantren. Wujudnya bisa dalam bentuk sertifikasi pendakwah. Dakwah, terutama berkaitan dengan isu-isu khusus yang berkembang di masyarakat, harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni secara keilmuan, tidak boleh asa hapal satu dua ayat. Sebaliknya, dari sisi pesantren, pasal dakwah pesantren ini mengingatkan kaum santri untuk lebih inovatif dalam berdakwah, sehingga pesan-pesan moderasi beragama sampai kepada masyarakat “zaman now”, generasi milenial juga.
ketujuh, terkait fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Selain fungsi pendidikan dan dakwah, UU Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren atau para pengasuhnya adalah sekaligus tokoh dan penggerak masyarakat, agen perubahan dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah, apalagi sekarang pemeintah mempunyai anggaran besar dalam bentuk dana desa.
Kedelapan, terkait pasal-pasal yang mengkritik pesantren. Apa ada? Ada. Ini terkait dengan pasal-pasal mengenai daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan kritik lain untuk pesantren. Beberapa pesantren mempunyai jumlah santri ribuan atau puluhan ribu melebihi kapasitas yang wajar. Saat nyantri di satu pesantren besar di Jatim selama beberapa tahun, saya hampir tidak pernah tidur di kamar, karena memang kamar hanya berukuran 3x3 meter yang berisi 39 kotak lemari santri. Ini tentu berpengaruh terhadap kenyamanan belajar, kebersihan, kesehatan dan juga keamanan pesantren. Dalam hal ini kritik sepenuhnya tidak bisa diarahkan ke pesantren, karena sebagian orang membawa anaknya ke pesantren tertentu dilandasi spirit keberkahan, bukan alasan lain. Soal ini kita diskusikan lain kali.
Kesembilan, otonomi pesantren bukan berarti pesantren harus menyendiri alias soliter. Pesantren tidak boleh tertutup dan harus bisa diakses oleh masyarakat. Masjid atau musholla pesantren adalah sekaligus tempat beribadah bagi masyarakat sekitar pesantren. Ini juga sekaligus antisipasi, jangan sampai ada agenda-agenda terselubung yang membahayakan negara oleh kelompok masyarakat tertentu di balik camp-camp khusus yang ikut-ikutan diberi nama pesantren.
A. Khoirul Anam
Redaktur NU Online, Dosen Unusia Jakarta
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua