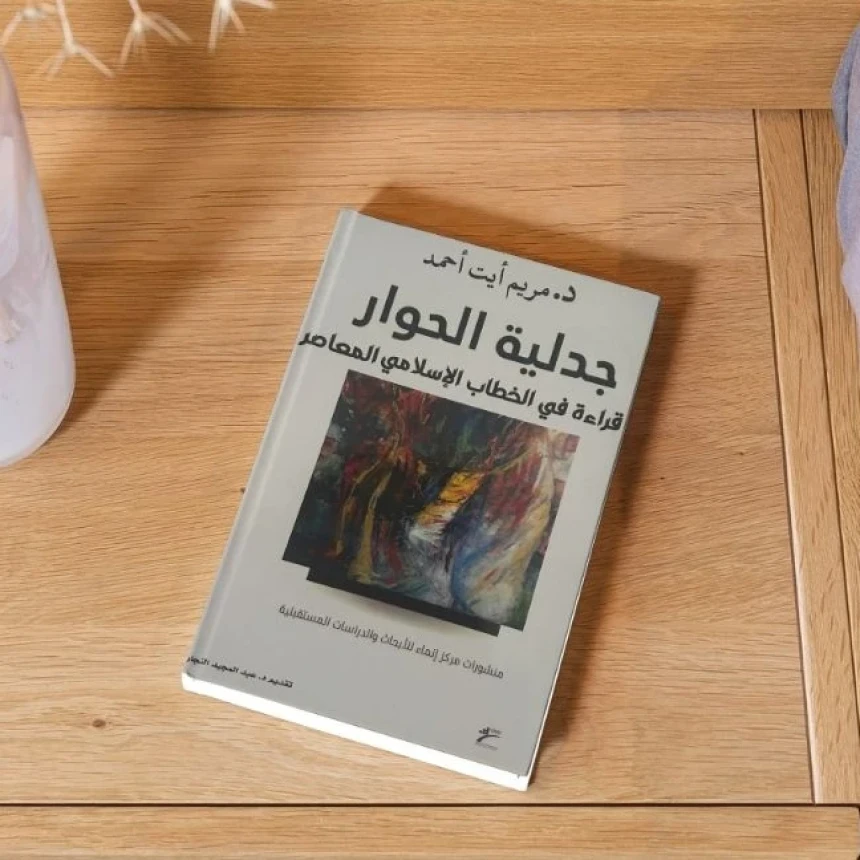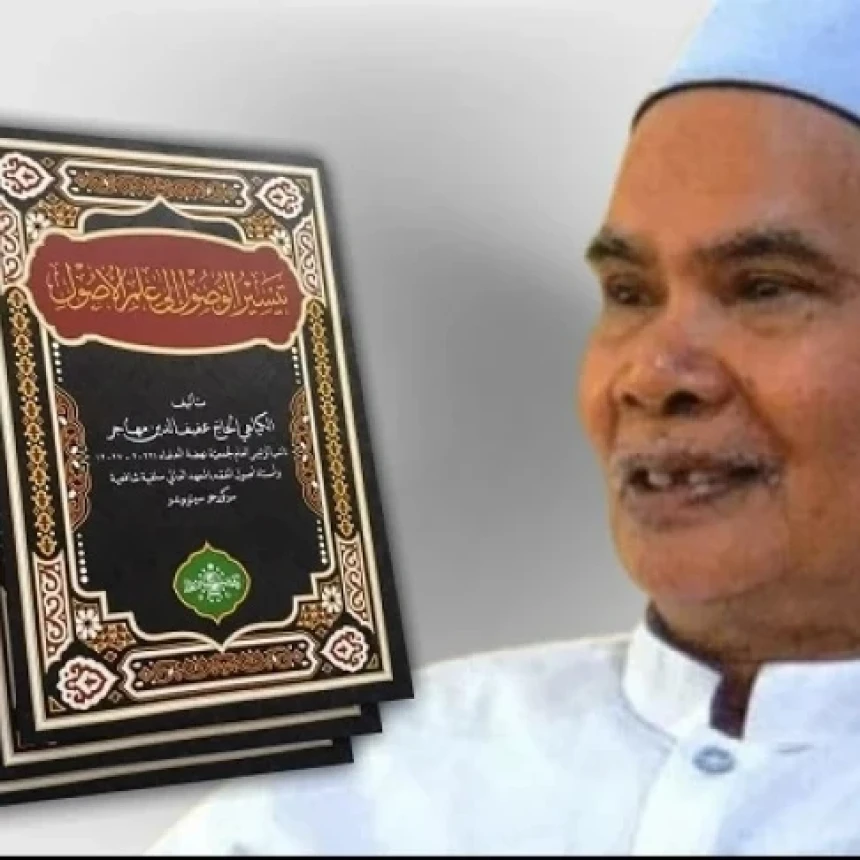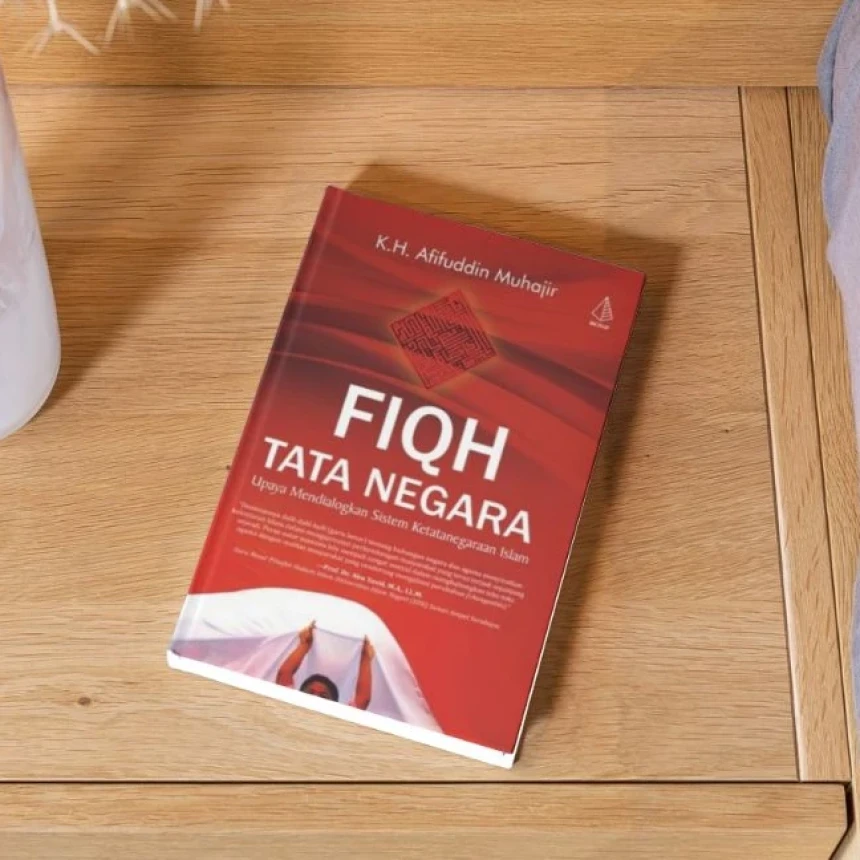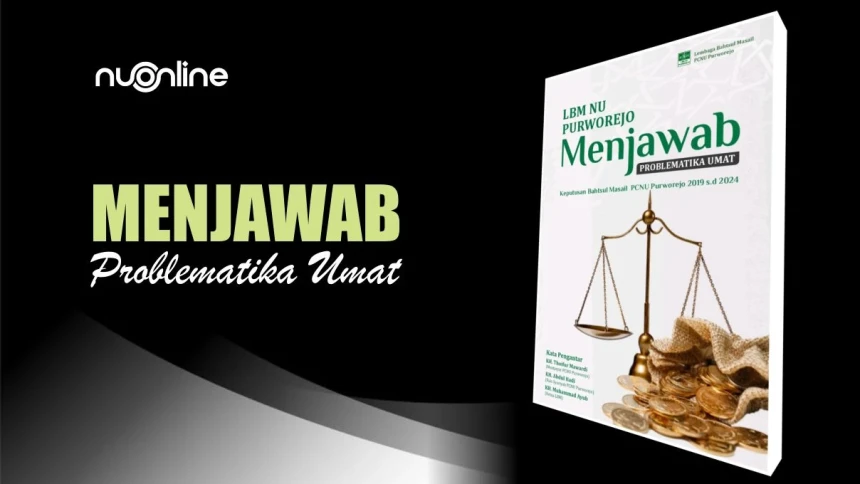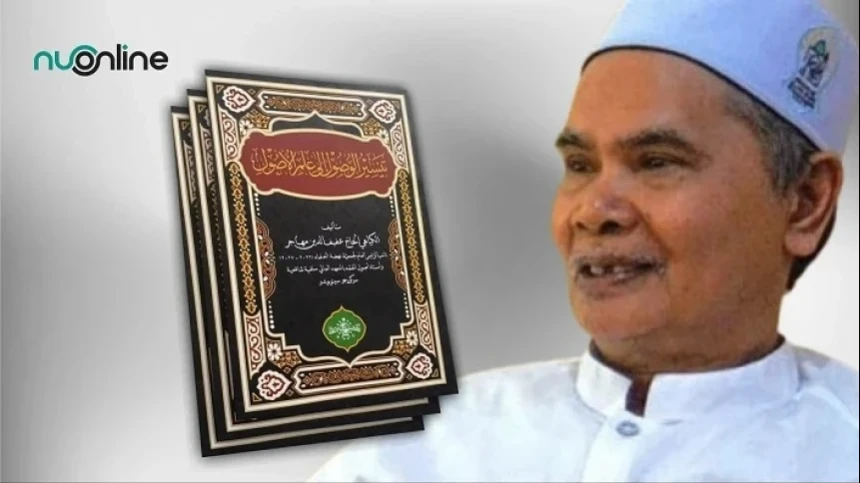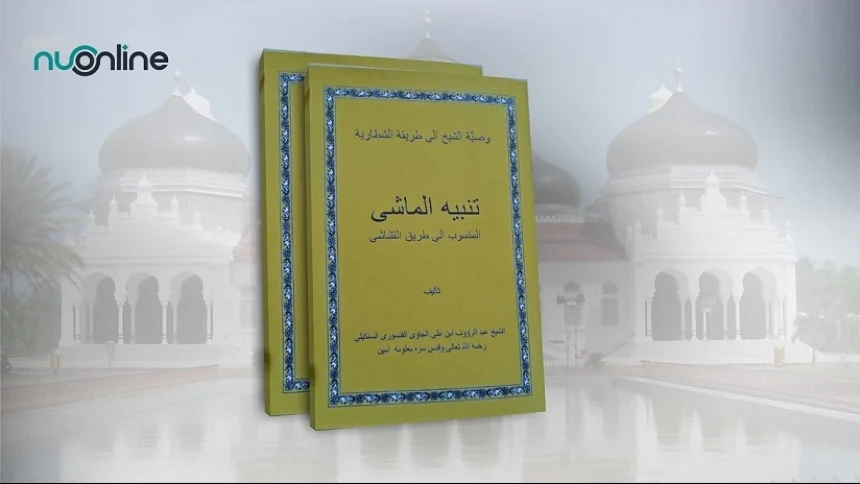Penulis: Prof Dr Rustopo
Penerbit: Ombak, Yogyakarta
Cetakan: Pertama 2007 (xxii + 419 halaman)
Peresensi: Lukman Santoso Az
"Akibat peristiwa gerakan 30 September 1965, etnis Tionghoa, selama 40 tahun lebih harus mengalami diskriminasi atau terkena cultural genocide, yakni pelarangan penggunaan bahasa, mengubah atau mengahancurkan sejarah dan atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya". (Tomy Su, 2006)<>
Kerusuhan Mei 1998 merupakan realitas sosial dari ekspresi ketidaksenangan masyarakat pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Citra orang-orang Tionghoa dalam pandangan masyarakat pribumi adalah negatif. Ini terjadi tidak terlepas dari perjalanan panjang politik diskriminasi ras yang diterapkan Belanda ketika menjajah Indonesia, yakni dengan memberikan status sosial yang lebih tinggi bagi orang Tionghoa dari pada pribumi. Politik diskriminasi ini selain menimbulkan kesenjangan sosial antara orang Tionghoa dan Jawa, juga membuat masyarakat pribumi menganggap etnis Tionghoa sebagai golongan yang pro-Belanda (penjajah).
Berlanjut pada masa kemerdekaan hingga tahun 1960-an, orang-orang Tionghoa, selain dianggap sebagai golongan eksklusif yang kerjanya mengeruk keuntungan ekonomi, juga dianggap sebagai penyokong gerakan-gerakan komunis. Karena itu, pada masa Orde Baru, semua kegiatan yang berbau Tionghoa dilarang pemerintah. Sehingga, tidak mengherankan jika selalu muncul penolakan keras terhadap semua bangunan dan eksplanasi sejarah yang mengaitkan identitas ke-Jawa-an dengan unsur-unsur Tionghoa, seperti penolakan terhadap pendapat Slamet Mulyana yang menyebutkan adanya elemen Tionghoa dalam diri beberapa wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Meski tampaknya realitas kultural telah berbicara lain, karena dalam realitas sejarah, etnis Tionghoa pada masa lalu telah bertemu, menyatu, dan melebur ‘menjadi Jawa’.
Dari konteks itulah, buku ini hadir. Buku yang ditulis Prof Dr Rustopo ini berupaya mengeksplorasi proses membangun identitas ke-Jawa-an yang dilakukan orang-orang Tionghoa di Surakarta sejak akhir abad ke-19 sampai sepanjang abad ke-20. Berbeda dengan buku-buku yang ada sebelumnya yang membahas mengenai orang Tionghoa, yang lebih melihat hubungan antara komunitas Tionghoa dengan aspek ekonomi atau politik sehingga orang Tionghoa di Jawa seolah-olah hanya melekat dengan modal, negara dan terpisah dari masyarakatnya. Maka, tulisan Rustopo ini secara cerdik menempatkan Tionghoa, baik sebagai komunitas maupun individu, menjadi satu ke dalam masyarakat dan kebudayaan Jawa.
Kehadiran tokoh-tokoh yang disebut Rustopo sebagai pekerja budaya, mulai dari Gan Kam, Tjan Tjoe Siem, Kho Djie Tiong, Koo Kiong Hie, Tio Gwat Bwee, Koo Giok Lian, Tan Gwan Hien, Liem Sio Nio, Lim Tan Swie sampai Panembahan Hardjonagoro atau Go Tik Swan ini, tidak sekadar menunjukkan adanya keinginan komunitas Tionghoa untuk ‘menjadi’ Jawa agar dapat diterima oleh masyarakat Jawa, melainkan mereka sebenarnya adalah Jawa itu sendiri.
Buku ini terdiri dari enam (VI) bab secara utuh. Pada Bab I, yang merupakan pengantar, Rustopo mengupas mengenai potret interaksi sosial dan kultural antara orang-orang Tionghoa dan Jawa. Interaksi sosial berkenaan dengan hubungan orang-orang Tionghoa dan masyarakat etnis Jawa di Surakarta dalam kehidupan yang kompleks dan dinamis. Interaksi kultural berkenaan dengan hubungan orang-orang Tionghoa dengan nilai-nilai dan unsur-unsur kebudayaan Jawa. Karena dalam kenyataannya, kedua jenis interaksi ini tidak bertemu. Dalam interaksi sosial, timbul masalah kesenjangan yang bersifat laten dan kadang-kadang menjadi penyulut timbulnya kerusuhan. Sebaliknya, dalam interaksi kultural, orang-orang Tionghoa melebur ke dalam nilai-nilai dan unsur-unsur kebudayaan Jawa.
Pada Bab II, Rustopo berupaya mengeksplorasi tentang Surakarta dan masyarakat Tionghoa pada kurun 1895-1998 dalam kaitannya dengan realitas budaya dan realitas sosial, yaitu dua dimensi kehidupan yang tidak saling bertemu atau bahkan bertolak belakang. Dalam pandangan Rustopo, Surakarta adalah lokus tumbuh-kembangnya kedua realitas yang tidak bertemu itu. Masyarakat Tionghoa di Surakarta, bagaimana pun merupakan bagian dari kedua realitas itu.
Pada Bab III, Rustopo membahas salah satu bagian dari proses interaksi kultural antara orang Tionghoa-Jawa di Surakarta, terutama tentang orang-orang Tionghoa yang berperan dominan dalam proses kreatif pembentukan Wayang Orang Panggung (WOP) dan proses pemasyarakatannya. Berdasarkan hasil penelitian Rustopo, wayang orang di Surakarta, mula-mula merupakan bagian dari tradisi pertunjukan di Istana Mangkunegaran yang eksklusif atau ’sakral’. Namun, berkat peran orang-orang Tionghoa, wayang orang istana itu bergeser menjadi bagian dari tradisi pertunjukan yang tidak sakral lagi, sehingga bisa dinikmati publik. Peran orang-orang Tionghoa dalam proses ini pun, mengalami perkembangan secara evolusioner, yaitu dari berperan sebagai kreator, berkembang menjadi penikmat WOP, dan berkembang lagi menjadi pelaku WOP.
Kemudian pada bab IV, Rustopo mengupas dua tokoh yang sangat kontras, tetapi keduanya sama-sama masuk ke dalam dunia Jawa dan membawanya sesuai dengan ide yang diyakini masing-masing, yakni Tjan Tjoe Siem yang memilih jalan untuk menggeluti Jawa dengan berperan sebagai guru besar bahasa dan sastra Jawa di Universitas Indonesia (UI). Sedangkan Kho Djien Tiong memilih menggeluti Jawa dengan menjadi ‘guru besar’ dalam seni pertunjukan lawak, yang di kemudian hari mampu melahirkan kelompok lawak populer, yakni Srimulat. Pada Bab V, Rustopo mengupas tentang kiprah Go Tik Swan dalam kebudayaan Jawa sebagai jalan atau proses evolusinya menjadi Jawa. Kiprahnya ini berkenaan dengan upayanya membangun citra atau identitas kejawaannya.
Dari itu Go Tik Swan muncul sebagai pelestari dan pengembang budaya Jawa, terutama dalam seni batik, keris, dan benda-benda purbakala. Sedangkan pada Bab V, yang merupakan bab kesimpulan, Rustopo memberikan benang merah, bahwa orang-orang Tionghoa yang menjadi Jawa sesungguhnya tidak sekadar mengikuti format Jawa yang sudah pakem yang disebut Nancy K. Florida sebagai Jawa yang dibekukan sebagai ‘tradisional’ atau adiluhung. Tetapi, mereka mengembangkan sendiri Jawa ‘baru’ dari akar-akar Jawa yang semakin rapuh.
Meski sejak awal Rustopo tidak dididik untuk menjadi sejarawan melainkan seniman, tapi, ia mampu membuktikan bahwa bekal pengetahuan, keterampilan, dan intelektual yang dimilikinya bisa memberi sumbangan penting bagi historiografi Indonesia tanpa menghilangkan jejak kesenimannya. Secara metodologis, Rustopo telah mampu membangun model penelitian sejarah untuk sebuah konstruksi dan eksplanasi dalam penulisan sejarah yang berbeda. Pada saat yang sama, Rustopo juga mampu memanfaatkan intuisi dan imajinasi kesenimannya untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode sejarah lisan, foto dan sumber material lain telah menghasilkan data dan sekaligus fakta sejarah yang sangat kaya dalam buku ini. Sementara, secara konseptual yang lain, hasil kajian dalam buku ini semakin memperkuat alasan untuk memikirkan kembali sumbangsih etnis Tionghoa dalam khazanah Indonesia.
Buku setebal 419 halaman ini sangat layak untuk dibaca oleh siapa pun, terutama bagi mereka yang masih tidak percaya bahwa masa lalu orang-orang Tionghoa merupakan sesuatu yang integral dalam sejarah masyarakat dan kebudayaan Jawa atau bahkan Indonesia. Sedangkan adanya pengasingan etnis Tionghoa dari Jawa yang terus berlanjut merupakan sebuah rekayasa politik dan bukan realitas sejarah.
Peresensi adalah kader Muda NU, pemerhati sosial-budaya pada Centre for Studies of Religion and State, Yogyakarta
Terpopuler
1
Hitung Cepat Dimulai, Luthfi-Yasin Unggul Sementara di Pilkada Jateng 2024
2
Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN 12%
3
Kronologi Santri di Bantaeng Meninggal dengan Leher Tergantung, Polisi Temukan Tanda-Tanda Kekerasan
4
Hitung Cepat Litbang Kompas, Pilkada Jakarta Berpotensi Dua Putaran
5
Bisakah Tetap Mencoblos di Pilkada 2024 meski Tak Dapat Undangan?
6
Ma'had Aly Ilmu Falak Siap Kerja Sama Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
Terkini
Lihat Semua