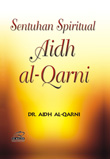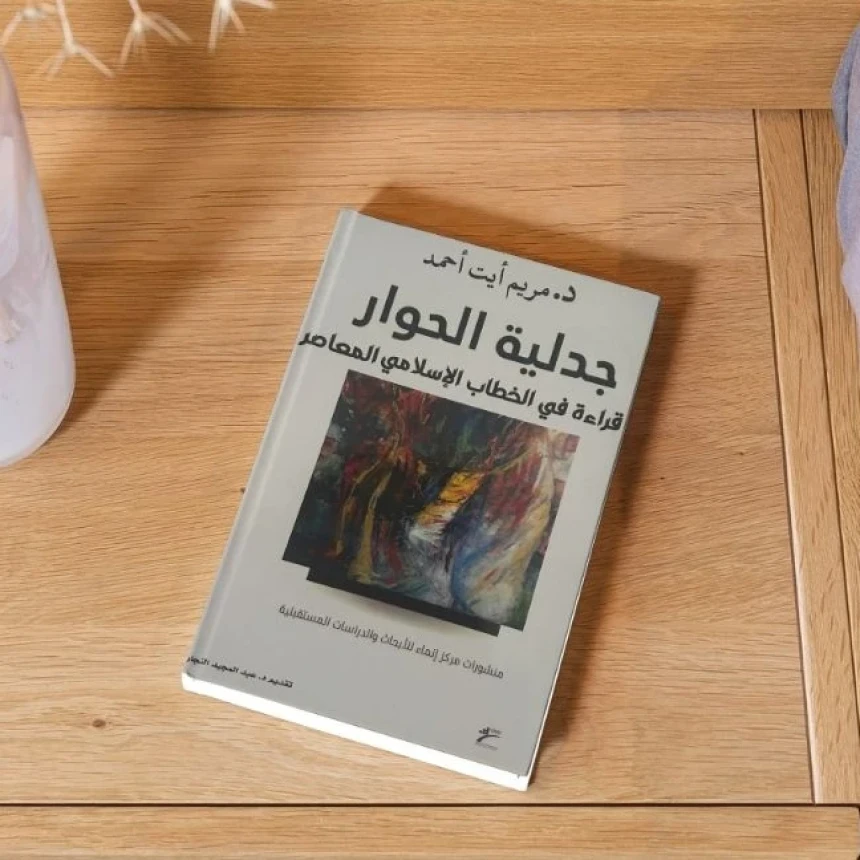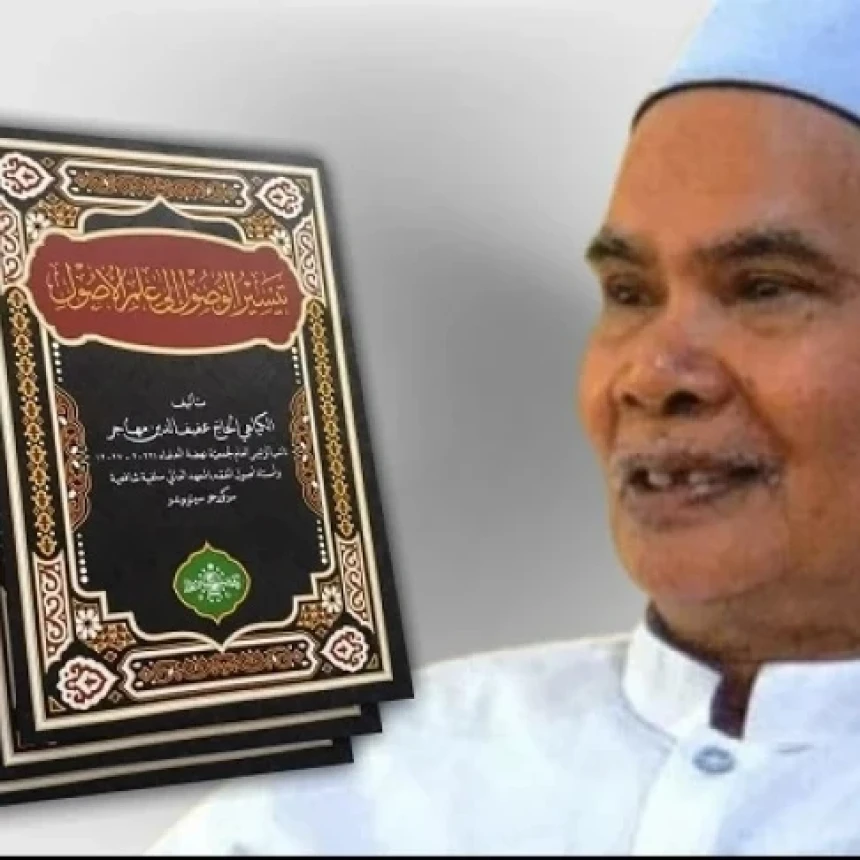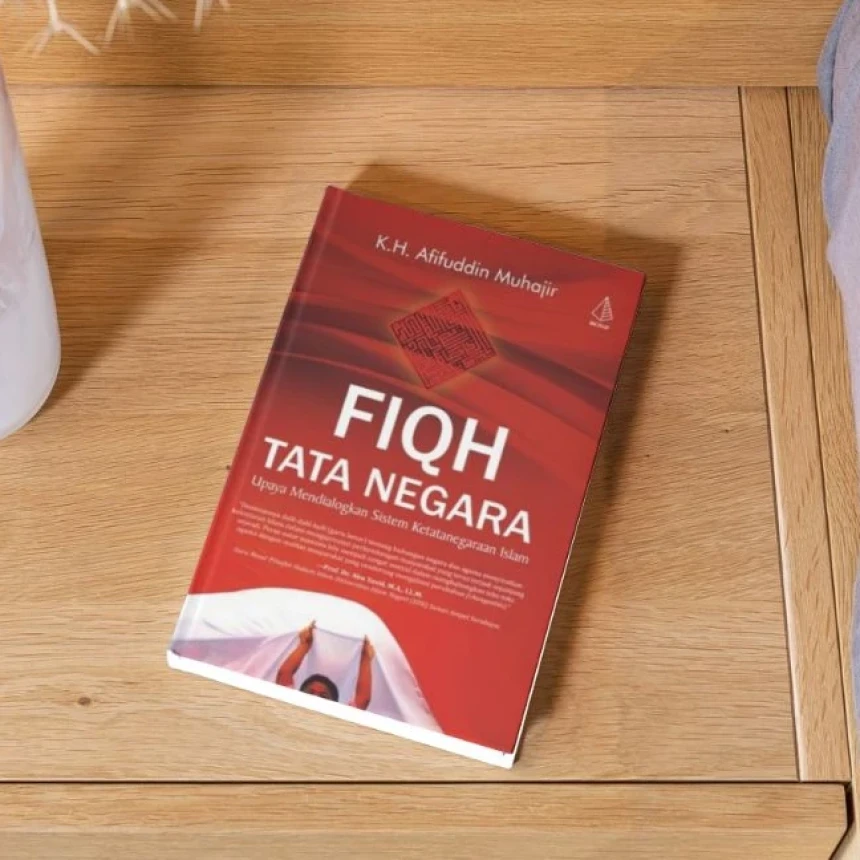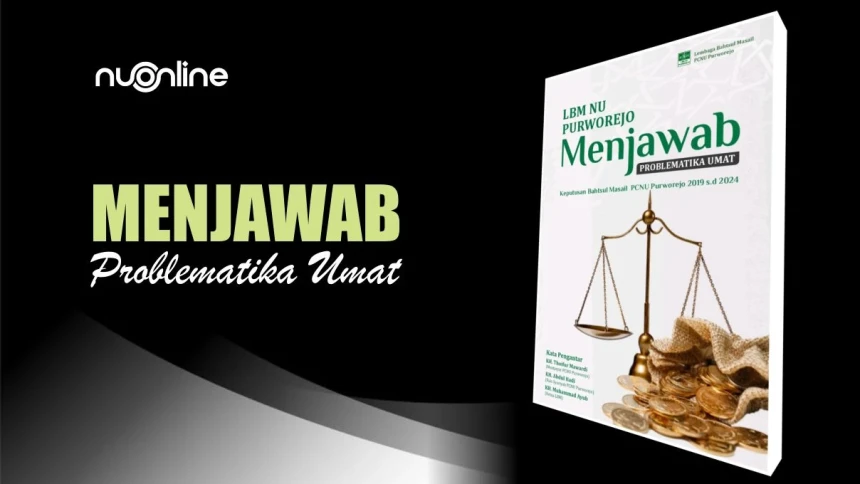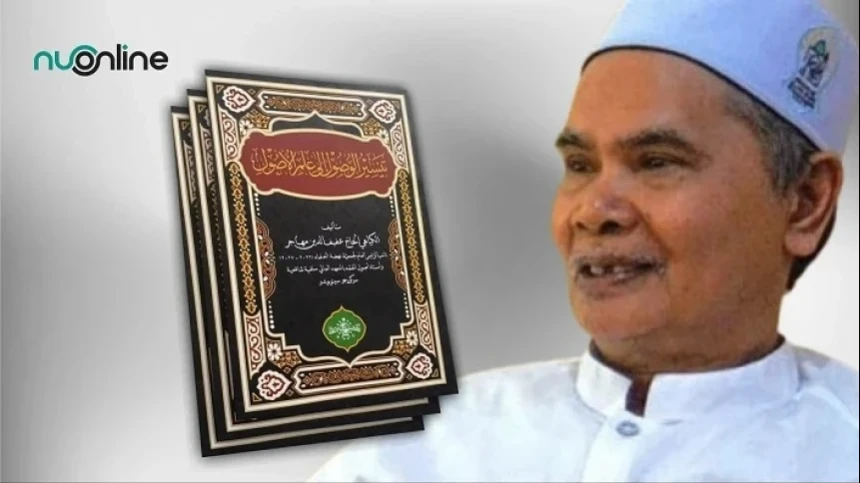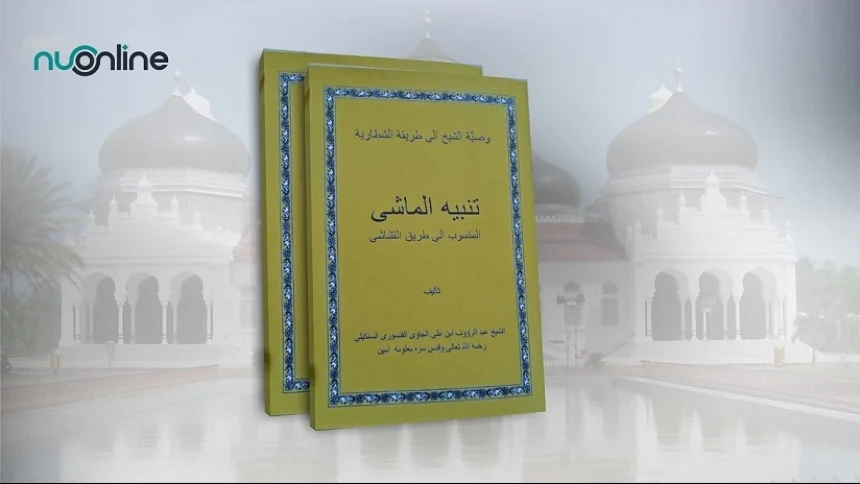Sentuhan Spiritual Aidh Al-Qorni
Selasa, 5 Desember 2006 | 05:43 WIB
Penulis: Dr. Aidh Al-Qorni, Cetakan: I, Juli 2006, Tebal : xiv; 644 Halaman, Peresensi: Puji Hartanto*
Masalah krisis moral, tampaknya menjadi catatan yang menarik sepanjang tahun 1997. agama yang dianggap sebagai benteng moralitas, seolah sudah semakin rapuh dengan banyaknya tindakan manusia yang tercerabut dari nilai-nilai agama. Krisis moral yang melanda umat manusia, mulai dari praktik aborsi, korupsi, kolusi, hingga kerusuhan dan pembakaran tempat ibadah, tampaknya semakin merajalela. Tragedi yang menggetarkan hati ini, tampaknya sudah menjadi nestapa kelam dalam peradaban umat manusia saat ini. Sehingga tidaklah berlebihan kalau Quraish Shihab dalam buku Lentera Hati, menyebut peradaban umat saat ini sudah memasuki jahiliyah baru. Yaitu sebuah peradaban yang memebenarkan penindasan, pembunuhan, ketidakadilan dan ketidakjujuran.
Kemudian, dari berbagai fenomena krisis moral <>tersebut, maka timbul pertanyaan tentang peran agama sebagai benteng moralitas. Mengapa ajaran agama yang begitu luhur, solah-olah tak mampu meredam krisis moral yang semakin buram ini? Agama sesungguhnya adalah bagaikan lampu yang menerangi jalan manusia. Dengan demikian, mereka yang yang mengabaikan agama, maka mereka seolah berjalan dalam kegelapan dan kesesatan. Yang menjadi permasalahan adalah, walaupun manusia mengaku beragama, namun dalam praktiknya ada orang yang mau menerima dan ada orang yang enggan menerimanya. Biasanya kesombongan dan keangkuhan yang ada dalam diri manusia membuat mata da telinga mereka tertutup menerima ajaran agama.
Buku karya Aidh Al-Qorni dengan judul “Sentuhan Spiritual” ini memang tidak bepretensi untuk mengikis habis kejahiliaan yang melanda sebagian besar umat manusia denga menebarkan “bunga-bunga sorga” beserta keindahannya. Sebaliknya, tujuan dari buku ini adalah tidak lain memberikan sebuah pencerahan atas kegersangan spiritual manusia dewasa ini. Menurut penulis buku ini, bahwa desawa ini, ajaran agama yang begitu luhur, telah dijadikan hanya sebatas slogan, alat legitimasi dan retorika-retorika politik (143). Sementara ajaran agama itu sendiri sulit untuk diwujudkan. Itulah sebabnya, kita sering melihat orang yang tidak sepadan antara ucapan dengan tindakan.
Lebih jauh, dari dahulu kita mengaggumi bintang di langit, bintang dipanggung, bintang dilapangan, akan tetapi enggan memandang cahaya bintang di hati. Sejak zaman purba, bintang di langit selalu menarik perhatian manusia. Bagi para pelaut ataupun musafir dipadang pasir, beberapa bintang tertentu bisa berperan sebagai kompas, memberikan pedoman untuk menentukan arah perjalanan agar tidak tersesat jalan. Sementara itu, kata Komarudin Hidayat (2005) dengan mengutip pendapat Imanuel Kant, bahwa kita seringkali melupakan bintang di hati yang perannya justru memberikan petunjuk moral.
Dalam setiap diri kita terdapat nurani, yaitu cahaya lembut yang selalu memancarkan kebajikan Ilahi. Namun demikian, volume serta frekuensinya akan tetap berbeda tergantung sejauhmana konsistensi seseorang dalam “menggosok” cermin hatinya. Oleh karena itu, agar seluruh tindakan dan perilaku kita mendapat bimbingan Ilahi, kita harus selalu mendengarkan hati nurani kita yang nyata-nyata terbebas dari segala interes dan ambisi pribadi. Lantas apa konsekuensinya? Kita tidak hanya akan mengalami kematangan spiritual serta merasakan kebersamaan atas kehadirat-Nya. Bahkan lebih dari itu, kita akan menjadi pribadi yang tercerahkan. Akal akan menjadi jernih dan emosi akan lebih terkendali. Sebab, dengan memperdalam ruang spiritual, kita akan lebih cerdas, arif dan bijak.
Kendati demikian, selama kita masih dalam level “manusia awam”, sebenarnya tidaklah ada garansi bahwa setelah kita “tercerahkan” itu lantas tidak akan tergoda lagi oleh berbagai wujud nafsu syahwat duniawi dalam kehidupan selanjutnya. Yang dimaksud adalah, orang yang telah tercerahkan itu paling tidak akan lebih peka dan efektif hati nuraninya, sehingga mungkin akan menjadi lebih santun, pemurah, dan penyabar. Keinginan untuk kepentingan sendiri atau kelompok sendiri mungkin akan masih tetap ada, akan tetapi tidak akan segera ditampilkan secara begitu saja dalam perilaku-perilaku vulgar yang membuat tuli terhadap aspirasi dan kepentingan orang lain. Dan, itu artinya, setelah melampui tahapan pencerahan spiritual, maka manusia yang sudah tercerahkan akan mengalami proses reaktualisasi diri sebagai “manusia baru”.
Ungkapan-ungkapan sebagaimana tersebut diatas mungkin terkesan bersifat utopis dan romantis. Namun, ditengah moralitas umat yang kian carut-marut, ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, serta berbagai tindak kejahatan lainnya, tampaknya jika hanya dengan melalui formula rasional empirik saja, tidaklah bisa menjadi jalan keluar yang baik. Maka formula yang berdimesi spiritual-etik pun menjadi amat diperlu
Terpopuler
1
Hitung Cepat Dimulai, Luthfi-Yasin Unggul Sementara di Pilkada Jateng 2024
2
Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN 12%
3
Kronologi Santri di Bantaeng Meninggal dengan Leher Tergantung, Polisi Temukan Tanda-Tanda Kekerasan
4
Hitung Cepat Litbang Kompas, Pilkada Jakarta Berpotensi Dua Putaran
5
Bisakah Tetap Mencoblos di Pilkada 2024 meski Tak Dapat Undangan?
6
Ma'had Aly Ilmu Falak Siap Kerja Sama Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
Terkini
Lihat Semua