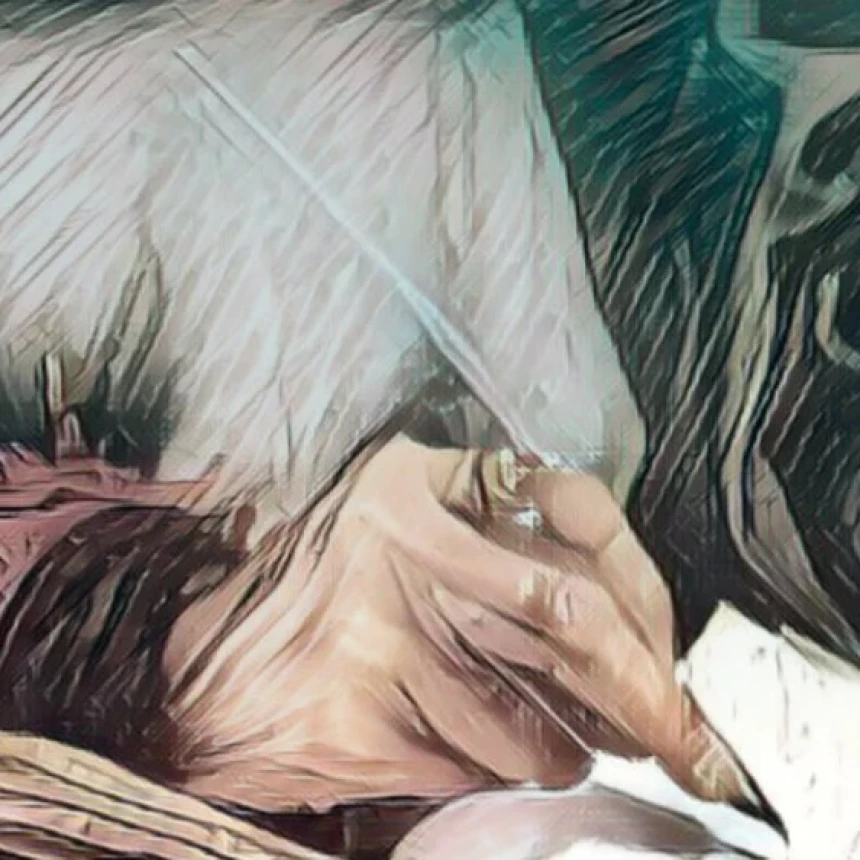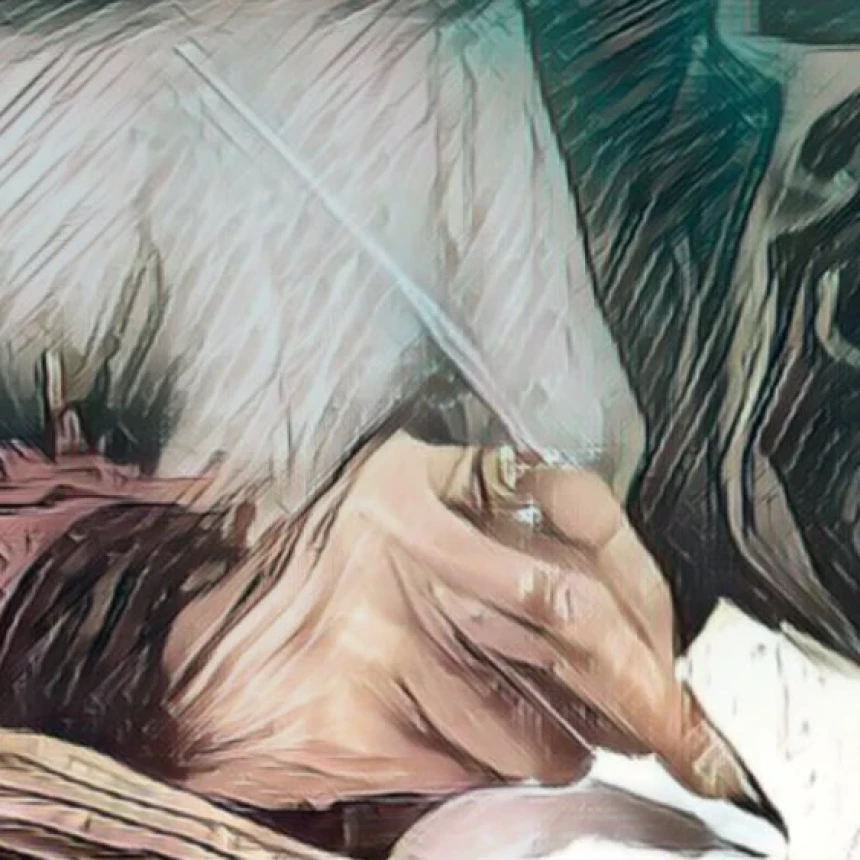Imam Abu Yusuf, Qadhil Qudhat Pertama dalam Sejarah Islam
NU Online · Sabtu, 18 Oktober 2025 | 10:00 WIB
Sunnatullah
Kolomnis
Dalam perjalanan hukum Islam, nama Imam Abu Yusuf menempati posisi yang sangat vital. Ia tidak hanya murid Imam Abu Hanifah, tetapi juga tokoh yang menjembatani antara dunia intelektual dan sistem pemerintahan. Di tangannya, fiqih Hanafi tidak hanya berkembang pesat di halaqah-halaqah maupun sekolah, tetapi juga tumbuh menjadi perangkat hukum yang diterapkan dalam sistem negara.
Namun sebelum kita benar-benar menelusuri jejak dan kiprahnya, tidak sempurna rasanya jika pembahasan ini tidak kita mulai dari nama lengkap dan pertumbuhannya hingga menjadi ulama tersohor. Karenanya, penulis akan membahas fragmen ini dari nama lengkapnya secara rinci, agar kita bisa mengenal utuh figure tersebut.
Nama Lengkap dan Rihlah Intelektualnya
Merujuk penjelasan Imam Syamsuddin ad-Dzahabi, seorang sejarawan Islam abad ketujuh, ulama yang masyhur dengan nama al-Qadhi Abu Yusuf ini memiliki nama lengkap Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Hubaish bin Sa’ad bin Bujair bin Mu’awiyyah al-Anshari al-Kufi. (Siyaru A’lamin Nubala, [Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1405 H], jilid VIII, halaman 535).
Ia lahir pada tahun 113 Hijriyah bertepatan dengan tahun 731 Masehi di Kufah, yang saat itu menjadi salah satu pusat ilmu paling bergengsi di dunia Islam. Di kota inilah Abu Yusuf kecil membuka matanya, tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, dan menapaki jalan panjang menuju ilmu pengetahuan. Namun jalan yang ia lalui dalam pertumbuhannya itu tidak mudah. Abu Yusuf lahir dari keluarga yang serba kekurangan, bahkan untuk sekadar kebutuhan pokok sehari-hari sering kali terasa berat.
Masa kecilnya diwarnai oleh perjuangan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Sedangkan masa depannya kelak? Maka jawabannya bisa ditebak akan sangat suram. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa bocah miskin dari lingkungan biasa ini akan menjadi seorang legenda tersohor, baik dalam hal intelektual maupun kekhalifahan.
Namun, keadaan yang serba kekurangan itu berubah ketika Abu Yusuf berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Karena setelah Imam Abu Hanifah melihat ketekunan, semangat, serta kecerdasan yang tampak bersinar dalam dirinya, ia memutuskan untuk menanggung biaya hidup dan kebutuhan belajarnya. Kemudian ia memberikan sejumlah uang agar Abu Yusuf bisa fokus menuntut ilmu tanpa harus khawatir akan urusan perut dan sandang.
Kisah ini kemudian direkam dan diabadikan oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam salah satu karyanya yang membahas sosok Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang memiliki peran penting di balik perkembangannya. Dalam karyanya disebutkan:
نَشَأَ فَقِيْرًا تَضْطُرُّهُ الْحَاجَةُ لِأَنْ يَعْمَلَ لِيَأْكُلَ وَتَدْفَعُهُ الرُّغْبَةُ فِي الْعِلْمِ، لِأَنْ يَسْتَمِعَ إِلىَ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمَحَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ فِيْهِ ذَلِكَ، أَمَدَّهُ بِالْمَالِ، فَانْصَرَفَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ. وَكَانَ قَدْ جَلَسَ إِلىَ ابْنِ أَبِي لَيْلىَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ إِلىَ أَبِي حَنِيْفَةَ، ثُمَّ انْقَطَعَ إِلَيْهِ
Artinya, “Ia tumbuh dalam keadaan miskin. Kebutuhan yang mendesak memaksanya bekerja untuk bisa makan, sementara keinginan yang kuat akan ilmu mendorongnya untuk mendengarkan para ulama. Hingga ketika Abu Hanifah melihat potensi itu padanya, ia memberinya uang, maka ia pun berbalik mencurahkan diri sepenuhnya untuk menuntut ilmu. Dan sungguh, ia pernah duduk belajar kepada Ibnu Abi Laila sebelum belajar kepada Abu Hanifah, kemudian ia berkomitmen total dan mengkhususkan diri hanya kepadanya (Abu Hanifah).” (Abu Hanifah: Hayatuhu wa Arauhu wa Fiqhuhu, [Kairo: Darul Fikr al-Arabi, 2008], halaman 22).
Di bawah bimbingan langsung Imam Abu Hanifah, potensi intelektual Abu Yusuf mengalami perkembangan yang sempurna. Komitmen totalnya untuk mengkhususkan diri dengan belajar kepada sang Imam, menjadikannya murid paling menonjol dalam lingkaran intelektual, yang berhasil menguasai ilmu syariat dengan komprehensif.
Kemudian setelah sekian lama berguru kepada Imam Abu Hanifah, ia tidak hanya menjadi seorang murid, tetapi juga berevolusi menjadi mitra diskusi sekaligus penerjemah paling cerdas dari setiap gagasan revolusioner sang guru, bahkan ia juga berhasil menyerap cara berpikir sang guru. Ia tumbuh menjadi seorang ahli fiqih dan ahli hadits yang tidak diragukan penguasaan keilmuannya. Dan yang paling menarik adalah menjadi nahkoda pertama dalam penyebaran mazhab sang guru.
Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Khairuddin az-Zirikli (wafat 1396 H), seorang sejarawan kontemporer terkemuka asal Beirut Lebanon. Dalam kitabnya ia mengatakan:
أَبُوْ يُوْسُفَ: صَاحِبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَتِلْمِيْذُهُ، وَأَوَّلُ مَنْ نَشَرَ مَذْهَبَهُ.كَانَ فَقِيْهًا عَلاَّمَةً، مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيْثِ
Artinya, “Abu Yusuf merupakan sahabat Imam Abu Hanifah, muridnya, sekaligus orang pertama yang menyebarkan mazhabnya. Dia adalah seorang ahli fiqih yang sangat alim, dan termasuk dari para penghafal hadits.” (al-A’lam lir Zirikli, [Darul Ilmi, t.t], jilid VIII, halaman 193).
Jika ditanya, “Apa kekhasan fiqih yang dibawa oleh Abu Yusuf?”
Secara metodologis, karakteristik fiqih yang dibawa oleh Imam Abu Yusuf tidak dapat dipisahkan dari kerangka epistemologi yang dibangun oleh gurunya, Imam Abu Hanifah. Dan benar adanya bahwa Imam Abu Hanifah memang masyhur sebagai ulama yang menonjolkan pendekatan ra’yu (rasio) dalam metode istinbath (penggalian) hukumnya.
Namun, penting untuk dipahami bahwa metodologi ra’yu dalam konteks pemikiran Imam Abu Hanifah bukanlah spekulasi bebas atau logika semata. Ra’yu yang dimaksud adalah sebuah metodologi nalar yang sistematis dan terstruktur, serta dibangun di atas fondasi sumber hukum Islam yang kokoh. Metode ini mencakup analogi, istihsan, dan tradisi.
Dengan demikian, maka kekhasan metodologi Imam Abu Yusuf dalam berfiqih pada hakikatnya merupakan cerminan dan pengembangan dari kerangka berpikir yang telah dirintis oleh gurunya. Sebagaimana Imam Abu Hanifah dikenal sebagai maestro metode rasional (ashabur ra’yi), Imam Abu Yusuf pun hadir sebagai penerus yang paling otentik dalam menjaga konsistensi aplikasi metodologi ini.
Penjelasan ini bisa kita jumpai dalam footnote kitab Qawathi’ul Adillah karya Imam Abu Manshur as-Sam’ani (wafat 489 H), yaitu:
لَزِمَ أَبَا حَنِيْفَةَ فَغَلَبَ عَلَيْهِ الرَّأْيُ
Artinya, “Abu Yusuf menetap (belajar) kepada Abu Hanifah, sehingga pendekatan rasional (ra’yu) mendominasi pemikirannya.” (Qawathi’ul Adillah fi Ushulil Fiqh, [Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999 M, tahqiq: Muhammad Hasan], halaman 102).
Qadhil Qudhat Pertama dalam Sejarah Islam
Reputasi Imam Abu Yusuf sebagai ahli hukum yang brilian, jujur, dan komprehensif rupanya sudah sampai ke telinga istana. Khalifah al-Mahdi, yang sedang berkuasa saat itu, mendengar tentang seorang ulama di Kufah yang tidak hanya menguasai teks-teks hukum, tetapi juga memahami realitas masyarakat yang kompleks. Maka, dipanggillah Abu Yusuf ke Baghdad.
Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Muhammad Badruddin al-Aini al-Hanafi (wafat 855 H) dalam salah satu karyanya, bahwa tujuan dipanggilnya Abu Yusuf tidak lain selain ingin diberi mandat sebagai Qadhi al-Qudhat (hakim tertinggi), dan sejak saat itu pula ia menjadi qadhil qudhat pertama dalam sejarah Islam.
Pengangkatan Abu Yusuf sebagai Qadhi al-Qudhat tidak sekadar menjadi episode singkat dalam sejarah, tetapi menjadi awal dari era baru dalam sistem peradilan Islam, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa kepercayaan ini tidak hanya diberikan oleh satu khalifah saja, tetapi tiga khalifah berturut-turut di era Dinasti Abbasiyah.
Pertama, ia diangkat oleh Khalifah al-Mahdi yang memerintah pada tahun 158 hingga 169 Hijriyah atau 775-785 Masehi. Selanjutnya ketika kekuasaan beralih kepada putranya, Khalifah al-Hadi yang memerintah pada tahun 169 hingga 170 Hijriyah atau 785-786 M.
Puncaknya adalah di era Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah pada tahun 170 hingga 193 Hijriyah atau 786-809 Masehi. Tidak hanya itu, Harun ar-Rasyid juga sangat mengagungkannya, menghormatinya, dan menjadikannya orang yang memiliki posisi yang sangat kuat dan terpercaya di era kepemimpinannya. Penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Badruddin al-Aini, dalam kitabnya ia mengatakan:
وَكَانَ أَبُو يُوْسُفَ سَكَنَ بَغْدَادَ، وَتَوَلىَّ الْقَضَاءَ لِثَلاَثَةٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ: الْمَهْدِى، وَابْنِهِ الْهَادِى، وَهَارُوْن الرَّشِيْدِ، وَكَانَ هَارُوْنُ الرَّشِيْدُ يُكْرِمُهُ، وَيُجِلُّهُ، وَكَانَ عِنْدَهُ حَظِيًّا مَكِيْنًا
Artinya, “Abu Yusuf tinggal di Baghdad, dan ia menjabat sebagai qadhi (hakim tertinggi) pada masa tiga khalifah, yaitu: (1) al-Mahdi; (2) putranya al-Hadi; dan (3) Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid sangat memuliakannya, menghormatinya, dan menjadikannya sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi serta kepercayaan yang kokoh di sisinya.” (Maghanil Akhyar, [Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006 M], jilid III, halaman 252).
Namun di tengah kesibukannya sebagai Qadhil Qudhat, mulai dari mengawasi sistem peradilan negara, menasihati Khalifah Harun ar-Rasyid, dan merumuskan kebijakan negara, Imam Abu Yusuf tetap menyisakan waktu untuk mengajar dan berkarya. Istana megah dan kursi hakim tertinggi tidak membuatnya lupa bahwa ia adalah produk dari sebuah sistem pendidikan yang mengubah nasibnya. Berikut adalah beberapa karya-karyanya yang terus dikaji hingga saat ini:
- Ikhtilafu Abi Hanifata wa Ibn Abi Laila,
- Al-Atsar li Abi Yusuf,
- Al-Kharraj li Abi Yusuf,
- Ar-Rad ‘ala Siyaril Auza’i, dan beberapa karya-karyanya yang lain.
Meski memiliki jabatan yang tinggi, ilmu yang luas, dan karya-karya yang terus dipelajari, sosok Abu Yusuf tetaplah seorang hamba yang rendah hati. Bahkan di waktu menjelang ajalnya, ia berdoa kepada Allah dengan doa sebagai berikut:
اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجْرِ فِي حُكْمٍ حَكَمْتُ فِيْهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ عِبَادِكَ تَعَمُّدًا، وَلَقَدِ اجْتَهَدْتُ فِي الْحُكْمِ بِمَا وَافَقَ كِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ. وَكُلُّ مَا أَشْكَلَ عَلَيَّ جَعَلْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَكَانَ عِنْدِي وَاللهِ مِمَّنْ يَعْرِفُ أَمْرَكَ وَلاَ يَخْرُجُ عَنِ الْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُهُ
Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku tidak pernah dengan sengaja berlaku curang dalam putusan yang aku jatuhkan antara dua hamba-Mu. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk memutuskan hukum sesuai dengan Kitab-Mu dan Sunnah Nabi-Mu. Dan setiap kali suatu hal membingungkanku, aku jadikan Abu Hanifah sebagai perantara antara aku dan Engkau. Demi Allah, dia di sisiku termasuk orang yang memahami perintah-Mu dan tidak menyimpang dari kebenaran yang dia mengetahuinya.” (Ibnu Khalikan, Wafiyatul A’yan, [Beirut: Dar Shadir, 1900 M], jilid VI, halaman 388).
Kalimat itu merupakan wasiat terakhir seorang pecinta keadilan. Ia tidak berbangga dengan jabatannya, tidak juga menyombongkan ilmunya. Yang ada justru kerendahan hati dan ketakutan hanya kepada Allah swt. Ia mengakui bahwa gurunya, Imam Abu Hanifah, tetap menjadi pemandunya bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Ia pun kemudian wafat pada hari Kamis, tanggal 5 Rabiul Awal tahun 182 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 798 Masehi. Wallahu a’lam.
Sunnatullah, Pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Jawa Timur.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua